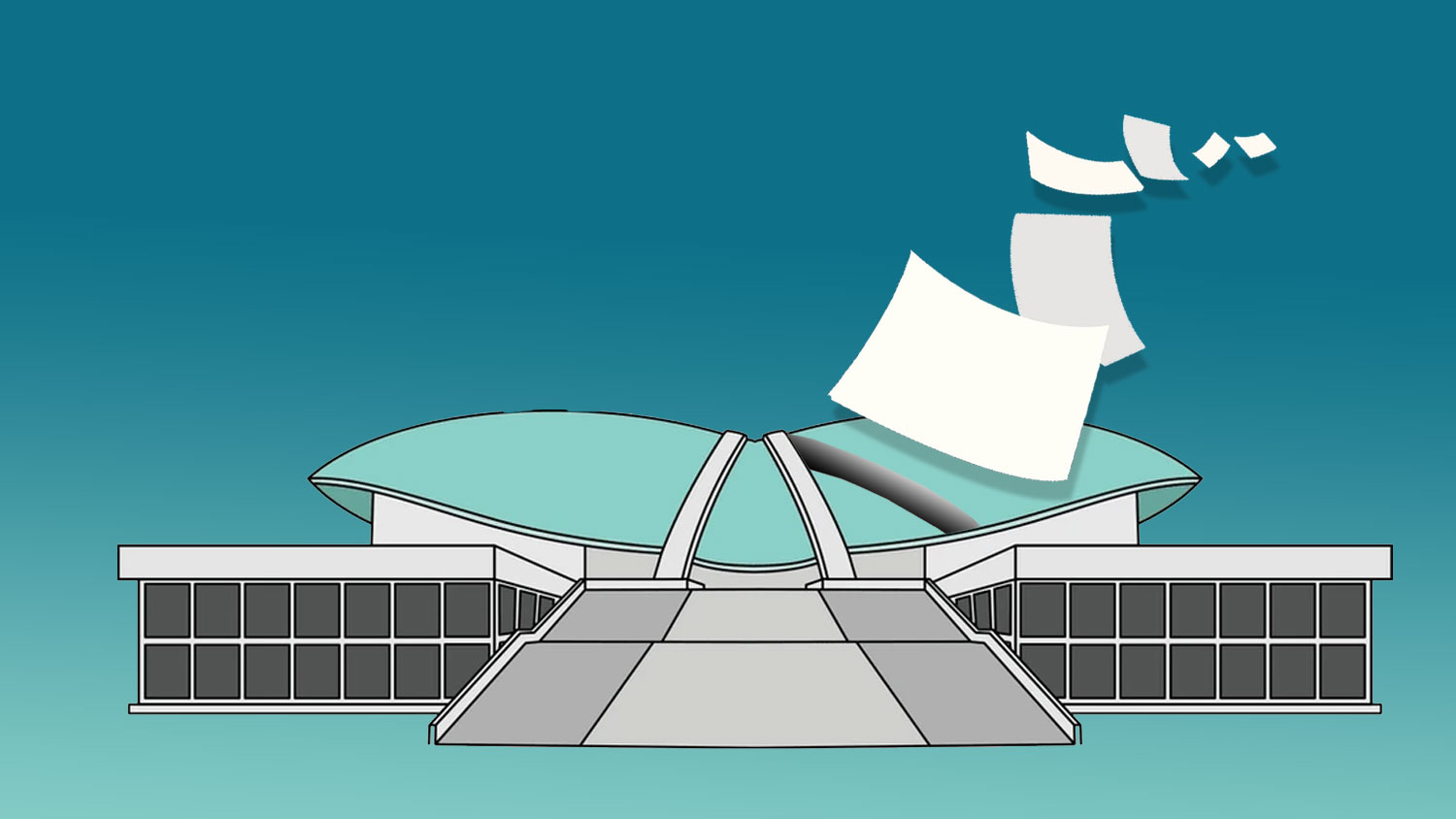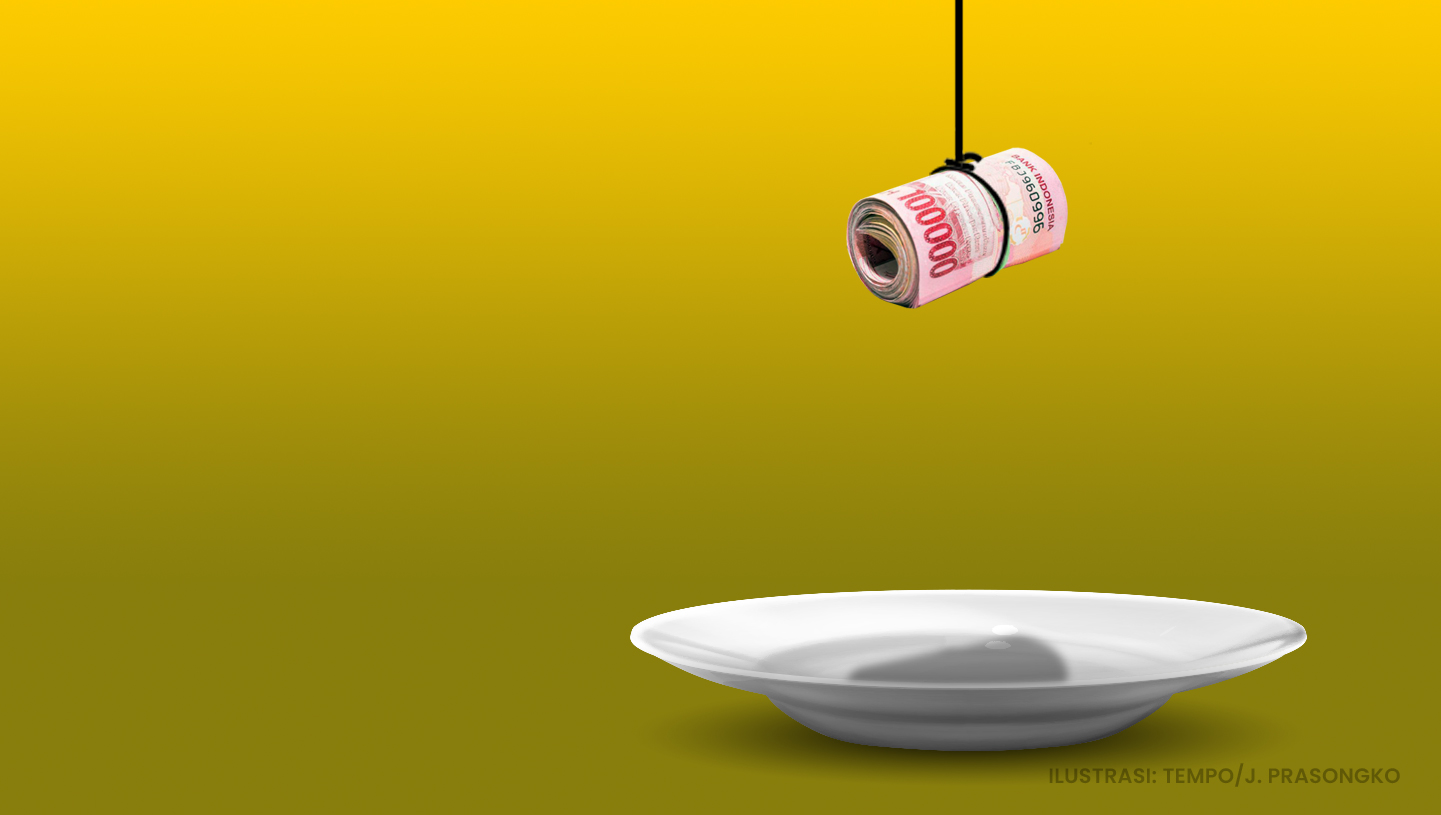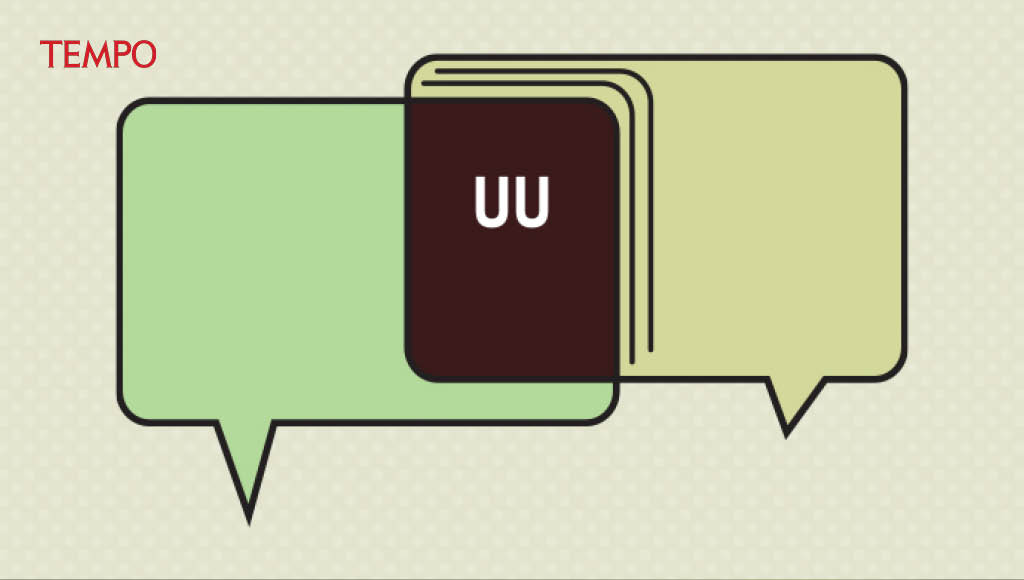Tiap kali kediktatoran runtuh, kekosongan timbul. Anehnya, selalu ada semacam rasa kecewa yang tak jelas. Barangkali karena demokrasi adalah sebuah terang, dan tiap terang dimulai dengan sebuah fajar, dan tiap fajar mempesona dengan keindahan yang singkat. Beberapa saat kemudian matahari akan membawa cahaya yang panjang dan tunggal, sering terlalu cerah, sering menjemukan. Jangan terkejut jika beberapa waktu setelah Orde Baru runtuh, orang akan kembali mengenangnya dengan rindu. Untuk apa demokrasi? Adakah demokrasi?
Siapa yang pernah mengalami perubahan besar sebuah masyarakat akan kenal dengan sindrom itu. Pekan lalu saya baca kembali Kompasiana yang ditulis P.K. Ojong di harian Kompas dan saya ingat tajuk rencana Harian Kami yang ditulis Nono Makarim pada 1966-1967. Tampaknya, mula-mula yang terasa setelah "Demokrasi Terpimpin" Bung Karno jatuh adalah harapan. Betapa kuat elan kebebasan itu, betapa jelas harapan itu: penulisnya, dua cendekiawan dengan cita-cita dan keyakinan, merekam dengan jelas suara yang menganggap masa "Demokrasi Terpimpin" itu sebagai masa gelap yang sedang (dan harus) ditinggalkan. Penyair Taufiq Ismail bahkan menyebutnya sebagai "tirani", ketika orang, karena represi dalam tubuh dan jiwa, dengan takut tak bisa mengakui bahwa 2 + 2 sama dengan 4.
Dan ternyata, kumpulan sajak Taufiq Ismail dari masa demonstrasi mahasiswa 1966 (mula-mula terbit dengan nama samaran, dalam bentuk stensil, karena takut sensor) menjadi buku laku. Tulisan Mochtar Lubis dari dalam penjara "Demokrasi Terpimpin", Catatan Subversif, juga tenar. Novelnya yang ditulisnya dalam tahanan, Senja di Jakarta —dulu tidak bisa dicetak di dalam negeri karena penulisnya adalah seorang makhluk terlarang—pada 1968 muncul di Indonesia, bahkan dibuat film.
Tapi berangsur-angsur, tulisan pada akhir 1960-an itu seperti menghilang dari ingatan. Bahkan ditinggalkan. Apalagi rasa lega dan harapan masa itu berumur sejenak. Sesudah itu rasa kecewa, bahkan kemarahan, kian lama kian panjang gemanya. "Orde Baru" yang menjanjikan tatanan yang baru, yang oleh sebagian cendekiawan Indonesia dikira akan lebih demokratis ketimbang "Demokrasi Terpimpin", akhirnya sesuatu yang dicerca: ketidak-bebasan masa Soekarno diulangi berlipat-lipat di masa Soeharto. Kebrutalan militer dan kekuasaan uang yang dulu tidak ada kini ditambahkan, dengan tingkat yang memuakkan. Dalam disilusi yang meluas itu, sajak Tirani dan Benteng Taufiq Ismail mulai dianggap bukan lagi sebagai suara yang memperjuangkan kemerdekaan berpikir dan kebebasan mimbar—apalagi kemerdekaan berpikir dan kebebasan mimbar itu kemudian ternyata tidak berlaku bagi mereka yang "kiri"—melainkan hanya bagian dari propaganda "Orde Baru". Kini banyak orang lebih tertarik puisi Wiji Thukul, penyair yang sampai hari ini bersembunyi. Dulu, yang memukau orang adalah keberanian Mochtar Lubis dengan Catatan Subversif, tapi kini yang tampil adalah keberanian Pramoedya Ananta Toer dari dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu.
Apa setelah ini? Kediktatoran telah runtuh batu sendinya. Kemerdekaan berbicara mulai mengambil ruang yang luas dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Terkadang terpikir oleh saya tidakkah sajak Wiji Thukul akan mengalami nasib yang sama seperti sajak Taufiq Ismail, dan tulisan-tulisan Pramoedya akan kehilangan auranya karena orang bakal lupa akan kerasnya penindasan ketika karya itu ditulis.
Kita akan bilang "jangan lagi!", tapi mungkin mustahil. Sebuah zaman akhirnya akan jadi sebuah cerita wayang yang tidak ditentukan oleh dalang ataupun para pahlawan lakonnya, melainkan oleh penontonnya. Dan tak setiap penonton sama dengan kita. Ketika zaman kediktatoran berlalu, dan demokrasi datang—dengan fajarnya yang singkat—sesuatu yang berbeda akan hadir, suka atau tak suka: sebuah suasana ketika tidak ada lagi Si Itu.
Adapun Si Itu adalah sesuatu di luar diri kita tempat kita meletakkan sumber tanggung jawab dan kesalahan. Sementara itu, demokrasi—berbeda dengan kekuasaan otoriter—tidak lagi punya Si Itu yang satu. Dulu ada PKI yang dituduh jadi biang keladi ini dan itu. Kemudian ada Soeharto dalam singkatan "SDSB" (yakni: Soeharto Dalang Semua Bencana). Bagaimana kelak, setelah Soeharto tak tampak bisa terus-menerus jadi biang kesalahan baru? Bagaimana nanti, setelah berdiri sebuah pemerintah yang dipilih secara bebas oleh banyak orang? Bukankah sumber tanggung jawab, juga pangkal sukses ataupun celaka, menjadi "banyak orang" itu?
Saya pernah membaca seorang penulis mengutip lelucon bagaimana seorang Katolik membela keyakinannya bahwa Sri Paus tidak pernah bersalah. "Setidaknya kami yakin ada satu orang yang tidak pernah bersalah. Kalian, yang percaya penuh kepada demokrasi, berasumsi bahwa mayoritas orang, berjuta-juta orang, tidak pernah bersalah. Bukanlah keyakinan itu mengandung risiko yang lebih besar?"
Risiko ini memang bertambah tajam pada akhir milenium. Kini orang berbicara tentang "Zaman Pencerahan Kedua". Dalam "Zaman Pencerahan Pertama" dulu, ada keyakinan bahwa manusia tak akan lagi mengambil keputusan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat berdasarkan sesuatu yang "tak rasional", melainkan berdasarkan Pengetahuan yang cukup. Kini, dalam "Zaman Pencerahan Kedua", ada argumen bahwa manusia akan mengambil keputusan yang sangat penting tanpa dasar Pengetahuan yang cukup—sebab tak ada pengetahuan apa pun yang memadai tentang hidup dan arahnya di kemudian hari. Orang kini hidup dalam "masyarakat risiko", dan tak jelas lagi apa dan siapa yang bisa jadi alasan kenapa dunia tidak menjadi lebih beres. Kapitalisme bisa tampak buruk bisa tampak baik, sosialisme bisa tampak bopeng bisa tampak cantik, demokrasi tidak sempurna, kediktatoran brengsek, dan agama kadang tampak membebaskan kadang tampak represif.
Apalagi ketika demokrasi terbentuk, dan tidak ada lagi buku yang dilarang, (dan buku yang dilarang akan mengesankan sebagai buku yang menyimpan Kebenaran), dan pahlawan jadi baur dengan orang ramai yang berani bicara. Keduanya bisa sama-sama betul atau sama-sama keliru. Di mana kemudian "Si Itu?" Haruskah, untuk mendapatkannya, akan ada nostalgia bagi "Orde Baru"?
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini