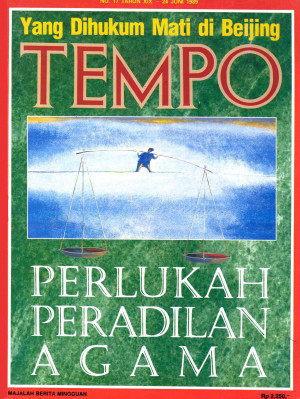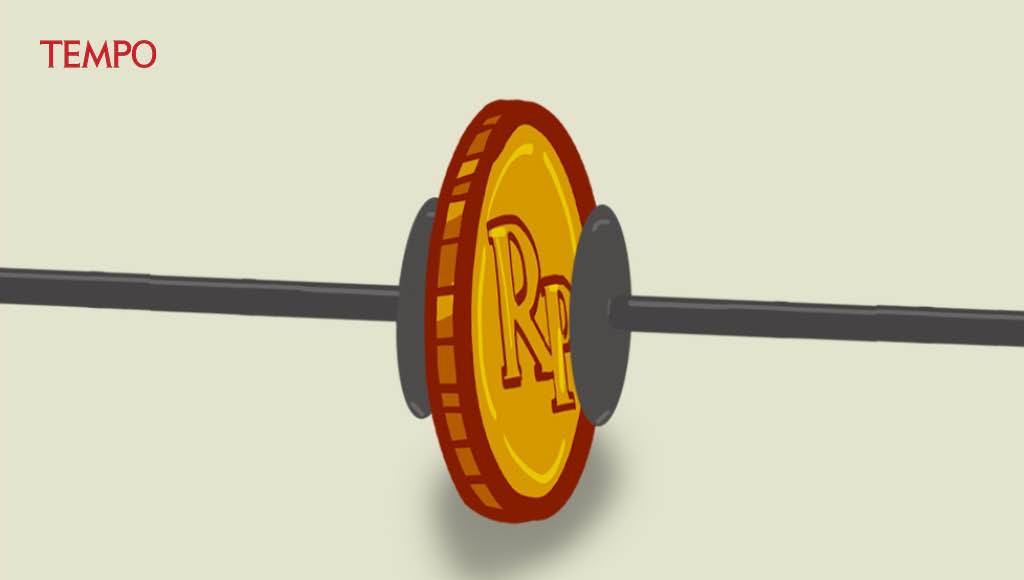DARI kelompok negara berkembang Indonesia kini sudah berada di peringkat ke-4 negara pengutang terbesar di dunia setelah Brasil, Meksiko, dan Argentina. Kenyataan ini tidaklah mengejutkan. Juga tidak bagi para wakil negara-negara anggota IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia), yang berkumpul di Den Haag Selasa dan Rabu pekan lalu. Beranggotakan 9 lembaga internasional dan 15 negara industri maju, IGGI dalam sidangnya yang ke-32 itu sepakat memberikan pinjaman senilai US$ 4.297,5 juta. Ini berarti 7% lebih tinggi dari pinjaman IGGI tahun lalu yang US$ 4.015 juta. Juga sedikit lebih banyak dari yang diusulkan Bank Dunia, sebesar US$ 4.200 juta. Indonesia bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan berbagai negara pengutang di Amerika Latin. Disiplinnya patut dipuji, padahal beban semakin berat karena rendahnya harga minyak, di samping berlipatnya jumlah cicilan dan bunga utang, akibat depresiasi dolar. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara tauladan ditinjau dari segi taatnya ia membayar utang -- satu sikap yang lama sudah ditinggalkan oleh negara-negara Amerika Latin. Memang, dalam dua tahun terakhir, ada imbauan dari pihak kita agar negara kreditor berusaha mempertimbangkan semacam hibah buat utang Indonesia yang kian membengkak itu. Imbauan ini kian terasa relevan, setelah Menlu AS Nicholas Brady mengajukan rencananya berupa keringanan pembayaran utang bagi negara-negara Amerika Latin. Tak jelas, adakah delegasi Indonesia mengungkit lagi soal keringanan itu, dalam sidang dua hari di Den Haag pekan silam. Tapi gelagatnya menunjukkan bahwa gagasan itu sudah disingkirkan jauh-jauh, sebelum sidang. Padahal, dalam kesempatan berpidato di dalam sidang, wakil IMF Kadhim al-Eyd mengakui, membengkaknya utang Indonesia itu 80% disebabkan oleh depresiasi dolar, yang nyata-nyata berada di luar kemampuan negara pengutang. Akibatnya, beban cicilan utang Indonesia per tahun meningkat dari US$ 2,7 milyar menjadi US$ 6,9 milyar. Dan jumlah utang membesar dari US$ 31 milyar menjadi US$ 50 milyar. Semua itu sebenarnya terasa semakin berat, karena Indonesia tidak diberi kesempatan untuk bisa mengharapkan satu rumus pembayaran yang lebih layak, atau katakanlah lebih fair. Yang tampaknya pasti hanya ini: bahwa kita hanya dinilai layak untuk beroleh pinjaman lebih besar. Komitmen IGGI tersebut banyak ditafsirkan sebagai realisasi dari kepercayaan IGGI yang masih tetap besar pada kemampuan Pemerintah RI untuk mengelola utang-utang luar negerinya. Semua utusan negara donor, kabarnya, memuji manajemen ekonomi makro Indonesia. Sanjungan mereka terutama ditujukan pada kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, serta usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri. Jatuhnya harga sejumlah komoditi ekspor Indonesia, serta gejala proteksionisme yang bisa menghambat ekspor dan perolehan devisa Indonesia, ternyata juga menjadi pembicaraan. Ketua IGGI Piet Boekman mengingatkan para donor agar tak melakukan kegiatan kontradiktif dengan memasang benteng proteksi -- satu teguran yang sesungguhnya lebih bersifat imbauan. Bukankah Pasar Tunggal Eropa yang akan ditegakkan tahun 1992 bisa menjelma jadi benteng proteksi yang luar biasa tangguhnya? Mungkin karena tak ada gagasan yang pukal (solid), yang bisa dijadikan pegangan bagi Indonesia selepas sidang IGGI itu, maka beberapa pakar di tanah air tercenung dibuatnya. Mantan Menteri Keuangan Frans Seda, misalnya, mempertanyakan mengapa Pemerintah terus menutup kebutuhan anggaran pemerintah (defisit fiskal) dengan bantuan luar negeri. Lalu ia beroleh kesan, meskipun bantuan luar negeri tidak secara eksplisit dan langsung dipergunakan untuk bayar utang, toh melalui penggunaannya utang itu secara implisit dimanfaatkan untuk menutup defisit Anggaran Pembangunan (Kompas, 19 Juni 1989). Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie mempermasalahkan mengapa bantuan luar negeri, yang selalu dikatakan hanya sebagai pelengkap, jumlahnya ternyata begitu besar. Sejauh ini Pemerintah telah meneken utang (komitmen) sejumlah US$ 70 milyar lebih, dan beban yang harus dipikul untuk melunasi utang pokok berikut cicilannya semakin besar. Bahkan menggerogoti APBN. Tapi Bank Dunia bisa melihat masalah ini dari sisi yang lebih cerah. Pemerintah RI dinilai oleh lembaga internasional ini sudah berusaha mengurangi defisit fiskalnya, terbukti dari angka-angka berikut. Defisit anggaran yang pernah mencapai -4,9% terhadap GDP (produk domestik kotor) pada 1986-87 telah turun jadi -3,2% terhadap GDP pada 1988-89. Rata-rata defisit anggaran yang dilakukan pemerintah sejak 1981-82 hingga 1987-88 adalah -2,8%, masih rendah dibandingkan Malaysia (-12,7%), Bangladesh (-9%), Pakistan (-6,3%), Filipina (-6,3%), dan Muangthai (-4,8%). Kendati beban cicilan utang Indonesia meningkat, hasil nasional GNP (produk nasional kotor) untuk membayar utang luar negeri telah turun dari 22,2% pada 1982-83 menjadi 19,3% pada 1988-89. Bantuan yang telah dijanjikan IGGI tadi sebenarnya masih jauh di bawah sasaran Pemerintah. Untuk Repelita V, Pemerintah menganggarkan bantuan luar negeri Rp 60,4 trilyun atau Rp 12 trilyun per tahun. Biasanya bantuan IGGI, menurut laporan Bank Dunia menutup 80% bantuan luar negeri-untuk Pemerintah. Sedangkan nilai bantuan yang dijanjikan IGGI kali ini, jika dirupiahkan dengan kurs Rp 1.775, baru sekitar Rp 7,6 trilyun atau sekitar 63,33% dari target. Sementara itu, dana rupiah yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek yang dibantu pembiayaannya oleh IGGI -- misalnya biaya untuk pembebasan lahan lokasi proyek masih terasa kurang. Untuk itu, sejak tahun anggaran 1986-87 Pemerintah harus meminta pinjaman bantuan khusus (special assistance loan). Dari sidang IGGI kali ini masih dikucurkan bantuan khusus itu -- yang bisa dirupiahkan seluruhnya US$ 1.855 juta dolar. Kalau dirupiahkan dengan kurs 1.775, seluruhnya hampir Rp 3 3 trilyun. Pinjaman bantuan khusus ini juga memberikan keuntungan lain bagi neraca pembayaran. Seperti pernah dikatakan Ketua Bappenas Saleh Afiff, pinjaman ini berbentuk valuta asing yang akan masuk ke cadangan devisa Bank Indonesia. Dengan demikian, bantuan khusus bisa memperkuat adangan devisa. Pemerintah telah pula menegaskan bahwa bantuan IGGI itu tidak dipakai untuk membayar utang. Keterangan ini sangat beralasan, sebab separuh dari utang yang ditawarkan IGGI berbentuk bantuan proyek, berupa barang modal dan jasa yang akan dipakai buat pembangunan. Sedang sisanya berbentuk tunai, yang akan dipakai untuk menunjang proyek-proyek itu (lihat: Tentang Program dan Proyek). Sekalipun begitu, pemerintah agaknya masih perlu secara rinci menjelaskan, bantuan IGGI itu sebenarnya untuk membiayai program atau proyek apa saja. Ataukah Buku Biru, yang berisi daftar proyek yang "dijajakan" pihak Bappenas di IGGI tiap tahun itu, isinya bisa diungkapkan sebagian, sekadar yang penting-penting saja? Setidaknya agar masyarakat tidak sekadar menduga-duga.Max Wangkar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini