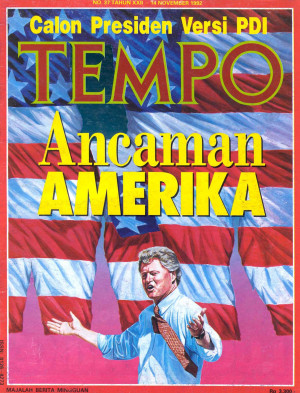HAK asasi wanita mulai bersemi nun di Lombok. Setidaknya, petugas tak lagi bisa seenaknya menangkap dan menuduh seorang wanita sebagai pelacur. Hakim Lalu Mariyun dari Pengadilan Negeri Praya, Kamis pekan lalu, membuat vonis yang berani dan amat jarang terjadi: menghukum Kepala Kantor Departemen Sosial Lombok Tengah selaku Ketua Tim PMTS (Penanggulangan Masalah Tuna Sosial -- WTS, gelandangan, pengemis). Tergugat ini harus membayar ganti rugi Rp 1,2 juta lebih kepada Rademan, seorang petani di sana. Penangkapan yang dilakukan Tim PMTS terhadap Satriah, anak gadis Rademan -- karena dituduh sebagai pelacur -- dinyatakan hakim tak sah. Perkara itu bermula dari kecurigaan penduduk Desa Wejegeseng terhadap rumah Rademan yang selalu dikunjungi banyak orang. Sebagian penduduk menyangka Rademan dan istrinya "mempekerjakan" Satriah, anak gadis mereka yang berusia 15 tahun. Karena laporan penduduk, Kepala Desa Lalu Darmasih menegur Rademan. Pasangan itu menyangkal tuduhan tersebut. "Masa, saya mau menjual anak sendiri!" kata Rademan kepada TEMPO. "Satriah kami pelihara baik-baik," ujar Rahma, istri Rademan nomor 7 dari 11 wanita yang pernah dinikahinya. Suatu pagi, demikian Rademan, bulan Juni silam, beberapa lelaki mendatangi rumah Rademan. Menurut Lalu Rusmat, pengacara Rademan, kelompok itu adalah anggota Tim PMTS Lombok yang biasa merazia pelacur. "Tanpa diperiksa dan disidik dan tanpa persetujuan Rademan, Satriah lantas dibawa tim itu ke SRW (Sasana Rehabilitasi Wanita) Budi Rini di Mataram. Rademan mencoba berbagai upaya, tapi ia mengalami kesulitan untuk mengeluarkan anaknya dari sasana rehabilitasi itu, kecuali ada lelaki yang bersedia bertanggung jawab sebagai suami Satriah. Karena itu, terpaksa Rademan membayar seorang pemuda di dusunnya, agar sudi menikahi Satriah. Setelah urusan itu beres, lelaki itu akan menceraikan Satriah. Begitu anak gadisnya lepas dari tahanan itu, Rademan tak mau berpangku tangan. Hatinya masih mendidih. Lalu, ia menggugat Kepala Kantor Departemen Sosial Kabupaten Lombok Tengah selaku Ketua Tim PMTS dan juga Kepala Sasana Rehabilitasi Budi Rini, Soedomo, agar membayar kerugian moril dan materiil yang dialaminya, sebesar Rp 100 juta. Dalam menjawab gugatan itu di pengadilan, Soedomo mengatakan bahwa sasana itu bukanlah tempat tahanan melainkan unit dari Departemen Sosial yang bertugas untuk mendidik warga yang punya masalah sosial, semacam wanita tunasusila. Tim PMTS ini sendiri bergerak sesuai dengan keputusan Bupati Lombok Tengah, April 1992. Bupati memberi tim itu wewenang, antara lain, melaksanakan kegiatan penyuluhan dan melaksanakan razia, penangkapan, serta pelayanan kepada penyandang masalah tunasosial. Namun, Hakim Mariyun berpendapat, betapapun tim ini harus memperhatikan harkat dan hak asasi warga masyarakat serta hak subjektif perorangan. Yang lebih penting, kata hakim itu, "Konotasi WTS itu tak dapat dinilai semata-mata dari sudut pandang ilmu sosial, tetapi justru yang lebih dominan adalah dari segi hukum." Hakim ini menunjuk pada asas praduga tak bersalah yang seharusnya dijunjung tinggi. Selain itu, tindakan membawa Satriah di luar kemauannya sendiri, menurut Mariyun, adalah tindakan merampas kebebasan seseorang. Selain itu, Mariyun mengingatkan bahwa pengertian penyidik dalam menangani kasus ini, sesuai dengan yang diatur oleh KUHAP (hukum acara pidana) adalah pejabat kepolisian RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. "Tim Penanggulangan Masalah Tuna-Sosisal, kendati di dalamnya terdapat polisi, bukanlah petugas penyidik yang dimaksud KUHAP," ujar hakim yang dikenal sering menangani soal hak asasi wanita di Lombok Timur itu. Akhirnya, Hakim Mariyun mengabulkan sebagian gugatan ganti rugi Rademan, yaitu sebesar Rp 1.249.000. Jumlah itu kecil bila dibandingkan dengan gugatan Rademan yang Rp 100 juta itu. Namun, ini cukup berarti, sebagai terobosan hukum, dan bisa dijadikan pegangan bagi wanita yang merasa ditangkap secara sewenang-wenang. Dan acungan jempol layak diberikan kepada Hakim Mariyun di Lombok itu, bila diingat bahwa keputusan itu diambilnya di daerah yang penduduknya mayoritas memegang teguh nilai-nilai kesucian wanita. Bila kelak keputusan Mariyun bisa menjadi yurisprudensi, lantas aparat mana yang berhak merazia pelacur? Tentu saja polisi. Tapi Nursjahbani Katjasungkana, Ketua LBH Jakarta, menganggap razia itu tak perlu. "Penangkapan dan penahanan seseorang dengan alasan ia pelacur, itu melanggar asas praduga tak bersalah dan melanggar hak kemerdekaan seseorang," katanya. Nursjahbani pernah menangani kasus yang mirip yang terjadi di Jakarta Agustus silam. Tiga wanita yang sebetulnya pulang bekerja dari sebuah bar di Jalan Hayam Wuruk disangka tim sebagai pelacur. Mereka diangkut ke Panti Rehabilitasi Wanita Mulya Jaya di daerah Pasar Rebo, Jakarta. Dua di antara tiga wanita ini baru dilepaskan setelah LBH turun tangan. "Sayangnya, mereka tak mau menuntut karena takut sama petugas," kata Nursjahbani. Leila S. Chudori (Jakarta) dan Supriyanto Khafid (Lombok)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini