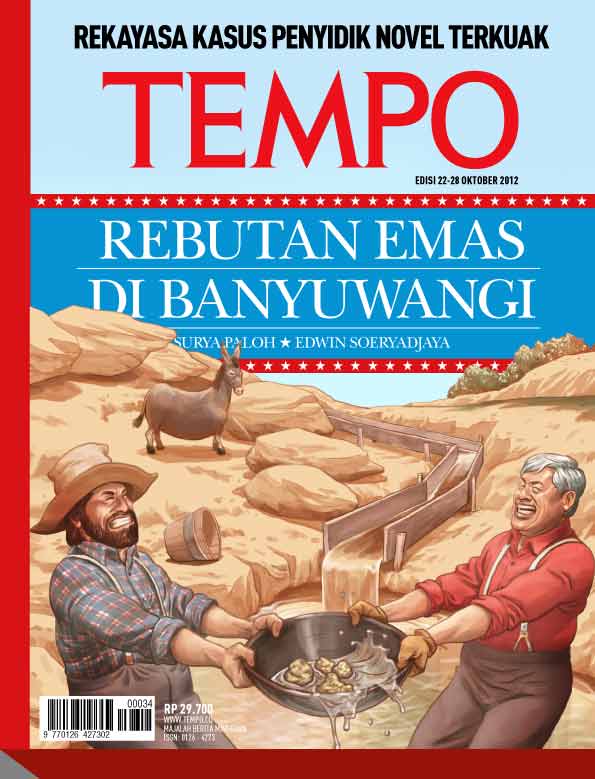Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ruang sipir rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan, Kamis pekan lalu, terlihat meriah daripada biasanya. Di meja terhidang beragam buah dan makanan yang semuanya dari sayuran. Sun An, 50 tahun, siang itu dikunjungi istrinya dan Edwin Partogi, pengacaranya, dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Wajah Sun An tampak gembira. ”Beberapa hari pada setiap Oktober, kami memang menjadi vegetarian,” kata penganut agama Buddha ini kepada Tempo.
Pria bertubuh kecil itu ditemani Ang Ho, 33 tahun, keponakannya. Istri Ang Ho tak hadir karena mesti menjaga anaknya di Jakarta. Dari kartu penduduk mereka, Sun An tercatat warga Teluk Gong, Jakarta Utara, sedangkan Ang Ho warga Kamal, Jakarta Barat. Keduanya menjadi penghuni Tanjung Gusta sejak setahun lalu. ”Bisnis saya dulu ada di Belawan, makanya sering datang ke Medan,” ujar Sun An.
Paman dan keponakan ini divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Medan pada 31 Januari lalu. Putusan ini, dua bulan kemudian, dikuatkan Pengadilan Tinggi. Mereka dituduh otak pembunuhan berencana terhadap Khowito alias Awie dan Dora Halim. Suami-istri ini tewas saat mobil Chevrolet Captiva mereka diterjang 27 tembakan senjata api di garasi rumah mereka di Jalan Akasia I, Medan, pada 29 Maret 2011. Menurut Edwin, atas putusan pengadilan itu, pihaknya kini tengah mengajukan kasasi. ”Prosesnya sedang berlangsung,” katanya.
Pembunuhan brutal itu terjadi pada pukul 21.30, saat Awie dan Dora baru pulang dari makan malam. Empat pria mengenakan helm memberondong mobil mereka. Di dalam mobil ada dua anak mereka, yang masing-masing berusia lima dan dua tahun, serta seorang babysitter. Ketiganya duduk di jok belakang dan selamat, sementara 19 peluru menembus tubuh Awie dan delapan menembus Dora.
Tiga hari setelah pembunuhan, polisi menangkap Ang Ho, yang sedang menginap di Hotel JW Marriott Medan. Pria bertubuh tegap ini diinterogasi di dalam kamar oleh lima reserse Kepolisian Resor Kota Medan. Mereka, kata Ang Ho, langsung menuduhnya telah membunuh Awie dan Dora. Ia membantah, tapi para reserse membawanya ke markas Kepolisian Sektor Medan Timur. Di sana, ia dipukuli. ”Saya ditampar dan kemaluan saya ditendang terus-menerus,” ujarnya.
Keesokan pagi, giliran Sun An yang ditangkap saat berada di Kisaran. Sepanjang perjalanan menuju Medan, dia disiksa dan dipaksa mengaku membunuh Awie dan Dora. ”Saat itu rahang saya sampai tak bisa bergerak akibat dipukul terus,” katanya. Di Medan, dia langsung dijebloskan ke tahanan Markas Komando Brigade Mobil di Jalan Bhayangkara.
Kepala Satuan Reserse Polres Kota Medan Komisaris Yoris Marzuki mengatakan tuduhan yang dialamatkan kepada Sun An dan Ang Ho sudah tepat. Penyidik yakin empat eksekutor pembunuhan adalah warga negara Malaysia dan di bawah perintah Sun An-Ang Ho. Beberapa pekan sebelum pembunuhan, ujar Yoris, mereka bertemu di kafe Hotel Cambridge, Medan. ”Empat eksekutor ini direkrut oleh Achui, teman Sun An,” kata Yoris. Motif pembunuhan: soal sakit hati dan utang-piutang.
Yoris mengatakan penyidik punya bukti kuat soal adanya empat eksekutor itu. Ang Ho, atas perintah Sun An, bertugas menjemput keempat pria itu saat mereka tiba di Medan. Setelah ”menggarap” orderan Sun An, keempat eksekutor dibawa ke Bagan Siapiapi, Riau, oleh Ang Ho, juga atas perintah Sun An. Hanya, kata Yoris, sesampai di Tanjung Balai, Sun An kemudian mengambil alih tugas itu. ”Helm yang dibawa keempat eksekutor itu ditinggal di mobil Ang Ho,” ujar Yoris.
Sun An menampik tuduhan itu. Menurut dia, dirinya memang pernah menjemput empat orang keturunan Cina—rata-rata berusia 19-25 tahun—dan itu atas permintaan Achui. Saat dihubungi Achui, ketika itu ia sedang di Kota Rantau Prapat menuju Bagan Siapiapi untuk melakukan sembahyang Cheng Beng—sembahyang khusus ditujukan untuk orang tua. ”Saya balik lagi ke Tanjung Balai demi menuruti permintaan Achui,” katanya. Rantau Prapat dan Tanjung Balai ditempuhnya sekitar tiga jam. Sun An menyatakan sudah lama mengenal Achui dan segan menolak permintaan temannya itu.
Ia mengaku tak mengenal keempat orang itu. Selama perjalanan, mereka juga tak banyak bicara, bahkan tak bertanya sedikit pun tentang nama mereka. Keempat orang yang ia jemput ini, kata Sun An, juga berbeda dengan empat warga negara Malaysia yang ia temui di Hotel Cambridge. ”Saya hanya tahu mereka juga pakai bahasa Hokkian,” ujarnya.
Ang Ho juga mengaku apes. ”Saya tidak tahu apa pun soal pembunuhan itu,” katanya. Ia mengaku hanya sesekali datang ke Medan untuk mengurus bisnis keramik dan batu gioknya. Dia menjemput keempat pria itu atas perintah pamannya. Ia juga tak akrab dengan Achui dan tak mengenal korban. ”Saya bingung kenapa dituduh membunuh,” ujarnya. Adapun Achui kini kabur ke Cina dan dinyatakan sebagai buron. Empat eksekutor yang disebut menghabisi Awie dan Dora juga raib. Polisi tak bisa menemukan jejak mereka.
Edwin Partogi menegaskan tak mungkin kliennya menjadi otak pembunuhan. Saat pembunuhan terjadi, Sun An berada di Rantau Prapat, yang berjarak sekitar 235 kilometer dari Medan atau delapan jam bila ditempuh dengan mobil. Sedangkan Ang Ho tengah di hotel. ”(Kasus) kedua orang ini mirip kasus Sengkon dan Karta di masa lampau,” katanya kepada Tempo.
Sengkon dan Karta dipenjara karena dipaksa mengaku sebagai pembunuh dan perampok. Sengkon divonis 12 tahun, sementara Karta divonis 7 tahun. Belakangan terkuak mereka bukan pembunuhnya. Kasus yang terjadi pada 1980-an itu sampai sekarang dikenang sebagai ”tragedi dunia peradilan Indonesia”.
Menurut Sun An, dia memang mengenal Awie dan ayahnya, Sarwo Pranoto, karena mereka sama-sama berbisnis kapal ikan di perairan Belawan. Sun An dan Sarwo memang punya masalah tiga tahun lalu perihal sewa-menyewa kapal. Namun masalah itu sudah tuntas. Selama penyidikan, kata Sun An, penyidik memaksanya mengaku membunuh Awie karena soal utang Rp 100 juta kepada ayah Awie. ”Saya dituduh menyewa pembunuh,” ujarnya.
Selama penyidikan, Sun An dan Ang Ho terus menerima siksaan. Menurut Sun An, karena demikian sakitnya, dia pernah meminta penyiksanya membunuh dirinya saja. Akibat penyiksaan itu, sampai kini pinggangnya terus terasa sakit. Dia juga mengaku telah diperas seorang penyidik selama pemeriksaan. ”Anehnya, penyidik itu malah membuat surat terima kasih kepada saya karena telah diberi uang,” kata Sun An. Kasus pemerasan ini sudah dilaporkan Edwin ke Markas Besar Kepolisian.
Lantaran tak tahan disiksa itulah Sun An dan Ang Ho akhirnya angkat tangan. Keduanya setuju menandatangani berita acara pemeriksaan yang, menurut Sun An, isinya tak ia pahami. ”Saya hanya sekolah sampai kelas III SD dan Ang Ho hanya kelas II SD,” katanya. Mereka saat itu memang didampingi pengacara dari polisi. ”Namun, kalau kami dipukuli, pengacara itu diam saja,” ujar Sun An.
Menurut Edwin, pengadilan terhadap kliennya, yang kemudian dituntut 20 tahun penjara, juga ganjil. Hakim hanya membuat putusan berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) keduanya yang sudah dicabut di tengah persidangan. ”BAP itu bukan barang bukti,” katanya. Menurut Edwin, tak ada satu saksi dan barang bukti yang menguatkan keduanya otak pembunuhan. ”Eksekutornya tak ada, jadi dari mana polisi tahu dan menyimpulkan keduanya merupakan otak pembunuhan ini?” ujarnya.
Putusan pengadilan tingkat pertama dan banding sudah jatuh. Belum berupa putusan tetap, memang. Karena itulah Edwin berharap Mahkamah Agung melihat keganjilan terhadap proses peradilan kliennya dan membebaskan keduanya dari hukuman yang semestinya tak mereka terima tersebut.
Mustafa Silalahi, Sahat Simatupang (Medan)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo