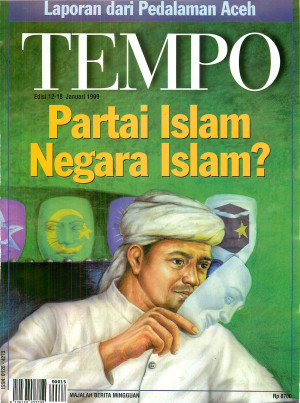Di Indonesia, hukum dibuat bukan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bangsa, melainkan untuk kepentingan mereka yang berkuasa atau berharta. Contohnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Landasan filosofis undang-undang agraria adalah mengutamakan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Ternyata, setelah hampir empat windu undang-undang tersebut diberlakukan, politik pertanahan selalu salah kaprah. Hak-hak rakyat atas tanah dinafikan begitu saja. Dengan cara-cara kekerasan, termasuk penggunaan perangkat hukum dan aparat militer, tanah warga diambil secara paksa atas nama kepentingan umum—meski sebenarnya adalah untuk kepentingan pengusaha atau penguasa.
Kalaupun ganti rugi diberikan, nilai ekonomi tanah yang diterima warga amat kecil. Setelah dicek, ganti rugi tanah untuk proyek Waduk Kedungombo, Jawa Tengah, ternyata cuma dihargai antara Rp 280 dan Rp 700 per meter persegi. Di Cimacan, Jawa Barat, ganti rugi tanah untuk proyek lapangan golf dipatok Rp 30 semeter persegi—dan setelah proses pengadilan, barulah harga itu dinaikkan tujuh kali lipat.
Walhasil, terjadi semacam latifundium (penguasaan kepemilikan tanah yang amat luas pada segelintir pengusaha). Dalam pada itu, lahan pertanian semakin menyusut dan porsi kepemilikan tanah petani dengan sendirinya menciut. Sementara itu, petani kehilangan hak dan akses pada tanah berikut sumber agrarianya.
Itu sebabnya berbagai kasus pembebasan dan penggusuran tanah tak henti-henti mencuat. Sekadar contohnya adalah kasus tanah Cimacan, Tapos milik mantan presiden Soeharto di Bogor, kasus Kedungombo di Jawa Tengah, kasus Banongan di Jawa Timur, serta clan Ohee di Irianjaya. Beberapa kasus yang lebih tepat disebut sebagai pencaplokan tanah terjadi di berbagai daerah lain, misalnya di Aceh, Sumatra Selatan, Lombok, dan Kalimantan.
Setelah rezim Orde Baru dimakzulkan bersama lengsernya Soeharto, penduduk setempat yang menganggap tanahnya dulu diambil secara paksa, ramai-ramai, menuntut balik tanah mereka. Krisis ekonomi yang membuat banyak orang kehilangan lapangan kerja, terutama di kawasan perkotaan, sedikit banyak berpengaruh pada militansi warga.
Di Situbondo, Jawa Timur, contohnya. Sejak 1996, warga enam desa berusaha menguasai kembali tanah PD Banongan, seluas 1.327 hektare, yang ditanami tebu. Namun, aksi mencabuti tanaman tebu dan menggantinya dengan tanaman jagung, yang didukung oleh sekitar 200 warga, berujung pada penangkapan terhadap 16 penduduk. Belakangan, 16 orang ini divonis pengadilan masing-masing dengan hukuman 10 bulan penjara.
Perlawanan warga berulang pada September 1998. Akibatnya, sebanyak 20 petani pekan-pekan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo. Mereka dituduh telah mencuri kelapa di lahan PD Banongan. Namun, tuduhan itu disangkal dengan keras. "Kami memanen jagung di tanah kami sendiri," ucap Mat Asan, 60 tahun. Belum lagi kasus 20 petani itu usai, empat warga lain telah pula diciduk polisi.
Para petani Situbondo ini berkeyakinan bahwa lahan yang mereka perjuangkan itu merupakan warisan nenek moyang mereka, yang menebangi hutan di situ pada 1912 untuk perkebunan tebu milik Belanda. Sejak saat itu, petani diperbolehkan menggarap tanah secara glebakan, yakni setelah tebu dipanen. Sistem yang lebih simpatik itu terhenti pada masa Jepang.
Belakangan, pada 1982, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo malah menyewakan 330 hektare dari lahan itu kepada CV Dason, dengan harga Rp 300 juta setahun. Sejak saat itu, para petani menyimpulkan sudah tertutup kemungkinan memperoleh kembali tanah mereka. Sebab, upaya untuk memperoleh hak kepemilikan tanah ataupun menempuh sistem bagi hasil ditolak pemerintah daerah.
Lain lagi nasib 400 petani di Kecamatan Wonosalam dan Bareng, Jombang, Jawa Timur. Mereka mengaku telah menggarap tanah bekas perkebunan Belanda sekitar 500 hektare sejak 1954. Lalu, pada 1975, dengan alasan untuk area penghijauan, pemerintah mengambil alih lahan tersebut. Ternyata, lahan itu kemudian dimiliki oleh perorangan dan perusahaan swasta. Berkali-kali petani memperjuangkan haknya, baik ke DPRD Jombang, ke Bupati Jombang, maupun ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta. Semua buntu, sia-sia. Bahkan, pada Oktober silam, sebanyak 28 petani ditangkap polisi. Mereka dituduh menyerobot lahan seluas 20 hektare milik Kepala Kepolisian Republik Indonesia Letnan Jendral Roesmanhadi di Desa Curahrejo, Kecamatan Bareng.
Kepala Kepolisian Resor Jombang Letkol Setiadi Purnomo mengaku tak bisa membenarkan tindakan warga. "Pak Roesmanhadi membeli sah tanah itu lewat lelang negara. Jadi, warga tak bisa begitu saja menanami lahan itu," kata Setiadi kepada Munib Rofiqi dari TEMPO.
Bekas lahan perkebunan tembakau zaman Belanda seluas 354 hektare di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumbersari, Jember, kini juga menjadi rebutan antara penduduk dan pihak TNI-AD. Para petani mengaku telah menggarap tanah itu sejak 1953. Pada 1964, pemerintah memutuskan tanah seluas 292 hektare yang terletak di lahan itu dijadikan obyek land reform (dibagi-bagikan untuk petani) dan seluas 62 hektare diberikan kepada TNI-AD.
Namun, prakteknya, TNI-AD menguasai lahan sampai seluas 200 hektare. Tanah itu kemudian disewakan kepada pengusaha tembakau dan tebu. Walhasil, konflik pun terjadi. Puncaknya, awal Desember lalu, ribuan petani membabat tanaman tebu di lahan seluas 137 hektare. Seorang petani, Inmargono, 40 tahun, ditangkap. Setelah rekan-rekannya berdemonstrasi ke Komando Distrik Militer (Kodim) Jember, barulah Inmargono dilepaskan.
Komandan Kodim Jember Letkol Subekti membantah tudingan bahwa instansinya merebut lahan petani. "Kami telah membebaskan tanah itu dan memberi ganti rugi kepada petani penggarap sejak tahun 1952, tahun 1954, dan tahun 1961," ujar Subekti.
Yang jelas, konflik tanah tidak hanya menyebabkan petani kehilangan tanah, tapi juga membuat mereka menanggung derita fisik. Buktinya, pada Senin akhir Desember lalu, enam petani penggarap tertembak peluru karet yang diberondongkan aparat keamanan ketika terjadi bentrokan antara karyawan PT Perkebunan Nusantaran II dan petani penggarap yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Batangkuis, Deliserdang, 47 kilometer dari Medan, Sumatra Utara.
Ironisnya, bentrokan itu hanya pengulangan belaka dari pertikaian yang tak kunjung selesai sejak puluhan tahun silam. Musababnya, setelah mengantongi hak guna usaha, pihak perkebunan menganggap berhak atas lahan seluas ratusan ribu hektare bekas perkebunan Belanda. Sedangkan BPRPI mengklaim bahwa tanah ulayat (hak adat Melayu) yang sejak dulu ada di tangan mereka tak bisa dikesampingkan begitu saja.
Agaknya, selain terhambat gara-gara country risk dan masalah utang swasta, pemulihan ekonomi juga bisa tersandung oleh masalah tanah rakyat, yang selama ini jauh dari asas keadilan sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Happy Sulistyadi, Zed Abidien (Surabaya), dan Bambang Soedjiartono (Medan)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini