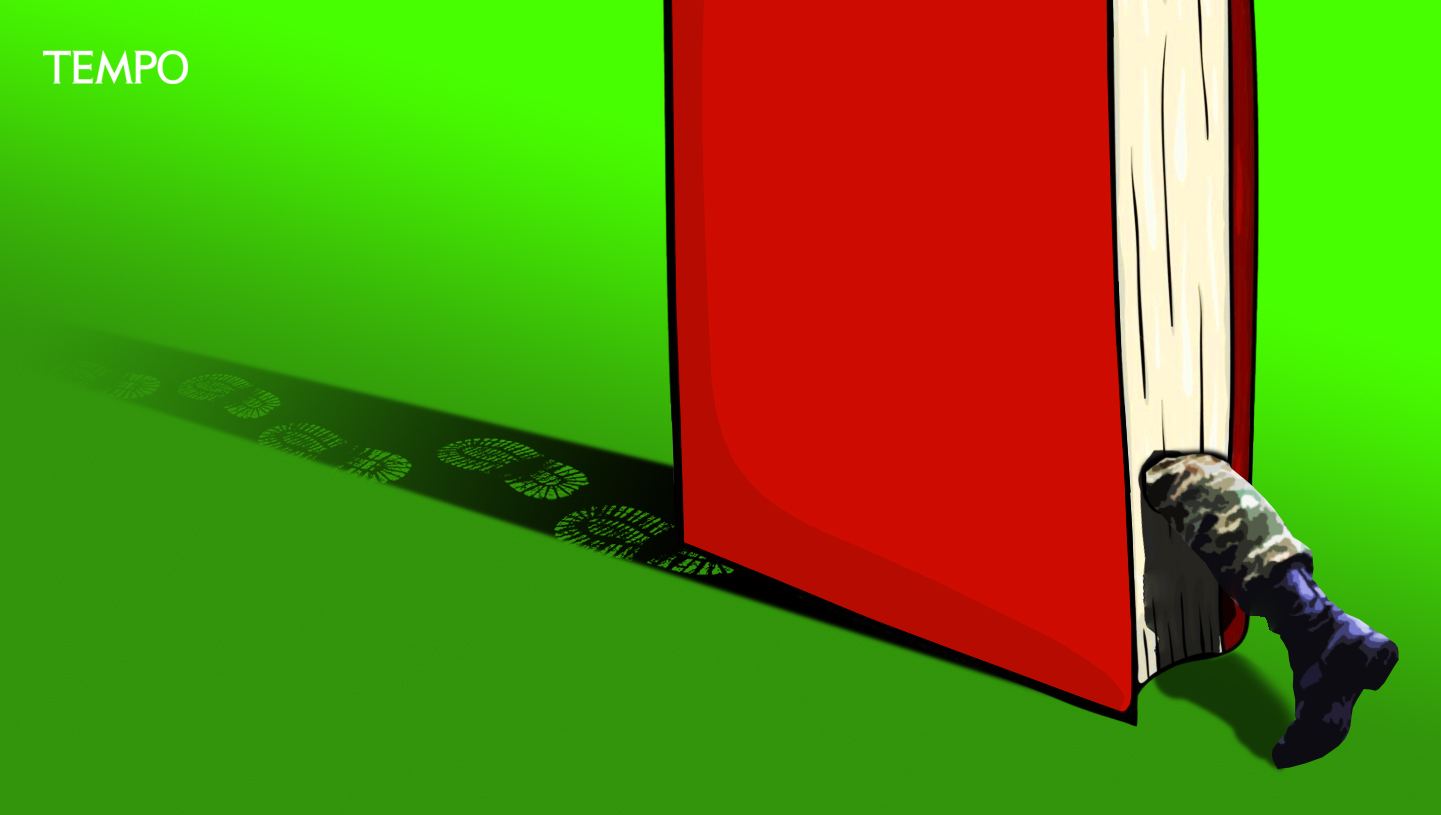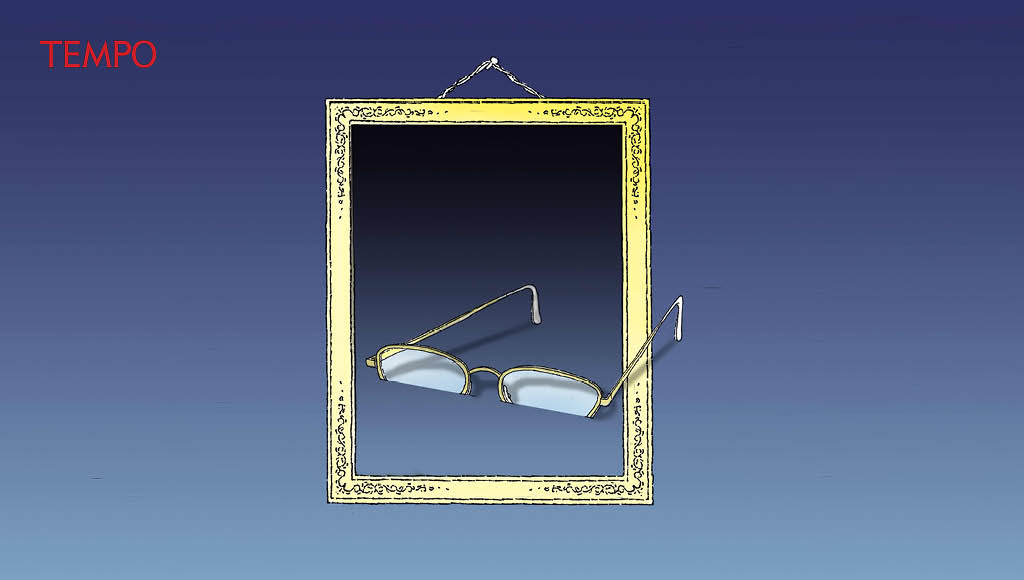Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setelah dua tahun tarik ulur, pemerintah akhirnya merestui perpanjangan operasi Freeport melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus hingga 2041. Bedanya dengan penambangan saat ini, Freeport tak sendiri. Dia ditemani oleh konsorsium BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium dan Pemerintah Papua yang menguasai 51 persen saham.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan dengan gegap gempita pada Jumat 21 Desember 2018. Seolah-olah, polemik penambangan oleh perusahaan asal AS itu selesai ketika sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Padahal, perpanjangan operasi justru menjadi mukadimah pemerintah merestui dosa yang lebih besar: kerusakan ekologis Papua (berikut pesisirnya) bagian barat daya dan Laut Arafura.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebagai perusahaan penambangan, Freeport tak lepas dari satu persoalan pelik yaitu pengelolaan limbah. Dalam mengelola tambang Grasberg, Freeport hanya mengambil sekitar 3 persen dari total material tambang, 97 persennya menjadi limbah atau dikenal dengan sebutan tailing/pasir sisa tambang. Jika mengacu ke target produksi puncak Freeport sebesar 300 ribu ton per hari, maka limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan mencapai 270 ribu ton per hari. Artinya, jika anda sudah berselancar di internet selama satu jam, pada saat yang sama Freeport sudah membuang limbahnya sebesar 11,25 ribu ton.
Jangan mengira ketika saya menulis pasir, muatannya sudah bersih. Material pertambangan justru membawa zat-zat mematikan bagi ekosistem. Audit lingkungan yang dilakukan oleh lembaga penilai independen, Parametrix (yang dibayar oleh Freeport), menyatakan setidaknya ada lima kandungan logam berat yang terkandung dalam limbah yaitu selenium, tembaga, arsen, mangan, timbal, dan kadmium. Ini belum termasuk risiko air asam sulfida dari batuan sisa pertambangan (acid rock drainage) yang turut hanyut dari gunung menuju laut.
Opsi Instan Mematikan
Pengelolaan limbah adalah salah satu hal yang menantang dalam pertambangan tembaga Freeport di Papua. Pasalnya, area pengerukan terletak di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut dan justru dikelilingi hutan lindung, danau, dan sungai-sungai.
Dari kerumitan kawasan tersebut, Freeport malah mengambil opsi mudah dan murah. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan, perusahaan sudah saja 253 juta ton limbah sepanjang 1974-1994 melalui sungai Aghwagon menuju sungai Ajkwa yang terletak di dataran rendah sejauh 70 km. Perusahaan awalnya hanya membuang limbah begitu saja di sungai. Tapi, karena banjir bandang yang terjadi pada 1994 turut membawa limpasan limbah dan menghancurkan rumah serta fasilitas umum, Freeport lalu membangun tanggul khusus penampungan limbah di sisi barat dan timur sungai Ajkwa(Ajkwa Deposition Area/ADA). Seiring bertambahnya produksi Freeport, kolam limbah semakin meluas. Dari awalnya sekitar 133 km2 , saat ini, ADA sudah dimodifikasi hingga meluas sepanjang 230 km2.
Tambang terdekat yang memiliki model pembuangan serupa adalah Ok Tedi yang dikelola BHP, perusahaan Australia. Ternyata, BHP memastikan metode ini merusak ekosistem Sungai Ok Tedi dan Sungai Fly sepanjang 1000 km, sekaligus mengganggu kehidupan 50 ribu penduduk sekitar. Perusahaan akhirnya hengkang dari tambang tersebut pada 2002.
Pemerintah sebenarnya sudah berulang kali meminta Freeport mengganti model pembuangan limbah dari sungai melalui pipa pada tahun 2017. Tapi Freeport menolak usulan itu karena tak layak secara teknis dan ekonomis. Penolakan ini aneh karena perusahaan sudah mengangkut bahan bakar minyak dan hasil tambang menggunakan sarana serupa.
Audit Merongrong, Freeport Berlalu
Dari sedemikian kompleksnya pengelolaan limbah berskala ekstra besar ini, audit menyeluruh baru dilaksanakan pemerintah pada tahun 2006. Pemeriksaan menyatakan pembuangan limbah Freeport melanggar kualitas air sungai yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dua tahun setelahnya, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar menerbitkan persyaratan pengelolaan limbah yang termuat dalam Keputusan Menteri Nomor 431/2008.
Namun kesalahan yang sama diulangi Freeport. Badan Pemeriksa Keuangan yang menghelat audit investigasi pada 2016 menemukan limbah Freeport sudah meluber dari sungai, muara, hingga laut. Pasalnya, kolam penampungan tak cukup menampung terjangan limbah. Terdapat perubahan bentang alam sebagai akibat tumpahan ini di area penampungan--termasuk di dalamnya hutan basah dan sungai(229 km). muara (220 km2) dan pesisir serta laut (1.243 km2). BPK juga menilai Keputusan Menteri 431/2008 sudah tak memadai dijadikan patokan pengelolaan limbah karena kerusakannya sudah terlalu parah. Berdasarkan riset Parametrix pada 2002, area yang tertutup limbah beserta ekosistemnya tak bisa tumbuh seperti sedia kala.
Satu dekade sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam risetnya juga menyatakan hal nyaris serupa terkait dampak pengelolaan limbah Freeport. Walhi menyatakan kandungan logam berat yang terkandung dalam limbah merusak keseimbangan rantai makanan. Bencana bermula dari tercemarnya tanaman seperti bayam air, cyperrus, kubis Cina, ubi jalar, dan daun singkong di dataran rendah. Sementara ada sekitar 700 burung, komodo, kangguru pohon, dan hewan lainnya yang menggantungkan hidupnya dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Peta citra satelit wilayah kerja Freeport Indonesia di Papua
Peta citra satelit wilayah kerja Freeport Indonesia di Papua
Kabar Baik yang Berumur Pendek
Setelah menerima audit BPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung terjun memeriksa di lapangan. Hasilnya, Freeport melakukan 48 pelanggaran. Meski begitu banyak dosa yang dilakukan perusahaan, pemerintah hanya mengganjarnya dengan sanksi administratif.
Pada awal 2017, penulis sempat berbincang dengan salah satu pejabat Kementerian Lingkungan yang menyatakan bakal mempertimbangkan menggugat Freeport secara perdata. Namun, saat itu penulis beranggapan: bagaimana mungkin gugatan ini akan dilayangkan sementara pada proses pelepasan 51 persen saham ke PT Inalum masih dalam proses negosiasi?
Kecurigaan penulis terbukti, hingga saat ini, Kementerian tak pernah menggugat apalagi menuntut perusahaan ke ranah pidana. Penanganan kasus jauh berbeda ketika Kementerian Lingkungan begitu galak menggugat PT Bumi Mekar Hijau yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dengan total permintaan ganti rugi Rp 7,8 triliun. Padahal, dalam kasus Freeport, BPK mencatat angka kerugian akibat eksosistem mencapai Rp 185 triliun!
Meski sanksi melempem, angin segar sempat berhembus dari Kementerian Lingkungan yang memperketat standar pengelolaan limbah Freeport dalam Keputusan Menteri Nomor 175 Tahun 2018. Beberapa isinya yang penting adalah memperketat angka retensi limbah, memperketat batas padatan (total padatan tersuspensi/total suspended solids) dalam kolam penampungan, sekaligus memindahkan titik pemantauan limbah.
Keputusan ini ditolak mentah-mentah oleh Kepala Eksekutif Freeport Richard Adkerson. Dalam suratnya ke Menteri Lingkungan Siti Nurbaya, Richard malah terang-terangan menyatakan kebijakan ini bermotif politis dan mengganggu jalannya negosiasi.
Lalu apakah Kementerian Lingkungan bertahan pada argumennya?
Ternyata tidak. Kementerian Lingkungan mencabut Keputusan Menteri 175/2018. Saat berbicara kepada publik, Menteri Siti juga tak menjelaskan alasannya. Sebagai ganti keputusan yang dicabut, kebijakan baru akan dibuat berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis yang saat ini tengah dibahas (bersama Freeport, tentunya).
Pengelolaan Limbah Harus Dirombak
Benih-benih harapan untuk perbaikan pengelolaan limbah Freeport gugur. Kini tinggal satu peluru yang tersisa: kajian strategis. Kajian ini menjadi vital karena pengerukan Freeport bakal massif melalui penambangan bawah tanah. Hingga akhir masa operasinya pada 2041, Freeport akan membuang 3 miliar ton limbah (Walhi, 2006). Volume segini setara dengan 909 kali lipat dari total kebutuhan pasir untuk mereklamasi 13 pulau di laut utara Jakarta.
Penyusunan kajian strategis mesti dikawal. Pemerintah semestinya tak membolehkan Freeport menggunakan sungai sebagai sarana pengangkutan dan penyimpanan limbah. Sebab, terbukti cara ini justru merusak. Freeport harus menggunakan pipa--atau cara lain yang tak merusak ekosistem--untuk mengangkut limbah sisa tambang.
Pemerintah juga harus menerapkan standar yang ketat untuk baku mutu limbah penambangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu, limbah yang ada juga harus dimanfaatkan dalam bentuk lain seperti material bahan bangunan supaya tak terbuang begitu saja.
Freeport pun tak boleh ingkar merehabilitasi kawasan yang sudah rusak. Hingga saat ini, tak ada satu pun tuntutan dari pemerintah supaya perusahaan melaksanakan hal itu. Berapa pun biayanya, itu adalah ongkos yang semestinya ditanggung perusahaan atas dosa yang telah dilakukan sejak 51 tahun lalu. Jika hal ini dibiarkan, pencaplokan Freeport justru menjadi tiket pemerintah memperluas bencana di Papua. (*)
Sumber Dokumen:
- Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Tahun 2013 Sampai dengan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan, 2017.
- Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport-Rio Tinto di Papua, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2006.
- Environmental Risk Assessment PT Freeport Indonesia, Parametrix Inc., 2002.
- Securities and Exchange Commission Annual Report Freeport McMoran Inc Form 10-K, Securites and Exchange Commission, 2015.