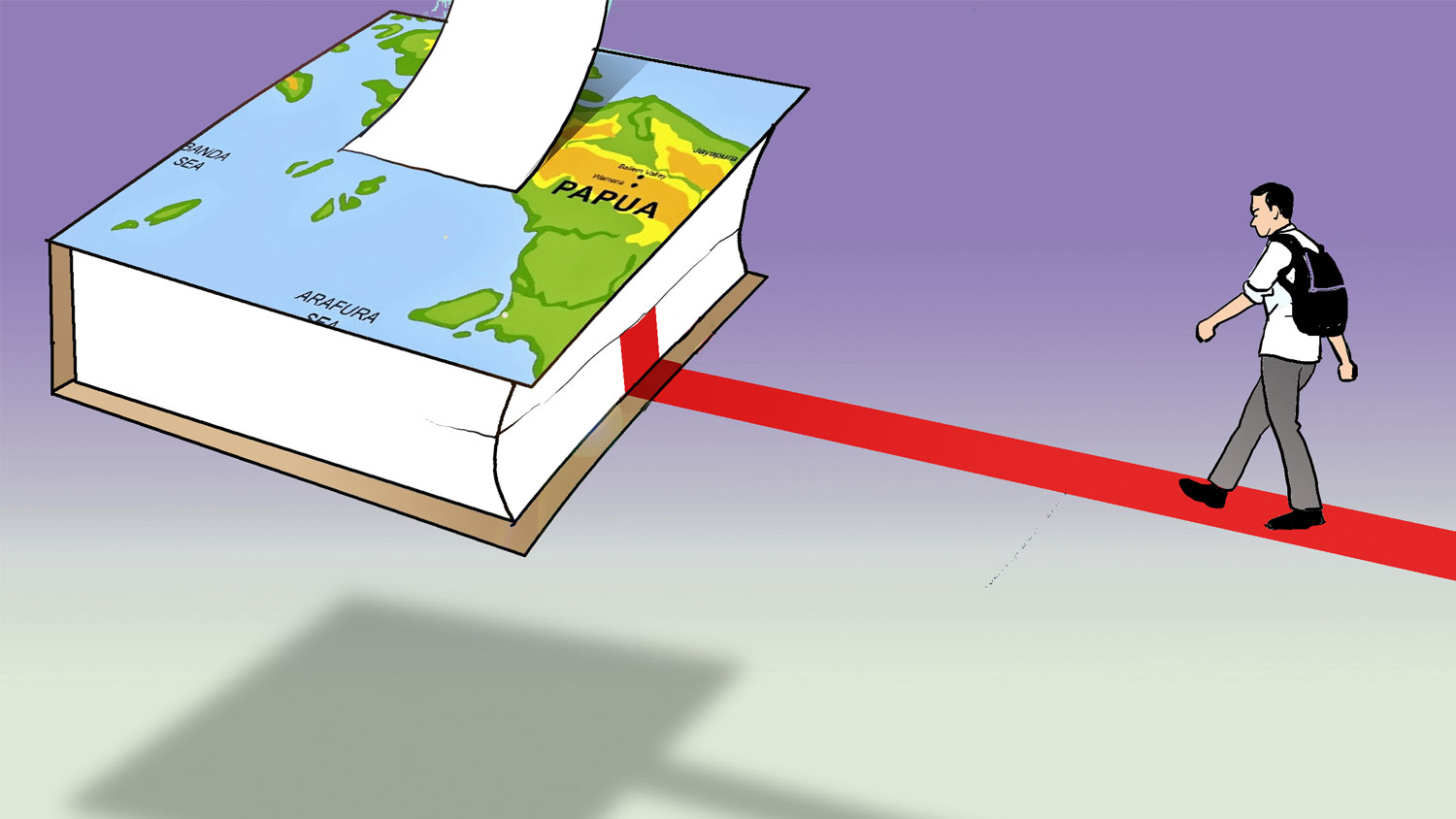Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apa yang diharapkan dari Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang baru di Papua? Undang-undang itu direvisi dengan cara basi, tidak demokratis, dan mengabaikan suara orang Papua. Sementara itu, isinya mengesampingkan hal-hal yang substantif, terutama hak berpolitik dan penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia di provinsi paling timur itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Joko Widodo mengusulkan perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua tersebut pada akhir 2020. Pemerintah bersama DPR merampungkan revisi undang-undang tersebut pada Senin lalu, 12 Juli 2021. Total ada 20 pasal yang diubah. Tiga pasal di antaranya merupakan usul pemerintah, yakni Pasal 1, Pasal 34, dan Pasal 76 tentang peningkatan dana otonomi khusus serta pemekaran wilayah daerah. DPR menambahkan perubahan 17 pasal lainnya, dengan alasan persoalan di Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui tiga pasal tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam Pasal 34 UU Otsus yang baru, DPR menyetujui usul peningkatan jumlah anggaran dana otonomi khusus Papua dari 2 persen dana alokasi umum nasional menjadi 2,25 persen. Hal itu patut disyukuri. Namun persoalan terbesar dana Otsus sebenarnya ada pada pemanfaatannya. Selama ini, setelah 20 tahun dikucurkan, tak tampak dampak signifikan dana Otsus bagi kesejahteraan masyarakat. Dua provinsi di Papua—dengan jumlah penduduk hanya 5 juta jiwa—masih menjadi provinsi termiskin di Indonesia.
Adanya Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3) seperti disebutkan dalam Pasal 68A bukanlah obat manjur untuk menyelesaikan persoalan pemerataan pembangunan itu. Meski BKP3 dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua, sulit untuk mengharapkan badan ini dapat bekerja dengan baik jika tak memperhatikan keinginan masyarakat Papua. Alih-alih, BKP3, yang dipimpin Wakil Presiden dan beranggotakan sejumlah menteri serta akan menempatkan sekretariatnya di Papua, akan terlihat sebagai institusi untuk memastikan dilaksanakannya agenda pusat.
Salah satu agenda pusat itu—yang sukar dibantah—adalah pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi. Hal itu terlihat dari perubahan mendasar Pasal 76. Dalam pasal yang baru, pemekaran provinsi di Papua, selain atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua (DPRP), dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR tanpa melalui tahap daerah persiapan. Jelas sekali, pasal baru ini merupakan langkah mundur dalam pengakuan hak-hak rakyat Papua untuk menentukan pembangunannya sendiri.
UU Otsus baru itu juga mengubah aturan mengenai hak berpolitik masyarakat Papua. DPR mencabut Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2001 tentang partai politik lokal dan menggantinya dengan keanggotaan orang asli Papua di DPR Papua dan DPR kabupaten/kota, mengadopsi Putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019. Padahal partai politik lokal telah menjadi simbol kekhususan daerah otonom, sebagaimana di Aceh. Papua sendiri sudah lama bersiap menyambut kehadiran partai politik lokal ini. DPRP, gubernur, dan MRP sudah menyetujui peraturan daerah khusus tentang parpol lokal sejak 2016. Namun Kementerian Dalam Negeri tak kunjung menyetujuinya.
Dengan daftar panjang catatan di atas, tidak mudah untuk percaya bahwa revisi UU Otsus ditujukan untuk memuliakan orang Papua. MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sudah menggugat Presiden Joko Widodo serta DPR atas rencana revisi yang dinilai mengabaikan aspirasi orang asli Papua ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi, belum sempat revisi itu disidangkan, DPR telah lebih dulu mengesahkannya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo