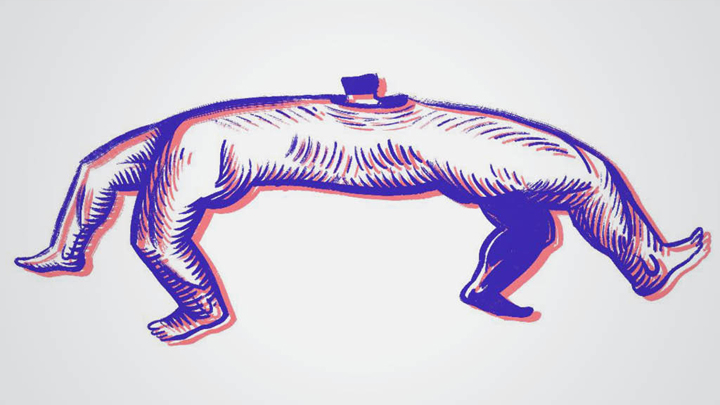Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SURVEI Transparansi Internasional pada 2017 menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat, birokrasi, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga paling korup. Dua tahun kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun ranking koruptor yang menempatkan DPR dan DPRD sebagai lembaga yang anggotanya paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi. Sepanjang 2014-2019, sebanyak 255 anggota DPR dan DPRD ditetapkan sebagai tersangka.
Di bawahnya, eksekutif atau pemerintah dengan jumlah tersangka 203 orang—merentang dari pejabat eselon III hingga eselon I. Peringkat ketiga ditempati wali kota dan bupati atau wakilnya sebanyak 108 tersangka. Peringkat keempat menteri atau kepala lembaga sebanyak 27 tersangka (Jatimtimes.com, 17 Juli 2019).
Dari ranking KPK pada 2019 itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa politikus partai politik merupakan aktor utama korupsi di Indonesia. Kasus seperti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga suap komisioner Komisi Pemilihan Umum yang belum lama terjadi, yang juga melibatkan politikus partai, memperjelas kekhawatiran bahwa politik dan partai politik kita makin identik dengan korupsi.
Indonesia pernah menjadi salah satu negara paling korup sedunia. Pada tahun-tahun terakhir menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto, Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup ketiga di dunia di bawah Kamerun dan Nigeria (Dwight Y. King, Journal of International Affairs No. 3, 2000). King menyebutkan dua gejala yang menjadi basis korupsi pada era Orde Baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertama, kekuasaan neo-patrimonial. Kekuasaan neo-patrimonial adalah kekuasaan politik yang diturunkan dari kemampuan penguasa untuk memenangi dan mempertahankan loyalitas serta dukungan dari elemen-elemen terpenting dalam kekuasaan dan masyarakat melalui pemuasan aspirasi yang bersifat material. Kekuasaan neo-patrimonial diikuti dengan pengempisan politik akar rumput yang dikombinasikan dengan upaya menutup kompetisi politik di lingkungan elite secara ketat supaya perbedaan politik tidak mengganggu basis kekuasaan.
Struktur patrimonial inilah yang kemudian ikut melahirkan basis kedua korupsi di Indonesia, yakni membesarnya kekuasaan negara yang ditandai, salah satunya, dengan melebarnya sayap kekuasaan birokrasi serta operasi alat dan aparatur kekuasaan negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Negara kemudian memiliki kekuasaan untuk mengendalikan bisnis serta mengatur konsesi dan fasilitas. Negara menguasai pelbagai lini industri, dari pertambangan, energi, hingga finansial. Kompetisi politik antarelite tidak melibatkan gagasan dan kebijakan, melainkan mengandalkan kekuasaan dan distribusi rente dan patronase.
Di sinilah peran partai politik penguasa pada waktu itu, Golkar, berfungsi sebagai salah satu mesin distribusi kekuasaan patronase terbesar. Dengan sistem kekuasaan yang demikian luas, korupsi dalam rezim Orde Baru merupakan “state enterprise”. Korupsi inheren dalam sistem kekuasaan yang terpusat.
Dalam sistem otoritarian, korupsi dan politik tak bisa dipisahkan. Seperti kata Montesquieu, korupsi hanya terjadi di dalam republik tapi tidak pada rezim despotis parce qu’il est corrompu par sa nature—karena sifatnya yang korup. Bukan karena rezim despotis itu bersih, justru karena despotisme sendiri sudah korup secara inheren (Herry Priyono, 2014). Itu sebabnya gerakan reformasi yang menjatuhkan Soeharto juga menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Setelah Indonesia memasuki era pasca-Soeharto, struktur negara neo-patrimonial dan sentralisme kekuasaan negara berubah. Meski demikian, sebagaimana dikatakan Hadiz (2010), sementara sentralisme kekuasaan memudar, elemen-elemen di dalamnya merekonstitusi diri dalam bentuk yang lebih cair, lentur, dan saling bersaing memperebutkan kepentingan dan patronase yang merentang hingga ke tingkat lokal. Dalam konteks ini, perluasan sistem kepartaian, termasuk korupsi di dalamnya, tumbuh.
Seiring dengan optimisme reformasi, sempat muncul pandangan yang mengatakan perluasan sistem kepartaian di Indonesia dipicu terutama oleh dua faktor. Pertama, pemilihan presiden secara langsung yang menghadirkan politik yang lebih personal dan politik kepartaian dengan basis ketokohan. Kedua, munculnya isu dan aspirasi baru dalam masyarakat pasca-Soeharto, terutama isu pemberantasan korupsi. (Jungug Choi, Asian Survey No. 4, 2010).
Namun, seiring dengan menguatnya politik patronase dan korupsi, terutama di tingkat lokal, argumen bahwa perluasan partai dalam masyarakat dipicu aspirasi antikorupsi menjadi terbantahkan. Sistem partai meluas pertama-tama bukan akibat dari aspirasi antikorupsi dan politik ketokohan, melainkan karena elite dan pemilih menemukan sejenis metode baru dalam mengupayakan dan memelihara akses ke sumber-sumber material, termasuk rente dan patronase. Dengan kata lain, perluasan partai yang menempel dengan politik lokal menghadirkan juga gejala desentralisasi korupsi di Indonesia (Nathan W. Allen, Pacific Affairs Vol. 87 No. 2, Juni 2014).
Peluang dan perburuan rente ini memainkan peran yang sangat penting dalam perubahan perilaku elite dan pemilih. Ia memperluas locus aktivitas politik yang semula terpusat pada skala nasional menjadi merentang hingga ke level lokal. Di arena-arena tempat negara memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi, kehidupan personal akan sangat ditentukan oleh mereka yang mengendalikan sektor publik. Kondisi ini memberikan insentif yang merangsang elite untuk terjun ke kancah politik. Pada saat yang sama, bagi massa pemilih, tercipta insentif setiap kali mereka berkoneksi dengan orang-orang yang berada di kekuasaan, minimal karena ikut kecipratan akses sumber daya negara.
Allen menegaskan, sistem desentralisasi politik yang semula dimaksudkan untuk memberikan sarana demokrasi yang lebih luas kepada rakyat pada akhirnya tidak menghasilkan kontrol dan akuntabilitas untuk menghapus KKN, tapi malah memperluas korupsi ke tingkat lokal. Logika patronase dan pencarian rente ini ikut membentuk motif perluasan partai, termasuk relasi-relasi yang lebih mikro dan prosedural di dalamnya. Di mana ada sumber daya yang gemuk, di situ partai berupaya makin kokoh bercokol. Inilah yang kiranya menjadi penyebab banyaknya jumlah politikus partai berurusan dengan KPK.
Di level nasional, munculnya pemilihan presiden langsung dan pemilihan legislatif yang terpisah menghasilkan semacam legitimasi ganda dalam desain ketatanegaraan di Indonesia: kekuasaan presidensial di satu sisi dan kekuasaan DPR di sisi yang lain. Meski dalam sistem presidensialisme presiden itu kuat dan merupakan primus solus, anggota DPR yang dipilih langsung menghasilkan klaim kekuasaan politis yang juga kokoh. Kontraksi antara eksekutif dan legislatif dalam dua posisi ini menghasilkan ketegangan sekaligus simbiosis mutualisme yang unik, yang sisi gelapnya tampak dalam kasus-kasus korupsi kebijakan publik. Inilah yang terjadi dalam perkara Hambalang, e-KTP, impor daging sapi, hingga impor bawang putih—bahwa korupsi selalu melibatkan tiga pihak: politikus, pejabat kementerian/birokrasi, dan pengusaha.
Kini pemilihan presiden secara langsung sudah dilakukan secara serentak dengan pemilihan legislatif. Namun, karena partai tetap memainkan peran penting dalam pengajuan calon presiden, politikus masih memegang peran penting dalam penentuan distribusi patronase dan pelbagai korupsi kebijakan publik. Melihat kasus-kasus tadi, kita khawatir korupsi akan berevolusi dan makin memiliki ciri institusional dalam sistem politik dan kepartaian. Korupsi menjadi inheren dan identik dengan institusi politik dan kehidupan partai (Herry Priyono, 2014). Ini akan menjadi kerusakan terbesar dalam sebuah republik. Mengapa?
Pada mulanya, sebagaimana dikemukakan para moralis dari Aristoteles hingga Hatta, politik adalah wahana untuk mencapai dignitas dalam keutamaan umum. Orang memasuki politik sebagai tindakan luhur dan terhormat. Moralitas politik inilah yang membuat para pendiri bangsa memberikan nama “republik” untuk Indonesia—sesuai dengan asal katanya, “res publica”, yang berarti hal yang publik. Dengan itu, para pendiri bangsa menegaskan prinsip bahwa hidup dalam republik berarti hidup dalam tujuan untuk mendahulukan keutamaan umum dan dignitas.
Pandangan moral ini sempat hidup pada elite Indonesia di masa lalu. Kini, korupsi secara brutal telah mengubah makna intrinsik politik dan mengubah esensi serta fungsi pranata politik menjadi alat untuk mengejar kepentingan privat. Demokrasi telah menumbuhkan pelbagai institusi politik yang penting di Indonesia saat ini, tapi politik dalam pengertian intrinsik justru makin luntur. Kita menemukan demokrasi, tapi kehilangan republik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo