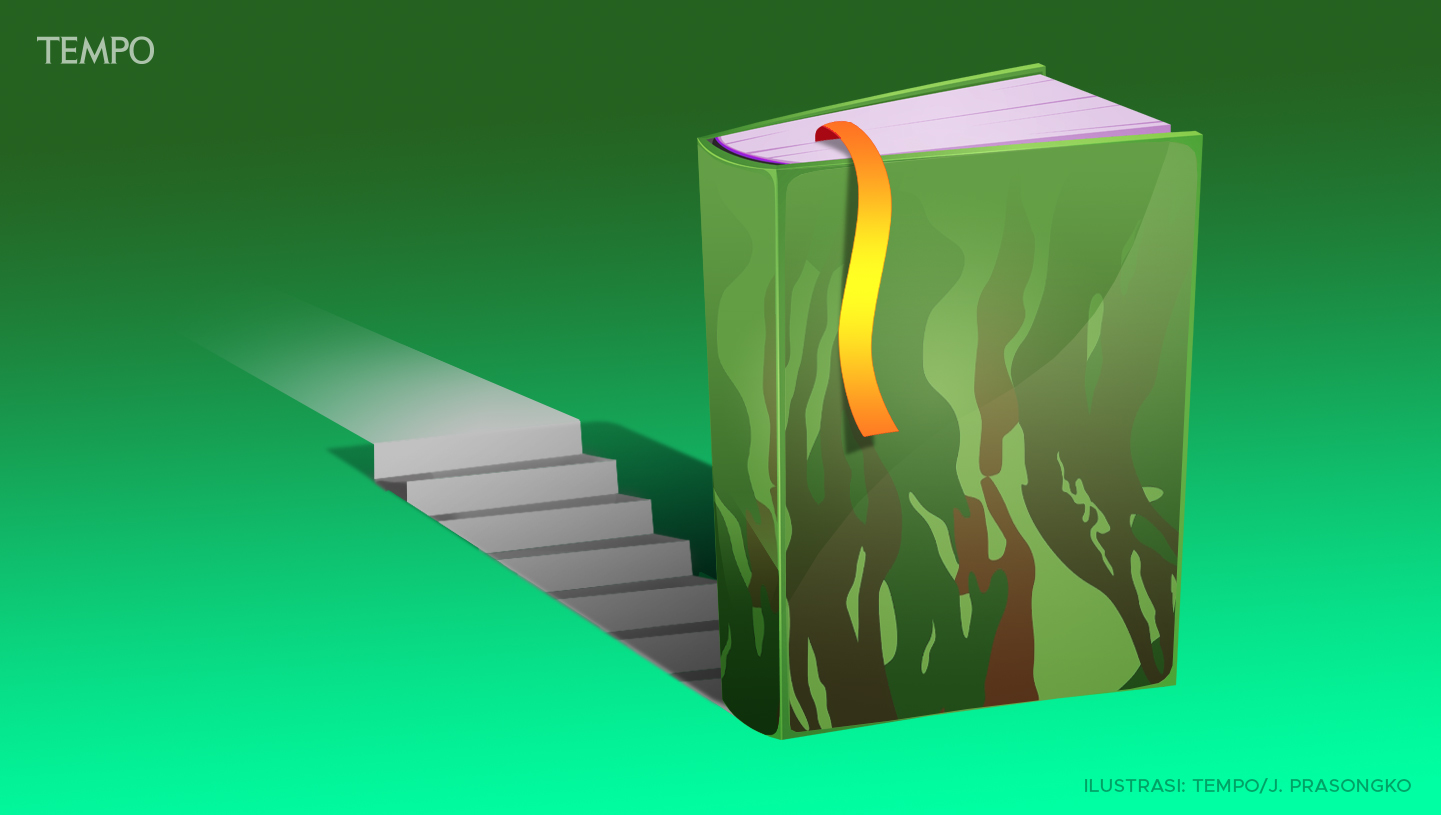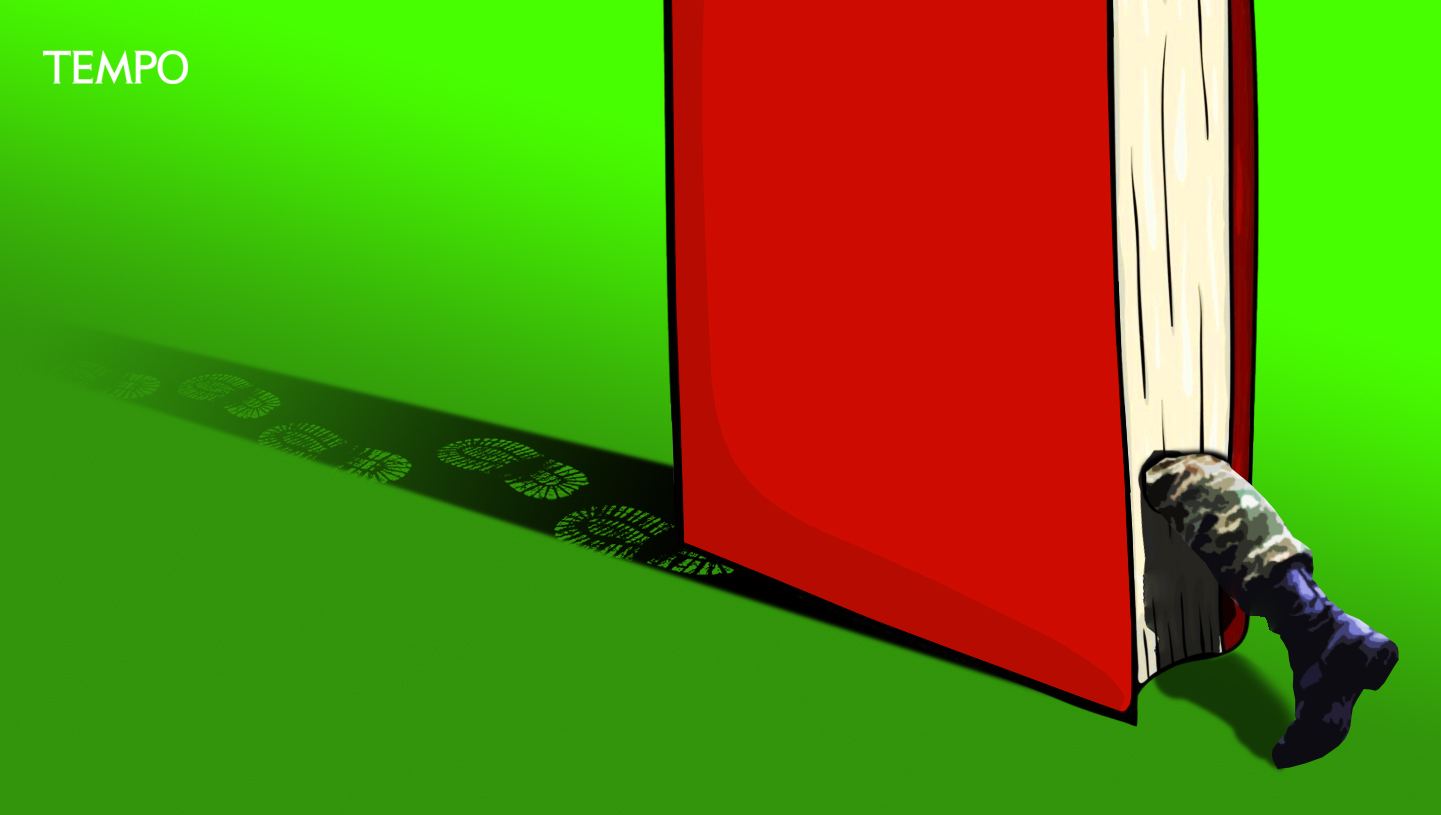Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Miko Ginting
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Vonis terhadap Meliana, perempuan yang dihukum 1,5 tahun penjara karena meminta suara azan dikecilkan di Tanjung Balai, memperpanjang rentetan korban delik penodaan agama. Menurut Setara Institute dan SAFENet, pada era Orde Baru terdapat 10 kasus yang diproses secara hukum. Setelah era Reformasi, penerapan delik itu melonjak sangat tajam: 89 kasus pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan 25 kasus pada masa Joko Widodo. Dari semua kasus itu, menurut Institute for Criminal Justice Reform, hanya satu kasus pada 1977 yang terdakwanya diputus tidak bersalah karena melakukannya di bawah tekanan dan ancaman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Apakah delik ini bermasalah karena kelonggaran rumusan norma atau penafsiran dalam praktik yang lari dari semangat delik itu? Sulit untuk menunjuk satu dari dua aspek itu sebagai biang keroknya. Rumusan yang tidak ketat dan penafsiran penegak hukum dan hakim yang melebar sama-sama punya peran.
Dulu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur soal delik penodaan agama. Pasal 156 KUHP hanya mengatur soal penghinaan terhadap golongan penduduk. Dalam perkembangan praktik peradilan, delik penodaan agama kemudian mulai dikenal. Selanjutnya, konfigurasi dan tekanan politik serta obsesi mengkonsolidasi kekuatan politik yang ada (demokrasi terpimpin) membuat Presiden Sukarno menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Konteks dan latar historis ini juga tertangkap melalui hasil Seminar Hukum Nasional I pada 1963. Salah satu rekomendasinya adalah perlu dipertimbangkan adanya hukum pidana (delik) agama. Jadi, sulit untuk meletakkan delik penodaan agama sebagai semata-mata sarana perlindungan agama.
PNPS 1965 itu memuat beberapa perbuatan, yaitu pertama, larangan melakukan penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama yang diakui secara sengaja di muka umum. Mekanismenya disyaratkan harus melalui peringatan dalam keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.
Kedua, larangan mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap yang dianut (baca: diakui pemerintah) di Indonesia untuk dengan sengaja di muka umum. Ketiga, larangan mengeluarkan perasaan atau perbuatan supaya orang tidak menganut agama apa pun juga dengan sengaja di muka umum. Kedua pasal ini yang kemudian dimasukkan ke KUHP melalui metode penyisipan menjadi Pasal 156a.
Delik ini menjadi permasalahan karena ukuran terpenuhinya delik itu bukan pada sifat perbuatan, melainkan faktor eksternal, seperti ketersinggungan dari mayoritas atau kelompok organisasi keagamaan. Ukuran perbuatan itu seharusnya berada pada sifat perbuatan itu sendiri. Misalkan, dalam penjelasan PNPS 1965 disebutkan bahwa perbuatan kategori kedua haruslah bersifat semata-mata ditujukan kepada niat untuk memusuhi dan menghina. Dengan ukuran ini, banyak kasus, termasuk Meliana, seharusnya tidak berujung pada penghukuman.
Namun, menggeser peralihan dari ketersinggungan mayoritas menjadi interpretasi penegak hukum dan hakim juga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Selain tidak kedap dari subyektivitas, faktor desakan masyarakat atau organisasi agama yang menstimulus rasa aman penegak hukum dan hakim juga penting untuk ditimbang.
Ke depan, delik penodaan agama seharusnya bisa dipertimbangkan kembali jika Rancangan KUHP memang diposisikan sebagai sarana evaluasi hukum pidana materiil. Kenyataannya, Rancangan KUHP justru memperburuk rumusan yang ada. Setidaknya ada dua unsur penting yang mendorong hal itu, yaitu hilangnya unsur "dengan sengaja" dan dimasukkannya unsur "penghinaan". Kedua hal itu berdampak pada semakin luas dan beralihnya penafsiran terhadap delik tersebut. Apabila unsur "dengan sengaja" dihilangkan, apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak menjadi tak penting sepanjang perbuatannya terpenuhi. Selain itu, penentuan perbuatannya meluas karena memasukkan pengertian "penghinaan" yang terkesan semakin subyektif.
Presiden Joko Widodo seharusnya mengambil posisi strategis, baik terhadap delik maupun kasus-kasus penodaan agama. Ia punya otoritas untuk mendorong evaluasi Rancangan KUHP atau merevisi pedoman penuntutan dalam kasus delik penodaan agama. Secara pribadi, Kaesang, putra Presiden Joko Widodo, pun pernah hampir menjadi "korban" dari delik penodaan agama ini.