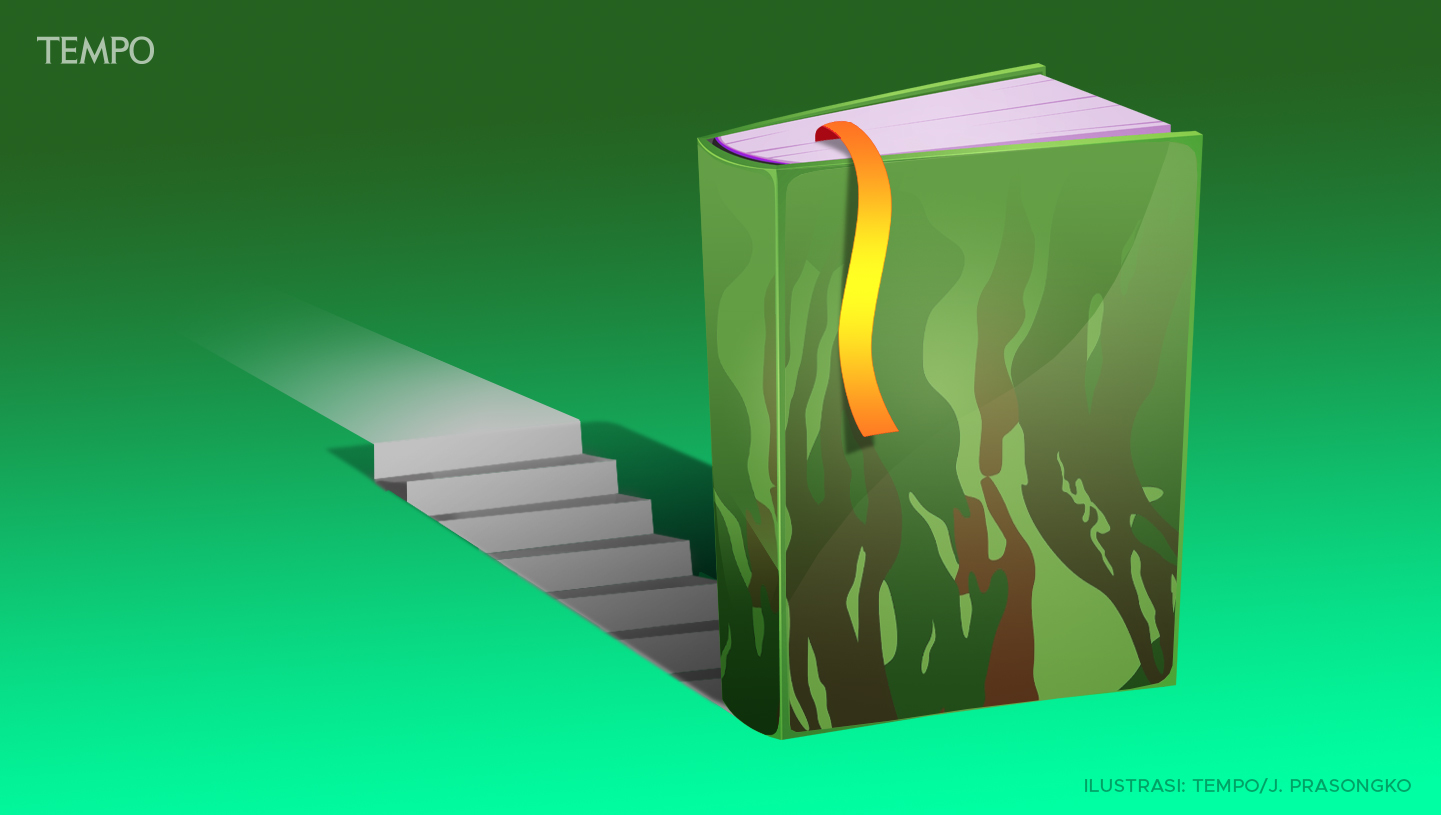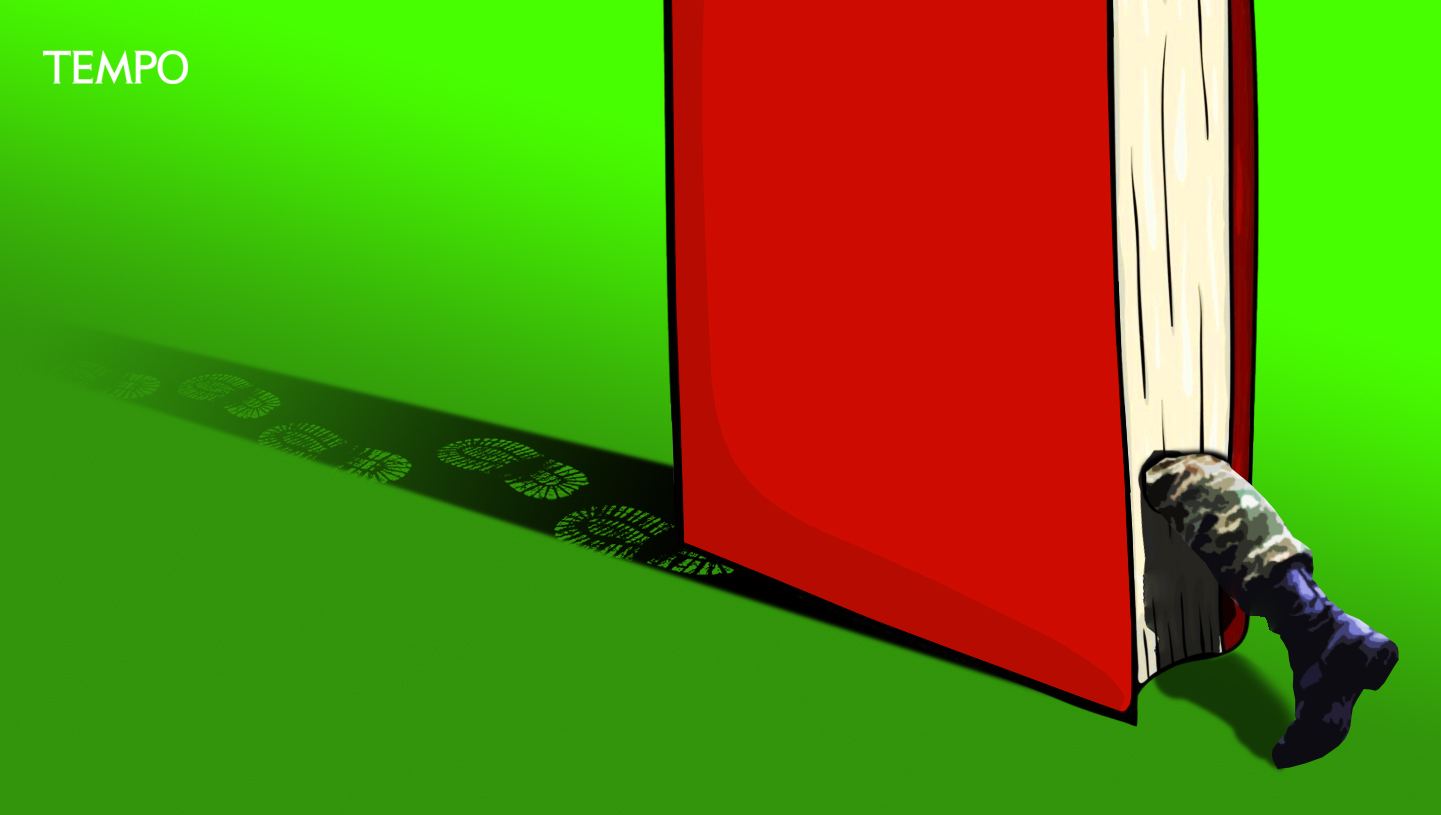Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Miko Ginting
Pengajar Hukum Pidana di STH Indonesia Jentera
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mahkamah Agung telah menjatuhkan vonis kepada Meiliana, ibu yang didakwa dengan delik penodaan agama, dengan 18 bulan pidana penjara. Sejak awal kasus ini mendapat sorotan publik karena dekat sekali dengan perasaan keadilan masyarakat, berputar dalam relasi mayoritas-minoritas kehidupan sosial beragama, pembuktian yang dianggap lemah, hingga perdebatan soal apakah ada keperluan untuk mempertahankan delik ini sebagai norma hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penafsiran hakim pada tingkat kasasi akan sangat menarik untuk dibahas. Namun, hingga hari ini, putusan tersebut belum dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, belum dapat dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Terlepas dari hal itu, persoalan norma dalam Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak kalah menariknya untuk dibahas dengan satu pertanyaan penting: jika delik itu masih eksis dalam hukum positif Indonesia, apa yang harus dilakukan agar penerapannya berjalan dalam koridor yang tepat?
Suatu norma hukum, terutama apabila membatasi perilaku dengan mencantumkan sanksi pidana sebagai sebuah konsekuensi, seharusnya dirumuskan secara tertulis (lex scripta), secara pasti/jelas (lex certa), dan secara ketat (lex stricta). Ketiga prinsip ini adalah prinsip yang fundamental dalam negara hukum. Meski demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa ada, bahkan banyak, norma hukum yang dirumuskan secara longgar dan memunculkan banyak penafsiran sehingga penerapannya berdampak secara negatif pada perlindungan hak individu.
Salah satunya adalah delik penodaan agama yang sampai saat ini masih berlaku melalui KUHP. Begitu juga dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, yang menyatakan delik tersebut konstitusional atau tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Ke depan, tampaknya perumus rancangan KUHP akan tetap mempertahankan delik ini. Dalam situasi dilematis ini, gerbang terakhir untuk memastikan penerapannya berjalan secara tepat adalah pada pertimbangan hakim yang mengadili kasus-kasus yang terkait "penodaan agama" ini.
Salah satu kajian penting dan lengkap serta dapat dijadikan acuan bagi hakim adalah Penafsiran terhadap Pasal 156 huruf a KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia). Kajian yang disusun oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Peradilan (LeIP) itu tidak hanya secara lengkap merumuskan berbagai perangkat analisis tapi juga secara mendalam menyediakan acuan bagi hakim untuk mendudukkan kembali penafsiran (reinterpretasi) yang tepat perihal delik penodaan agama.
Ada beberapa unsur yang perlu menjadi acuan hakim. Pertama, adanya unsur kesengajaan. Unsur ini harus diartikan kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk) yang dalam delik ini harus diartikan bahwa perbuatan itu harus semata-mata diniatkan atau dimaksudkan untuk menghina atau menodai suatu agama. Kedua, unsur di muka umum. Unsur tersebut harus diartikan bahwa perbuatan itu dilakukan secara lisan atau secara fisik.
Ketiga, unsur permusuhan. Unsur ini harus mengandung kebencian yang mendalam terhadap suatu agama, bukan sekadar keyakinan atau pandangan yang berbeda. Keempat, unsur penodaan agama dan penyalahgunaan agama. Sejalan dengan unsur sebelumnya, unsur ini seharusnya diartikan bukan sekadar pandangan atau keyakinan yang berbeda, tapi juga harus mengandung unsur permusuhan dan menghina secara obyektif.
Dalam kerangka ini, salah satu parameter penting adalah siapa yang akan menentukan suatu tindakan atau ucapan lisan memenuhi unsur permusuhan sebagai dasar penodaan agama? Jika mendasarkan pada keterangan ahli, tentu sama sekali tidak tepat. Jika mendasarkan pada ketersinggungan masyarakat, maka bias dan persepsi mayoritas-minoritas kemungkinan besar akan berperan besar. Di titik ini, kembali peran hakim menjadi penting untuk memeriksa apakah benar suatu perbuatan maupun ucapan lisan mengandung unsur permusuhan untuk menodai agama secara obyektif.
Persoalannya, hal ini hanya dapat dipenuhi jika hakim dapat mengesampingkan bias dan posisi pribadinya. Sebaliknya, hakim harus dapat menempatkan dirinya pada posisi yang independen dan imparsial secara obyektif. Hal ini lebih sulit karena berada di tengah dorongan pandangan pribadi dan tekanan massa yang sering kali ditemui dalam kasus-kasus seperti penodaan agama. Solusi ini tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan, tapi mungkin inilah hal yang bisa dilakukan saat ini, terutama di tengah upaya untuk tidak mempertahankan delik penodaan agama ini dalam negara yang demokratis.