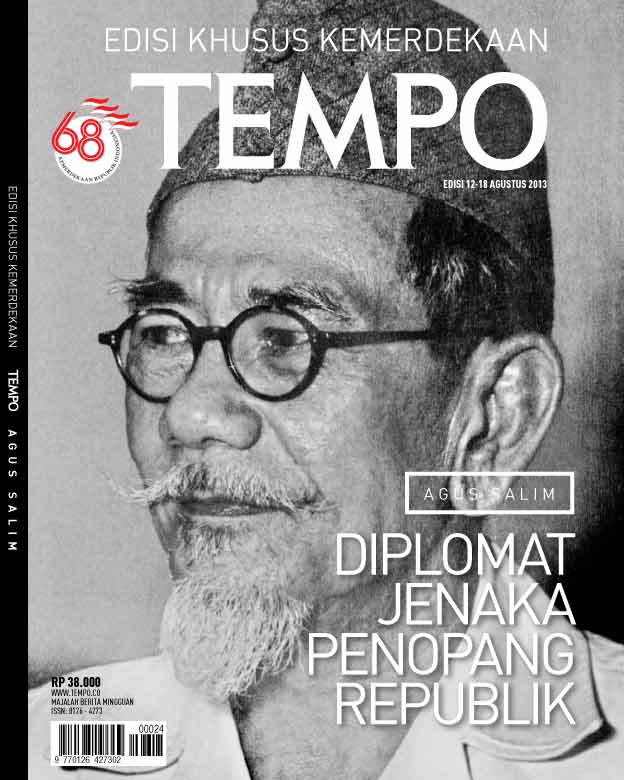Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Demokrasi adalah sebuah teater dan antiteater. Ia dimulai dengan penolakan terhadap panggung, pajangan, gerak, permainan cahaya, pilihan kostum yang dipergunakan raja (di Eropa: juga Gereja) untuk membangkitkan imajinasi tentang kekuasaan yang mempesona dan mencengkam.
Dalam naskah Jawa ada Serat Mahasastata yang mengkodifikasikan tata cara dan tata busana kraton yang harus dipatuhi sebagaimana kewibawaan Raja dipatuhi. Di balairung, di sitihinggil, baginda, punggawa, dan abdi adalah sosok-sosok yang berperan dan disaksikan, untuk dikagumi, setidaknya dinilai.
Peran panggung, tempat upacara dipertunjukkan, begitu penting dalam kekuasaan di masa silam, hingga Clifford Geertz, dalam satu studi tentang kerajaan Bali abad ke-19 menyimpulkan, "Power served pomp, not pomp power". Kekuasaan itulah yang melayani kemegahan upacara, kata Geertz, dan bukan sebaliknya.
Saya tak yakin kesimpulan dalam Negara, The Theater State in 19th Century Bali itu benar. Tapi Geertz bisa dengan hidup melukiskan pertautan upacara ngaben raja-raja Bali dengan kemegahan dan kelanggengan derajat mereka:
"Seluruh upacara merupakan demonstrasi yang diulangi dengan beribu-ribu cara, dengan beribu-ribu citra, tentang betapa digdayanya hierarki menghadapi kekuatan yang paling ampuh dan membuat semua melata -- Maut, anarki, gelora hati, api. 'Raja telah dibumihanguskan! Hidup derajatnya!"
Itu adegan dan kesan di abad lalu, tentu saja -- yang kini umumnya tak diakui lagi. Perubahan dalam sejarah telah merontokkan aura dari pentas macam itu. Beberapa tahun yang lalu saya ikut upacara ngaben keluarga sebuah puri besar di Bali. Upacara itu masih tetap spektakuler meskipun saya tak bisa mendapat kesan bahwa inilah bagian dari yang disebut Geertz "teater metafisik." Seorang anggota keluarga puri berkata: "Kami hanya bisa menyelenggarakan ngaben yang besar jika rakyat ikut membantu puri. Kami berutang budi kepada para petani itu."
Raja pergi dan raja datang, tapi jelas makin merasuk sebuah kecenderungan baru: para petani Bali itu, dan orang kebanyakan di manapun di negeri ini, telah mengenal sumber-sumber kekuasaan lain, pembawa aura lain, yang dirayakan tiap kali: Republik Indonesia. Yang gemerlap dalam "negara teater" Geertz telah dibongkar sebagai hanya "sandiwara" -- sebuah kata yang mengandung cemooh atau sikap tak percaya.
Di zaman ini, teater,"sandiwara" itu, dibenturkan ke "realitas".
Bukan kebetulan jika semangat menegaskan "realitas" hidup sehari-hari datang berbareng dengan revolusi demokratik. Dalam sejarah kesenian, semangat itu diwakili "Realisme". Di Indonesia, misalnya, Pelukis S. Soedjojono menyuarakan semangat "Realisme" sebagai bagian dari "Revolusi Agustus". Di Prancis abad ke-19: Coubert. Dalam sepucuk surat bertahun 1851, pelopor "Realisme" dalam seni rupa Prancis itu menyatakan: "Aku tak hanya seorang sosialis, tapi juga seorang demokrat dan pendukung ide republik."
"Realisme" dan "demokrasi": cetusan anti-teater sebagai kehendak membongkar apa yang mereka anggap mitos dalam panggung politik raja-raja dan pembesar agama. Mitos disejajarkan dengan fantasi, dan fantasi atau imajinasi diletakkan sebagai lawan ilmu dan rasionalitas. Dengan pemikiran seperti itulah Tan Malaka, misalnya, tokoh Marxisme Indonesia (yang percaya bahwa Marxisme itu ilmiah), menggugat manfaat cerita Ramayana bagi bangsanya. Ia tak ingin mengutamakan teater. Ia ingin "ilmu bukti".
Tapi demokrasi juga akhirnya punya tuntutan teaternya sendiri. Di zaman modern, gerakan massa merupakan bagian kehidupan politik yang tak terbendung. Pawai, suara semboyan, nanyian perjuangan, poster, kata-kata bergelora, dan kostum yang spesial tampil di jalan, di lapangan dan di tribun-tribun. Politik dan estetik bertaut; nilai yang diutamakan makin lama bukan transparansi seperti yang semula dicita-citakan demokrasi, melainkan yang oleh Walter Benjamin disebut "nilai pameran", Ausstellungswert.
Dewasa ini "nilai pameran" itu bisa kita saksikan di sebuah pentas yang sangat efektif: televisi. Citra, bukan fakta, jadi menentukan. Ilmu bukti tak berlaku. Demokrasi berpisah dengan "realisme". Yaron Ezrahi menulis sebuah buku, Imagined Democracies (Cambridge University Press, 2012) dengan sub-judul "necessary political fictions".
Ezrahi tak serta merta mengecam politik sebagai kehidupan yang memerlukan fiksi. Agaknya baginya apa boleh buat, demokrasi, sebagai arena persaingan dan perbantahan, akhirnya lebih mementingkan opini ketimbang kebenaran. Kini konstituen yang menentukan pilihan politiknya bukanlah makhluk yang melihat dunia dari posisi "aku berpikir", tapi dari "aku-nonton-televisi." Dan siapa menjamin ada kebenaran dalam TV?
Tapi hidup berjalan dengan apa yang disebut Ezrahi sebagai "suspension of disbelief": kita lebih baik tak terus menerus merisaukan "kebenaran" dari pentas yang disebut politik itu. Seperti ketika kita membaca novel atau menonton film, kita memasuki fiksi sebagai fiksi -- dan dari sana kita mengembangkan imajinasi. Kita menjelajah pelbagai kemungkinan makna. Kita kreatif.
Kita bisa tersesat, tapi kata "sesat" bukan kata yang tepat. Teater punya "kebenaran"-nya sendiri, yang berbeda dari yang ditemukan "ilmu bukti". Dalam teater, seperti dalam politik, "kebenaran" selalu menggetarkan tapi selalu dalam proses. Tanpa arah yang pasti.
Demokrasi adalah pergulatan di tengah yang tak pasti itu. Mungkin itu kelebihannya. Ketidak-pastian sering diingkari, padahal itulah hidup itu sendiri.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo