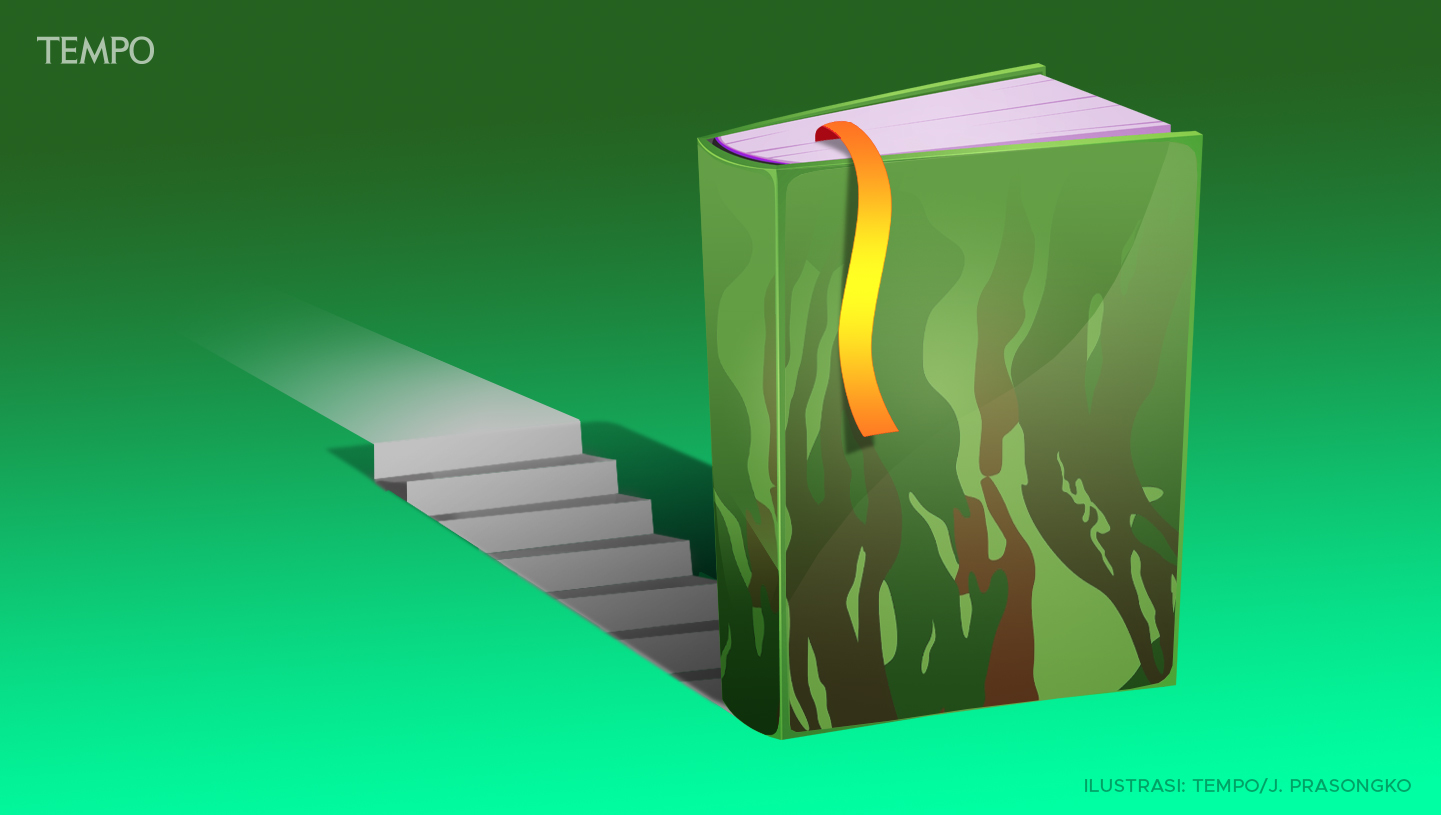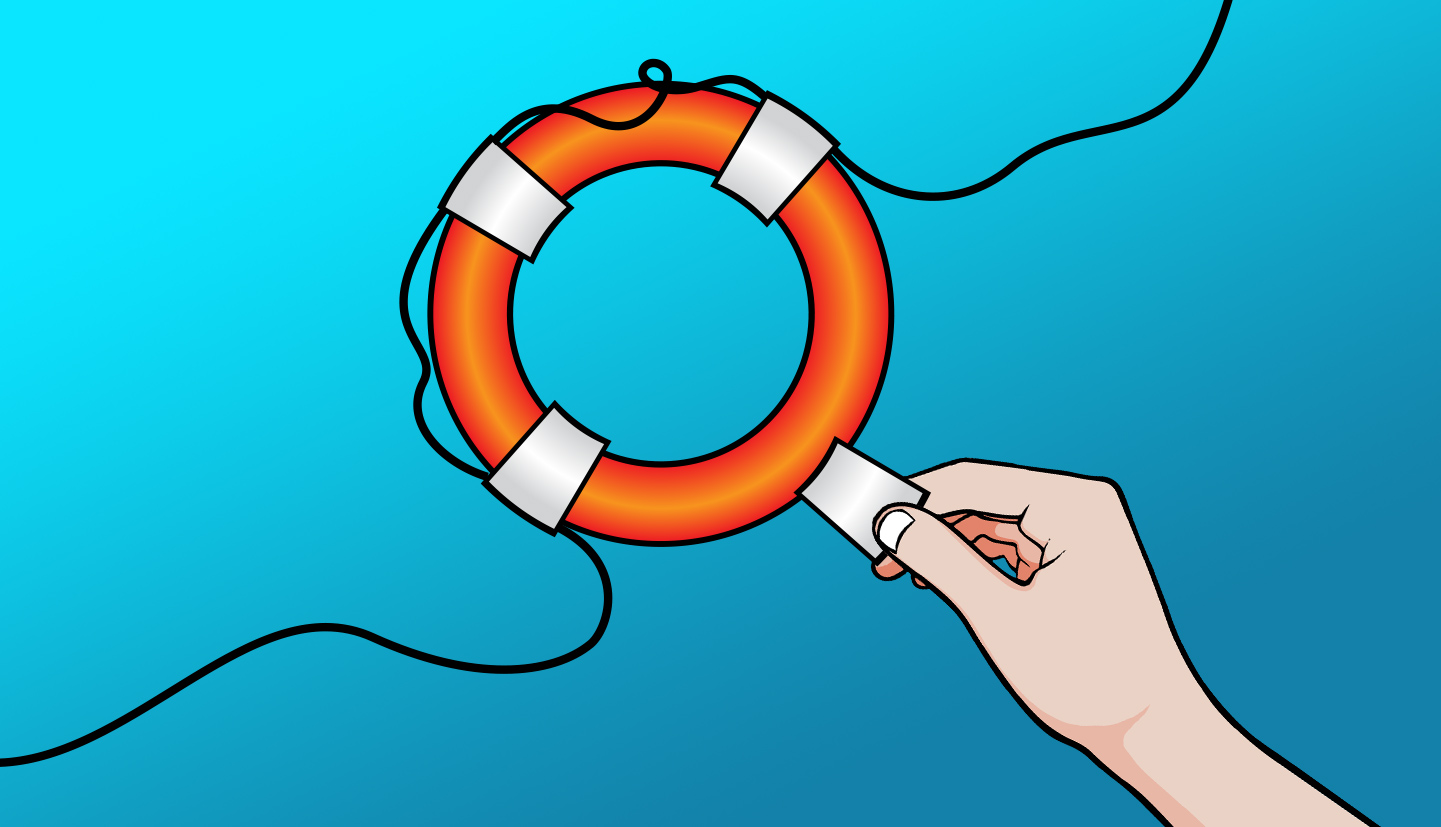Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Edwin Partogi Pasaribu
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada masa awal jabatannya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. memberi perhatian terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu sebagai bagian dari tugas besar yang dititipkan Presiden Joko Widodo kepadanya. Niat Menteri Mahfud ini perlu disambut dan dikelola baik agar tidak seumur jagung dan "gugur" sebelum waktunya, seperti yang dialami Luhut Binsar Pandjaitan ketika simposium untuk tragedi 1965, yang diprakarsainya pada April 2016, mendapat tentangan dari kementerian lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Upaya penyelesaiannya tidaklah mudah. Sejak 1998, hanya perkara Timor Timur pasca-Referendum 1999 dan kasus Tanjung Priok 1984 yang berhasil disidangkan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Selain kasus masa lalu, ada kasus Abepura yang pernah dibawa ke Pengadilan HAM (permanen). Hasil persidangan terakhir ini masih menyisakan masalah dalam konteks keadilan karena putusan hakim berujung pada pembebasan terdakwa dari segala dakwaan. Inilah bagian unik dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat ketika peristiwa dan korbannya ada tapi tidak ada pelaku yang dihukum.
Dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Bandung pada 3 Desember lalu, Mahfud menyatakan akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu ini dengan cara non-yudisial tanpa mengabaikan mekanisme yudisial atau sebaliknya. Mahfud juga menyampaikan bahwa sekarang saatnya negara mengambil keputusan dan tidak mengambangkannya lagi. Ini merupakan pernyataan yang cukup maju dari pemerintah. Anggaplah ini sebagai kelanjutan dari agenda Joko Widodo pada periode sebelumnya dalam Nawacita yang belum menuai hasil.
Pemerintah saat ini kembali membahas rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dulu undang-undang ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 karena konstruksi hukumnya dinilai keliru. Di satu sisi, undang-undang ini menyatakan putusan komisi bersifat final dan mengikat. Tapi, di sisi lain, bila presiden menolak memberikan amnesti kepada pelaku, kompensasi korban tidak diberikan dan digelar pengadilan HAM untuk memutusnya.
Para korban pelanggaran HAM masa lalu masih menunjukkan kegigihannya menuntut keadilan, seperti dilakukan para korban dan keluarga korban dalam Aksi Kamisan setiap Kamis sore di depan Istana Negara, Jakarta, sejak Januari 2007. Tuntutan mereka patut dijawab pemerintah.
Pemerintah dapat mulai menyelesaikannya dengan bertanya kepada para korban mengenai model penyelesaian yang mereka kehendaki. Setelah itu, pemerintah memutuskan model yang akan diterapkan. Bila sulit mendapat pilihan yang ideal, jalan tengahnya adalah mekanisme yang paling mungkin untuk diterapkan. Di sini pemerintah dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil keputusan.
Namun ada baiknya pandangan kita tidak dibatasi oleh pendekatan hukum, yang membutuhkan proses panjang dan penuh tantangan. Misalnya, bila pemerintah mendorong mekanisme KKR, dibutuhkan waktu lama untuk penyusunan undang-undang hingga pelaksanaannya. Tapi mekanisme hukum ini memang harus tersedia sebagai jalan pengungkapan kasus tersebut.
Selain jalan yudisial maupun non-yudisial, yang tidak kalah penting adalah upaya negara untuk memenuhi hak para korban dan mengenang peristiwa kemanusiaan yang pernah terjadi agar tidak terulang. Langkah apa yang bisa dilakukan?
Pertama, setiap pelanggaran HAM berat menimbulkan hak atas reparasi (pemulihan) bagi korbannya. Salah satu bentuknya adalah permintaan maaf. Pemerintah dapat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas peristiwa pelanggaran HAM berat. Contohnya telah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000 dan Wali Kota Palu Rusdi Mastura pada 2012 dalam kasus peristiwa 1965.
Kedua, pemerintah membuat memorialisasi sebagai peringatan agar tragedi yang sama tidak terulang. Dalam beberapa kasus, memorialisasi ini telah ada, seperti Museum Omah Munir di Malang, Monumen Simpang KKA dan Monumen Rumoh Geudong di Aceh, Tugu Korban Kerusuhan Mei di pemakaman Pondok Ranggon, dan Monumen Reformasi Trisakti di Universitas Trisakti.
Ketiga, pemerintah memberi rehabilitasi psikososial. Ini merupakan salah satu hak korban, selain bantuan medis dan psikologis oleh negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Yang dimaksudkan "rehabilitasi psikososial" dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah semua bentuk layanan psikologis dan sosial yang ditujukan untuk meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
Pemenuhan rehabilitasi psikososial hanya mungkin terjadi bila kerja sama LPSK dan kementerian atau lembaga terkait berjalan. Namun upaya LPSK untuk melakukannya sejak 2018 dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden belum menuai hasil.
Kinilah saatnya pemerintah mengambil langkah nyata dengan menyediakan mekanisme pengungkapan pelanggaran HAM berat dan mengakhiri impunitas. Saatnya kita memuliakan kedudukan korban sebagaimana dimandatkan konstitusi.