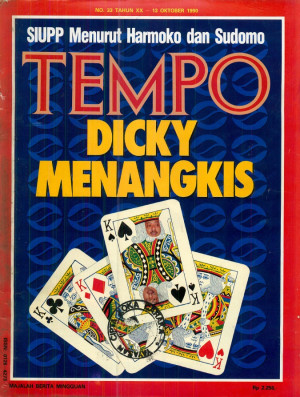INILAH sebuah kalimat dari sebuah buku sejarah tentang pers Hindia Belanda di awal abad ke-20: "Wartawan jangan coba-coba menunjukkan bahwa ia mempunyai pendapat sendiri atau berusaha mengadakan penyelidikan yang bebas...atau...mengecam tindakan penguasa ini atau yang lainnya, karena ia menghadapi risiko kemarahan pejabat yang ditimpakan kepadanya, dengan segala akibat yang menyertainya .... " Kalimat itu tercantum dalam buku G.H. von Faber, A Short History of the Press in the Dutch East Indies, yang terbit di tahun 1930. Edward C. Smith mengutipnya dalam Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia. Dan kita pun tahu: ingatan kita tak selamanya panjang. Kita misalnya lupa akan lelaki pendek berkepala bulat itu, Parada Harahap, yang belum lagi berumur 17 tahun dan menulis kepada koran Pewarta Deli di Medan. ~Diceritakannya nasib susah para kuli onderneming di tahun 1916 itu. Kemudian, seperti dikisahkan oleh Soebagijo I.N., dalam Jagat Wartawan Indonesia, Parada tak cuma bercerita. Ia menggugat. Waktu itu, di perkebunan milik Belanda di Sumatera, banyak orang Belanda yang tiba-tiba ditikam oleh kuli-kuli perkebunan. Pemerintah kolonial pun mengeluarkan pisobelati-ordonantie, sebuah aturan khusus yan~g melarang para kuli membawa pisau belati. Bagi Parada Harahap, ini adalah ketidakadilan. Di harian Benih Merdeka di Padangsidempuan, diceritakannya bahwa kekerasan tak cuma dilakukan sepihak -- para tuan besar onderneming dan staf mereka semuanya orang Belanda -- juga membawa pisau, yang disembunyikan pada tongkat yang mereka bawa. Kenapa mereka ini diperbolehkan membawa senjata, sedangkan para kuli tidak? Parada Harahap tak sendirian. Ia, yang kemudian pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan dan penerbit yang sukses, (naik mobil ke mana-mana), lahir dari ~aman ketika jurnalisme Indonesia masih belum terkena sinisme terhadap diri sendiri. Memang ada ketidakpastian di tiap jengkal: si wartawan sewaktu-waktu bisa ditindak oleh penguasa kolonial, si penerbit setiap kali bisa kehabisan modal (dan itu juga terjadi pada Parada Harahap), tapi mereka tahu bahwa mereka tengah melakukan sesuatu yang penting bagi orang banyak. Bagi rakyat banyak. Saya, yang hidup di ~zaman ini, kadang bertanya: tidak takutkah wartawan wartawan waktu itu ? Tidak takutkah Parada Harahap? Tidak, jawab orang-orang yang lebih tua. Betapapun kolonialnya Belanda, (kata mereka), negeri jajahan Hindia Belanda diperintah berdasarkan hukum, dan nun jauh di Nederland ada parlemen yang bebas. Kesewenang-wenangan memang terjadi di tanah koloni ini, tapi ada suatu mekanisme yang seakan-akan menjanjikan bahwa selalu ada harapan bahwa perbaikan akan lahir. Dan tak kurang dari itu, (kata orang-orang tua pula), masa antara tahun 1920-an dan 1930-an itu menyembunyikan sebuah optimisme: Indonesia suatu hari akan merdeka. "Jembatan emas" akan terbentang. Hak-hak yang selama ini ditiadakan oleh penjajah akan ditumbuhkan. Nampaknya itulah sebabnya, ketika B.M. Diah mendirikan harian Merdeka di tahun 1945, kurang dari tiga bulan setelah Proklamasi, ia mencantumkan semboyan di bawah logo korannya itu: "Berfikir merdeka, Bersuara merdeka, Hak rakyat merdeka": Diah dan Merdeka adalah suatu ekspresi dari suatu masa yang penuh dengan keyakinan. Di masa itu, kemerdekaan berpikir bukanlah sesuatu yang menakutkan, kemerdekaan bersuara bukan sesuatu yang mencemaskan. Tetapi betapa singkatnya masa penuh keyakinan itu. Jika dibaca buku Sejarah Pembreidela~n Pers di In~donesia, tak sampai dua dasawarsa kemudian, di tahun 1957, sepuluh harian dan tiga kantor berita dibredel oleh penguasa. Pembredelan ini cuma berlangsung 24 jam, namun sesuatu yang makin meruyak telah terjadi. Di satu pihak, ada orang-orang pers yang sepertinya hantam sana hantam sini dan saling menuduh dengan ingar. Di lain pihak, orang-orang yang punya kekuasaan yang cemas menyaksikan semua itu, yang selalu berpikir, seperti pemerintah Hindia Belanda dulu, bahwa kemerdekaan adalah laut yang berbahaya. SIT dan SIUPP adalah gejala kecemasan itu. Memang menakjubkan bahwa kecemasan itu berlangsung sejak abad ke-19, lewat akhir tahun 1950-an dan terus hingga kini. Maka, mungkin tak ada sebenarnya tanda perubahan zaman. Jika ada yang berubah, agaknya, itu adalah bahwa harapan telah berganti dengan sinisme: ada asumsi bahwa bangsa kita, bagaimanapun, tak akan bisa baik-baik "berpikir merdeka, bersuara merdeka" -- biarpun setelah 45 tahun merdeka. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini