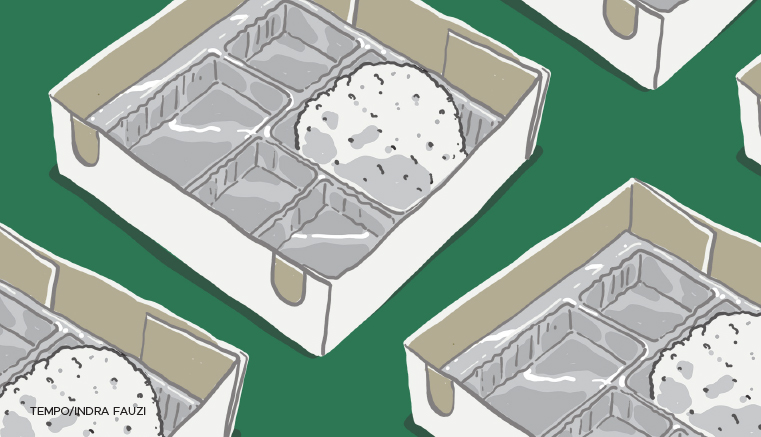Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

DOKTRIN pertama kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kepada Ubaid Mustofa Mahdi setiba di Suriah empat tahun lalu adalah halal membunuh orang di luar Islam. Ubaid dicekoki ajaran itu bersama puluhan laki-laki lain dari berbagai negara di sebuah gedung di Jarabulus, kota perbatasan dengan Turki, dalam masa “orientasi” selama dua hari. “Kalau tidak mau ikut, akan dipenjara,” kata Ubaid dalam wawancara dengan Tempo di kompleks kantor intelijen Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Rmelan, Suriah, Sabtu, 25 Mei lalu.
Ubaid tak bertemu lagi dengan istri dan anaknya yang berusia tiga tahun setelah mereka tiba di tempat penampungan itu. Perempuan dan anak-anak dipisahkan dari laki-laki dewasa. Selesai “penataran”, Ubaid dan para lelaki lain langsung dikirim ke sebuah gurun yang tak begitu jauh dari Kota Homs, sekitar 350 kilometer di barat daya Jarabulus, untuk mengikuti pelatihan militer. Setiap hari selama sebulan mereka disuruh berlari di padang pasir dan push-up. Ubaid juga diajari memereteli dan merakit kembali senjata api, seperti AK-47.
Tiga hari sebelum tiba di Jarabulus, Ubaid dan keluarganya sampai di Istanbul, Turki, pada 22 Februari 2015 bersama rombongan pelancong asal Indonesia. Setelah pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara Ataturk, Ubaid dan keluarganya beserta 13 orang lain memisahkan diri dari rombongan yang diberangkatkan agen perjalanan ternama di Jakarta itu. Mereka menuju terminal bus dan membeli tiket tujuan Gaziantep, yang terletak sekitar 1.100 kilometer di tenggara Istanbul. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 12 jam, Ubaid dan keluarganya tiba di tujuan.
Melalui aplikasi pesan Telegram, rombongan diberi perintah oleh seorang petugas dari ISIS agar menginap di sebuah hotel di Gaziantep. Instruksi selanjutnya datang dua hari kemudian. “Isinya, ada tiga taksi yang menjemput dengan kode ‘Mustofa’,” ujar Ubaid, yang kini ditahan SDF di penjara Derik, Al-Malikiyah, sekitar 30 kilometer di timur laut Rmelan.
Mustofa juga nama tengah pria 29 tahun itu, baik pada nama asli maupun aliasnya. Nama sebenarnya bukan Ubaid Mustofa Mahdi. Ia mendapat nama ini di Suriah. Ubaid meminta nama pemberian orang tuanya tak ditulis karena alasan keamanan. Ia ingin pulang ke Indonesia suatu hari nanti. Menurut Ubaid, jaringan ISIS di Indonesia cukup kuat. Ia mengetahui hal tersebut sejak bergabung dengan kelompok teroris ini hingga dua tahun lalu. Sejak 17 November 2017, ia ditahan SDF, gabungan prajurit Kurdi dan Arab Suriah yang beroperasi di wilayah Kurdi dan bukan bagian dari pasukan militer pemerintah Suriah.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo