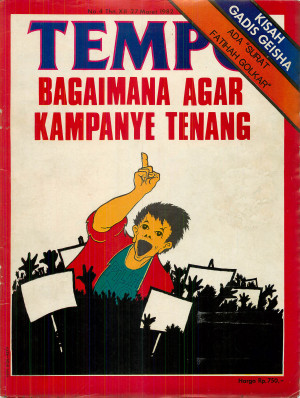KERUSUHAN yang timbul menyusul kampanye Golkar di Lapangan
Banteng, Jakarta, pekan lalu mengundang banyak pemikiran dan
pertanyaan. Mengapa bisa timbul, berkembang dan meluas menjadi
pengrusakan oleh massa? Yang lebih menarik lagi: mengapa
sebagian besar yang terlibat dan ditahan adalah pemuda serta
pelajar SLP dan SLA.
"Yang jelas mereka ternyata cecunguk langganan Kopkamtib yang
sudah-sudah. Semua ontestan pemilu sudah tahu," kata
Pangkopkamtib Sudomo pada pers pekan lalu. Ia tidak, mengungkap
apakah para pelajar tersebut termasuk kategori "cecunguk
langganan Kopkamtib". Namun ia menjanjikan, dalam waktu dekat
mereka -- yang katanya tertangkap "on the spot " (di tempat)
karena membakar dan melempar batu-akan segera dibawa ke sidang
pengadilan. Mereka umumnya berumur sekitar 17 tahun. Dengan kata
lain, anak-anak itu masih mengedot di awal Orde Baru, tahun
1966.
Keterlibatan para pelajar dalam kegiatan kampanye Pemilu 1982
memang merupakan gejala baru yang menarik. Sebagian pelajar SLA
termasuk pemilih karena ber-usia di atas 17 tahun hingga menjadi
salah satu sasaran para kontestan pemilu untuk digaet. Tapi
ternyata banyak pelajar yang dibawa umur pun ikut melibatkan
diri dalam kampanye.
Banyak pelajar dilaporkan mendatangi pos komando (posko)
kampanye PDI dan PPP di Jakarta, menawarkan diri membantu kedua
parpol tadi memasang tanda gambar.
Di hari pertama masa kampanye, 15 Maret misalnya, 65 pelajar SMA
serta STM dan mahasiswa mendatangi rumah Ipik Asmasubrata, Ketua
DPD PDI Jakarta. Mereka didaftar dan dibagi dalam beberapa
kelompok dan menyebar untuk memasang tanda gambar PDI. Esoknya
jurnlah yang datang bertambah. Bahkan pada 17 Maret sekitar 200
pelajar, masih dalam pakaian seragam sekolah, datang untuk
membantu hingga Ipik terpaksa menyelenggarakan "kursus kilat
politik" untuk mereka. Mereka juga menyatakan diri hendak
menjadi saksi dalarn penghitungan suara di Tempat Pemungutan
Suara di daerah masing-masing.
Gejala yang serupa terjadi juga di tempat lain. Di Bandung, di
hari-hari pertama masa kampanye, kantor PDI Kodya diserbu
pelajar dan tukang becak yang ingin membantu kampanye. "Ini
spontanitas saja, bukan karena suruhan atau anjuran
siapa-siapa," ujar Memed yang mengaku pelajar kelas 11 SMP NU.
"Saya belum punya hak pilih, tapi saya mau membantu yang lemah."
"Kami ingin menolong kontesun yang kecil, itu pahala," kata
Yusuf, pelajar kelas III SMP Muhammadiyah, yang seperti banyak
pelajar lain datang ke kantor PDI membawa kaus sendiri untuk
disablon tanda gambar Banteng. Bukan hanya PDI, menurut Yusuf
banyak temannya yang membantu PPP berkampanye. "Kami membantu
parpol bukan karena benci pada Golkar, tapi karena rindu
keadilan. PPP dan PDI sangat kekurangan dana dan fasilitas.
Golkar ùkan sudah banyak dibantu pemerintah," katanya.
Di Yogyakarta gejala serupa juga muncul. Subandi, 18 tahun,
pelajar suatu SMA swasta tatkala dijumpai di markas PDI
menyebut, ia berniat berkampanye untuk PDI hanya karena ingin
mengimbangi poster Golkar yang berbunyi: "Pelajar Pilih Golkar".
"Saya ingin membuktikan tak semua-pelajar memilih Golkar,"
katanya.
Benarkah para pelajar sekarang--setidaknya di beberapa kota
besar--seperti diutarakan kedua pelajar Bandung tadi, memiliki
kesadaran yang tampaknya cukup lumayan? "Mereka sesungguhnya
punya kesadaran tinggi," kata Dr. Sarlito Wirawan Sarwono,
psikolog UI yang mengajar di beberapa perguruan tinggi. "Hanya
para pelajar itu bingung mencari pilihan, sebab kedua parpol
belum mempunyai tokoh yang patut didukung, sedang Golkar
dianggap punya kelemahan. Hingga mereka kemudian mendukung
parpol dengan tidak rasional." Reaksi begitu, menurut Sarlito,
"bisa dimengerti".
Para kontestan pemilu sendiri tampaknya memang "mengincar" para
pelajar. Itu terlihat dari beberapa tanda gambar bertuliskan
"Pelajar Pilih Golkar" atau "Pramuka Pilih Golkar". Toh jumlah
pelajar yang "sadar politik" mungkin sekali tidak begitu besar.
Kehadiran sebagian besar mereka di Lapangan Banteng pada 18
Maret lalu boleh jadi karena sebab yang lain.
"Hari itu saya bolos sekolah bukan mau ikut kampanye, tapi
karena kepingin melihat artis Safari dari dekat," tutur
Krisnanto, 17 tahun, pelajar STM Budi Utomo sambil menyedot
rokok kreteknya. Diakuinya, sekolahnya siang itu tidak libur,
tapi banyak guru dan murid yang tidak datang. Krisnanto sendiri
tidak tertarik untuk ikut kampanye. "Itu urusan negara, saya
tidak mau ikutikutan. Ngeri efeknya, salah-salah nyawa bisa
melayang," ujarnya.
Absennya para guru dari sekolah masing-masing tatkala kampanye
Golkar berlangsung pekan lalu bisa dimengerti. Mereka sebagai
anggota Korpri dan PGRI memang diinstruksikan untuk menghadiri
kampanye tersebut lewat kepala sekolah masing-masing serta
diwajibkan mengisi daftar hadir. Hingga akibatnya pelajar
sekolah siang yang "nganggur" hari itu.
Berbagai atraksi kesenian yang ditampilkan dalam kampanye
ternyata merupakan daya tarik besar bagi kehadiran para pelajar
dan remaja. Belajar dari pengalaman kerusuhan di Lapangan
Banteng, pimpinan Golkar DKI Jaya telah menginstruksikan pada
semua wilayah agar tidak menonjolkan atraksi-atraksi dalam
kampanye. "Ini terutama untuk mencegah para pelajar dan anakanak
di bawah usia memilih berbondong-bondong datang menghadiri
kampanye," ujar Ketua DPD Golkar DKI Jaya Achmadi.
Dalam pertemuannya dengan ketiga kontestan pekan lalu,
Pangkopkamtib Laksamana Sudomo juga meminta agar pelajar di
bawah usia 16 tahun tidak perlu ikut kampanye. "Itu memang
disepakati parpol dan Golkar, tapi cuma khusus untuk Jakarta."
kata Sabam Sirait, Sekjen DPP PDI Senin lalu.
Menurut Sabam, untuk daerah lain ketentuan itu tidak berlaku
karena memang tidak ada larangan bagi anak sekolah mengikuti
kampanye. "DKI Jaya karena situasinya lain, parpol dan Golkat
sepakat mengambil keputusan semacam itu," kata Sabam.
Situasi Jakarta mungkin memang lain. Itu terlihat dari banyaknya
perkelahian antarsekolah di Ibukota dalam beberapa tahun
terakhir ini. "Para pelajar Jakarta sekarang lebih nekat dan
agresif. Jika terjadi 'gerakan', mereka bisa lebih berbahaya
daripada mahasiswa," ujar seorang perwira menengah ABRI.
Maksudnya, para pelajar itu secara emosioal gampang
dibangkitkan dibanding para mahasiswa yang mungkin lebih
"dingin".
Itu sudah terbukti pekan lalu. Apakah benar para pelajar dan
remaja itu "cecunguk", ditunggangi, benar-benar sadar atau cuma
sekedar ikut-ikutan saja, itu perlu diselidiki lebih jauh. Tapi
yang pasti, cara penanganannya tentulah perlu lebih mengena
Dalam kerusuhan kemarin yang melanda beberapa bagian Kota
Jakarta, para petugas nampaknya tak banyak menggunakan peralatan
yang lazimnya digunakan untuk menghalau para demonstran.
Misalnya saja, gas air mata, salah satu "senjata" yang termasuk
ampuh untuk menghalau kaum perusuh di mana pun, tak kelihatan
digunakan. Kecuali di Lapangan Banteng, setelah ribut-ribut
sulit dikuasai lagi.
Seorang ahli psikologi di Jakarta, membandingkan
kerusuhan-kerusuhan itu dengan yang sering terjadi di Amerika.
"Lihat saja apa yang terjadi di Kota New York, ketika beberapa
tahun lalu lampu padam total di sana: Perampokan, perkelahian,
huru-hara." Seorang pengamat asing membenarkan: "Menurut saya,
peristiwa semacam di Lapangan santeng itu lazim terjadi kalau
ada festival lagu-lagu rock di Amerika. Selagi menonton dan
dalam perjalanan pulang, banyak yang jadi histeris, lalu
mengamuk, memsak apa saja yang terterlihat di depan matanya,"
katanya.
Membandingkdn remaja di lndoncsia dengan anak-anak Amerika
barangkali bisa dianggap mencari-cari. Seperti kata seorang
pengamat di Jakarta, "latar belakang sosial dan budaya kedua
negeri pasti, kerusuhan seperti itu, di mana pun, biasanya
meledak dalam suasana massa yang bergerombol. Atau dalam
kata-kata Pangkopkamtib Laksamana Sudomo timbulnya suasana
"crowd" (gerombolan orang). "Suasana crowd itu yang membikin
rambut saya bertambah putih," katanya setengah berkelakar. "Apa
itu yang namanya Malari, Lapangan Banteng, apa pun, crowd selalu
membuat saya khawatir," katanya. Suatu kekhawatiran yang
tentunya dirasakan setiap orang tua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini