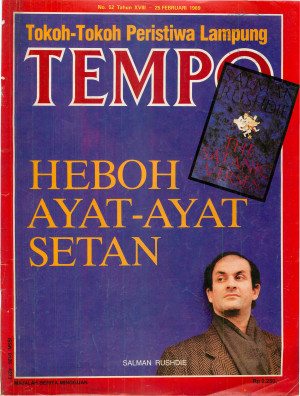SEMULA penduduk desa mengira, Badar telah bertobat. Bekas penghuni bui itu tampak rajin menghadiri pengajian "Imam" Warsidi di langgar, dekat pertigaan jalan Dusun Cihideung. Orang pun kian yakin ketika mereka melihat residivis itu intim dengan Imam Bakri, imam salat di langgar sebelum Warsidi datang 1,5 tahun lalu. Badar pun tampak sebagai jemaah yang dekat dengan Warsidi. Sebagai sesama jemaah lokal, dia juga jadi akrab dengan Jayus, penyumbang tanah untuk permukiman jemaah Warsidi itu. Setelah gerakan Warsidi dkk. meledak, dua pekan lalu, penduduk dukuh itu pun mencoba menebak-nebak. Ada yang menghubung-hubungkan semangat perlawanan Badar, yang kini buron, dengan kematian Marzuki, sobatnya dulu ketika sama-sama menjalani hidup gelap. Maruki tewas di-"petrus", beberapa tahun lalu. "Mungkin Badar kecewa dengan cara pengadilan seperti itu," kata seorang tokoh di Desa Rajabasa. Pengikut Warsidi memang tersebar di banyak desa, seperti Labuhan Ratu VI (yang sering disebut Desa Pancasila). Ada pula jemaah yang datang dari tempat jauh, seperti Sidorejo di Kecamatan Jabung, atau Desa Sri Wibowo di kecamatan Labuhan Maringgai. Ada dugaan, para jemaah itu tergiur masuk barisan Warsidi lantaran didorong rasa kecewa atas kondisi sosialekonomi yang mereka hadapi. Impitan sosial-ekonomi, oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Edi Sudrajat, diakui sebagai satu pendorong timbulnya ancaman seperti gerakan ekstrem di Dukuh Cihideung itu. Masalah pertahanan-keamanan, ujar Edi pada acara pelantikan Pangdam V Diponegoro di Semarang, pekan lalu, memang tak bisa lepas dari masalah di sektor lain. Lampung Tengah, dengan penduduk sekitar 1,8 juta jiwa, memang menyimpan banyak masalah. Untuk ukuran satu wilayah administratif setingkat kabupaten, Lampung Tengah yang beribu kota Metro agaknya terhitung sangat luas luas: 9.200 km persegi, hampir 3 kali lipat luas Daerah Istimewa Yogyakarta, yang punya empat kabupaten dan satu kota madya. Perkembangannya pesat. Di zaman pnjajahan Belanda, di awal abad ini, Lampung Tengah dikenal sebagai onder afdeling Sukadana, yang dibagi dalam tiga distrik: Sukadana, Labuhan Maringgai, dan Gunung Sugih. Setiap distrik, pada masa itu, diperintah oleh seorang asisten wedana. Pada masa itu kewenangan para pemuka adat mendapat pengesahan. Para pemuka adat ini (pesirah) kedudukannya dalam pemerintahan setingkat dengan desa. Pasirah dipilih oleh musyawarah antarkepala kampung, plus kepala suku yang ada pada setiap kampung. Tanah di sekitar permukiman marga diklaim sebagai hak marga. Eksploitasi wilayah, oleh Belanda sebagai penjajah, sering terbentur pada hak pemlhkan suht mendapatkan tanah perkebunan dan buruh-buruhnya. Belanda toh tak kekurangan akal. Dengan merayu para pemuka adat, pemerintah Belanda bisa memdapatkan konsesi tanah untuk transmigrasi. Pada 1941, para pendatang Jawa telah menjadi penduduk mayoritas di situ. Tak mengherankan bila di kemudian hari nama-nama desa di situ berbau khas Jawa atau Sunda. Sebut saja, misalnya, Dukuh Cihideung, Sidorejo, Sidodadi, atau Srikaloko. Pendatang baru itu tentu saja sering mengusik aturan main di tingkat marga tadi Konflik pun tak terhindarkan. Di zaman republik, kedudukan pasirah berangsur-angsur tersisih. Lembaga pasirah dibubarkan, September 1952, dan pemerintahan nagari dibentuk untuk menggantikannya. Tapi ada hal yang esensial di balik keputusan itu: hak penguasaan marga atas tanah adat mulai ditumbangkan. Dalam keadaan demikian, program transmigrasi lebih deras mengalir. Hal itu sempat menimbulkan ketegangan sosial. Buntutnya, 1956 penduduk asli Sukadana mengirim mosi tak percaya kepada pemerintah pusat. Tak ada hasilnya, justru pemerintah menghapus hak-hak adat. Singkat kata, para transmigran terus mengalir dan beranak pinak. Tanah menjadi barang mahal. Apa boleh buat, hutan Gunung Balak, yang berada di selatan Jepara, digasak oleh orang-orang yang lapar tanah itu. Menurut seorang bekas pegawai Kehutanan Lampung, terjadi tahun 1970-1976. "Karena mereka seperti diizinkan oleh pemda untuk menggarap tanah di situ," ujarnya. Pemda tampaknya waktu itu kehabisan akal. Kehadiran komunitas baru itu memang seperti tak bisa dicegah. Bahkan, kabarnya, pemerintah daerah seperti mebherikan angin dengan mengakui kehadiran desa-desa baru, dengan segala perlengkapannya, di sekitar hutan lindung itu. Bahkan pemda seolah melindungi desa-desa terlarang dengan membentuk Kecamatan Gunung-Balak, yang hampir 30% tanahnya merupakan hutan lindung. Syahdan, banjir besar melanda Lampung, 1979 Sementara itu, waduk Way Jepara yang mengairi 22.000 ha sawah menghadapi ancaman pendangkalan yang serius. Apa boleh buat. Kebijaksanaan lama mesti ditinjau kembali. Hasilnya, pemerintah ingin kembali pada peraturan 1937, yang menetapkan Gunung Balak sebagai kawasan hutan lindung. Jalan pintas pun ditempuh: Kecamatan Gunung Balak dihapus 1985, dan desa-desa yang ada dimasukkan ke tiga kecamatan sebelah sembari diatur kembali tata ruangnya. Upaya menghutankan kawasan itu digenjot. Ribuan keluarga digusur dari daerah terlarang itu keluar melalui transmigrasi lokal, ke Kabupaten Lampung Utara. Mereka dijanjikan akan diberi tanah garapan di daerah permukiman baru. Sebagian dari mereka memang telah dipindahkan. Pada tahun anggaran 1983-84 dan 1984-85 saja, ada sekitar 10 ribu KK atau sekira 40 ribu jiwa, sebagian besar dari Gunung Balak, dipindahkan ke Lampung Utara. Tahun-tahun berikutnya ribuan KK yang lain menyusul. Selesai? Belum. "Masih ada 10 ribu lebih KK yang belum terangkat," ujar Bupati Lampung Tengah Suwardi Ramli kepada Syafiq Basri dari TEMPO pekan lalu. Untuk memindahkan semuanya, menurut Suwardi, diperlukan dana tak kurang dari Rp 15 milyar. Secara terus terang, Suwardi mengakui bahwa biaya penggusuran itu terlalu besar untuk bisa dipikul pada Pelita V ini. Proyek penghutanan kembali itu telah dilakukan secara bertahap. Daerah-daerah yang nyata-nyata diketahui sebagai kawasan hutan lindung segera dibebaskan dari permukiman dan perladangan penduduk. Namun, batas-batas hutan lindung, menuryt rcgistrasi 1937 luar, belakangan kabur lantaran patok-patok yang pernah dipancangkan telah lama menghilang. Dicabut oleh para peladang. Oleh sebab itu, Departemen Kehutanan sejak 1984 mencoba membuat pemetaan kembali. Lewat proyek yang disebut program rekonstruksi itu, Departemen Kehutanan hendak membuat patok-patok baru agar kawasan hutan lindung diketahui secara persis batas-batasnya. Dana dari Departemen Kehutanan untuk pemetaan itu telah turun lewat DIP 1986/ 1987. Kabarnya, sekarang proyek itu telah mcmasuki tahap pematokan. "Itulah yang membuat keresahan di kalangan penduduk," ujar sumber TEMPO yang bekas aparat Kehutahan di Lampung itu. Desa yang terlewati proyek rekonstruksi itu antara lain Labuhan Ratu, desa asal dari beberapa jemaah Warsidi. Keresahan itukah yang mendorong orang tergiur menjadi jemaah Warsidi? Seperti juga Mendagri Rudini, Menteri KLH Emil Salim menolak kemungkinan itu. "Peristiwa Way Jepara itu tak ada kaitannya dengan orang yang tergusur dari hutan lindung Gunung Balak," ujarnya kepada wartawan, seusai menemui Presiden di Bina Graha, Sabtu lalu. Desa Cihideung, tempat kerusuhan itu berlangsung, terlalu jauh dari Gunung Balak. "Mereka yang terlibat bukanlah penduduk yang tergusur tanahnya," tambah Emil, yang mengaku baru saja kembali dari Lampung. Gunung Balak juga menghasilkan perkara sampai ke pengadilan. Hampir lima tahun silam, 120 orang bekas laskar 45 menggugat pemerintah daerah dan Mitsugoro (perusahaan patungan antara Mitsubishi dan Kosgoro). Para penggugat, yang dimotori oleh Muhamad Nur, mengklaim tergugat telah menyabot hak tanah mereka seluas 2.400 ha, yang terletak di sekitar Desa Sribawono, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Tengah. Tanah di dekat Gunung Balak itu telah dihibahkan kepada 120 anggota laskar Lampung itu pada 1953, sebagai balas jasa terhadap perjuangan mereka. Hibah itu, kabarnya, memperoleh pengesahan dari pemuka adat setempat. Dalam perkembangannya, tanah itu sebagian digarap oleh pendatang, sebagian lagi oleh PT Matsugoro. Keruan saja, eks pejuang itu marah dan memperkarakan kasus itu ke pengadilan. Tapi PN Metro hanya mengegolkan sebagian gugatan itu. Mereka tak puas, lalu naik banding ke Pengadilan Tinggi. Mentok lagi. Rupanya, mereka belum jera. Sekali lagi, mereka kasasi ke Mahkamah Agung. Malang, Putusan MA September tahun lalu tetap seperti pengadilan terdahulu. Para bekas pejuang itu dinyatakan tak berhak atas tanah 24 ribu ha yang sering disebut tanah 4 kali 6 itu. Pertimbangan MA, antara lain, pada proses itu pemuka adat tak menyebut nama-nama laskar yang berhak atas tanah itu. Tanah itu kini kembali ke PT Matsugoro, untuk usaha perkebunan jagung, sebagian lainnya digarap oleh sekitar 800 penduduk. "Perkara tanah 4 kali 6 itu kini sudah selesai," kata Bupati Suwardi Ramli. Tapi boleh jadi sengketa lain bakal muncul. Pasalnya, sebagian dari tanah itu, kabarnya, masuk ke dalam proyek perluasan hutan lindung Gunung Balak. Masih dari kawasan yang kisruh itu, tersebutlah Desa Labuhan Ratu VI. Desa yang lahir 1970-71 itu penghuninya sebagian eks tapol PKI, sebagian lainnya transmigran militer. Perkembangan selama hampir 20 tahun ini memang membuat perbedaan eks-tapol dan militer tak lagi menonjol. Apalagi sejumlah penghuni baru muncul, garis perbedaan itu meluntur. Namun, belakangan ada kekecewaan yang tersembunyi di desa itu. Para anak-anak eks tapol itu, kabarnya, sebagian kesulitan mencari pekerjaan, lantaran tidak "bersih lingkungan". Dan kepahitan itu agaknya kini makin mendalam setelah peristiwa Cihideung. Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, yang membawahkan Cihideung, yakin bahwa sekitar 60 warga Labuhan Ratu VI aktif menjadi jemaah Warsidi. "Sebagian dari mereka adalah eks tapol atau anak-anaknya," ujarnya. Apakah kekecewaan itu yang mendorong mereka jatuh ke rangkulan Warsidi?Putut Tri Husodo, Ahmadie Thaha, Tri Budianto Soekarno, dan Effendi Saat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini