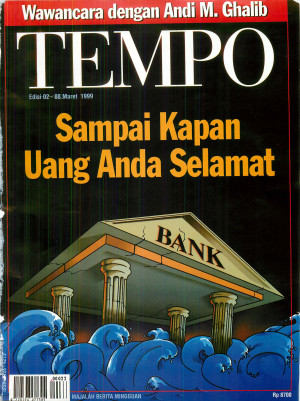Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SUATU hari tahun 1983. Benedict R. O'G. Anderson, guru besar studi Asia dari Cornell University, AS, mendarat di Bandar Udara Kemayoran. Ini merupakan kedatangannya yang pertama sejak 1972, ketika ia secara resmi ditangkal pemerintah Orde Baru. Baru beberapa menit ia menginjakkan kaki ke bumi Jakarta, datang serombongan orang yang mengaku sebagai aparat keamanan. Ben, demikian panggilan akrabnya, ditarik ke sebuah ruangan. Ia diminta segera hengkang. Padahal, kedatangannya untuk menghadiri konferensi sastra dan bahasa Asia Tenggara telah mendapat izin resmi dari kedutaan besar Indonesia di AS. Ben memang tak mampu berbuat banyak. Ia bergegas kembali ke pesawat yang sebelumnya membawanya terbang dari Bangkok. Tapi, teror tidak berhenti di situ. Rombongan aparat itu masuk ke kabin pesawat, kembali menyergap Ben dan memaksanya agar menyerahkan paspor miliknya. Jika tidak, ia akan ditangkap. ''Kalau begitu, tangkaplah saya," jawab Ben sengit. Ia memang urung ditangkap, tapi tetap harus meninggalkan Jakarta. Di pesawat, merasa terhina oleh perlakuan itu, penulis buku Java, in A Time of Revolution itu merasakan sakit yang menggedor-gedor sekujur tubuhnya. ''Sepanjang perjalanan Jakarta-Bangkok, saya harus berbaring di lantai pesawat karena seluruh badan saya terasa sakit, padahal tidak ada masalah dengan kesehatan saya," kata Ben lagi. ''Saya merasa ditipu habis-habisan. Saya harus mengalah pada intel."
Teror militer kepada Ben Anderson adalah sekelumit kenyataan pahit yang harus diterima ahli Indonesia itu setelah pada 1965 Ben bersama para ''Indonesianist"—demikian julukan umum terhadap peneliti asing yang menggunakan Indonesia sebagai subyek studinya—lainnya seperti Ruth McVey menerbitkan Cornell Papper, versi lain dari peristiwa G30S-PKI. Kertas kerja yang mempertanyakan peran Soeharto dalam peristiwa berdarah tersebut memang menyengat pemerintah Orde Baru, yang sedang berusaha keras meyakinkan rakyat bahwa peristiwa itu adalah ulah PKI.
Sebagai ilmuwan, Ben adalah seorang yang tekun. Beberapa buku karangannya seperti Pemuda Revolusi (1967), Language, Fantasy and Revolution (1987), The Idea of Power in Javanese Culture, atau Imagined Communities, menunjukkan betapa ia mampu memandang Indonesia dari berbagai sudut, mulai dari kedudukan bahasa dalam pembentukan kesadaran nasional, gagasan kuasa dalam kebudayaan Jawa, wayang, sampai soal Ratu Adil. Bagi Ben Anderson, kedatangannya ke Indonesia mungkin seperti sebuah perjalanan nostalgia. Dua puluh enam tahun lamanya guru besar dan peneliti Cornell University, salah satu pelopor studi Indonesia di AS itu—selain pendahulunya George T. Kahin, tentunya—tak diperkenankan menghirup udara Jakarta akibat namanya yang masuk daftar hitam pemerintah Indonesia. Selama 26 tahun itu, begitu rindunya pada Indonesia, Ben malah tak mau mendengarkan bunyi gamelan karena khawatir sakit hati. Namun, ''diam-diam saya setel juga untuk mengenang," tuturnya tertawa.
Dalam ceramahnya bertajuk ''Nasionalisme, Kini dan Esok" yang diselenggarakan untuk merayakan ulang tahun Majalah Tempo ke-28, Kamis pekan lalu, Ben kembali mengingatkan akan perlunya nasionalisme dipandang sebagai ''proyek bersama". Hanya dengan cara pandang demikianlah nasionalisme bisa mengikat suatu bangsa tanpa harus membuat satu kelompok bangsa menjadi budak dari kelompok yang lain. Ben memberi contoh. Pangeran Diponegoro, yang dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia, dalam memoar yang dibuatnya, setelah ia diasingkan ke Sulawesi, tidak pernah menyebutkan perjuangannya selama ini adalah untuk membebaskan tanah Jawa. Yang diakuinya adalah ''menaklukkan" tanah Jawa. Dengan demikian, ''Mengaitkan nasionalisme dengan sejarah nenek moyang adalah berbahaya," kata Ben kepada Leila S. Chudori, Arif Zulkifli, Nurur Rokhmah Bintari, dan fotografer Rully Kesuma dari TEMPO, yang menemuinya di Galeri Cemara pekan lalu.
Anda tidak percaya terhadap konsep negara bangsa (nation state)?
Saya percaya pada nation, tapi state nanti dulu. Jika ingin proyek bersama yang bernama nasionalisme ini berlangsung, harus dilakukan berdasar pada sukarela berkorban. Itu yang menjadi semen untuk membuat masyarakat berjalan dengan baik. Tapi, kalau masih ada orang merasa tidak diajak, bahkan digebuki, hak sendiri dirampas orang sebangsanya, lama-kelamaan perekat itu kering. Idenya sebenarnya bagus, tapi kalau orang pusat goblok dan rakus, akan terjadi banyak masalah.
Setelah Soeharto jatuh, banyak daerah yang ingin lepas dari Indonesia. Apakah hal ini timbul karena Indonesia sebenarnya tidak siap sebagai negara bangsa?
Adanya bangsa Indonesia semacam kebetulan. Ingat, tahun 1811 Belanda dicaplok Inggris. Mengapa Belanda bisa kembali? Tentu bukan karena menang perang tetapi ada semacam deal dengan Inggris agar Belanda menyerahkan Sri Lanka dan Afrika Selatan. Seandainya Inggris punya kebijakan politik lain, mungkin Indonesia sekarang menjadi bagian dari Malaysia. Jadi batas Indonesia yang terjadi sekarang ini semacam kecelakaan sejarah. Tetapi lama-lama kebiasaan hidup bersama dalam institusi yang sama mampu menimbulkan perasaan solidaritas. Karena itu, jalan keluar dari tuntutan pemisahan diri itu, Indoneisa memerlukan semacam sistem federasi. Tapi itu pun harus ada basis hukumnya, tidak bergantung hanya pada itikad orang pusat. Daerah harus dikasih cukup kesempatan untuk merasa jadi tuan di tanah sendiri.
Banyak yang memperkirakan, kalau Tim-Tim lepas dari Indonesia, akan terjadi perang saudara?
Ini susah diterka. Tapi harus diingat, waktu penyerahan kedaulatan tahun 1945, ada peristiwa Andi Aziz, pemberontakan RMS. Saya tidak heran kalau nanti ada konflik, tetapi skalanya tidak besar dan tidak bertahan lama. Orang yang mendapat keuntungan dari pendudukan Indonesia tentu akan panik kalau nanti Kopassus keluar. Padahal, sewaktu saya bertemu dengan Xanana, ia sama sekali tidak terlihat dendam. Saya kira demikian pula Bung Hatta dan Bung Karno pada peristiwa Westerling, tidak dendam kepada orang Ambon. Jadi belum tentu ada konflik yang keras di Tim-Tim nanti. Mereka sudah begitu banyak menderita.
Dulu Ali Moertopo pernah berusaha meyakinkan Anda bahwa keputusan masuk ke Tim-Tim adalah keputusan yang baik?
Ya, Ali Moertopo dan timnya berusaha meyakinkan saya bahwa soal Tim-Tim bisa diselesaikan hanya dalam tiga minggu. Waktu itu mereka sedang bikin tur di AS. Tadinya mereka yakin bisa menangani Tim-Tim seperti ketika di India masuk Goa, yang bisa diselesaikan selama 10 hari. Padahal informasinya salah, kesombongan pemerintah Indonesia sangat besar. Masalah Tim-Tim jadi berlarut-larut karena mereka frustrasi, sehingga di Tim-Tim tentara menjadi begitu buas.
Bisa ceritakan saat Anda dilarang masuk Indonesia tahun 1972 karena Cornell Paper?
Saya dilarang masuk karena saya tidak bersedia meralat Cornell Paper (sebuah penelitian awal tentang Gerakan 30 September 1965). Saya memang diberi kesempatan untuk itu. Paper itu sendiri bocor pada 1966. Tapi pemerintah RI tahu bos saya, Pak Kahin (George T. Kahin, ahli Indonesia), orang yang pernah memperjuangkan Indonesia dan terkenal di Indonesia. Saya sendiri saat itu masih ingusan dan diyakinkan (orang) bahwa kalau saya masuk ke Indonesia, lalu mendapat informasi yang lebih lengkap, saya akan melihat bahwa penelitian itu banyak kesalahan. Saya lalu mengunjungi Indonesia tahun 1967 selama dua bulan dan tahun 1968 selama tiga bulan. Tapi apa yang diharapkan pemerintah (Indonesia) itu ternyata tidak terjadi. Saya sering mengatakan bahwa (penelitian) ini banyak salahnya, tapi versi pemerintah (Indonesia) memiliki kesalahan yang jumlahnya sepuluh kali lipat. Dalam analisis, saya selalu mengatakan ini adalah sebuah uraian sementara karena banyak faktor yang tidak terbongkar.
Misalnya?
Pertama, kami sama sekali tidak punya informasi tentang peran dinas rahasia di luar negeri seperti AS, Inggris, Cina, dan Rusia. Kami tidak punya bukti sama sekali, tapi bukan berarti bukti itu tidak ada. Di samping itu, waktu itu belum ada Mahmilub kecuali yang diberlakukan terhadap Nyono. Jadi, saat itu, kami sama sekali belum tahu mengenai Biro Khusus (PKI) dan proses verbal Mahmilub. Kedua, waktu itu kami belum tahu pasti apakah isu bahwa para jenderal yang kabarnya dicongkel matanya dan dipotong kelaminnya memang benar-benar terjadi atau tidak. Itu kan membangkitkan histeria. Bukti pasti yang baru akhirnya saya dapatkan pertengahan 1980-an. Dari visum ternyata (penyiksaan fisik) semacam itu tidak terjadi. Dari situlah kami menyadari bahwa mereka sudah merencanakan histeria ini—dengan dingin—agar orang membenarkan segala yang terjadi tahun 1965. Sejak dulu, saya juga sudah curiga dengan istilah Gestapu. Urutan kata ''Gerakan September 30" itu kan tidak normal dalam bahasa Indonesia. Ini kan upaya agar peristiwa itu mirip dengan Gestapo. Terlalu banyak hal yang tidak jelas.
Soal keterlibatan Soeharto, apakah menjadi bagian yang perlu Anda koreksi juga?
Kami hanya mengajukan pertanyaan, mengapa orang yang memegang komando kesatuan di Jakarta tidak diserang. Mengapa Untung kena. Mengapa Latief kena. Aneh. Belakangan dia (Soeharto) mengaku bahwa dia di rumah sakit. Yang aneh, mengapa Latief tidak dieksekusi. Banyak yang menduga hal itu karena tidak diperbolehkan Bu Tien, karena keluarga Harto dengan Latief dulu akrab sekali. Lalu muncul misteri sosok Syam, apa betul dia mati atau bunuh diri.
Anda mengaku sebagai murid George Kahin tapi tidak seperti Kahin, yang percaya pada peran tokoh-tokoh politik seperti yang terlihat pada buku-bukunya, yang selalu membicarakan pemikiran politik tokoh besar. Anda lebih percaya pada pergerakan di level akar rumput. Kenapa?
Ada dua sebabnya. Pertama, saya adalah anak tahun 1960-an, masa lahirnya pemberontakan mahasiswa. Kahin lebih percaya pada ''Si Siluman" (negara) daripada saya. Saya condong anarkis. Kedua, saya produk pendidikan Eropa yang belajar bahasa, sastra, dan sebagainya. Sejak tingkat SMA sampai universitas, saya belajar bahasa Latin, Yunani, Rusia, Prancis, Jerman. Ada perasaan bahwa budaya sangat menentukan. Adapun Pak Kahin tidak begitu tertarik pada sastra dan budaya. Kebudayaan itu, bagi saya, tidak hanya di atas awan sana, tapi di mana-mana, termasuk pada level bawah.
Anda seorang kulturalis yang paham betul dengan kebudayaan Jawa. Tetapi di antara Indonesianis yang lain, Anda yang paling ''tidak halus", cenderung sinis dalam mengemukan kritik.
Saya jarang tampil di forum resmi. Paling, bicara di telepon. Saya memang lebih senang dengan bahasa jalanan yang tidak resmi. Bahasa resmi Orde Baru itu memuakkan bukan main. Maka, saya tidak pernah ke forum atau mengunjungi pejabat. Itu bedanya (dengan beberapa peneliti lain). Saya kira, pada saat membuat riset tahun 1960-an, (penyajian) saya masih cukup sopan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo