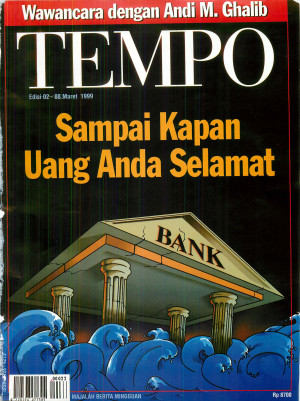Bhisma gugur, dan kita dengar adegan terkenal ini: di medan perang itu tubuh tua itu terlentang, basah lengket oleh darah, berlubang-lubang oleh luka, tapi anggun. Sosok gagah yang hampir mati tapi tak kunjung sekarat. Badan rusak yang tegak karena disangga oleh puluhan anak panah—benda tajam yang menembus dada sampai ke punggung. Sebuah estetika kematian? Mungkin. Tapi juga sebuah keindahan tentang kekejaman.
Kekejaman adalah satu unsur utama sebuah "epik" —sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia pernah diterjemahkan sebagai "wiracarita". Terjemahan ini tentu saja bentukan dari kata wira (keberanian) dan carita (kisah), dan saya kira ini temuan yang tepat. Sang pahlawan, yang selalu hadir di sana, tidak akan ada tanpa keberanian. Kita tahu keberanian di sini punya arti yang tertentu, dalam sebuah kisah yang tentu saja punya geraknya sendiri. Kita menemukan sesuatu yang brutal yang, seakan-akan dengan cara yang ajaib, menemukan bentuk, menemukan irama.
Irama memberi arus batin sebuah tembang, sebuah epos. Dari sana ia bisa membuat banyak hal jadi elegan dan yang elegan menjadi memukau, dan yang memukau menjadi halal. Wiracarita adalah juga sebuah apologi untuk pengrusakan dan kematian. Para pahlawan—umumnya laki-laki, dan umumnya identik dengan "jagoan"—menjadi segumpal tenaga yang, dengan sifat kasar dan terkadang jorok, melintasi apa yang destruktif, yang sakit dan yang mati. Bertahun-tahun kita mengenalnya: dalam Mahabharata dan Ramayana, dalam puisi Perang Troya dan lakon Mushashi, dalam film koboi dan silat Hong Kong, dan juga kisah-kisah revolusi, kita selalu bertemu dengan sang jagoan sebagai bagian yang bernyala-nyala dari bayang hitam kebengisan. Dalam sejarah, yang hitam itu pun bergerak seakan-akan menjadi sublim. Para anggota kasta kesatria—sebagaimana halnya para samurai dalam sejarah Jepang dan para pangeran dalam Mahabharata—menampilkan yang hitam itu sebagai sesuatu yang dalam, khas dan tak tertembus. Di baliknya adalah kepiawaian yang bermula dari membunuh. Kepiawaian menguasai.
Ada seorang sastrawan Jerman yang bergabung dengan tentara Hitler yang melukiskan dengan memukau bagaimana seorang desertir dihukum mati oleh regu tembak di sebuah hutan di Prancis. Saya kutip dari sumber kedua: Sebentang tanah terbuka di antara pepohonan. Daun-daun musim semi berkilau karena hujan. Batang pohon, tempat orang terhukum itu disandarkan, tampak berlubang-lubang oleh peluru yang ditembakkan oleh regu-regu hukuman dalam eksekusi sebelumnya. Ada dua kelompok bekas peluru: satu buat kepala dan satu buat dada. Tak begitu jelas berapa orang pernah mati di sini. Di dalam lubang itu beberapa ekor lalat yang menyukai daging busuk tampak tertidur.
Kemudian datang rombongan itu: dua kendaraan militer. Si calon korban. Para penjaga. Penggali kubur. Perwira medis. Seorang pastor. Sebuah peti mati putih dari kayu murahan. Hukuman itu -- dengan wajahnya yang tampan. Matanya lebar, dan di rautnya ada sesuatu yang kekanak-kanakan. Ia mengenakan celana abu-abu yang mahal dan baju sutera. Ada lalat melintasi wajahnya, dan bertengger di kupingnya. Penutup mata dipasang. Sebuah salib dibawakan. Lalu sang perwira medis menyematkan sebuah kartu merah di dada si terhukum, sebesar kartu remi. Para prajurit bersiap, membidik. Tembakan salvo. Lima lubang hitam tampak di kartu merah itu, seperti tetesan hujan. Tubuh itu berkelojot, sebentar. Lalu penjaga kemudian datang, mengelap borgol yang tadi di tangan terhukum itu dengan saputangan dari kain sifon. Seekor lalat menari di antara cahaya matahari...
Sebuah reportase yang memukau. Tetapi dengan itu ia juga memualkan: di dalamnya ada cukup detail, mengagumkan sekali, tetapi detail itu dipaparkan dengan sikap memandang kekejaman itu dengan keasyikan seorang "aesthete".
Fasisme (di Jerman dan di mana saja) memualkan kita karena para ideolognya menulis tentang kekerasan sebagai peristiwa estetis. Kekerasan bahkan diangkat sebagai kemestian yang luhur manusia. Tetapi tak cuma itu. Fasisme mengerikan karena baginya "manusia" adalah sebuah pengertian yang tidak inklusif: ada mereka yang layak disebut "manusia" (yakni "Kita") dan ada yang tidak (yakni "Mereka"), dan ada beda hakiki di antara keduanya. Di sini kekerasan adalah bagian dari latihan agung Manusia mengalahkan "Mereka"—seperti dalam sport para juara menaklukkan gunung karang dan dalam avontur sang penjelajah mengalahkan puak-puak orang hitam. Menguasai "yang-bukan-kita".
Tapi fasisme tak hidup sendiri. Kekerasan dapat menjadi halal dalam sebuah ekspresi yang sama sekali tak elegan: sebagai bagian lumrah dari proses menguasai dan dikuasai. "Kekuasaan itu tumbuh dari laras bedil"—sebuah ucapan Mao Zhedong yang terkenal—merumuskan bagaimana ruang yang terbatas dan sumber yang langka tidak hanya melahirkan ekonomi, tetapi juga destruksi. Ketika setiap orang merupakan unsur yang dianggap "berlebihan" bagi orang lain, maka yang "berlebihan" itu harus tidak ada.
Argumen ini—pikiran Sartre dapat ditafsirkan seperti itu—tentu tak melihat perbedaan besar antara kekuasaan dan kekerasan, antara ekonomi dan perang, antara kelangkaan dan putus asa. Sebaris panjang orang yang antre beras dalam sebuah krisis pangan memang terdiri dari orang-orang yang tak mengharapkan adanya orang lain di tempat itu, di saat itu. Tapi tak ada konsekuensi yang lurus ketika kita mengatakan "sayang ada orang lain" dan mengambil bedil untuk—kalau perlu—membunuh seorang orang lain. Sebuah catatan kaki dalam Reflections on Violence Hannah Arendt: "Ada satu jarak yang amat jauh yang harus ditempuh, dari sikap 'menafikan [orang lain]' secara teoretis sampai ketika seseorang yang berakal sehat memutuskan untuk membunuh, menyiksa, memperbudak".
Namun -- demikianlah Arendt akan dibantah -- kita juga punya kemarahan yang meledak. Amarah ini memang bisa membenarkan kekerasan, dan orang ramai-ramai bisa ikut teriak "Joss!", sebuah sorak untuk keberanian mengacungkan tinju. Tapi kemarahan itu tak memerlukan argumen filsafat, meskipun orang bisa datang dengan dalil agama. Kemarahan tak pernah bisa jadi kepastian tentang sesuatu yang mutlak. "Kita memuji orang yang marah atas dasar yang benar, kepada orang yang tepat, pada saat yang kena, dan dalam jangka waktu yang pas". Ini kita pinjam dari Aristoteles, nun jauh di luar abad ke-20, di luar Ambon.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini