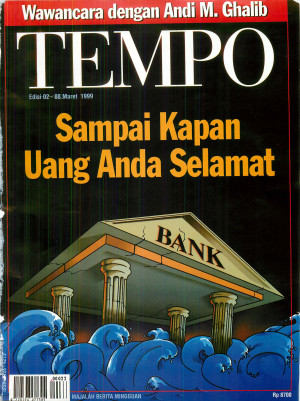Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
| The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World | ||
| Penulis | : | Benedict Anderson |
| Penerbit | : | Verso, London dan New York, 1998 |
| Tebal | : | 374 + x halaman |
Pada 1983, Ben Anderson menulis buku tentang nasionalisme yang kini hampir klasik, Imagined Communities. Dalam buku tersebut, Anderson menyatakan bahwa nasionalisme lahir bukan atas dasar ras, agama, atau daerah, melainkan karena dibayangkan. Bangsa adalah komunitas yang dibayangkan karena pada dasarnya anggotanya tidak mengenal satu sama lain, tapi dalam benak masing-masing ada bayangan mengenai keterkaitan mereka sebagai comradeship, persaudaraan yang horizontal dan mendalam. Imajinasi ini hadir karena adanya pemahaman tentang waktu homogen dan kosong (homogeneous, empty time), yang diukur dengan jam dan kalender.
Tesis tentang nasionalisme itu tampaknya masih dipertahankan Ben Anderson sampai kini, setidaknya seperti terlihat dalam buku terbarunya yang terbit pada akhir 1998. Buku ini merupakan kumpulan tulisannya yang merangkum dua tema pokok: nasionalisme dan Asia Tenggara. Lima esai tentang nasionalisme dalam buku tersebut menunjukkan bagaimana Anderson mempertegas tesis Imagined Communities dengan memperluas cakupan temanya, seperti soal dua model identitas modern dan posisi eksil (exile) dalam nasionalisme di era kapitalisme global.
Ketika membicarakan pembentukan identitas pada masa modern (dalam esai Nationalism, Identity and Logic of Seriality), profesor international studies dari Cornell ini tetap menekankan pentingnya surat kabar yang bisa membawa kondisi keserentakan dalam pembentukan imajinasi tentang identitas tak terbatas.
Lihatlah Hadji Misbach, seorang haji komunis, yang tidak merasa dirinya sebagai bagian dari kosmos Jawa, tapi bagian dari identitas revolusioner, kesadaran ''zaman bergerak" (age in motion) yang berada dalam satu rangkaian arus perubahan dunia. Ini terjadi pada 1920, ketika ia berpidato di depan rapat akbar di Delanggu, kota kecil di pelosok Jawa, tentang apa yang ia sebut sebagai djaman balik boeono (revolusi) dengan merujuk, lewat surat kabar, peristiwa tumbangnya monarki oleh kaum Republik di Oostenrijk (Austro-Hungaria). Lewat surat kabar, Hadji Misbach yang Delanggu membayangkan dirinya berada dalam keserentakan dengan kaum Republik Austro-Hungaria.
Identitas tak terbatas dan tak terikat ala Hadji Misbach ini, menurut Anderson, berlawanan dengan identitas satunya yang cenderung terbatas dan menyempit, yang juga kreasi modernitas. Inilah jenis identitas yang dibentuk oleh sensus dan pemetaan, yang berpikir dalam kategori numerik, dan melupakan adanya pecahan dan keragaman. Di sini identitas dikhayalkan sebagai sesuatu yang utuh, anonim, dan total. Contohnya adalah identitas berdasarkan etnisitas. Kategori mayoritas-minoritas dalam nomenklatur politik pada dasarnya adalah ciptaan identitas berwatak sensus macam ini.
Sementara itu, dalam esai Long Distance Nationalism, Anderson membicarakan nasionalisme dalam konteks kapitalisme global, di mana peran kaum eksil sangat menentukan. Agaknya bahasan ini menegaskan, selain kapitalisme cetak, kapitalisme transportasi yang memungkinkan rangkaian migrasi besar-besaran sejak abad ke-16 sampai kini harus dihitung tatkala berbicara tentang nasionalisme. Menurut Anderson, saat ini eksil politik bisa memainkan peran signifikan sebagai nasionalis jarak jauh karena, di satu sisi, ia ''bebas" dari negaranya: tidak membayar pajak dan tidak disiksa atau dipenjarakan rezim; tapi, di sisi lain, sebagai kelompok yang cukup mapan di Dunia Pertama, ia bisa mengirimkan uang, senjata, dan pamflet serta membangun sirkuit komunikasi internasional untuk ''mengobok-obok" negaranya.
Seperti sudah disebutkan, selain menyajikan tema nasionalisme, buku ini menampung tulisan Anderson tentang Asia Tenggara. Di sini lagi-lagi kita akan menemukan sosok spesialis ahli Asia Tenggara plus. Ia bukan saja poliglot (mahir dalam berbagai bahasa), tapi juga esais yang menulis dengan bahasa yang evokatif dan bertenaga tentang pelbagai wilayah Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, dan Filipina) dengan alur pikiran yang sering mengejutkan.
Tanpa kikuk dan kagok, ia bisa berpindah dari satu tema atau area ke yang lainnya dengan daya pikat yang sama. Hal inilah yang membuat dia tidak ''habis" tatkala pada 1972 ditangkal ke Indonesia karena tulisannya dalam Cornell Papers tentang G30S/PKI. Segera saja ia mendalami studi Thailand dan mulai melihat Indonesia tidak lagi dari lapangan, tapi dari naskah-naskah kuno. Dan di sinilah justru teruji tingkat erudisi sarjana yang lahir di Cina dan sampai kini tetap berkebangsaan Irlandia ini.
Dalam Professional Dreams, misalnya, Anderson menunjukkan aspek ''heterodoks" dan ''radikal" dalam budaya Jawa, dengan menelaah Serat Centhini (abad ke-18) yang menggambarkan sodomi dan Suluk Gatholoco (abad ke-19) yang menjadikan penis yang beronani sebagai sang hero dalam kisah ini (gatho: penis, ngloco: onani). Penis ini digambarkan jelek, bau, suka berdebat dengan tokoh agama, dan suka mengisap opium. Anderson menganggap Centhini dan Gatholoco sebagai ungkapan utopia fantasmagoria khas Jawa (fantasmagoria adalah istilah dari Walter Benjamin yang artinya ''suasana seperti mimpi"). Fantasmagoria ini, dalam bacaan Anderson—meminjam analisis Ann Kumar—mencerminkan adanya antagonisme kalangan seni dan budaya terhadap kelas bangsawan yang berkedudukan tinggi tapi tak menghasilkan apa-apa.
Dalam kesempatan lain, ketika menulis politik Thailand, Anderson secara mengejutkan mengaitkan pembunuhan politik di Thailand pada 1980-an dengan transformasi politik dari kediktatoran birokrat-militer menuju sistem politik parlementer borjuis yang lebih stabil. Sistem parlementer adalah sistem yang paling cocok dengan kepentingan borjuasi baru di Thailand sehingga untuk memperoleh kursi diperlukan segala daya dan dana. Pembunuhan-pembunuhan politik yang dilakukan demi memenangi kursi parlemen, seperti yang diduga dilakukan oleh Kamnan Poh menjelang pemilihannya sebagai Wali Kota Saensuk, adalah indikasi pentingnya arti parlemen dalam politik Thailand.
Karena menggeluti pelbagai wilayah dan tema, tak ada salahnya jika perspektif Anderson acap kali mendedahkan suatu ''mambang perbandingan" (spectre of comparisons). Istilah yang lantas menjadi judul buku ini dia pinjam dari ungkapan Jose Rizal, el demonio de las comparaciones, dalam novel nasionalisnya, Noli Me Tangere. Mambang perbandingan itu sendiri dalam pengalaman Anderson bermula pada 1963 ketika ia terperanjat mendengar Soekarno mengagumi Hitler—bukan sebagai Hitler yang fasis, anti-Semit, atau pembantai, melainkan sebagai nasionalis yang mampu menggerakkan Jerman membangun keagungan Third Reich. Sebagai orang Eropa yang melihat kejahatan Hitler secara taken for granted, ia menjadi pening oleh pujian Soekarno terhadap sikap nasionalis Hitler. Ia seperti dipaksa melihat Hitler dengan teleskop terbalik. Dan pandangan teleskop terbalik yang selalu menghantuinya bertahun-tahun setelah itu merupakan momen yang mengilhami cara pandangnya kemudian yang juga dihantui mambang perbandingan.
Kritik kecil terhadap buku ini: tak ada tulisan Anderson yang berisi tanggapan baliknya atas kritik dan komentar sarjana lain, misalnya Ernest Gellner, Partha Cattherjee, dan Homi Bhaba, terhadap tesis nasionalismenya. Kita tidak tahu bagaimana Anderson mempertahankan tesisnya. Tapi, bagaimanapun, meski tidak semonumental Imagined Communities, buku The Spectre of Comparisons tetaplah karya berharga untuk studi nasionalisme dan Asia Tenggara.
Ahmad Sahal
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo