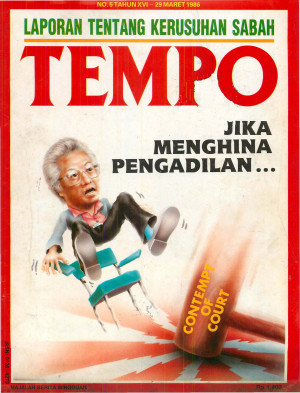TAK banyak orang seperti Takdir Alisjahbana. Dalam usia 78, dia bukan saja memastikan diri sebagai eminence grise, sang empu berambut putih, dalam kalangan kebudayaan Indonesia. Takdir, yang lama dikenal dalam buku pelajaran anak-anak sekolah sebagai pelopor kesusastraan modern Indonesia tahun 30-an, juga ternyata masih tetap jadi tokoh sentral, di pentas perdebatan yang dimulainya ketika ia baru berusia 27 tahun dulu. Dengan rambut yang seluruhnya sudah jadi uban, tapi dengan wajah bersih dan pikiran yang runtut, pemikir, penyair dan novelis itu pekan lalu masih tahan untuk tiap kali muncul dalam sebuah pertemuan tiga hari yang tampak istimewa di Jakarta. Ini pertemuan sastrawan yang secara periodik diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki oleh Dewan Kesenian Jakarta, dan umumnya dihadiri sastrawan dari banyak kota di Indonesia. Tapi kali ini, temanya lain dari yang lain, bahkan layak dicatat: meninjau kembali apa yang disebut Polemik Kebudayaan, yang dimuat di pelbagai media Indonesia di antara tahun 1935 dan 1939. Polemik itu berjangkit setelah S. Takdir Alisjahbana, waktu itu pemimpin majalah Poedjangga Baroe, menulis sebuah tulisan di berkala kebudayaan yang cuma beroplah sekitar 3.000 itu. Judulnya, Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru. Dengan gaya retorika Takdir yang khas -- terang, berapi-api, dan ditutup dengan kalimat yang berkibar seperti bendera perang tulisan itu mencoba membongkar apa sebenarnya yang disebut "Indonesia". Bagi Takdir, pengertian "Indonesia" berkaitan erat dengan semangat "keindonesiaan", dan semangat itu "adalah ciptaan abad kedua puluh". Zaman Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, Borobudur, dan Hang Tuah belum mencerminkan semangat "keindonesiaan" itu. Bahkan, kata Takdir, buku Hang Tuah menurut pengertian sekarang "dapat diartikan anti Indonesia," karena mengandung penghinaan terhadap satu bagian dari lingkungan kepulauan ini. Zaman Hang Tuah seperti itu, kata Takdir, adalah zaman "prae-Indonesia". Dengan istilahnya yang mengejutkan, Takdir malah menyebutnya sebagai "zaman jahiliah keindonesiaan". Maka, baginya, kemauan bersatu menjadi Indonesia tidaklah berurat-berakar di masa silam. Tapi pada harapan untuk sederajat dengan bangsa lain kelak di kemudian hari. Orientasi ke masa depan itulah yang kemudian membawa Takdir ke kesimpulan lain: "sekarang ini tiba waktunya kita mengarahkan mata kita ke Barat". Sebab, kata Takdir, "semangat keindonesiaan yang menghidupkan kembali masyarakat bangsa kita yang berabad-abad selaku mati ini, pada hakikatnya kita peroleh dari Barat". Takdir menunjuk contohnya: lahirnya Budi Utomo. Bahkan perkataan "Indonesia" itu sendiri "kita peroleh dari bangsa Barat" . Posisi Takdir yang seperti itu, dan caranya mengungkapkan yang polemis, memang segera menimbulkan reaksi. Yang pertama dari Penyair Sanusi Pane, seorang pengikut teosofi dan pengagum warisan kebudayaan India. Kemudian oleh Poerbatjaraka, ahli terkemuka kesusastraan Jawa. Dengan gembira Takdir, yang menyingkat namanya jadi S.T.A., membalas. Bahkan ia juga menyerang orang lain. Khususnya mereka yang berbicara dalam kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia di tahun 1935. Di sini ia terutama dihadapi oleh tokoh pergerakan nasional, Dokter Sutomo, orang yang 20 tahun lebih tua. Takdir memang orang termuda yang terlibat dalam pelbagai debat yang kemudian dikumpulkan dalam buku Polemik Kebudayaan oleh Achdiat Kartamihardja di tahun 1948 itu. Baik Penyair dan Kritikus Ajip Rosidi maupun Subagio Sastrowardoyo menilai bahwa dari segi pandangan sebenarnya S.T.A. tak istimewa. Ajip, dalam tulisannya di tahun 1982, menilai Takdir 50 tahun yang lalu itu hanya sebagai "seorang muda yang bersemangat, walaupun pandangannya masih terbatas". Menurut Subagio, dalam sebuah makalah yang terlengkap yang meninjau kembali polemik itu pada pertemuan sastrawan pekan lalu itu, sebenarnya Takdir dalam debat itu "hanya menang dalam kefasihan berbahasa Indonesia dan kegigihan berargumentasi". Tapi Subagio toh menganggap: Anehnya, justru ide-ide Takdir itulah yang "mencengkamkan pengaruhnya yang begitu mendalam" pada kehidupan generasi zaman revolusi dan dasawarsa pertama zaman merdeka. Subagio misalnya mencatat bahwa 'sikap budaya' Takdir itu -- dengan "tarikan emosional yang lebih kuat ke kebudayaan Barat" -- tampak pada para sastrawan yang kemudian disebut "Angkatan '45", dengan tokoh seperti Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rivai Apin. Bahkan juga pada Penyair Sitor Situmorang, meskipun kemudian tokoh ini dikenal sebagai orang nasionalis. Pikiran S.T.A. juga "akrab" dengan sikap tokoh politik yang terkenal, Sutan Sjahrir, pemimpin PSI (Partai Sosialis Indonesia). Subagio malah menunjukkan: sikap budaya seperti yang dibawakan Takdir erat kaitannya dengan partai itu. Maka, orang pun rada heboh. PSI, yang dilarang oleh Presiden Soekarno di tahun 1960, sudah lama jadi kata yang tak begitu enak -- meskipun di awal kemerdekaan pengaruhnya memang besar di kalangan intelektual Indonesia. Orang di luarnya biasa menganggap PSI sebagai kelompok kecil politisi yang omong Belanda, pintar tapi congkak, gemar diskusi tapi tak bisa menggerakkan rakyat. Anehnya, ia tetap dipandang berat. Bahkan', setelah ternyata kalah dan jadi partai keeil dalam pemilu 1955, PSI sering dicap sebagai kekuatan "di belakang layar". Tuduhan seperti ini terus juga sampai Peristiwa 15 Januari 1974 -- hingga orang yang dicap "PSI" sering merasa seperti kena cap buruk. Tak heran bila dalam pertemuan sastrawan itu ucapan Subagio ditanggapi ramai ketika ia menyebut beberapa nama sebagai budayawan yang "simpati batinnya amat dekat dengan PSI". Misalnya Mochtar Lubis. "Bisa dicek ke Kopkamtib benarkah saya anggota PSI," Mochtar membantah, setengah mengejek. Mochtar Lubis, novelis dan wartawan yang dulu memimpin harian Indonesia Raya itu, memang bukan anggota PSI. Tapi agaknya yang dimaksud Subagio sebagai "PSI" bukanlah persis organisasinya, melainkan semacam "subkultur", sikap dan pandangan tentang pelbagai soal kebudayaan dan kemasyarakatan, yang ada ditemukan di kalangan cendekiawan, khususnya di kota-kota besar Indonesia. Toh Subagio sendiri tampak mempertajam kaitan politik itu. Menurut penyair dan kritikus ini, "daya hidup dan kekuatan" sikap budaya yang dirumuskan Takdir Alisjahbana "bertumpu" pada "daya hidup PSI sebagai partai politik." Bukti: ketika PSI dibubarkan Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI, tampak "pengaruh ide-ide budaya Takdir Alisjahbana" menyusut. Sejak itu, kata Subagio, kecenderungan kalangan kebudayaan ialah "menggali nilai-nilai lama dalam kebudayaan tradisional". Ini terutama tercermin dalam kalangan sastrawan yang dimaklumkan oleh Ajip Rosidi di tahun 1960. Dan Subagio mungkin bisa menambahkan. bahwa di tahun-tahun itu pula orang berseru "USDEK", yang antara lain mengandung semboyan untuk memegang teguh "kepribadian" dan kebudayaan nasional". Tampaknya memang suatu ide atau sikap budaya bisa hidup subur karena suatu tumpuan politik, tapi Subagio pun bisa dibantah dalam menyederhanakan soal ini. Sebab, bisa juga dibuktikan: sikap budaya ala S.T.A., yang memandang Barat dengan simpati, sama sekali tidak bergantung pada ada tidaknya PSI. Sikap itu umum terdapat di kalangan cendekiawan Asia. Sikap itu juga masih terasa pada generasi cendekiawan Indonesia sekarang, yang sangat jauh sentuhannya dengan dunia politlik tahun 50-an, bila mereka berbicara tentang hak asasi, pemerataan sosial, kebersihan pemerintahan, ekonomi, teknologi, pendidikan, seni desain. Seperti terungkap dalam suara Takdir sendiri sejak tahun 30-an dulu itu, banyak orang di Asia merasakan dengan akut ketertinggalannya dari Eropa dan Amerika Serikat, alias "Barat". Bahkan tak jarang yang merasakan bahwa "Timur" yang dianggap menenteramkan ternyata tak kalah mencemaskan. Dalam makalahnya, Asrul Sani mengungkapkan kenyataan itu dengan tajam: ternyata, "Timur yang selalu diagungagungkan klni tampak dalam sosoknya yang paling kejam dan jahat". Ia berbicara tentang masa setelah penjajahan Jepang, tapi ia juga bisa bicara tentang masa yang lain. Mungkin itulah sebabnya tidak teramat aneh, bila sikap budaya ala Takdir bukan hak cipta S.T.A. seorang -- dan akan ada terus, dengan atau sonder PSI. Di kutub lain kecemasan akan "Barat", dan keinginan untuk mendapatkan jalan yang cocok buat diri bangsa sendiri, juga akan terus tampak, dengan atau sonder USDEK. Orang masih ingat bagaimana belum lama ini Gubernur Jawa Tengah Ismail merombak sebuah bangunan rumah sakit yang sudah memakai model pilar Yunani dengan bentuk joglo. Dalam prosesnya yang nyata nanti, kedua sikap budaya itu (dan mungkin tak cuma kedua itu saja) akan ikut sama-sama bekerja. Sastrawan dan ahli ilmu sosial Umar Kayam melukiskan proses itu dalam makalahnya pekan lalu sebagai "proses yang penuh dengan suasana tarik tambang, konfrontasi, akan tetapi juga berbagai kompromi, saling mengisi". Suatu mosaik yang terdiri dari berbagai unsur, suatu "proses yang akan lama". Polemik tahun 30-an, seperti dikatakan Umar Kayam, tentu belum membayangkan rumitnya praktek penjadian kebudayaan itu. Indonesia, sebagai wadah yang merdeka, yang semakin memungkinkan pelbagai unsur sosial-budaya untuk tampil, bahkan belum lahir. Di satu sisi, dunia "Barat" belum sedekat sekarang kehadirannya. Di sisi lain, dunia tradisi belum terbukti punya kekuatan bertahan dan lahir kembali seperti di hari ini. Tahun 30-an tentu belum cukup punya bahan untuk melihat bahwa kebudayaan daerah, misalnya, ternyata dapat muncul dalam bentuk seperti sekarang -- yang oleh seorang peserta dari daerah, Mursal Esten, disebut "budaya Minangkabau plus minus, budaya Sunda plus minus" dan seterusnya. Walaupun anak-anak menyanyi rock dan merayakan Valentine Day. 50 tahun setelah tulisan Takdir Alisjahbana dalam Poedjangga Baroe, bahan tentu lebih cukup untuk tak sekadar mengulang sebuah polemik lama. Pertemuan sastrawan pekan lalu itu tampaknya akan jadi bahan bertolak ke sebuah pembicaraan, suatu hari kelak, dengan bahan-bahan baru, bukan sekadar gagasan garis besar dan omongan cemplang-cemplung. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini