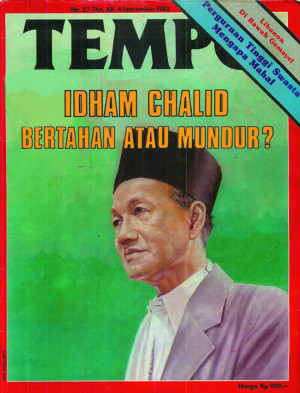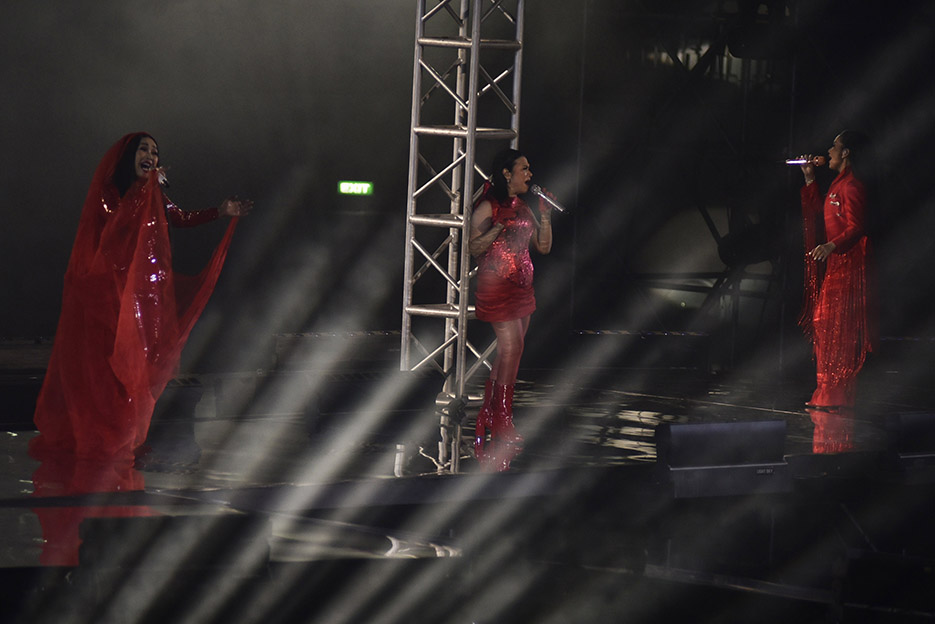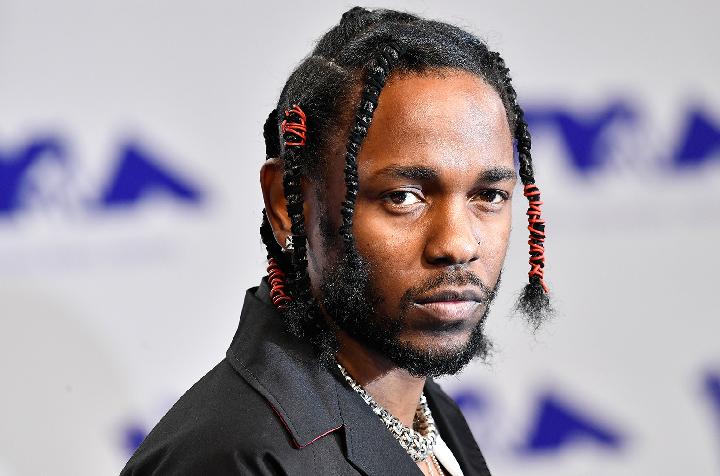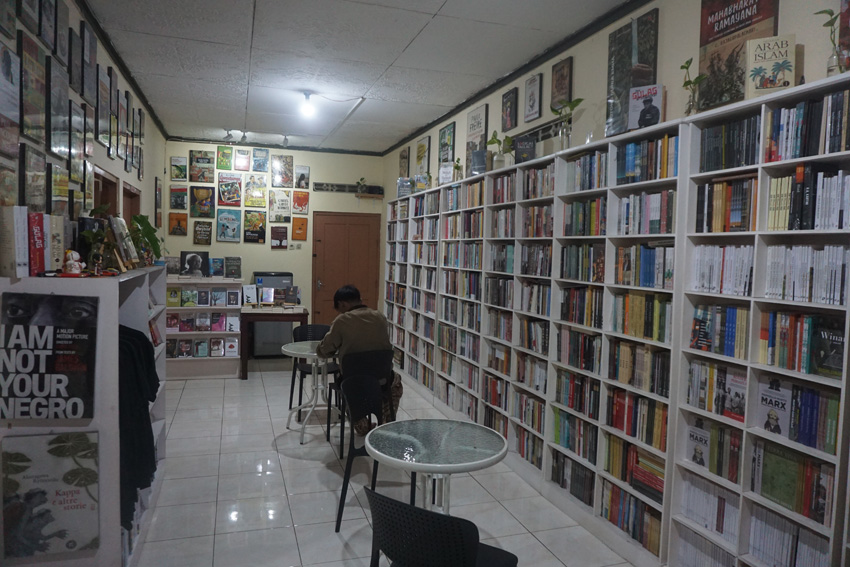THE ROAD TO POWER: INDONESIAN MILITARY POLITICS, 1945-1967
Oleh: Ulf Sundhaussen
Penerbit: Oxford University Press, 1982. 274 halaman dengan Bab
Pengantar, Bibliografi dan Indeks.
PADA umumnya penelitian sosial yang membahas peranan politik
kaum militer (ABRI) di Indonesia dapat digolongkan ke dalam dua
kelompok utama, yakni kalangan 'tradisionalis' dan kalangan
'revisionis'. Kedua kelompok ini umumnya mengakui kekhasan
sejarah keterlibatan sosial-politik ABRI dan melihatnya dari
proses sejarah sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Mereka
menganggap bahwa keterlibatan sospol ini, yang lazim dikenal
sebagai Doktrin Dwifungsi ABRI, merupakan keunikan sejarah
sehingga pembahasan yang mereka lakukan umumnya bersifat
penjelasan belakangan (post-facto).
Adanya kesadaran sejarah ini membedakan para peneliti ini dari
pengamat awam, yang banyak diantaranya sudah apriori melihat
Dwifungsi ABRI sebagai pertanda gejala militeristis yang
seringkali dihubungkan dengan sumber latihan utamanya dulu,
yakni tentara pendudukan fasis Jepang, khususnya untuk perwira
yang berasal dari PETA.
Perbedaan utama antara kalangan 'tradisionalis' dan kalangan
'revisionis' adalah dalam menilai perkembangan pelaksanaan
fungsi sospol itu sendiri, sejak periode revolusi kemerdekaan
sampai kini, yang ditandai oleh dominasi ABRI dalam politik
Indonesia. Kalangan 'tradisionalis', seperti halnya Ulf
Sundhaussen ini mencoba mencari jawaban, menyimpulkan bahwa
kegagalan sistem politik sipil sebelumnya telah memaksa ABRI
mengambil alih kemudi politik negara. Hal ini dijelaskan secara
terperinci oleh sarjana Australia asal Jerman ini dengan
periodisasi sejarah yang teratur, yakni periode munculnya
kerangka politik (1945-1949) periode cobaan (195()-1958)
periode akomodasi politik (1957-1962) periode konfrontasi
(1962-1965) dan periode pengambilalihan (1966-1967).
Kalangan 'revisionis' umumnya berpijak lebih luas daripada
sekedar menyalahkan politisi sipil yang gagal, dalam melihat
munculnya ABRI sebagai kekuatan politik yang dominan di
Indonesia. Pertanyaan dasarnya adalah bukan lagi "mengapa ABRI
menjadi dominan" tapi sudah melangkah menjadi semacam ramalan
"mengapa ABRI akan tetap dominan". Jawabannya tentu tidak bisa
lagi menyalahkan politisi sipil zaman 1950-an, tapi dengan
menghubungkannya dengan sistem politik ekonomi secara
keseluruhan, misalnya dengan mengembangkan teori "kepentingan
korporasi" yang banyak dipakai dalam membahas peranan politik
kaum militer di negara Dunia Ketiga sekarang. Pandangan ini
misalnya dianut oleh Harold Crouch, sama-sama jebolan
Universitas Monash (Australia) dengan Ulf Sundhaussen, dalam
bukunya yang diterbitkan Cornell University Press tahun 1978,
The Army and Politics in Indonesia, yang membahas periode
post-1966.
Dengan penelitian historisnya, Ulf Sundhaussen banyak
mengemukakan akar problem yang menyebabkan munculnya ABRI
sebagai kekuatan politik terkuat di Indonesia sekarang. Salah
satu masalah pokok adalah usaha pemerintahan sipil tahun 1945
sampai 1948 untuk mengontrol kekuatan militer (NI). Tokoh utama
di belakang usaha ini adalah Amir Sjarifuddin, baik sebagai
Menteri Keamanan dalam kabinet Sjahrir I maupun sebagai Perdana
Menteri dua kabinet RI setelah Sjahrir.
Amir mengecam pimpinan TNI (waktu itu bernama TKR dan diubah
menjadi TRI sebelum diresmikan sebagai TNI), baik yang berasal
dari PETA maupun eks KNIL dan berusaha menandinginya dengan
membentuk TNI Masyarakat yang berasal dari laskar. Pada Februari
1946 Amir membentuk embrio dari komisaris politik gaya partai
Marxis, yakni dengan didirikannya Staf Pendidikan, yang
membawahkan Pendidikan Politik Tentara (Pepolit). Pepolit inilah
yang memiliki Opsir Politik (Komisar Politik), yang semuanya
diambil dari Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) pimpinan Amir
sendiri. Tiap divisi TRI memiliki 5 Opsir Politik, yang memiliki
jalur khusus ke Menteri Keamanan.
Pertentangan dengan segera timbul antara komandan di lapangan
dengan Opsir Politik ini, seperti kasus almarhum Letjen Gatot
Soebroto, yang bahkan melarang penempatan Opsir Politik itu di
kesatuannya. Timbulnya 'Peristiwa Madiun' (September 1948), yang
dipelopori oleh Front Demokrasi Rakyat pimpinan Amir
Sjarifuddin, dan bertahannya TNI sebagai kekuatan utama RI
memimpin perang gerilya setelah Aksi Militer II (Belanda)
Desember 1948, merupakan titik balik yang penting dari
konseptualisasi peranan sospol ABRI di Indonesia. Dapatlah
dikatakan, bahwa usaha memencilkan ABRI dari peranan politik
setelah 1950 mencerminkan kurang tanggapnya politisi sipil
terhadap peristiwa sejarah pada masa 1946-1950, khususnya
persepsi sebagai 'penyelamat bangsa' dari ABRI selama perang
gerilya menyusul Aksi Militer II.
Inilah sebenarnya akar sejarah dari berbagai peristiwa tahun
1950-an, yang ditandai oleh peranan politik ABRI sebagai
'kekuatan penekan' terhadap berbagai pemerintahan sipil. Ada
tiga hal yang sangat peka bagi kalangan perwira TNI/ABRI:
þ diangkatnya politisi sipil sebagai Menteri Pertahanan (dengan
pengecualian Sultan Hamengku Buwono IX, yang dalam pemilihan
tahun 1946 justru menjadi favorit perwiraperwira TKR), khususnya
Iwa Kusumasumantri.
þ ide pembentukan kekuatan militer lain diluar ABRI, misalnya ide
Angkatan Kelima dari PKI pada tahun 1964 dan awal 1965.
þ ide masuknya kembali politisi sebagai Opsir Politik, seperti
halnya ide Nasakomisasi ABRI pada masa akhir Demokrasi
Terpimpin.
Dalam pelaksanaan doktrin Dwifungsi sekarang, ketiga hal itu
dianggap sudah selesai. Kalaupun ada kebutuhan karena
perkembangan zaman (misalnya tentang pemisahan jabatan Menhankam
dengan Panglima ABRI), maka hal itu sepenuhnya diserahkan pada
pihak ABRI menyelesaikannya sendiri.
Ulf Sundhaussen juga mengungkapkan komitmen sekelompok perwira
ABRI terhadap pembangunan ekonomi sesudah terciptanya
konsolidasi intern ABRI pada tahun 1960. Kelompok ini berpusat
di Seskoad Bandung, dengan almarhum l.etjen Suwarto memainkan
peranan sentral. Sebenarnya, pikiran mengenai pembangunan
ekonomi ini juga banyak didorong oleh Doktrin TNI/AD waktu itu,
yakni Pertahanan Rakyat Semesta, yang juga digodok oleh Seskoad
padatahun 1961.
Banyak tokoh militer yang hadir dalam penggodokan tersebut
kemudian menjadi pemegang kendali utama pemerintah Orde Baru,
seperti Presiden Soeharto, Darjatmo (Ketua DPR/MPR), Sudirman
dan Sutopo Jowono (Gubernur Lemhanas) disamping yang sudah
meninggal seperti S. Soekowati dan Sarbini. Tidaklah
mengherankan bahwa pemerintah Orde Baru menjadikan pembangunan
ekonomi sebagai salah satu ciri utama, yang membedakannya dari
pemerintah sebelumnya. Ini sekaligus memberikan legitimasi
(keabsahan) untuk Doktrin Dwifungsi ABRI yakni berusaha
menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi
bertahap. Sayangnya, dalam uraiannya mengenai hal ini, Ulf
Sundhaussen tidak secara jelas mengemukakan mengapa pembangunan
ekonomi tidak jalan waktu itu walaupun disebutnya juga bahwa
sekitar 80% budget negara dipakai untuk modernisasi ABRI.
Buku Sundhaussen juga kurang membahas peranan ABRI sebagai suatu
kekuatan birokrasi nasional yang terkuat. Untuk suatu negara
kesatuan yang begitu luas dan heterogen seperti Indonesia, ABRI
bolehlah dianggap sebagai kekuatan birokrasi nasional yang
pertama-tama yang mampu memiliki wilayah kontrol ke segala
penjuru tanah-air. Ini sebagian disebabkan oleh kepentingan
tugasnya untuk menyelesaikan masalah keamanan di berbagai tempat
dan sebagian karena konsolidasinya yang cepat dibandingkan
birokrasi sipil. Kemampuan ini menyebabkan ABRI tidak saja
berperanan pada tingkat nasional, tapi juga memiliki rentang
kendali yang kuat pada politik di tingkat paling bawah
(kelurahan).
HAL lain yang tidak diketengahkan oleh Sundhaussen adalah
munculnya "kepentingan korporasi" ABRI sebagai kekuatan
birokrasi dan hubungannya dengan peranan politik ABRI di
masa-masa sesudahnya. Pada akhir 1950-an dan khususnya pada masa
Demokrasi Terpimpin dan pra-30-S/PKI, biaya untuk operasi
politik banyak diperoleh dari perluasan kegiatan ABRI, misalnya
dalam perusahaan negara dan aktivitas ekonomi lainnya. Hal ini
belum dengan jelas dicakup dalam Doktrin Dwifungsi ABRI walaupun
sudah mulai dipikirkan dalam usaha pelestarian nilai '45.
Kiranya hal yang penting ini harus dirampungkan dulu oleh ABRI
generasi '45, sehingga ada pedoman yang jelas mengenai konsep
dan perilaku ekonomi. Masalah ini merupakan 'sisi lain' dari
pembangunan ekonomi, yakni bagaimana menciptakan konsistensi
antara "ideal" tentara revolusi dan alat perjuangan bangsa dari
ABRI denan pengaruh pembangunan ekonomi yang baru sekarang
dirasakan.
Hal lain yang perlu ditambahkan, dan yang belum dibahas
Sundhaussen, adalah pelembagaan kerjasama ABRI dengan kelompok
sipil. Hal ini sudah berlangsung, misalnya pada Golkar untuk
partisipasi politik. Yang belum jelas adalah tentang terciptanya
suatu mekanisme pengambilan keputusan politik yang melembaga,
dan sudah dicoba, sehingga pada saat kaum perwira (dan
purnawirawan) ABRI generasi '45 meninggalkan gelanggang politik
negara, mekanisme ini sudah tahan uji dan tidak ada "bom waktu"
untuk generasi berikutnya. Walaupun hal ini tidak dibahas oleh
Sundhaussen, bukunya telah memberikan perspektif sejarah yang
demikian luas, sehingga patut dibaca oleh publik politik pada
umumnya.
Burhan Magenda
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini