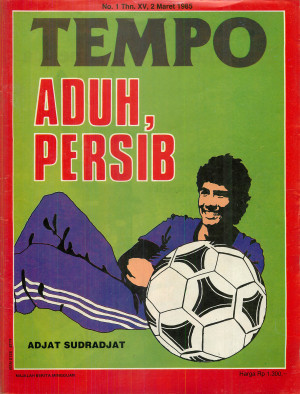AKU DALAM BUDAYA Oleh: Dr. Toeti Heraty Penerbit: PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1984, 250 halaman BUKU ini sama sekali bukan esei, catatan, atau kesaksian tentang suatu lingkungan budaya, seperti dikesankan judulnya. Aku dalam Budaya adalah sebuah studi ilmu filsafat - disertasi untuk memperoleh gelar doktor, yang dipertahankan Januari 1979 di Universitas Indonesia. Kendati terasa memancing, judul buku agaknya tak bisa lain. Judul itu memang menggambarkan seluruh isi yang merupakan studi sejumlah konsepsi "aku" dalam kaitannya dengan kenyataan dan lingkungan sekeliling yang dengan kata lain adalah "budaya". "Siapakah Aku?" Sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dalam filsafat, dan hampir semua pemikir dalam sejarah filsafat mengkajinya. Sejumlah di antaranya malah menjadikannya fokus seluruh pemikiran, misalnya eksistensialisme. Namun, Aku dalam Budaya, tak bisa dikatakan meneruskan tradisi ini. Ia lebih tepat dikatakan penelitian "aku" (term ini tak bisa digantikan dengan: individu ata- manusia) dalam filsafat modern Barat. Dalam ilmu filsafat, penelitian jenis ini barangkali terbilang langka - selain sebagai disertasi, bisa dipastikan ia harus orisinil dan satu-satunya. Dalam arti, hampir tak terbayangkan memperbandingkan berbagai prinsip "aku" pada sejumlah aliran filsafat. Sebab, semua "aku" itu mempunyai konotasi, tekanan, dan ekstensi yang berbeda-beda. Ada, misalnya yang diartikan "subyek" yang dipertautkan dengan "obyek". Ada yang berarti "individu". Dan ada pula yang dipertentangkan dengan konsepsi "nonaku". Tetapi ada pola pemikiran lain yang bisa membangun gagasan. Dalam perkembangan ilmu-ilmu filsafat, terdapat cabang, yaitu filsafat antropologl, yang memanfaatkan ilmu ilmu lainnya, khususnya biologi, psikologi, dan sosiologi. Nah, Aku dalam Budaya membangun tekanan penelitiannya ke dalam tubuh sejarah filsafat sendiri. Beberapa tekanannya, ontologi, fenomenologi, dan filsafat bahasa, yang dikenal pula sebagai filsafat analitik. Dalam menggali pemikiran-pemikiran pada sejarah filsafat, pengarang tidak terikat pada kronologi. Karena itu, satu hal pasu, Aku dalam Budaya bukan sejarah perkembangan pemikiran manusia tentang "aku". Studi yang ditempuh acak dan sangat selektif. Dengan demikian, terbuka alur bagi pengarang untuk menyorongkan semacam kesimpulan. Tapi patut dicatat, studi pemikiran-pemikiran yang merupakan tubuh karangan adalah bagian pokok, dan seperti layaknya disertasi, kesimpulan tidak utama. Pengarang mengawali permasalahannya bila kita mau memburu kesimpulannya dengan pemikiran - pemikiran Descartes, filosof abad ke-16, yang pertama kali mendefinisikan "jiwa". Tekanan pada pemikiran Descartes di satu sisi adalah "aku berpikir" (berasal dari kesadaran yang merupakan prinsip dasar ontologi) dan di sisi lain keterbatasan yang berpangkal pada Tuhan (harus dibedakan dari Tuhan pada filsafat transendental). Selanjutnya - masih dalam mengga1i ontologi - keterbatasan dipertentangkan dengan "kehendak" melalui pemikir lain, Maine de Brian. "Subyek" mulai berwujud. "Subyek" lalu menjadi nyata dengan meneliti fenomenologi. Dengan tekanan di antaranya buah pikiran Merleau Ponty, "subyek" sekaligus dikaitkan dengan "budaya". Hubungan keduanya adalah dunia "makna-makna" yang mendapat penjabarannya pada filsafat bahasa. Aliran filsafat ini (dengan tokoh-tokoh Bertrand Russel dan Wittgenstein) menekankan pemikiran pada kata-kata dalam bahasa yang memiliki arti relatif - yang dikenal sebagai kata-kata deiktik. Kaitannya adalah bahwa kata kata deiktik dan bahasa, yang sangat ditentukan oleh subyek kata "aku", adalah dunia simbol. Pada Bab IX, studi-studi pemikiran dijahit menjadi satu. Misalnya kehendak dengan prinsip kegagalan, ungkapan kekhilafan dalam bahasa mitik-simbolik dengan kesadaran religius di bawah judul "Aku Mitik". Dan pada Bab X, "Kesimpulan", digariskan tipis bahwa manusia pada dasarnya hidup di tengah mitos dan dunia simbol, di antaranya pesona teknologi dan konsumerisme. Yang barangkali menarik, seluruh kerangka berpikir pada buku ini seperti ingin mengesahkan prinsip "pribadi" dalam "fenomenologi Jawa" - kalau bisa dibilang begitu. Orang Jawa sering mengatakan, prinsip ini adalah pribadl yang sebenarnya, sementara pribadi pada masyarakat Barat adalah produk ancaman "non-aku". Namun, perjalanan ke Barat ini barangkali terlampau jauh. Seperti diutarakan Soedjatmoko pada Kata Pengantar, pendekatan filsafat Barat yang apriori sekuler terlampau sempit untuk mencapai situasi budaya seperti di Indonesia. Jim Supangkat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini