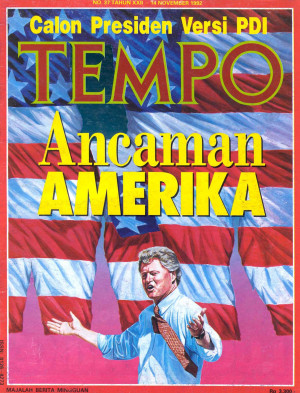MENUTUP Jakarta International Festival of the Performing Arts (JIFPA) ke-2 di Gedung Kesenian Jakarta, Jumat dua pekan lalu, Sukarji Sriman menampilkan The Circle of Bliss 2, garapan tari berdasarkan falsafah Jawa Cakrahayu atau Lingkaran Kebahagiaan. Karya sepanjang 40 menit ini dikembangkan dari The Circle 1 yang pernah tampil di forum Indonesian Dance Festival dan mendapat pujian kritikus tari New York, Anna Kisselgoff, ketika pentas perdana di American Dance Festival di Durham, North Carolina, AS. Ketika layar terangkat, empat penari wanita dan satu pria berdiri mematung membentuk siluet: seorang di sudut kanan belakang membelakangi penonton, yang lain berderet diagonal di kiri-depan menghadap penonton. Dari atas, layar belakang dibasuh tiga lampu: merah di kiri dan kanan, biru di tengah. Seiring dengan gaung musik elektro-akustik tatanan Moh. Ikhlas dan Donny Irawan, kelima penari bergerak perlahan. Mula-mula di tempat: merendah, tangan kanan menjangkau ke depan, tangan kiri ditekuk di depan dada. Tak lama mereka berpindah dengan langkah kecil meluncur cepat sesekali berhenti mematung dalam pose dan pengelompokan yang bervariasi: dua berhadapan dengan tiga, tiga rebah di lantai melintang di belakang, dua berdiri tegak di kanan-depan. Ketika musik menampilkan pukulan cepat dan ritmis pada metalofon, lampu menjadi benderang, dan gerak pun menjadi cepat dan ritmis pula. Suara, gerak, dan suasana saling mengisi. Biru temaram untuk adegan tiga penari empat hobo dan dua lampu jingga untuk tarian tunggal Deddy Pudja Indra. Akhirnya, kelima penari menghambur dari sisi kanan, empat jatuh terkapar, Deddy tinggal tegak. Lampu pun meredup ketika Deddy ngeloyor ke samping kanan. Kuintet 10 menit ini adalah Perjalanan Terakhir yang ditambahkan Sukarji di awal The Circle 1 yang 30 menit. Untuk ini, lorong tengah auditorium ditutupi kain putih pan jang menuju tengah pentas ke sebuah trap yang menempel di layar putih yang menjadi latar belakang panggung. Akibatnya, pentas dan auditorium terbelah simetris kiri dan kanan. Sementara pentas disiapkan, di silang tengah lorong penonton, Sukarji bergerak sangat perlahan di atas level. Dari kiri dan kanan, empat penari wanita mendekat perlahan dan membimbingnya ke depan. Dari belakang, lima penari wanita mengiring. Selama 25 menit, 13 penari wanita dan tiga pria merayu dan merintangi perjalanan Sukarji dengan tujuh macam cobaan: jasmani, akal, nafsu, suara hati, kegelapan, dialog dengan sukma sendiri, dan untuk "mati di dalam hidup". Sukarji mengalahkan semua rintangan. Pada akhir cerita, di tengah sunyi, dengan tenang dan pasti Sukarji menaiki tangga meninggalkan para penggodanya duduk tepekur di lantai pentas. Di tengah gumam penari yang menyarankan mantra, di puncak tangga, pada saat yang tepat, Sukarji melepas kain yang membelit tubuhnya dan menghilang di celah layar putih untuk menyatu dengan Tuhannya. Lampu redup dan penonton pun riuh bertepuk. Sukarji bekerja secara akumulatif. Ia menekuni satu karya dan secara kontinu mengembangkannya. Cara ini mengandung risiko dan membutuhkan waktu untuk mengendapkan rasa dan pengalaman. Akhirnya, jika Cakrahayu hendak dipadu dengan rasa Jawa, di tubuh para penari harus bersemayam rasa Jawa yang pekat: halus dan tanpa beban (sumeleh). Agaknya, pacu waktu di Jakarta kini mempersulit penari mengembangkan rasa dimaksud lewat renungan, kontemplasi, dan meditasi. Yang pantas dihargai, Sukarji telah menampilkan yang terbaik. JIFPA ke-2 yang berlangsung dari 5 September s/d 30 Oktober ini diisi oleh 13 grup mancanegara, 10 grup Nusantara, dan sebuah grup musik Indo-Belanda. Dari luar negeri terbagi menjadi: 9 grup musik, 3 tari, dan 3 teater, mewakili AS, Australia, Austria, Belanda, Jepang, Filipina, Korea, Jerman, Prancis, dan Kanada. Dari dalam negeri: 4 grup musik, 3 tari, dan 3 teater. Dari variasi program, tergambar kiblat JIFPA: musik dan Barat. Pemirsanya kelas menengah ke atas dan warga asing. Tak heran, beberapa "grup rakyat" yang diangkat kehilangan penonton lama dan belum berhasil meyakinkan penonton baru. Grup Teater Titian dan Sawung Jabo adalah dua contoh. Tiga penata tari Jakarta tampil: Tom Ibnur membuka festival, Boi G.S. pentas pamit untuk ke Hong Kong, dan Sukarji Sriman menutup festival. Tak sempat muncul nama beken seperti Sardono, Maruti, dan Gusmiati. Atau Arifin C. Noer, Rendra, Putu Wijaya, dan Riantiarno. Alasannya mudah ditebak: tak tersedianya dana. Tentu, tak semuanya negatif. Kita patut angkat topi kepada TEMPO dan Kompas yang penuh simpati patungan menopang Suita '92 yang menyuguhkan karya-karya musik eksperimental. Muncul beberapa pertanyaan: mungkinkah di masa datang JIFPA lebih banyak menampilkan grup Indonesia? Mungkinkah JIFPA menjadi forum kajian dan bandingan prestasi seniman-seniman kita sendiri? Jika tidak, lantas festival ini diadakan untuk siapa? Tetapi barangkali, ketika pariwisata semakin menjadi raja, kesenian memang harus menyesuaikan diri. Para seniman pun dituntut untuk belajar menjadi tuan rumah yang ramah: lebih memberikan ruang kepada para tamu dan menekan ambisi sendiri. Yang ini bukan Cakrahayu atawa Lingkaran Kebahagiaan, tetapi lingkaran setan. Sal Murgiyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini