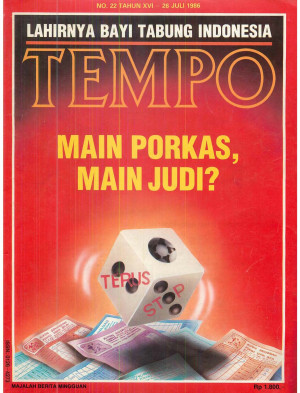PEMENTASAN baru dimulai kalau sudah ada lima orang penonton. Penonton yang kelima tak jarang baru muncul pukul 9 malam, jadi pertunjukan dimulai setelah pukul 9. Kalau sampai pukul 10 calon penonton baru empat atau kurang, pertunjukan dibatalkan, dan uang karcis dikembalikan. Pernah dengar sebuah grup hiburan dengan nasib sedih seperti itu? Itulah Wayang Orang Ngesti Pandowo, Semarang, di saat-saat akhir sebelum dilakukan perombakan yang, agaknya, layak menjadi suatu contoh. Sejak grup ini memperoleh pemimpin baru, pertengahan bulan lalu, gedung di tepi jalan protokol Kota Semarang itu bagai hidup kembali. Ngesti Pandowo, yang lahir di Alun-alun Madiun, Jawa Timur, 1937, dan menetap di Semarang sejak 1954, mulai pertengahan Juni yang lalu bernaung di bawah Yayasan Mekar Giri dari MKGR. Sehari setelah status baru itu, gebrakan dilakukan. Mashuri, 49, manajer pengganti, langsung memutuskan pertunjukan diciutkan dari lima menjadi hanya dua setengah jam. Dan sebelum anak wayang berpentas, panggung dibuat bising oleh grup band mahasiswa Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang. Yang diperdengarkan: lagu-lagu pop dan, malah, beberapa lagu rock. Penonton yang berjubel oleh publisitas yang gencar sebelumnya menyambutnya dengan keplok. Usai acara musik, barulah cerita wayang yang telah diperas itu dipergelarkan. Dan penonton tetap terpaku. "Ini upaya pelestarian juga. Kami harapkan tidak hanya orang tua yang paham kesenian tradisi. Orang muda pun perlu! Nah, untuk mengajak mereka mencintai, dibutuhkan teknik tersendiri," kata Mashuri. Sambil mencari-cari beberapa grup musik yang bisa diajak bekerja sama, setiap malam hiburan selingan berganti-ganti. Ada tari-tarian biasa, ada lawak, ada tari kreasi baru. "Tapi kami tidak meniru Srimulat, selalu dengan musik dari grup yang sama," ujar Mashuri. Tentang penyingkatan wayang orangnya sendiri, "itu tidak mengurangi kualitas dan plot cerita," ujar manajer yang pensiunan PJKA ini. Harap diingat juga, waktu bubar pertunjukan sangat penting. "Kalau pertunjukan baru selesai pukul 1 atau 2 dinihari, bagaimana anak-anak sekolah dan pegawai bisa nonton? 'Kan harus bekerja siang harinya?" Karena itu tontonan Ngesti Pandowo, di malam libur atau tidak, ditentukan selalu usai tepat pukul 11.00 malam. "Pada jam itu kendaraan umum dan bis kota masih banyak." Kemudian soal disiplin organisasi. Pertama, keluarga Ngesti diwajibkan mendaftar kembali, untuk mengetahui berapa sebenarnya pendukung wayang orang ini. Sudah 125 orang mendaftar ulang, sedang jumlah semuanya diperkirakan sekitar 150. Ternyata sebelum ini memang tak diketahui persis berapa jumlah anggota grup -- aneh juga. Kedua, pemain harus sudah datang ke tempat tontonan paling telat pukul 7 malam, dan mengisi daftar hadir. Setengah jam kemudian pergelaran mulai. "Biarpun pemain itu nantinya muncul pukul 10 malam, pukul 7 harus sudah ada di panggung," kata Mashuri lagi. Sebelum ini tak pernah ada disiplin seperti itu. Pemain yang akan muncul di pentas belakangan dengan tenang datang pukul 10 malam -- dengan alasan sudah hafal ceritanya, dan berhias juga bisa cepat. Bagaimana kalau ia, misalnya, tiba-tiba saja berhalangan hadir? Bisa repot -- kecuali kalau diingat bahwa seluruh bangunan wayang orang itu sendiri memang sudah begitu rapuh. "Sekarang ini rasanya seperti mendapat rumah baru," kata Kaning Tjiptosuwarno, 54, pemain yang biasa memerankan Betara Guru di grup ini. "Ada penonton atau tidak, kami tetap datang dan tetap main. Dulu, datang, tidak ada yang memuji tidak datang, tidak ada yang memarahi. Kalau datang dan main pun honornya tak pernah lebih dari Rp 250," tuturnya. Sekarang, setiap pemain mendapat minimum Rp 750 semalam, biarpun umpama tak ada penonton. Nyatanya, setiap pemain rata-rata mengantungi lebih dari Rp 2.000 tiap hari, karena penonton ternyata melimpah. Setiap malam rata-rata pengunjung mencapai 200 orang, dengan harga karcis Rp 500 sampai Rp 1.000. Jumat pekan lalu, ketika yang dipentaskan lakon ketoprak (setiap Selasa dan Jumat, acara tetap), separuh gedung yang berkapasitas seribu orang terisi. Kabarnya, malah, ketika band mahasiswa Untag muncul sebagai selingan, gedung penuh. "Saya bertekad mengembalikan Ngesti Pandowo ke masa jayanya seperti di tahun 1960-an," ujar Mashuri, seniman tari asli Semarang ini. Waktu itu, seperti dituturkan Suratno, 52, para anggota Ngesi tak perlu mcncari kerja tambahan di siang hari. "Kami cuma belajar menari, bahkan kursus bahasa Inggris. Anak para pemain disekolahkan. Penghasilan semalam cukup untuk membeli lima kilo beras," kata laki-laki yang sudah 44 tahun ikut Ngesti Pandowo ini. Kesuraman dimulai -- biasa, pada grup kesenian yang disebut tradisional -- ketika pemimpin dan sekaligus pendirinya, Ki Sastro Sabdho, meninggal pada 1967. "Sejak itu tak ada pemimpin yang berwibawa," tutur Kaning. Ki Narto Sabdho (almarhum) yang pernah mengambil alih kepemimpinan Ngesti, tak juga mampu mengembalikan kejayaan itu sampai akhir usia beliau. Tapi dapatkah jumlah penonton yang di atas ratusan orang itu dipertahankan? Mashuri optimistis. Setelah diriset (nah, riset pula), kebijaksanaan sekarang ini sudah menunjukkan cara pengelolaan masa kini: penonton sebenarnya bukan tak menyenangi wayang orang atau ketoprak, tetapi mendapat kesulitan menonton pertunjukan itu. Kesulitan angkutan. Kesulitan mengetahui jam pementasan. Kesulitan mengetahui cerita yang dimainkan. Dan lain-lain. Nah, "Resep perbaikannya 'kan hanya kerja keras dan disiplin?" kata Mashuri. Adapun mengenai selingan, baik tari-tarian maupun musik, resep itu sudah diuji hampir sebulan setengah ini dan nampaknya memberi harapan. Bahkan lebih memberi harapan, tampaknya, dibanding usaha tahun lalu untuk menaikkan jumlah penonton dengan memasukkan bintang-bintang populer. Gepeng, misalnya, memegang peran Petruk dalam wayang. Sitoresmi juga diseret ke dalam lakon ketoprak. Penonton memang membanjir tapi tidak seimbang dengan biaya (honor dan promosi, terutama), sehingga cara itu tidak bisa diandalkan. Cara lain lagi dilakukan di Surabaya oleh grup yang berbeda. Wayang Orang Sriwandowo, sejak beberapa saat setelah Ngesti di Semarang melakukan gebrakan. Memang, masih terbatas pada akal-akalan memasarkan karcis. "Sekarang karcis masuknya diundi," kata Ichsan, 52, sutradara grup yang bercokol di sekitar THR Surabaya ini. Yang menang undian berhak mendapat hadiah sementara ini mesin jahit, rantang, dan kompor. Sistem undian berhadiah ini sudah berlangsung sejak awal bulan ini. Memang, harga karcis jadi naik dua kali lipat -- dari Rp 500 dan Rp 750 menjadi Rp 1.000 dan Rp 1.500. Tapi penonton bertambah. "Rata-rata penontonnya 50 orang. Kemarin malah bisa 68," tutur Ichsan lagi, pekan lalu. Sebelumnya, nasib Sriwandono tak berbeda dengan Ngesti penonton sekitar sepuluh orang, dan sering grup itu tiba-tiba saja menutup kembali pintu masuk yang tadinya sudah dipentang. Putu Setia, Laporan Aries Margono (Ja-Teng) dan Biro Ja-Tim
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini