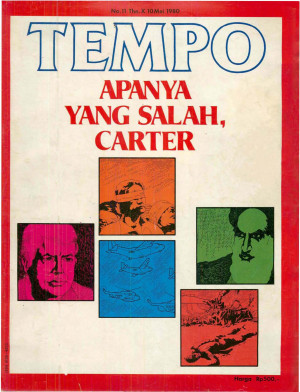LOS
Naskah dan sutradara: Putu Wijaya
Produksi: Teater Mandiri
HUKUMAN mati diketengahkan lagi. Sandiwara Putu Wijaya, Los, 23
April sampai 2 Mei di Taman Ismail Marzuki, pertama kali menarik
karena topik tersebut. Selama hampir dua jam pertunjukan itu
mengikat penonton di kursi dengan menampilkan seorang terhukum
mati yang sedang menunggu pelaksanaan tembak.
Jangan kuatir: si terhukum hanyalah boneka -- yang bukan main
besar, dua kali ukuran kita, terbuat dari sabut dan kapuk. Lagi
pula benda tercinta yang berkumis ini diceritakan terus-menerus
tidur sampai tontonan selesai -- sampai ia habis ditembak. Toh
proses menunggu eksekusi rupanya selalu mencekam.
Semula memang ada sangkaan sandiwara ini akan "mempersoalkan"
hukuman mati. Setidaknya, semangat pembelaan kepada kelompok
semacam HATI misalnya, terasa dari dikesankannya kebaikan (atau
keakraban dengan) si terhukum yang diceritakan sebagai bajingan
tengik itu. Ada juga sindirian kepada kebrutalan perlakuan
terhadap tahanan, di tempat "yang sekarang namanya lembaga
pemasyarakatan".
Massif dan Kelam
Tapi seperti dituturkan pengarangnya sendiri dalam folder,
setelah waktu berjalan lebih separuh menjadi jelas bahwa cerita
sebenarnya tidak penting lagi. Topik hukuman mati, termasuk
pro-kontranya, hanyalah diambil sebagai bahan dan bukan hasil
alias "opini". Hasilnya sendiri memang berharga semacam rasa
sayang kepada manusia, katakanlah -- juga terhadap para sipir
penjara dengan watak mereka yang sama-sama tercinta.
Bayangkan: di hampir akhir si terhukum dihadapkan pada regu
tembak. Ditembak sekali, tak mempan. Ada jimat? Atau karena ia
masih tidur? Ditembak lagi, tak mempan. Sekali lagi. Lalu sekali
lagi -- karena para tukang tembak telanjur "syur". Yang terjadi
kemudian pertentangan antara keluarga si terhukum (diwakili
ibunya, yang keras kepala) dan dokter -- sebab si ibu memaksa
membawa 'Jenazah" pulang untuk dimakamkan. Bagaimana orang belum
mati mau dikubur? "Pokoknya kan sudah ditembak. Jangan sadis!"
Bisa digambarkan kocaknya sandiwara -- yang bersandar justru
pada kekuatan Putu Wijaya dalam bermain-main dengan logika atau
prinsip atau teori. Lebih-lebih karena, seperti biasanya, Putu
mengikut sertakan massa sebagai bahan pembuat berbagai
pengelompokan dan hiruk-pikuk. Mereka terdiri pertama dari
semacam balatentara atau polisi yang menahan si terhukum,
dikepalai oleh tokoh 'Yang Mulia' yang dimainkan Renny Putu
Wijaya Dan kedua khalayak di luar pihak penjara keluarga korban
yang juga dipimpin Renny (Ibu), dua orang wartawan dan tamu lain
yang kehhatannya pejabat.
Dengan menggunakan gerak karikatural untuk kelompok Yang Mulia,
juga sipir penjara, dokter, wartawan, pejabat, dan dengan warna
dusun pada kelompok keluara. Putu melaksanakan kebiasaannya
"mengacau-balaukan" ruang yang oleh Koedjito telah ditata cukup
sugestif dengan dinding penjaranya yang massif dan kelam.
Jenis progresi Putu Wijaya, yang hampir selalu bukan plot yang
lurus, disandarkan pada ritme yang diungkapkan dengan
mengeksploatasi berbagai bentuk dan terutama perubahan
terus-menerus. Sebagai satu bukti pemberontakan kepada melodrama
adalah kesadaran pada ancaman kebosanan Putu hampir selalu
membuyarkan adegan sebelum benar-benar berakhir. Atau sebelum
benar-benar menghanyutkan.
Adegan terbagus ialah ketika muncul seseorang -- berpakaian
pengamen menyanyikan lagu melankolis Jawa: Yen ing tawang ana
lintang, di tengah upacara makan malam terakhir (ingat upacara
makan Kusni Kasdut dan keluarganya?). Wajah para keluarga dan
cara makan mereka seperti manusia yang sudah dibetot
kesadarannya, dungu dan sayu -- dan suasana sedih dan lucu hadir
bersama, saling desak mendesak. Dan di tengah keributan karena
si terhukum "tak mempan peluru", tiba-tiba wartawan mengangkat
tustelnya -- dan semua orang, termasuk sipir, keluarga, dokter
bergaya sebentar untuk dipotret.
Ini memang pertunjukan Putu yang bagus. Di samping Renny yang
dengan baik membawakan dua peran penting, kepala sipir yang
diperankan Budhi Setiawan juga mengangkat drama ini dengan
penampilannya yang gesit, justru pada saat tontonan bisa kendur,
yakni saat penampilan individual. Ia dibantu dengan baik
misalnya oleh Kamsudi Merdeka sebagai salah seorang petuga
penjara. Dan hampir seperti ada peningkatan kesadaran seni
rupa, boleh dibilang tiap adegan dibikin dengan komposisi,
warna, dan cahaya yang impresif tanpa menjadi dramatis.
Demikianlah Putu Wijaya, satu-satunya dramawan (yang
sehari-harinya makin sibuk) di TIM yang tetap bisa muncul dengan
ajek, telah mewujudkan kreasi terakhirnya. Mungkin memang tidak
lagi menampilkan greget 'rasa pahit (seperti Lho misalnya),
namun juga tidak berpura-pura menjadi pejuang.
Meski begitu jangan dikira tak ada sejenis pesan -- dirumuskan
atau tidak. Suara tabuh yang dipalu dari belakang secara
periodik, yang dikatakan sebagai degup jantung si terhukum "yang
menggelisahkan tidur orang seluruh kota", tetap terkenang. Dan
persis di bagian penutup, ketika tubuh boneka besar dirobek,
tampak baterai yang menyala di bagian dada. Lampu panggung padam
sudah. Tapi kelap-kelip jantung tetap ada.
Syuba Asa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini