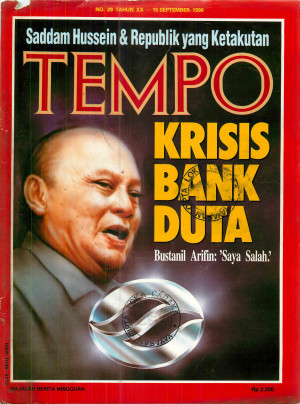MENCARI IDENTITAS NASIONAL DARI TJOE BOU SAN SAMPAI YAP THIAM HIEN Oleh: Leo Suryadinata Penerbit: LP3-ES, Jakarta, 1990, 216 halaman BABA bisa menjadi Indonesier atawa orang Indonesia, kata Lim Koen Hian (1896-1951) ketua Partai Tionghoa Indonesia. Pendapat ini banyak yang menyokong. Tapi penentangnya pun ada. Misalnya perkumpulan Chung Hwa Hwee, yang cenderung menempatkan baba, peranakan Cina, sebagai kawula Belanda. Sesungguhnya memang ada perdebatan tentang format sosial politik baba di Indonesia. Dan ini pula yang menjadi tema buku Mencari Identitas Nasional, yang menguraikan delapan tokoh baba. Yang disebut terakhir adalah Tjoe Bou San (1891-1925), Kwee Hing Tjiat (1891-1939), Kwee Tek Hoay (1896-1951), Liem Koen Hian, Kwee Kek Beng (1900-1974---), Auw Yong Peng Koen alias P.K. Ojong (1920-1980), Oey Tjeng Hien alias Haji Abdul Karim (1905-1988), dan Yap Thiam Hien (1913-1989-). Leo Suryadinata menulis semua tokoh itu kecuali P.K. Ojong oleh Frans Parera. Semua tokoh yang ditampilkan dalam buku ini sudah meninggal. Lima orang dikenal sebagai penulis atau wartawan, dua orang (Karim dan Yap) aktivis, dan Koen Hian dua-duanya, yakni penulis sekaligus aktitivis. Mereka ini adalah orang yang banyak mencurahkan pemikiran dan kegiatan dalam mencari format ideal bagi warga negara keturunan Cina bagi pembentukan ke Indonesiaan. Leo, sebagai pakar yang menekuni masalah pembauran di Indonesia, tidak melihat peran pengusaha yang cukup berarti di bidang ini. Tidak seorang pun pengusaha yang ia tampilkan. Termasuk pengusaha seperti Nyoo Han Siang, yang dikenal mempunyai minat dalam masalah pembauran di masa hidupnya. Karim memang pengusaha, tapi belum tergolong taipan. Lagi pula ia lebih menonjol sebagai aktivis muslim. Atau Leo beranggapan bahwa penekanan buku ini pada bidang pemikiran, bukan praxis. Kecuali Yap, ketujuh tokoh yang ditampilkan agaknya kurang mempunyai akseptabilitas luas sebagai tokoh Indonesia. Betapapun, Karim Oey masih dipandang sebagai tokoh Islam, dan P.K. Ojong lebih dianggap sebagai intelektual Katolik. Semangat P.K. Ojong masih dapat dirasakan dalam koran -- Kompas -- yang didirikannya. Kelima tokoh lainnya, sesuai dengan masa mereka berkiprah, merupakan tokoh Tionghoa. Mereka berpikir dan bertindak dalam kerangka kepentingan golongan Tionghoa peranakan. Meskipun yang dijadikan "bendera perjuangan" adalah melawan diskriminasi rasial. Di sisi lain, kelima tokoh yang punya kecakapan menulis ini mempunyai jasa yang besar dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia. Meskipun bahasa yang mereka pergunakan bergaya "Melayu-Tionghoa". Rasanya, pemakaian bahasa Indonesia tidak mungkin meluas dan meningkat begitu cepat tanpa peran media massa Tionghoa di zaman Belanda. Lepas dari jalan pemikirannya, Kwee Kek Beng, dan harian Sin Po yang dipimpinnya, harus dicatat punya andil besar dalam hal penyebarluasan bahasa Indonesia itu. Di bidang pemikiran masalah asimilasi pada zaman Belanda, tercatat tiga aliran penting berkembang di lingkungan peranakan. Aliran pertama menghendaki peranakan menjadi kawula Belanda. Kelompok kedua menganggap Tiongkok merupakan tanah air mereka yang asli, seraya menolak menjadi kawula Belanda dan menentang gagasan "baba menjadi Indonesier". Sementara itu, aliran ketiga menghendaki agar peranakan secara total menjadi orang Indonesia. Ketiganya dapat diikuti dengan seksama dalam buku ini. Leo dengan lancar mengutarakan spektrum perbedaan pemikiran itu di zaman Belanda. Kini perdebatan ketiga pemikiran itu sudah tidak relevan. Karena, secara hukum, mereka yang berstatus WNI adalah Indonesier. Karena, perdebatan telah beralih ke bidang sosial budaya. Sebagai orang yang berkewarganegaraan Indonesia, apakah mereka harus menghilangkan seluruh identitas ke-Tionghoa-annya atau tidak. Kalangan LPKB, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, yang kemudian perannya diganti oleh Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa), berpendapat bahwa peranakan WNI secara sosial budaya mesti berbaur total dengan pribumi. Seluruh identitas Cina harus dihilangkan, termasuk nama diri. Pengacara terkenal dan pejuang hak-hak asasi manusia Yap Thiam Hien ternyata berpendapat lain. Ia tidak setuju asimilasi yang dipaksakan. Apalagi bila proses itu cuma diartikan sekadar pergantian nama diri. Tampaknya, Yap lebih cenderung kepada aktualisasi diri sebagai pejuang dan menempatkan diri secara penuh kepada kepentingan bangsa Indonesia. Ini, menurut Yap, jauh lebih penting dari ganti nama yang sifatnya artifisial. Dan Yap membuktikan prinsipnya. Kendati ia seorang Protestan yang saleh, masyarakat Indonesia mengenang kehadirannya sebagai juru bicara dan pembela rakyat yang menderita. Karena hal ini, agaknya, Leo memandang lebih penting menulis biografi Yap dalam bukunya daripada Nyoo Han Siang. Tampaknya format baba yang dirintis Yap akan menjadi acuan penting dalam proses pembentukan kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia di masa mendatang. Seperti yang kini terlihat dari munculnya nama Arief Budiman, Kwik Kian Gie, atau Christianto Wibisono. Ridwan Saidi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini