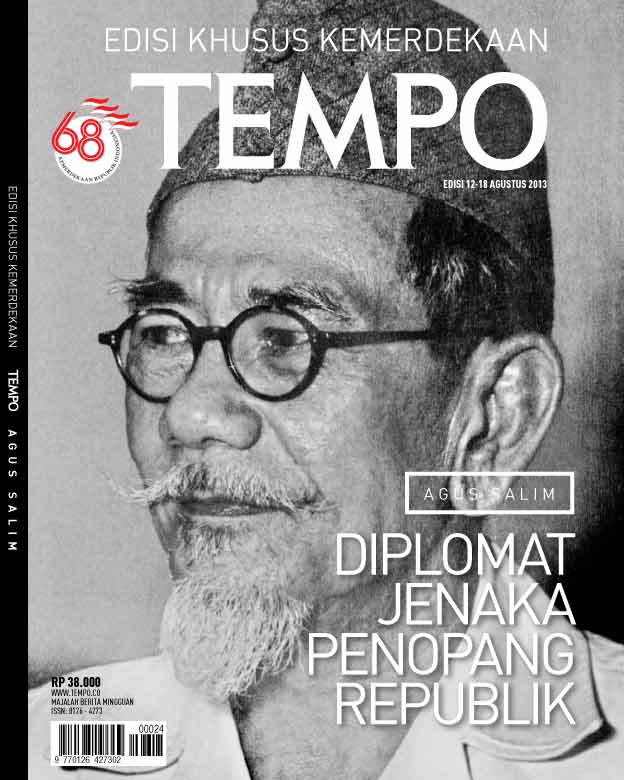Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tidak ada yang tau di mana perempuan itu jadi aneh tingkahnya. Mungkin di tempat kerjanya di Jakarta atau di tengah jalan ketika ia memutuskan untuk pulang kampungnya berjalan kaki. Sampai di kampung, pada suatu siang yang pecah menjadi kegemparan.…"
Kisah berjudul Setan yang Menjelma Menjadi Agar-agar yang disajikan pada kanvas 120 x 100 sentimeter itu salah satu karya Ugo Untoro pada pameran tunggalnya bertajuk "Melupa" di Ark Gallery, Yogyakarta, hingga akhir Juli lalu.
Ugo Untoro, 43 tahun, perupa yang ber–angkat dari garis, mendadak, pada 2007, menghadirkan karya instalasi berupa jasad kuda sebenarnya ("Poem of Blood"). Pameran instalasi yang mengisahkan nasib kuda: dipuja-puja di arena pacuan, difungsikan sebagai penarik gerobak, sampai akhirnya selesai di rumah jagal. "Poem of Blood", menurut saya, sampai hari ini bukan hanya pameran spektakuler Ugo, melainkan juga pameran instalasi perupa Indonesia yang paling total dan mengundang pertanyaan: apa yang bakal diciptakan Ugo Untoro setelah "Puisi Darah Tumpah" itu?
Ternyata "puisi instalasi" seperti menjadi titik balik: Ugo kembali ke elemen yang diakrabinya sejak awal berseni rupa, garis—garis-garis Ugo yang tipis lebih menyajikan suasana bukan alami, lebih menampilkan garis itu sendiri daripada garis sebagai elemen untuk melahirkan bentuk. Dalam katalog pameran "Papers and Ugo" di Taman Budaya Yogyakarta pada 2011 dengan kurator Aminudin T.H. Siregar, bisa dicermati garis-garis Ugo dari akhir 1980-an hingga 2008.
Sebelum "Puisi Darah Tumpah", garis-garis Ugo masih diniatkan untuk melukiskan hal yang bersuasana realistis: ada gambar Bung Karno, gambar lelaki merokok memegang cangkir minum, dan gambar seorang anak tidur, misalnya. Selain itu, adalah bentuk-bentuk yang "samar", bentuk fantasi—kepala kuda disangga empat kaki tanpa tubuh; figur-figur berkepala kuda; perempuan ditiduri banteng; serta dua figur berdiri, satu memegang garpu dan satu memegang sumpit, siap berebut sebiji buah di meja.
Juga gambar-gambar yang disusun seperti komik, bahkan ada yang memang komik meski hanya sehalaman lengkap dengan judul Pendekar Cambuk Sakti. Dan, sudah tentu teks, misalnya: "Tukijo tewas dg luka2 di seluruh tubuhnya, 2 bajingan tengik itu, preman picisan, meneruskan garapannya lagi, sampai gadis itu tewas juga. (Tdk bersambung)."
Terkesan ada ketika Ugo tak cukup hanya berbicara dengan garis; ia memerlukan kata. Dan pada pameran termutakhirnya ini, "Melupa" itu, yang ada hanyalah kata-kata tersusun menjadi kalimat dan kalimat-kalimat tersusun menjadi kisah. Ugo pada 2013 ini "menemukan" bahwasanya menggambar adalah menulis dan menulis adalah menggambar. "Menggaris membentuk kuda saya rasa sama dengan menggaris membentuk huruf berbunyi 'kuda'," katanya.
Bagi saya, "Melupa" bukan sekadar "melupakan" bentuk dan menggantinya dengan huruf-kata-kalimat-kisah. Dari 20-an karya yang dipamerkan (tak semuanya tulisan pada kanvas, ada juga tulisan pada buku, pada rokok dan bungkusnya, pada meteran, serta pada lakban), terasa suatu spontanitas menggaris yang kemudian mengalir memenuhi atau tak memenuhi kanvas. Spontanitas yang mengalir sebagai kisah, yang terciptakan dalam suasana ketika jarak antara sang perupa dan kanvas hilang. Pertemuan antara Ugo dan kanvas (kanvas bisa diganti apa saja) seolah-olah melebur keduanya, dan itu memungkinkan Ugo berkisah tanpa peduli "kiblat": apakah garis pertama dan terakhir yang membentuk huruf-huruf itu berada di batas tepi kanvas atau agak ke tengah, apakah tulisan memenuhi kanvas atau hanya mengisi sebagian, apakah itu kanvas datar atau lakban yang melengkung, atau bungkus rokok yang kotak, atau rokok yang silinder. Bahkan ia tak peduli apakah tulisan itu terbaca atau tidak.
Dan semua karya Ugo itu bukanlah kaligrafi dalam makna yang lazim: susunan huruf yang membentuk kata yang direka secara artistik. Lebih bisa dibilang, dalam menciptakan karya-karya yang hanya huruf-kata-kalimat-kisah ini, Ugo menumpahkan begitu saja apa pun yang digagasnya, yang ada dalam benaknya.
Dalam hal ini, sebenarnya ia mirip Affandi, yang tak "memperhitungkan" segala elemen seni rupa, komposisi, dan sebagainya. Affandi hanya menumpahkan emosinya dengan memelototi cat dari tubenya langsung ke kanvas, mencoret-coretkannya sesuai dengan gerak emosi dengan berpedoman pada obyek yang menjadi sumber munculnya emosi itu. Bila kemudian terasa lukisan Affandi artistik, ada komposisinya, itu karena tangan dan dirinya sudah seperti hafal akan obyek yang membuatnya terangsang untuk "memindahkan" obyek tersebut ke kanvas.
Akan halnya Ugo, obyek itu adalah kisah yang muncul ke alam sadarnya, yang "membimbing"-nya untuk menuliskannya—sebagai seorang perupa—pada kanvas, pada permukaan apa saja. Pengalaman estetiknya yang mengendap, saya kira, dengan sendirinya menjadikan kanvasnya tetap mengandung jejak-jejak pengalaman itu—walau misalnya ia tak berniat menyusun komposisi, menggoreskan aksen-aksen, dan semacamnya.
Maka ada Akhirnya Anjing pada kanvas merah dengan tulisan putih yang tak sepenuhnya memenuhi kanvas. Ada sejumlah baris kalimat di alinea terakhir yang agak melengkung, lalu sisa kosong kanvas. Ada Regasa (ini nama tokoh dalam kisah) yang hanya mengisi penuh sekitar seperenam kanvas di sisi kiri. Ada Puntung Panjang yang dituangkan dalam beberapa gaya tulisan dan beberapa ukuran huruf, juga ada berbagai susunan alinea. Dan itu semua, menurut saya, jejak-jejak pengalaman estetik Ugo.
Pun Ugo tak harus melebur ke dalam kanvas; bisa juga itu lakban, atau bungkus rokok, atau buku, atau meteran yang membuat ia "harus" berkisah.
Dari esai di katalog (ditulis oleh Stanislaus Yangni, mahasiswa Pascasarjana Institut Seni Indonesia, Yogyakarta), gambar tulisan Ugo konon lahir dari rasa bosan pada yang bentuk, pada yang artistik. Lalu kenapa yang lahir adalah huruf-kata-kalimat yang berkisah?
Tampaknya, seperti sudah sedikit disinggung, ada ketika Ugo memerlukan kata. Ia sudah merasa begitu mudah menuangkan bentuk orang, pohon, meja, kuda, dan sebagainya, dan dengan cara apa pun jadilah sebuah karya yang pantas, yang artistik, yang komunikatif. Ada sesuatu yang lebih daripada itu yang hendak ia tuangkan di kanvas atau apa pun, sesuatu yang bisa "langsung" berbicara, dan itu adalah huruf-kata-kalimat tadi. Dan ini bukan karena Ugo tak mampu membuat bentuk untuk mewadahi rasa yang hendak ia tuangkan dan komunikasikan ke dunia luar. Justru, sebaliknya, ia merasa sudah begitu gampang menciptakan bentuk-artistik itu, dan tetap ada yang dirasa kurang, atau ia terperangkap pada kejenuhan dengan semua yang sudah ia ciptakan.
Bagi saya, "Melupa" seperti mengembalikan kegiatan kreasi ke asal-usulnya: re-kreasi, sesuatu yang terbebas dari pamrih, sesuatu yang tak pernah terjawab ketika dipertanyakan, sebenarnya untuk apa kita mencipta karya yang disebut karya seni. Konon, ini seperti anak-anak yang bermain di pantai melemparkan kerikil dan batu ke arah laut—hanya laku, tak untuk apa pun.
Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo