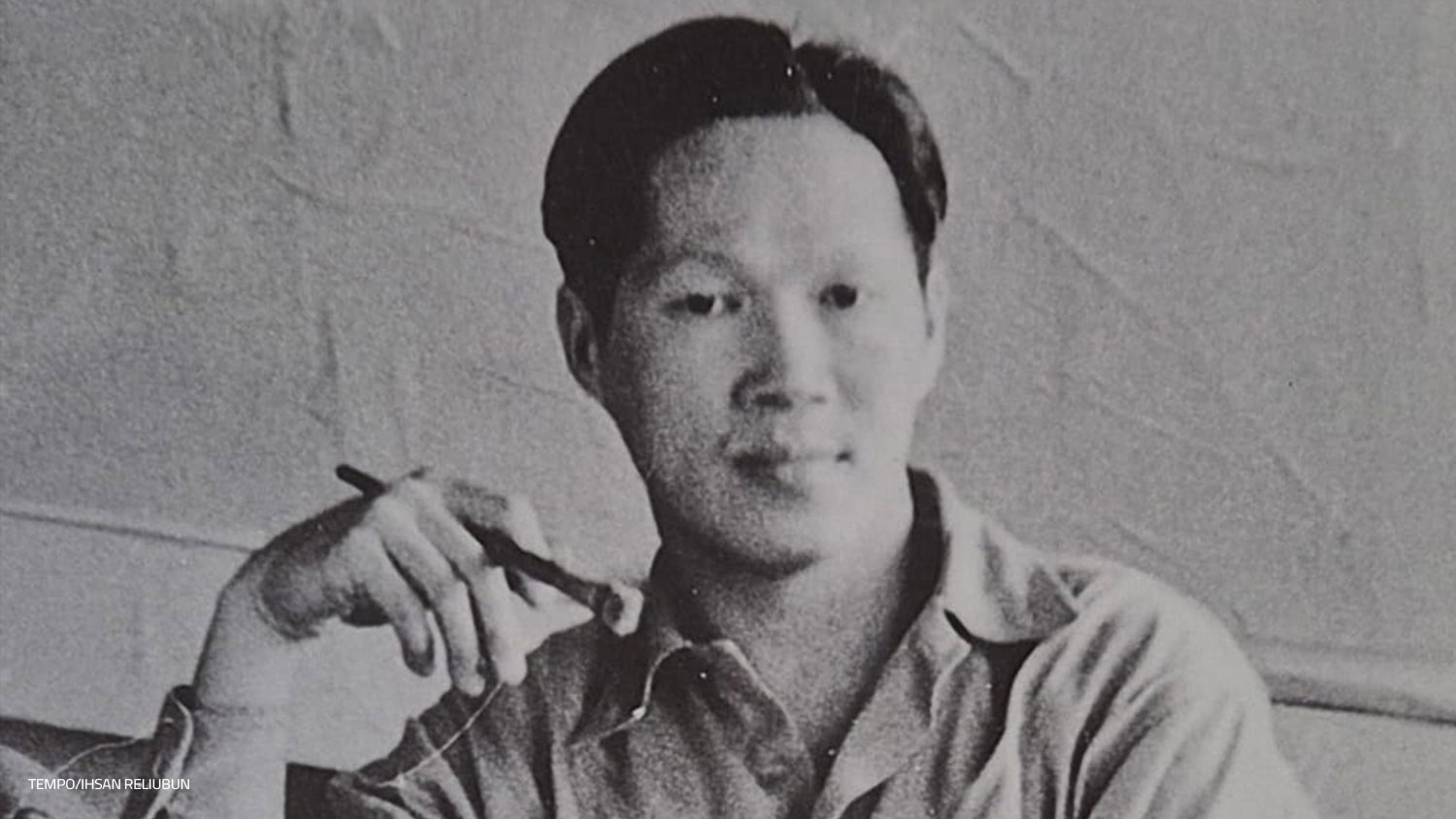Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Judul buku: Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan
Editor: Akhmad Sahal dan Munawir Aziz
Penerbit: Mizan, Jakarta
Cetakan: Pertama, Agustus 2015
Salah satu buku yang paling dibincangkan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang pada awal Agustus lalu adalah Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan. Pertanyaannya: dengan adanya buku yang disunting Akhmad Sahal dan Munawir Aziz ini, apakah istilah Islam Nusantara menjadi semakin jelas?
Pembacaan yang hati-hati dan utuh terhadap buku ini akan sampai pada kesimpulan yang jelas. Namun, karena dia semacam gado-gado yang memuat kumpulan tulisan lama maupun baru, panjang maupun pendek, makalah serius dan juga cerpen, tak mudah bagi pembaca umum untuk menangkap dan menyarikan elemen-elemen pokoknya. Sebagai penyunting, Akhmad Sahal telah berupaya merenda semua unsur gado-gado itu agar mudah disantap dan maknyus. Namun, karena dia tidak merinci pengantarnya ke dalam poin-poin, pembaca yang kurang awas akan kehilangan jejak akan makhluk bernama Islam Nusantara itu.
Resensi ini berupaya menangkap dan meringkas elemen-elemen pokok Islam Nusantara ke dalam poin-poin pokok. Elemen pertama yang paling tampak dalam pembacaan kita adalah aspek lokalitas. Tidak seperti Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah yang lebih merujuk ke etos atau semangat, Islam Nusantara merujuk ke suatu ruang dan tempat, dan karena itu peka terhadap lokalitas.
Ini setidaknya tergambar dari tulisan-tulisan almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Afifuddin Muhadjir, Amin Abdullah, Husein Muhammad, dan Abdul Moqsith Ghazali. Mereka berupaya mengetengahkan argumen fiqh dan Ushul Fiqh yang kokoh untuk menjustifikasi pentingnya pertimbangan lokalitas dalam perumusan maupun pelaksanaan hukum Islam agar kemaslahatan mudah didapat dan kemafsadatan bisa disumbat. Teknik menggapai kemaslahatan dan menyumbat kemafsadatan itu bisa disebut kontekstualisasi, pribumisasi, ataupun rekonstruksi ajaran-ajaran Islam dalam kerangka lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta benda umat manusia.
Elemen kedua adalah semangat non-sektarianisme. Elemen ini diulas dengan lihai oleh almarhum Nurcholish Madjid dan Said Aqil Siraj lewat reinterpretasi yang segar terhadap konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Dengan mengelak dari friksi-friksi sektarian dalam Islam, Aqil Siraj menempatkan konsep Ahlus Sunnah sebagai suatu metode berpikir (manhaj al-fikr) ketimbang sebuah mazhab. Dia menandaskan bahwa Ahlus Sunnah bukanlah firqah atau sekte vis-à-vis Ahlul Bait atau Syiah, namun tenda besar yang mampu menampung keragaman mazhab dan pemikiran yang bersifat lentur dan fleksibel.
Reinterpretasi Nurcholish Madjid tentang konsep "jamaah" lebih menarik lagi. Menurutnya, kata jamaah dalam frase Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung semangat non-sektarianisme, terlebih bila diinjeksikan dengan paham irja atau menunda penghakiman atas silang sengketa umat Islam dalam soal-soal akidah, ibadah, maupun muamalah antar-sesama. Konsep irja ini didasarkan pada keinsafan bahwa hanya Tuhan hakim yang paling adil di akhirat nanti, dan karena itu manusia selaiknya menghindarkan diri dari dogmatisme dan paham keagamaan yang mutlak-mutlakan.
Elemen ketiga adalah paham kebangsaan, dan juga demokrasi. Islam Nusantara sebagaimana yang dapat ditangkap dari tulisan almarhum Gus Dur, Din Syamsuddin, maupun Masdar Farid Mas'udi, adalah corak keislaman non-sektarian yang sudah mampu berdamai dengan keragaman dan paham kebangsaan Indonesia. Dari paparan Gus Dur soal paham kebangsaan NU dan Din tentang NKRI sebagai negara perjanjian dan kesaksian, kita dengan jelas dapat menangkap bahwa warga NU maupun Muhammadiyah sudah nyaman dengan Indonesia sebagai negara bangsa yang bersifat "semua untuk semua." Debat tentang negara Islam, konsep khilafah, dan turunan-turunannya, dengan demikian tak lagi relevan.
Ini terobosan penting bagi kedua ormas Islam terbesar Indonesia itu, karena mereka menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektarian ke-NU-an atau ke-Muhammadiyah-an. Dan itu berkah besar yang punya dampak stabilitas yang mungkin kurang diakui. Karena itu Gus Dur melihat ini sebagai aspek yang khas pada muslim Indonesia dan layak dikaji. Secara retoris Gus Dur bertanya: bagaimana mungkin sebuah konsep negara "sekuler" (saya beri tanda kutip karena studi terakhir Jeremy Menchik justru menyebut Indonesia sebagai negara berpaham nasionalisme berketuhanan atau godly nationalism), justru dipertahankan antara lain oleh ayahnya sendiri, KH Hasyim Asy'ari, dengan menggunakan ajaran-ajaran agama?
Intinya, Muslim Nusantara adalah kaum yang sudah dapat secara damai menyandingkan paham kebangsaan dengan paham keagamaan dan karena itu benturan antara kalangan nasionalis sekuler dan kaum Islamis di sini tidaklah separah dan seberdarah-darah di negara dan kawasan mayoritas muslim lainnya. Untuk itu kita mungkin bisa dengan bangga berkata: ini adalah ihwal yang sangat spesial pada Islam dan Muslim Nusantara. Produk bagus yang bernama Islam Nusantara ini siapa tahu bisa juga diekspor agar mendunia dan tidak terkunci di dalam kepekaan dan kesadaran lokalitasnya.
Kekhasan itu dapat dilacak lebih jauh dari ulasan Yahya Cholil Staquf tentang sejarah panjang bagaimana Islam merangkul, bukan memukul Nusantara. Kuatnya dimensi esoterisme Islam yang menampik formalisasi beragama di kawasan ini, sebagaimana diulas Haidar Bagir atau digambarkan oleh cerpen mistis-ciamik Mustofa Bisri alias Gus Mus, dapat pula ditambahkan sebagai elemen kelima. Ya, elemen esoterisme dan non-formalisme dalam beragama.
Itulah sekurang-kurangnya lima elemen pokok Islam Nusantara yang saya tangkap dari buku ini. Memang masih banyak hal yang belum selesai seperti definisi yang paling tepat dan mengena tentang apa itu Islam Nusantara sebagaimana dipersoalkan Aziz Anwar Fachrudin, dan bagaimana pula hubungannya dengan Islam Berkemajuan dan aspek-aspek lain. Namun, berbeda dengan perdebatan tak kenal juntrungan di media sosial, buku ini sangat membantu pemahaman kita akan apa itu hakikat Islam Nusantara. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya sudah ada semacam konsensus diam-diam (ijma' sukuti) di kalangan arus utama Muslim Indonesia tentang apa, mengapa, dan bagaimana Islam Nusantara.
Persoalannya, selalu ada kelompok-kelompok lama atau baru yang belum bisa berdamai dengan kenyataan itu. Kelompok inilah yang disebut kaum Islamis yang seringnya lebih mengutamakan Islam sebagai gincu, bukan sebagai bumbu yang menyedapkan kehidupan bersama. Bagi mereka ini, yang diperlukan bukanlah Islam Nusantara, tapi bagaimana mengislamkan Nusantara. Seolah-olah Indonesia dan segmen terbesar umatnya belum lagi Islam dan akan lebih baik dengan Islam versi mereka. Astaghrifullah, la hawla wala quwwata illa billah.
Novriantoni Kahar (Dosen Universitas Paramadina)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo