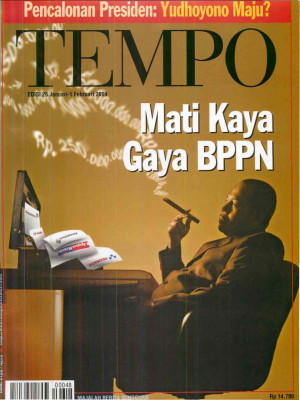Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak kurang dari empat dasawarsa lamanya Fadjar Sidik menjelajahi "dinamika bentuk dan ruang" hanya dengan sebuah manifesto tak lebih dari 300 kata. Di lingkungan akademis yang tumbuh dari suasana romantik sanggar, Fadjar menjalarkan semangat modernis yang meletup dari pandangan kritis-rasionalnya. Pada 1970-an, tak segan ia membonceng sepeda motor butut, bertandang menyaksikan kelahiran abstrakisme baru—bidang warna rata, garis yang ditarik dengan mistar—di kamar kos muridnya.
Pelukis ini meninggal dunia pada Minggu, 18 Januari 2004, di rumahnya, di Yogyakarta, setelah menderita gagal ginjal beberapa lama. Cat telah mengering di tempatnya melukis, meski Fadjar masih menghasilkan sejumlah lukisan bertarikh 2003.
Sesungguhnya kalangan seni rupa tak pernah sungguh-sungguh melupakan Fadjar Sidik. Pameran tunggalnya yang terakhir berlangsung pada September 2002 di Museum Affandi, Yogyakarta. Namun itu bukanlah pamerannya yang terpenting. Pasar yang marak mencecar karyanya menerbitkan sebuah buku tebal yang sayangnya—maaf—buruk. Tak kepalang, seorang art dealer membeli sejumlah besar lukisannya senilai Rp 300 juta (Majalah TEMPO, rubrik Layar, 25 Agustus 2002). Sesungguhnya semua itu tampak tak sepadan dengan pencarian "kemurnian" Fadjar Sidik.
Yang terlewat selama ini ialah bagaimana mengamati secara kritis pencapaian seni lukisnya.
Manifesto seni lukis Fadjar menyorongkan dua hal: medium yang kekal dan pokok lukisan yang tak niscaya perlu berubah. Dia memohon kepada kita—sihir seorang magis—untuk tidak memperkarakan medium seni lukisnya, tapi lebih mengkaji pergeseran perhatiannya dari pokok figuratif ke raut nirmana; dari ruang representasional (pictorial) ke bidang yang cuma asyik mencacah bentuk (picturesque). Alasan kehadiran seni lukisnya, katanya, sama saja dengan cap tangan manusia purba yang tertera di dinding gua 20 ribu tahun silam.
"Entah mengapa," tulis Fadjar pada 1970-an, "hasil industri itu banyak yang bentuknya indah dan enak dilihat, tapi tidak untuk dilukis; mereka perlu rusak dulu baru bisa dilukis atau dibuat patung.... Saya kehilangan obyek-obyek pelukisan yang artistik dan puitis. Ah, daripada menggambar obyek-obyek hasil kreasi para desainer industri itu, mengapa tak menciptakan bentuk sendiri saja untuk keperluan ekspresi murni yang bisa memenuhi tuntutan batin yang paling dalam?"
Fadjar tentunya tak menyangkal keindahan dapat lahir dari kegunaan. Yang menyebabkannya grogi menghadapi alam justru adalah lenyapnya perlahan-lahan sifat magis bumi oleh produk-produk teknologi atau jejak agresif desain yang terkesan baku. Itulah yang dialaminya ketika ia asyik melukis selama 1957-1961 di Bali.
Fadjar tak urung menyebut lukisannya sebagai "desain ekspresif"—suatu keinginan untuk mendamaikan antara abstraksi dan empati. Jejak empati Fadjar (terhadap alam) kemudian melantunkan bukan bentuk-bentuk naturalistik, melainkan sejenis raut khayal yang hidup-bernapas atau biomorfik. Wacana abstraksinya—dorongan ke arah geometri—melahirkan sejenis negasi atau ketakutan terhadap ruang (horror vacui). Demikianlah, Fadjar berada dalam antagonisme semacam itu selama puluhan tahun perjalanan seni lukisnya.
Lukisan modernis, ujar Greenberg, adalah tahap terakhir yang secara prinsip tak ingin membebaskan representasi obyek-obyek yang dikenali. Apa yang dibebaskan adalah representasi dari jenis ruang yang dapat ditempati oleh obyek-obyek itu. Tatkala bidang lukisan kemudian dipahami sebagai perubahan ke arah kesepadanan dengan bidang permukaan dari yang nyata dan yang material, seni lukis akan mencapai tahap kemurniannya. Demikianlah kemurnian modernisme dalam seni lukis diartikan sebagai suatu self-definition.
Nyaris membosankan, Fadjar menjelajahi terus-menerus bidang lukisannya yang bertegangan semacam itu. Bidang lukisannya tak berubah menjadi sepenuhnya rata, melainkan tetap bernuansa. Ia juga tak seutuhnya menjadi abstrak; dinamika keruangannya malahan beranak-pinak ke sejumlah bentuk asosiatif: burung, ular, gunung, matahari, bulan, bintang, dan sang kala. Yang kian terasa pada karya-karyanya yang terakhir adalah kekosongan latarnya yang kian menjalar lebar.
Terasing oleh alam yang pernah dilukisnya, sejumlah lukisan Fadjar Sidik menularkan suasana yang sama kepada pemirsanya: raut tercacah, penggalan-penggalan mandiri yang seakan sulit bertaut. Bukankah ini cermin pengalaman individual kita yang kian tersekat-sekat, semacam kerumunan cerah tapi menyakitkan?
Sesungguhnya kita tak mampu mengkhayalkan diri tinggal dalam dinamika ruang dan bentuk—jejak modernisme—seperti yang dihadirkan dalam lukisan-lukisan Fadjar Sidik.
Dilahirkan di Surabaya, 8 Februari 1930, Fadjar Sidik adalah pengajar yang mampu merangsang diskusi tajam di lingkungan Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Ia mengajar di sana sejak 1961 dan baru pensiun pada 1995. Dalam suasana yang kian menjauh dari dinamika intelektual—khususnya di kalangan seni rupa di Yogyakarta—kepergian Fadjar Sidik adalah sebuah kehilangan.
Hendro Wiyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo