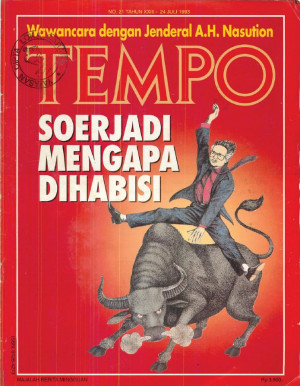ULANG tahun ke-70 Prof. Dr. R.M. Koentjaraningrat, 27 Juni la- lu, dirayakan di rumah muridnya, Meutia F. Swasono. Dalam acara itu, dipersembahkan sebuah buku karya Koentjaraningrat disunting oleh tuan rumah, yang tak lain adalah putri Proklamator Bung Hatta. Buku itu memuat beberapa tulisan Koentjaraningrat mengenai masalah kesukubangsaan tentu sangat relevan di Indonesia dan aktual di dunia. Masalah ini memang sudah lama ditekuni Koentjaraningrat, dan menjadi tema utama buku ini, di samping memasalahkan antropologi sebagai ilmu terapan dan pembangunan. Indonesia adalah negara kebangsaan yang majemuk, plural society. Persatuan dan penyatuan menjadi semboyan yang di- dengungkan dan didambakan. Namun, itu tetap saja majemuk, dilihat dari sudut agama, etnis (kesukubangsaan), dan keturunan ras (Cina, Arab, India, Eropa, dan lain-lain). Orang Indonesia sering merasa bahwa masalah ini khas Indonesia, tak ada di masyarakat negara lain. Dalam buku ini, Koentjaraningrat menyoroti masalah kemajemukan suku bangsa, agama, dan lain-lain dalam masyarakat dan negara nasional. India, Yugoslavia, dan Belgia mengalami masalah kemajemukan ini sama seperti Indonesia. Golongan etnis, agama, dan lain-lain menempati daerah tersendiri dan memiliki kesatuan teritorial. Namun, dalam sejarah kesatuan teritorial ini, ada proses, misalnya transmigrasi. Daerah menjadi multi-etnis, agama, dan lain-lain. Homogenitas hilang, dan timbul reaksi kesukuan atau agama. Mayoritas merasa takut terdesak oleh minoritas, di samping, secara historis, mungkin sudah ada pertentangan etnis, agama, dan rasial itu. Topik yang dibicarakan Koentjaraningrat kini terasa menjadi hangat. Sebab, terjadi konflik di berbagai tempat, seperti di Yugoslavia, India, dan Uni Soviet. Di Indonesia sendiri, masalah konflik etnis dan agama pernah pula mengguncang. Ada delapan peristiwa yang dikategorikan Koentjaraningrat dalam gejolak itu: Republik Maluku Selatan (RMS) yang menentang Republik Indonesia, peristiwa bekas anggota KNIL Kapten Andi Abdul Azis (Bugis melawan non-Bugis), pemberontakan Daru'l Islam di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, PRRI di Sumatera Barat, serta Permesta di Sulawesi Selatan. Pemberontakan memang sudah berakhir tahun 1960-an. Namun, menurut Koentjaraningrat, perbaikan hubungan antarsuku belumlah memadai karena keadaan ekonomi buruk. Hanya di Jakarta dan beberapa kota besar hal itu mulai tampak. Banyak anak muda tak memakai identitas daerah atau suku nenek moyangnya walau belum ada kajian rinci. Tentu, faktor pendidikan nasional dan pemakaian bahasa Indonesia punya peran yang tak kecil. Benarkah kebudayaan dan identitas nasional akan memperkukuh kesatuan masyarakat majemuk? Untuk ini, Koentjaraningrat meneliti tiga negara, yakni India, Yugoslavia, dan Belgia. Makalah Koentjaraningrat setebal 500 halaman mengenai Yugoslavia tampaknya perlu ditulis ulang, setelah negara itu pecah menjadi ''bekas Yugoslavia'', dengan penelitian baru. Namun, bagaimanapun, Koentjaraningrat telah melihat memuncaknya ketegangan etnis di Yugoslavia. Kasus India mungkin paling mirip Indonesia. Dari sejarah, rupanya penguasa kolonial, seperti halnya para pemimpin nasionalisnya, ingin menciptakan negara nasional pada akhir penjajahannya. Sejak mula, bekas British-India itu sudah me- ngidap perpecahan, misalnya melahirkan Pakistan dan India. Belakangan, muncul Bangladesh. Pertanyaannya kini, mampukah India sendiri mempertahankan kesatuannya? Belgia lahir karena perbedaan Protestan dan Katolik pada 1830 dari Nederland. Namun, di Belgia sendiri ada dua golongan penduduk, yakni Vlaam dan Wallon. Yang satu berbahasa Belanda kuno dan yang lain Perancis kuno, ditambah dengan masih adanya segolongan kecil yang berbahasa Jerman. Konflik antara golongan Vlaam dan Wallon terjadi sejak 100 tahun lebih. Toh, Belgia tetap bersatu. Rasanya, Koentjaraningrat perlu menampilkan Swiss, yang memiliki masyarakat majemuk, berbahasa Jerman, Perancis, dan Italia, dengan agama yang berbeda-beda setiap agama bersifat agak ''fundamentalis''. Namun, sepanjang sejarahnya, negeri itu damai. Mengapa Swiss tak disebut oleh Koentjaraningrat? Mungkin setiap sarjana lebih tertarik pada objek pembahasan yang memang menimbulkan masalah. Bab terakhir mendiskusikan penerapan antropologi dan pusat- pusat penelitian Indonesia di luar negeri, seperti Universitas Cornell, Monash, dan Yale. Tapi, sejauh mana antropologi bisa dipakai untuk social engineering? Kalau manusia bisa belajar dari kesalahan sejarah dan antropologi bisa dipakai untuk rekayasa sosial, mungkin dunia kini lebih aman dan damai. Onghokham
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini