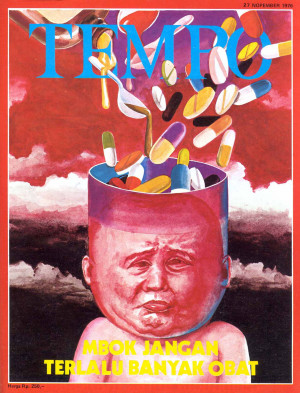DI Teater Arena TIM (10 s/d 12 Nopember) 3 anak didik Akademi
Tari LPKJ mencoba menunjukkan bulunya. Mereka menampilkan hasil
penyerapan mereka ke daerah-daerah, di mana mereka telah
melakukan banyak pengamatan dan penelitian terhadap
tarian-tarian rakyat.
Wiwiek Sipala, kelahiran Kendari Sulawesi Tenggara yang
dibesarkan di Ujung Pandang, mengetengahkan bentuk "Gandrang
Bulo", sebuah tarian rakyat daerahnya sendiri sambil memberikan
interpretasi baru. Deddy Luthan, berdarah Minang yang lahir di
Jakarta, mengetengahkan karyanya yang bersumber pada "Indang"
yang akarnya pada kesenian rakyat Sumatera Barat. Lalu Zailani
Idris dari Kutai, menampilkan "Jentreng" yang diilhami oleh
gerak-gerak tari Jawa Barat Tarawangsa, Bangreng, Benyang serta
Pencak Silat.
Sebagaimana umumnya akibat dari penelitian-penelitian analitis
dari sebuah akademi, yang sempat menonjol dari tangan ketiga
orang ini adalah usaha untuk menampilkan bentuk. Mereka
menangkap gerak, beberapa komposisi fisik dari tariaN rakyat
serta mengikutkan kostum yang dapat memberikan warna lokal. Dari
tiga unsur itu, mereka mencoba mengadakan sedikit variasi,
kombinasi, pelebaran ruang seluas lantai arena. Hasilnya adalah
semacam comotan yang tidak sempat meraih roh tarian-tarian
rakyat tersebut. Beberapa bagian wadagnya terhidang dengan kaku,
sebagaimana sering kita jumpai pada pertunjukan kesenian rakyat
yang disuguhkan pada turis.
Rakyat
"Gandrang Bulo" dari tangan Wiwiek Sipala mencoba memenuhi ruang
dengan cara memecahkan penarinya menjadi beberapa kelompok yang
terpencar. Satu kelompok melanjutkan suasana inti. Sementara itu
dua kelompok lain memberikan suasana sampingan.
Wiwiek memasukkan juga adegan-adegan perkelahian dan hampir
sampai pada suasana dramatik. Sayang sekali perhatiannya pada
ruang tidak diimbangi oleh ketelitian detail. Sehingga yang
tercapai adalah usaha untuk "memenuhi ruang bukan usaha untuk
menguasai" ruang. Tentu saja ruang yang penuh itu menjadi hampa
dan kosong karena tak ada kegempalan pada isinya.
Hal yang sebaliknya dilakukan oleh Dedy Luthan, yang
mengumpulkan penarinya dalam garis diagonal di tengah arena.
Anwar mencoba menampilkan beberapa gerakan-gerakan tangan secara
massal dengan pukulan-pukulan gendang. Ia mulai dengan posisi
dasar sebuah garis dan kemudian tinggal memberikan bunga-bunga
kecil. Tapi karena tak ada kecermatan pada para penarinya
sudut-sudut kecil yang hendak ditampilkannya tidak mencuat. Ini
memerlukan kekompakan tentu saja, sehingga peralihan-peralihan
posisi yang kecil-kecil bisa berlangsung rapih lalu memberikan
pesona yang lembut.
Apalagi kemudian muncul lagu dengan syair yang berisikan lirik
yang rendah hati, mengucapkan maaf karena mereka masih dalam
taraf mahasiswa. Hal yang seharusnya bisa menjadi lugu dan pasti
mengharukan kalau benar-benar dilontarkan dari jiwa pertunjukan
rakyat yang memang terus terang dan sederhana.
"Jentreng" dari tangan Zailani Idris,ditopang oleh tembang dan
gamelan Sunda yang pada mulanya memang memanggil suasana rakyat
sana. Apalagi kelihatan sebuah obor yang mengingatkan pada
tarian "Cak" Bali. Tapi tak lama kemudian mulai terasa bahwa
yang lebih menonjol adalah tembang-tembang di belakangnya.
Perhatian Zailani pada Jawa Barat sama dengan perhatian
rekan-rekannya yang terdahulu, yakni hanya pada permukaan. Pada
bagian-bagian selanjutnya suasana yang gemulai berubah menjadi
kegelisahan untuk menampilkan sesuatu yang berbau kontemporer.
Sebetulnya kalau saja Zailani memang ingin memperhatikan
kehidupan sehari-hari dengan caranya sendiri, seharusnya ia
lebih membebaskan dirinya. Karena kalau tidak demikian
pengertian "rakyat" dan pengertian "tradisionil" akhirnya hanya
akan menjadi "beban" bukannya kekayaan yang mendorong. Soalnya
karena ketiga mereka waktu terjun ke daerah mungkin hanya
menonton, tidak melibatkan diri secara rohaniah pada kesenian
rakyat setempat. Dan ini separuhnya tentu saja kesalahan para
pembimbing mereka tatkala menjadi pengamat ke pelosok-pelosok
sana.
Setelah masa jedah, muncul Farida Feisol dengan 6 buah nomor
yang disatukannya dalam satu judul "Resume". Nomor terakhir yang
bernama "Tenang Kembali" pada malam terakhir tidak dimainkan,
barangkali karena beberapa pertimbangan yang "non-artistik"
sifatnya, mengingat kondisi dan situasi. Nomor-nomor lain,
semuanya bertolak dari balet, kecuali "Perkelahian" yang
mengemukakan unsur silat. Farida mencoba memberikan puisi-puisi
kecil kehidupan. Ia seorang yang perasa. Tapi penari-penari yang
mendukung perasaan-perasaannya itu tidak mempunyai persipan
fisik yang kelar, sehingga yang lebih menonjol adalah ketidak
kompakan dan ketidak trampilan dalam bergerak.
Nancy Hasan yang jangkung dan Sentot yang berotot, termasuk dua
yang terbaik dari para penari malam itu, yang siap melaksanakan
ide-ide Farida. Tak heranlah kalau nomor "Makan Siang" yang
mereka bawakan berdua yang mengisahkan dua orang yang pernah
mempunyai hubungan intim bertemu kembali dan mengalami saat-saat
lampau yang indah merupakan nomor Farida yang terbaik malam itu.
Dengan proporsi dua buah kursi, Nancy dan Sentot sempat memukau
penonton dengan olah tubuh dan berbagai komposisi yang menarik.
Sementara di belakang (meskipun dilaksanakan dengan kurang sip)
Edi De Rounde dan Eny A. Yusuf berdialog satu sama lain,
sehingga nomor itu merupakan gabungan dari gerak dan dialog lalu
berhasil membangun suasana dramatik.
Suasana dramatik juga berhasil ditampilkan oleh nomor "Kematian"
di mana kelihatan beberapa orang berjubah hitam mengangkat
seorang penari yang berpakaian putih. Akan tetapi "Makan Siang"
tetap merupakan nomor yang lebih unik dan berhasil untuk
dicatat.
Putu Wijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini