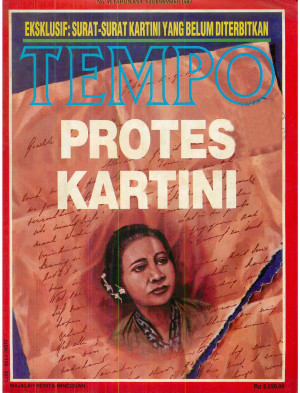Naskah: Jean-Claude Carriere Set dan kostum: Chloe Obolensky Musik: Toshi Tsuchiton Pemain: Mallika Srabha, Ryszar Cieslak, George Corraface, Mamadao Dioume, Jeffery Kisson, Yoshi Oida, Tapa Sudana, Vittono Mezzogiorno, dll. Sutradara: Peter Brook MAHABHARATA memasuki bulan kedua di New York. Sabtu siang pertengahan bulan lalu itu, gedung tua Mejestic di Brooklyn, New York, kembali hidup. Mengibarkan bendera merah dengan tulisan Mahabharata, ia seperti sebuah kapal yang sedang menunggu para penumpang. Orang-orang bergegas datang, memegang peta, seperti takut tersesat. Beberapa menit menjelang pukul satu, masih banyak yang berdiri di depan pintu dengan jaket-jaket musim dingin. Beberapa orang masih kelihatan terbirit-birit takut terlambat. Sementara itu, seorang lelaki berdiri di pintu, memegang sepeda sambil mengangkat dua buah tiket yang barangkali mau diopernya. Sejak pementasannya yang pertama, 12 oktober, kritik yang diterimanya dari berbagai media massa pahit. Semua menuding pertunjukan Mahabharata itu gagal. Banyak yang marah, karena biayanya terlalu mahal. Ada yang mencemooh, para pemainnya yang datang dari berbagai negara tak becus berbahasa Inggris. Ada yang merasa pementasan itu seperti menggurui orang Amerika dengan ajaran moral Timur. Sebagian menganggap Peter Brook sudah gagal mengangkat keagungan dalam puisi yang luhur itu. "Mementaskan Mahabharata hanya dalam sembilan jam itu sinting," kata mereka. Saya berusaha luput dari tanggapan itu dan memasuki gedung sebagai penonton yang lapar. Saya seperti berada dalam sebuah reruntuhan bangunan habis perang. Ketika saya masuk ke ruangan pertunjukan, saya seperti dilemparkan ke dunia lain. Tidak ada layar. Panggung telanjang. Panggung bagai rongga ke masa lalu, hanya kelihatan sungai kecil sepanjang tembok belakang, yang mengingatkan saya pada Gangga. Di atasnya ada papan sebagai titian menyeberang. Arah depan lantai pertunjukan ada kubangan air kecil, satu lantai dengan barisan pertama penonton. Pertunjukan seperti berlangsung di pendopo. Memakai kaus belang, seorang lelaki mengumumkan dengan ramah bahwa cerita akan dipenggal menjadi tiga bagian. Kemudian lampu meredup. Seorang anak kecil muncul ke dekat kubangan air. Lalu seorang setengah tua membawa lentera menyusuri kali. Menyeberang jembatan, lalu masuk ke tengah-tengah panggung dan memanggil anak kecil ltu. "Kamu bisa menulis?" katanya. Anak kecil itu menjawab tidak. "Aku sudah membuat puisi, tapi belum aku tuliskan." Anak kecil itu bertanya siapa lelaki itu. "Aku Vyasa. Aku membuat puisi tentang kamu." Ganesha, yang memakai topeng gajah, lalu muncul membawa buku untuk menuliskan puisi itu. Dan kisah keluarga Bharata yang agung itu pun mulai, yang dengan perlahan-lahan diarahkan menjadi kisah tentang umat manusia, kisah tentang siapa dan dimana saja. Dimulai dengan mengusut Vyasa, tokoh demi tokoh berserak, dikuntit dan dipreteli sehingga muncul esensinya yang paling dalam. Prabu Santanu, Dewi Gangga, Bhisma, Amba, Drestarata, Pandu, Yudhistira, Arjuna, Duryodana, Karna, Drona, Kresna, dan sebagainya dibeberkan dengan jelas. Cerita mengalir tangkas. Adegan sambung-menyambung kadangkala terasa terlalu bergegas. Tak ada waktu untuk mengendap dan bernapas, begitu banyak yang terjadi, semuanya penting dan bagus, dengan penuturan yang sederhana. Vyasa kadang kala menjadi tukang cerita, kadang kala menjadi salah satu pelaku. Ia berbicara kepada tokoh-tokoh dan juga bicara langsung kepada penonton. Sementara ltu, sungai kecil di latar belakang sekali-sekali gemerecik karena diinjak kaki atau diseret jubah pemain yang menimbulkan bunyi yang secara aneh mengingatkan kita pada bumi, alam, manusia, dan tiba-tiba kita dibawa ke pelosok India, Jepang, Afrika, Bali. Lantai pementasan yang dilapis tanah menggenangi ruangan dengan rasa akrab. Tak lama kemudian, unsur api yang merupakan barang tabu di panggung-panggung Barat mulai kelihatan. Ketiga unsur itu: air, tanah, dan api, terus menjiwai pemaparan Mahabharata sampai ke ujungnya. Seluruhnya yang terjadi di depan penonton bukan lagi pertunjukan, tetapi sebuah peristiwa. Sambil membangun cerita, mengenalkan tokoh, lakon menyengatkan humor dengan wajar. Kisah itu menjadi hidup, bagaikan gurita ia merangkul penonton dengan ketat, mengajak menjadi saksi mengapa perang saudara yang panjang itu terjadi. Para pemain dukung-mendukung memikul cerita, keluar-masuk sebagai pemain sekaligus pekerja panggung. Tokoh-tokoh penting tak luput mengangkat properti, menggelarkan tikar, membangun seting, memikul usungan buat pemain lain. Banyak yang merangkap memainkan beberapa peran tanpa menyembunyikan dirinya, hanya dengan mengganti kostum. Penonton melihat kecekatan, kesederhanaan yang imajinatf, disiplin yang tinggi, dan permainan kelompok yang padu. Tontonan terasa lurus dan makin lama makin teguh. Citra India terasa dari kostum yang ditata dengan bagus dan warna musik yang menyatu dengan peristiwa. Tetapi kedua elemen itu sedemikian terbukanya sehingga ia tidak berhenti pada India, tetapi bisa di mana bahkan kapan saja. Teater Barat pada umumnya ingin meyakinkan penonton bahwa apa yang ada di panggung benar-benar terjadi. Pertunjukan dipertahankan sebagai ilusi untuk menghasilkan emphaty. Peter Brook menuturkan Mahabharata mengikuti tradisi Timur, sebagaimana juga yang terasa pada teater Brecht. Tidak ada yang disembunyikan, proses dibuka, penonton dialak melihat ke dalam dapur. Anehnya, keluguan ini sama sekali tak menghilangkan emphaty. Justru penonton menjadi lebih tenggelam dan kompleks, karena sementara ia terbawa dalam peristiwa, ia juga sadar pada realita di sekitarnya, dan sadar bahwa semua itu hanya tontonan. Dengan cara seperti itu Mahabharata mengajak penonton bersikap awas. Adegan-adegan teateral, seperti pertemuan Kunti dengan Karna, menjadi dalam. Indah bukan karena ornamen-ornamennya tetapi karena dia monumental dan polos. Para pemain yang berasal dari Inggris, Senegal, Trinidad, Jerman, Yunani, Turki, Afrika Selatan, Vietnam, Prancis, India, Jepang, Polandia, dan Indonesia, muncul dengan latar belakangnya masing-masing. Yoshi Oida dari Jepang memainkan tokoh Drona dan Kitchaka dengan warna Jepang. Tapa Sudana, yang memerankan Pandu, dalam bercinta dengan Madri menyanyikan langgam Jawa, Yen ing Tawang Ono Lintang. Buat teater Peter Brook, ini masuk saja. Bekas sutradara di Royal Shakespeare London itu pernah mengaku bahwa ia ingin menyuguhkan salad, gado-gado. Tapi campuran itu tidak hanya sekadar eksperimen, sudah mencapai harmoni. Ia membebaskan teater dari keterbatasannya pada perbedaan ras, bangsa, geografis, dan kultur. Peter Brook memamerkan kedalaman teater dengan cara sesederhana mungkin. Mahabharata lalu terbeber tanpa keangkeran, tanpa keangkuhan. Adegan-adegan hebat seperti sumpah Bhisma untuk tidak kawin seumur hidup, sumpah Dewi Gandari ketika menutup matanya dengan kain hitam, kutukan kepada Pandu, lahirnya Korawa, wejangan Kresna kepada Arjuna, kematian Bhisma, dan sebagainya, dipaparkan dengan singkat. Sutradara tak berusaha memberi komentar. Ia percaya, peristiwa itu akan berbicara dengan sendirinya. Satu-satunya primadona dalam pertunjukan itu adalah cerita. Semua pemain baik Ryszard Cieslak, aktor kelas satu dari kelompok Grotowsky, yang memainkan Dhritarastha, Jeffery Kisson (Karna), George Corraface (Duryodana), Mariam Goldschmidt (Drupadi), Buruce Myers (Ganesha, Kresna), Yoshi Oida (Drona, Kitchaca), Tapa Sudana (Pandu, Salya, Cica, Maya), Vittorio Mezzogiorno (Arjuna), semuanya bermain bagus, tidak pernah bermain sendiri. Mereka muncul sebagai tim. Bagian pertama Mahabharata bernama Permainan Dadu, sekitar 2 jam 45 menit, gencar menanamkan informasi pada penonton sambil menancapkan adegan-adegan yang mengesankan. Berbagai peristiwa dan kejutan beruntun membuat bagian ini menjadi padat, kaya, dan indah. Inilah bagian yang paling berhasil dalam Mahabharata Peter Brook. Setelah istirahat dalam bagian kedua, Masa Pembuangan dalam Hutan, cerita dibiarkan berkembang sendiri, karena penonton sudah siap. Unsur tontonan dan lelucon menonjol mengimbangi kepadatan bagian pertama. Pada bagian ini penonton tertawa, menarik napas, dan menikmati Bima bercinta, Arjuna menyamar jadi wanita, Kitchaca, yang dimainkan oleh Oshida dengan lucu sekali, hendak memperkosa Drupadi. Diakhiri dengan perang meletus. Panjangnya hampir sama dengan bagian pertama. Sebelum bagian ketiga, penonton mendapat waktu untuk makan malam. Hampir seluruh lobi teater tiba-tiba berubah menjadi tempat piknik. Orang-orang duduk di lantai, bersandar di tembok pilar, dan membuka perbekalannya di lantai, lalu makan. Di bawah gedung yang diubah menjadi telanjang dan tua itu muncul suasana bersahaja yang benar-benar bersatu dengan apa yang sudah dan akan terjadi selanjutnya di atas panggung. Ini bagian dari konsep Peter Brook, meskipun untuk konsep itu harus dikeluarkan jutaan dolar. Untuk sebuah negeri kaya tempat teater menjadi bisnis, barangkali hal tersebut sebagian dari hal yang biasa. Tetapi kadang kala di sana ada ironi, persis ketika seorang penyair berkata kepada Gandhi "Kemiskinan Anda mahal harganya." Bagian ketiga bernama Peperangan. Konon, Peter Brook menyiapkan sungguh-sungguh adegan pertempuran ini. Selama tiga jam penonton diajak ke medan Kuru Setra. Melihat bagaimana Bisma gugur, rebah, bertancapkan panah-panah. Drona menuangkan kendi berisi darah, melumuri muka dan sekujur tubuhnya, sebelum kepalanya ditebas. Bima merobek dada Dursasana dan minum darahnya dengan cara menggigit pita merah dari dadanya. Bagian ketiga ini mengingatkan pada peperangan dalam film-film Kurusawa. Peter Brook, dengan barang-barang yang sederhana: roda pedati, tangga, dan dinding-dinding anyaman, berhasil menggambarkan peperangan dahsyat dan bergelora. Bagian ini kenyang oleh pemaparan gambar-gambar yang spektakuler tetapi sama sekali menghindari trik dan penggunaan teknologi panggung. Kreativitas sutradara dan stamina pemain terasa tinggi. Tetapi ada terasa yang hilang: rasa. Misteri yang tadinya hadir sebagai bayang-bayang cerita jadi kongkret dan rasional. Keindahan yang kental di bagian pertama berkurang di bagian kedua, menjadi cair, lalu mengering pada bagian ketiga. Peter Brook tidak lagi menahan dirinya dan membiarkan peperangan itu berlangsung sebagai peperangan rasa keluarga Bharata. Ia melukiskannya secara wadag, mungkin sebagai hadiah buat penontan yang telah penat duduk selama enam jam. Mahabharata berlanjut dengan masuknya Yudhistira ke surga bersama anjing, meninggalnya Dhristarashta dan berakhir dengan wafatnya Kresna. Lalu kain digelar di tengah untuk kelima pemusik yang berasal dari Jepang, Iran, dan India. Digelar juga di sekitarnya untuk semua pemain. Sementara itu, musik lembut memanggil kembali suasana India, para pemain duduk tenang, masih dengan kostum tetapi sudah meninggalkan karakter perannya. Mereka kembali sebagai pribadi-pribadi, bertegur sapa, mengunyah nyamikan yang diedarkan. Lampu-lampu kecil dinyalakan dan ditaruh di atas kubangan air. Suasana sederhana dan misteri datang kembali. Kemudian lampu-lampu itu dihanyutkan di sungai kecil. Satu per satu menjauh dan padam. Indah sekali. Ruangan menggelap, musik makin lirih, tetapi tak sempat sepi, karena penonton langsung melanjutkannya dengan tepuk tangan panjang. Peter Brook berhasil menyampaikan kisah Mahabharata, tidak sebagai seorang guru kepada murid, tetapi sebagai seorang sahabat yang sederhana. Ia tidak mengotori panggung dengan tipu daya, tidak menjadikan Mahabharata sebagai senjata untuk menghasut, memihak, dan membuat album para pahlawan. Untuk memaparkan seluruh Mahabharata dalam sembilan jam, Peter Brook memerlukan persiaan 10 tahun, dengan sembilan bulan latihan bersama pemain-pemainnya. Banyak yang harus dikorbankan. Tokoh Salya tak mendapat porsi yang semestinya. Tokoh Widura justru lenyap sama sekali, karena dianggap sudah terwakili oleh Bhisma dan Drona. Sementara itu, berbeda dengan yang dikenal dalam babad perwayangan Jawa, Drona muncul sebagai guru yang bijaksana, bukan orang yang culas. Sementara kritik pedas menghujani Mahabharata di New York, sehingga mungkin akan menyulitkan Peter Brook mendapat biaya untuk mengangkatnya ke layar perak, penonton trus saja mengalir. Ini luar biasa. Di New York, suara kritik biasanya bagaikan perintah dewa. Tapi kali ini penonton lebih percaya pada apa yang mreka lihat sendiri. Pertunjukan Mahabharata, di samping sebuah fenomena, konsep teaternya, seni laku, serta citra tontonannya buat saya adalah sebuah master piece. Putu Wijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini