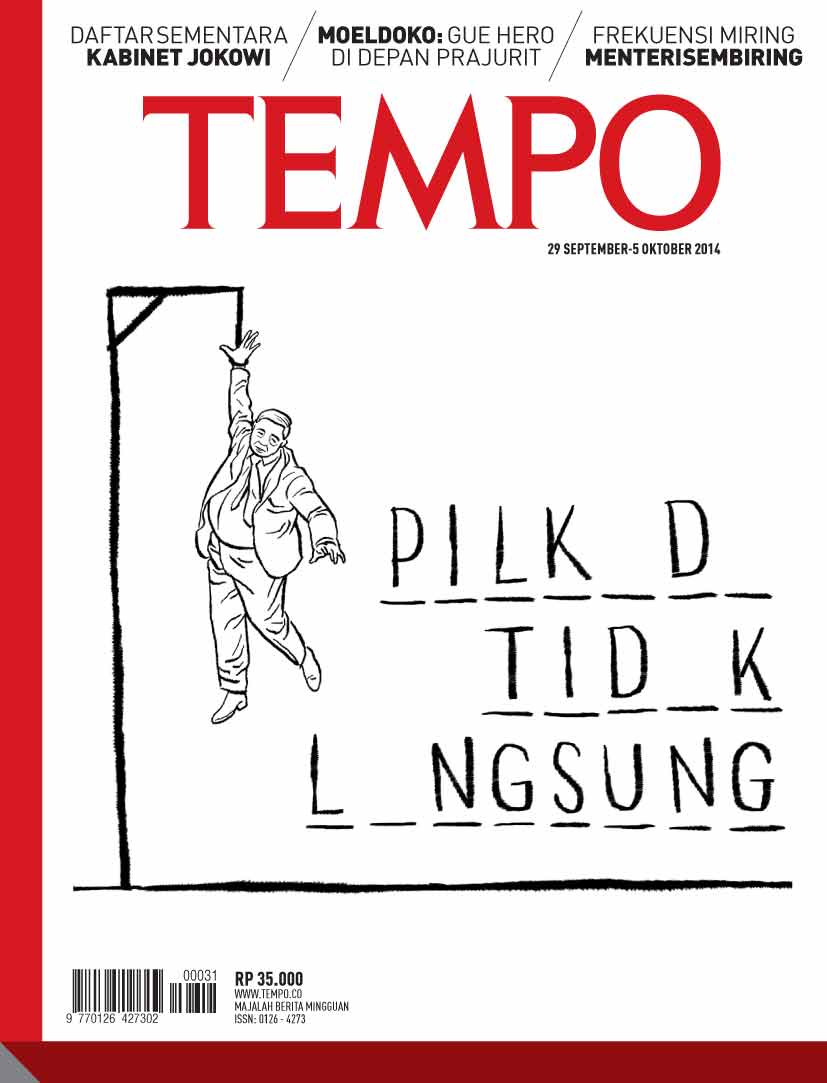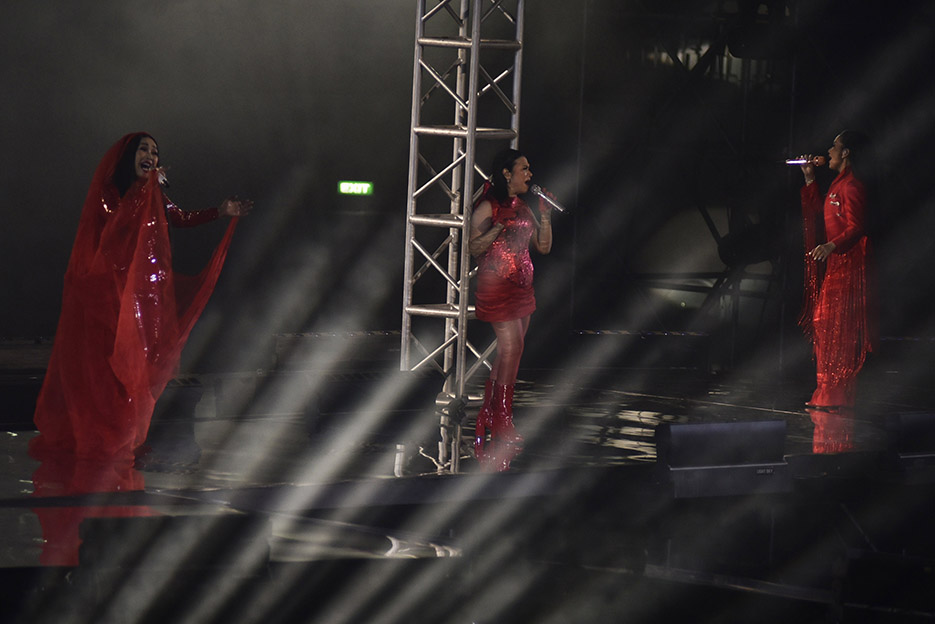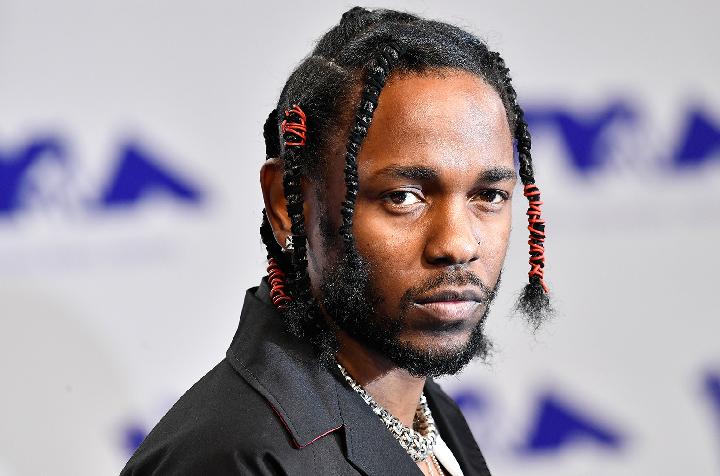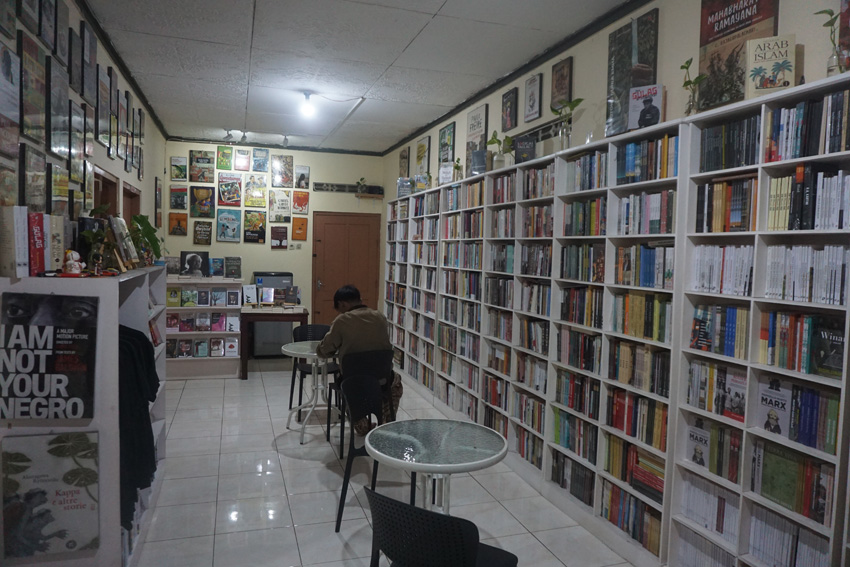Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
The Look of Silence (Senyap)
Sutradara: Joshua Oppenheimer dan Anonim
Produksi: Final Cut for Real (Denmark)
Tahun: 2014
DUA kurun sejarah paling kuat membentuk sosok bangsa-negara Indonesia. Pertama, sekitar 100 tahun lalu, sebuah badai revolusi mental besar-besaran yang disebut nasionalisme. Kedua, sekitar 50 tahun lalu, terkoyaknya landasan berbangsa tersebut dalam pembunuhan sekitar sejuta warga-bangsa oleh sesamanya pada 1965-1966.
Menuturkan kedua kurun sejarah itu tidak mudah. Selain masalahnya sendiri rumit, setiap usaha menuturkan terancam disergap perdebatan emosional. Terlebih sulit karena berbagai pembungkaman, penyangkalan, dan pemalsuan fakta oleh berbagai pihak yang terlibat atau mereka yang menolak sejarah itu dikisahkan terbuka.
Dalam novel empat jilid (tetralogi), Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) menjadi penutur paling ulung tentang awal terbentuknya Indonesia: Bumi Manusia (1980), Anak Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1985), dan Rumah Kaca (1988). Tidak ada karya sastra lain dari Indonesia yang berdampak internasional sehebat keempat novel ini. Sudah diterjemahkan dalam puluhan bahasa asing di dunia, tetralogi itu menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa asing di dunia yang mempelajari Indonesia. Di tanah airnya sendiri, semua novel ini secara resmi dinyatakan terlarang.
Dengan medium film, Joshua Oppenheimer dan mitra kerjanya yang anonim dari Indonesia hingga kini menjadi penutur paling unggul tentang sejarah 1965-1966. Mereka menyelesaikan dua film. Yang pertama, The Act of Killing (2012)—selanjutnya disingkat TAoK—atau Jagal dalam terjemahan resminya. Yang kedua, The Look of Silence (selanjutnya disingkat TLoS) atau Senyap, baru diedarkan akhir Agustus lalu di sejumlah festival di Eropa.
Tokoh utama dalam TLoS bernama Adi Rukun: pria gagah berusia 44 tahun, anak bungsu, orang tuanya lanjut usia, dan berbahasa Jawa Timuran. Adi juga seorang suami dalam keluarga dengan dua anak remaja. Ia lahir dua tahun sesudah kakaknya, Ramli, dibunuh dengan siksaan keji dalam masa pembantaian 1966. Bentuk siksaan itu dirinci dan diperagakan ulang dengan bersemangat oleh dua pembunuhnya sendiri (Amir Hasan dan Inong) untuk direkam Oppenheimer pada 2003. Hasil rekaman itu disaksikan Adi secara pribadi pada 2012.
Alur-cerita utama dalam TLoS mengikuti pengalaman Adi menjumpai beberapa pembunuh 1965-1966 di sekitar kampungnya. Dia menjumpai anak-istri Amir Hasan beberapa tahun sesudah kematian Amir. Adi juga menemui pamannya sendiri yang membantu—walau tidak langsung—para pembunuh 1965-1966 sebagai sipir penjara. Adegan paling dramatis dalam TLoS menggambarkan kegagapan para pembunuh menghadapi serangkaian pertanyaan Adi yang menggugat penjelasan dan pertanggungjawaban moral mereka atau keluarga mereka. Adi tidak berminat melakukan balas dendam, tapi membawa semacam perdamaian dan rujuk pribadi.
Film TLoS mengingatkan saya pada film dokumenter bertema serupa dari Kamboja, peraih puluhan anugerah penghargaan internasional, Enemies of the People (2009, Lemkin). Tokoh utamanya Thet Sambath, wartawan dan sekaligus ko-sutradara film yang dibintanginya. Seperti Adi, Sambath datang dari keluarga korban. Kakak dan ayahnya dibunuh dalam pembantaian oleh pemerintah komunis Khmer Rouge pada paruh kedua 1970-an, yang memakan korban nyaris dua kali lipat jumlah korban 1965-1966 di Indonesia.
Sambath tidak sekadar mampir sebentar di rumah beberapa algojo Khmer Rouge dan merekam perbincangan dengan mereka tentang cara mereka membunuh para korban. Selama 10 tahun ia mendekati dan dengan hati-hati membina kepercayaan Nuon Chea, tokoh terpenting setelah Pol Pot dalam Khmer Rouge. Tujuannya mengorek pemikiran sang tokoh tentang pembantaian oleh partainya. Hasilnya luar biasa. Nuon Chea tak hanya berbicara secara terbuka di depan kamera, dia juga menjadi sangat akrab dengan Sambath. Di ujung film, Nuon Chea ditangkap untuk diadili. Agustus lalu, pada usia 88 tahun, ia divonis penjara seumur hidup.
TAoK dan TLoS merupakan sepasang film wajib tonton bagi siapa pun yang ingin memahami Indonesia di masa lampau dan masa kini. TAoK menggambarkan Indonesia sebagai negara preman dan jagal yang hidup dengan harta dan kuasa berlimpah serta bebas dari hukum. Di situ tidak ada satu pun tokoh seperti Adi Rukun, yang menggugat banjir darah 1965-1966 yang tak terbahas dalam buku pelajaran sejarah dan pelakunya tidak pernah diadili.
Sebaliknya, dalam TLoS, tidak ada jagal yang berkeliaran di antara pejabat tinggi negara seperti dalam TAoK. Di sini, hampir semua pelaku pembunuhan 1965-1966 sudah tua renta, pikun, dan loyo serta tanpa jabatan, apalagi kekuasaan politik. Sebagian besar tak berdaya menghadapi seorang Adi yang maju sendirian (kecuali si pembuat film yang sering bersembunyi), tanpa makian, megafon, demonstrasi, atau petisi massal.
Indonesia dalam TAoK dan TLoS seakan-akan dua dunia yang berbeda. Di film pertama, para preman dan jagal menguasai negara: dari pejabat kementerian, parlemen, gubernur, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di film kedua, negara justru absen. Dalam TLoS, pembantaian 1965-1966 seakan-akan menjadi persoalan pribadi (keluargamu membunuh keluargaku). Maka, siapa pun yang berminat menonton, layak menonton TAoK dan TLoS, dan tidak hanya salah satu, untuk mendapatkan gambaran berimbang.
Bukan hanya dalam hal isi TAoK dan TLoS berbeda. Gaya bertutur keduanya pun sangat kontras. TAoK memukau jagat perfilman karena secara gemilang menggugat kaidah dan batasan yang lazim tentang film dokumenter. Ia menggugat batasan fakta dan fiksi, antara sejarah dan bualan, antara korban dan pahlawan. Seperti teater Brecht, di sepanjang film TAoK, berkali-kali penonton diingatkan bahwa yang mereka saksikan bukan kenyataan fakta sejarah apa adanya, melainkan tontonan yang sengaja dibuat-buat di depan kamera. Banyak adegan menggambarkan para tokoh menyiapkan pembuatan film. Pengambilan gambar mereka disela teriakan "cut, cut, cut".
Sebaliknya, film TLoS bertutur dengan banyak mengandalkan ilusi realisme. Seakan-akan sebagian besar yang kita tonton adalah peristiwa nyata. Seakan-akan pembuat film dan kamera tidak (sengaja) hadir di adegan yang tampil. Dialog dramatis di antara para tokohnya berlangsung spontan. Padahal sulit dibayangkan apakah seorang Adi akan menjumpai berbagai mantan algojo itu serta mengajukan berbagai pertanyaan di waktu, tempat, dan cara yang telah ditempuhnya seandainya tidak ada kamera pembuat film yang hadir di situ dan merekam semua peristiwa itu.
Untuk semua jasa mereka itulah kita layak berterima kasih sebesar-besarnya kepada Joshua Oppenheimer dan tim produksi. TAoK dan TLoS merupakan sumbangan yang tidak terkira nilainya bagi upaya bangsa ini mencicil utang sejarahnya. Pembantaian 1965-1966 memungkinkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkesinambungan, bersamaan dengan teror-negara Orde Baru selama lebih dari 30 tahun. Sebagian besar dari kita adalah penikmat dan sekaligus korbannya, dengan bentuk, aspek, dan ukuran berbeda-beda. Maka utang sejarah 1965 bukan milik seorang atau bahkan sejuta korban seperti Adi sekeluarga dan para pembunuhnya.
Ariel Heryanto, Profesor di Australian National University, penulis buku Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture (2014)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo