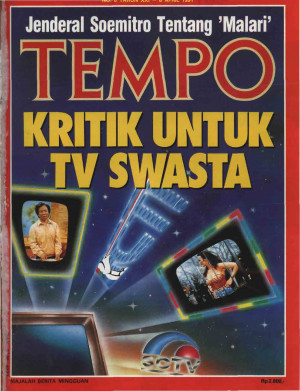DANCES WITH WOLVES Cerita/skenario: Michael Blake Juru kamera: Dean Semier Pemain: Kevin Costner, Mary McDonnel Sutradara: Kevin Costner MEMBUAT film yang lebih panjang dari rata-rata masa putar umumnya -- 1,5 sampai 2 jam -- bukan hanya tabu di Indonesia, tetapi juga di Amerika. Karenanya, aktor Kevin Costner, 35 tahun, yang memulai debut penyutradaraannya mendapat banyak tantangan. Apalagi ia hendak memainkan peran utamanya sendiri. Belum lagi film itu akan banyak mempergunakan bahasa yang memerlukan teks. Lebih-lebih film Western yang seakan-akan sudah tamat riwayatnya setelah Michael Cimino membangkrutkan United Artists dengan membuat Heaven's Gate (1980). Costner akhirnya hanya menemukan perusahaan film independen sambil membuka koceknya sendiri. Ia menyediakan belanja US$ 18 juta -- termasuk relatif murah -- untuk mengerahkan ratusan penduduk asli Indian Sioux, kuda, banteng, dan pasukan kavaleri. Setelah lima bulan yang menyangkut puluhan lokasi di wilayah Dakota Selatan, lahirlah Dances With Wolves. Awal-awalnya dielu-elukan dengan sinis oleh pasar. Tak dinyana film ini meledak. Dances terjadi pada tahun 1860-an. Letnan kavaleri John Dunbar lolos dari maut, padahal dia sudah menyongsongnya. Bahkan ia dihadiahi predikat pahlawan. Dunbar kemudian memilih ditempatkan di pos yang ada di wilayah Indian. Di sana ia bersahabat dengan seekor serigala. Dan kemudian menjadi warga suku Sioux yang sesungguhnya amat cemas pada kedatangan orang kulit putih. Tentara kemudian menangkap Dunbar dan menganggapnya pengkhianat. Apa yang membuat Dances unggul? Saya kira mula-mula adalah tema cerita. Adaptasi dari novel Michael Blake itu mengetengahkan masalah aktual dan relevan bagi Amerika yang telah banyak dosa terhadap bangsa Indian. Blake mengungkit persoalan lama yang belum pernah terselesaikan. Eksistensi bangsa Indian (Sioux) -- penduduk asli benua Amerika -- yang merupakan duri di dalam daging. Pada masa lalu saudara-saudara kulit merah itu hanya tampil di layar untuk mengotori kamera dan kemudian dibersihkan oleh para jago tembak, tapi kini lain. Dalam Dances mereka hadir sebagai daging yang berjiwa. Mereka bukan binatang, tapi manusia-manusia yang berpikir dan berbudi. Betapapun memang ada juga yang masih buas. Sebaliknya, para kulit putih di dalam film ini terasa cenderung jahat. Blake berhasil mengolah novelnya sendiri menjadi skenario yang padat, memikat, dan menyemburkan pesan. Meskipun kita mesti duduk tiga jam, tak pernah terasa ada waktu yang sia-sia. Sosok Letnan John Dunbar yang dimainkan dengan bagus oleh Costner tidak sebagaimana umumnya pahlawan dalam film Western. Ia lebih suka mereguk kesepian di sebuah benteng di kawasan Indian yang angker sambil menulis buku hariannya. Cenderung konyol. Dances bukan cerita kegagahan fisik, tetapi cerita tentang kegagahan kemanusiaan yang mengharukan dalam bingkai kekerasan. Banyak darah dipamerkan di depan mata kita dengan penggambaran langsung yang menimbulkan rasa ngeri. Tetapi Costner tidak menjadikan itu sebagai tujuan. Sasarannya adalah kasih sayang. Blake dan Costner -- mereka berkawan baik -- telah saling mengisi dalam Dances. Mereka tidak hanya berbicara tentang nasib bangsa kulit merah yang perlahan-lahan "seperti dimusnahkan", tetapi tentang kondisi manusia. Bagaimana orang berperang untuk melindungi keluarganya. Bagaimana orang berjuang untuk mempertahankan kehadirannya dalam pemusnahan yang agaknya satu ketika akan tuntas. Bagaimana orang kembali menemukan arti. Costner, sebagai sutradara dengan keterampilam aktor (The Untouchables, No Way Out) telah menggelindingkan kemanusiaan itu dengan puitis dan indah. Karakter-karakter sampingan hadir memperkaya warna dan perwatakan. Lelucon-lelucon kecil lepas liar di sana-sini menunjukkan hasil pengamatan tajam. Kejelian seorang aktor. Lalu yang mempesona adalah selera seni rupanya. Dengan juru kamera Dean Semler, Dances adalah sebuah lukisan. Kita tertelan oleh lanskap Amerika yang dahsyat. Padang rumput, bukit cadas, lautan kerbau liar bagai kartu pos molek tetapi tak kehilangan daya gigitnya. Costner berhasil memadukan kemolekan dan kebrutalan. Bagi yang kenal nasib bangsa Indian pada masa ini, film ini amat menggugah. Mereka yang hidup miskin di dalam daerah reservasi itu sebenarnya tak semata-mata butuh bantuan ekonomi. Kebutuhan mereka yang lebih mendesak adalah pengakuan pada kehadiran mereka. Costner menangkap itu. Ia menyampaikan suaranya yang lantang dengan akrab. Lalu film bukan hanya sebuah film, tetapi dialog. Namun, yang tak bisa dicegah adalah bahwa film ini tetap saja menokohkan orang putih walaupun simpatinya luar biasa terhadap penduduk asli. Awal cerita yang begitu keras dan teguh, ke belakang buat saya sedikit kendur oleh bumbu cinta yang masih terasa Hollywood. Namun, bagaimanapun, ini adalah film yang mencekam dan bagus serta dikemas dengan cermat. Putu Wijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini