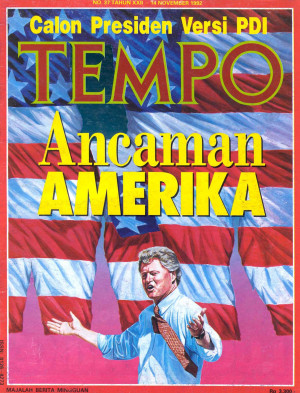MEMASUKI usia ke-24 tahun, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki mulai berbenah. Menjelang ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 10 November, taman berumput ditata rapi, sedangkan fasilitas panggung-panggung pertunjukan dilengkapi. Pintu gerbang pun baru. Khusus menyambut ulang tahun ini, diselenggarakan "Festival November", yang menyajikan tak kurang dari 20 mata acara, termasuk di antaranya seminar dua hari tentang peranan Pusat Kesenian Jakarta, yang akan diselenggarakan minggu depan. Pesta ulang tahun seperempat abad TIM tahun depan juga tengah dipersiapkan, berupa retrospeksi. Dalam posisinya seperti sekarang, peranan PKJ, yang lazim disebut TIM alias Taman Ismail Marzuki, layak dipertanyakan. Ketika didirikan 24 tahun lalu, TIM memang merupakan satu satunya sarana kesenian yang memadai dan "bergengsi". Grup kesenian yang akan tampil di sana harus melalui seleksi seperti yang kini juga masih dilakukan untuk beberapa acara. Tapi kini TIM tak lagi sendiri. Sejak tahun 1987, Gedung Kesenian Jakarta (yang berdiri tahun 1816 dengan nama Schouwburg) kembali digunakan sebagai panggung kesenian setelah bertahun-tahun tak berfungsi. Sebelumnya pun telah berdiri gelanggang remaja di lima wilayah Jakarta yang perannya lebih kurang juga sebagai panggung kesenian. Belakangan, tumbuh pula beberapa panggung "swasta" milik para seniman beken seperti Rendra, Teguh Karya, Ray Sahetapy, yang juga mementaskan kesenian berbobot. Dengan peta seperti itu, apakah pamor TIM lantas pudar? "Tidak. Panggung-panggung seperti itu tak berpengaruh apa-apa terhadap keberadaan TIM," jawab Pramana Padmodarmaja, direktur TIM. Sebab, kata Pramana, TIM tidak cuma merupakan bangunan fisik untuk kegiatan kesenian, tapi sebuah pusat kesenian yang meliputi beberapa lembaga seperti Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, dan Yayasan Kesenian Jakarta. Dan yayasan itu pun memiliki dua perangkat, yaitu Taman Ismail Marzuki dan Institut Kesenian Jakarta. "Panggung tak resmi itu justru sangat membantu untuk memperkenalkan karya-karya eksperimental atau inovatif yang memang sulit untuk dijual. Sebab, orientasi panggung seperti itu memang tidak komersial," kata Pramana. Meski begitu, karya yang pernah dipentaskan di panggung "partikelir" itu bisa saja suatu saat juga dipentaskan di TIM. Salah satu panggung "swasta" itu didirikan oleh Rendra sejak 1988 di rumahnya di Desa Cipayung, Depok, atas bantuan Kelompok Gramedia. Luasnya 25 x 10 meter, dengan kapasitas sekitar 50 penonton yang duduk lesehan di tikar. Beberapa di antara penonton adalah tetangga Rendra yang hanya mengenakan kain sarung dan bertelanjang kaki. Suasananya santai dan akrab. Di sanggar Bengkel Teater itu, pekan lalu, dipentaskan Possessed Dispossed oleh kelompok Entr'acte Theatre dari Australia, yang kemudian juga main di TIM. Selain dua lampu sorot, digunakan pula 10 obor, 10 lampu minyak, dan 3 petromaks. Keuntungan panggung ini, menurut Rendra, bebas dari tetek-bengek birokrasi yang kini juga masih dihadapi pengelola TIM. Sejak tiga tahun lalu aktor Ray Sahetapy yang memimpin Teater Oncor juga membuat panggung pertunjukan di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. "Dengan panggung seperti ini, seniman lebih bebas dan spontan," ujar Ray. Menurut suami aktris Dewi Yull ini, panggung seperti itu merupakan alternatif bagi budaya instant atau kemasan. Teguh Karya, sutradara Teater Populer, juga punya panggung "partikelir" di sebuah rumah antik berarsitektur campuran Banten-Portugis. Dihuni sejak tahun 1983, rumah itu terletak di tengah kampung di kawasan Kebon Pala, Jakarta Pusat. Di sanalah tempo hari dipentaskan Jayaprana karya Jeff Last, sebelum dimainkan di TIM. Ia juga membangun panggung lain di sanggarnya yang lama di Kebon Kacang, Jakarta Pusat, yang sudah dihuni sejak tahun 1972. Setelah direnovasi, panggung itu diberi nama "Teater Dalam Gang Tuti Indra Malaon", untuk mengenang almarhumah Tuti, salah seorang aktris seniornya. Panggung itu ditata seperti halnya teater "resmi" dalam format lebih kecil. Arenanya berukuran 5 x 6 meter, diapit tempat duduk berkapasitas 80 penonton di kiri-kanannya. Di ketiga sisi panggung itu juga ada balkon kecil. Suasana setengah resmi itu dilengkapi dengan adanya tempat penjualan karcis seharga Rp 5.000 dan Rp 2.500. Meski begitu, para penonton tampaknya masih merasakan suasana keakraban. Menurut Teguh, munculnya panggung seperti itu wajar saja. Sebab, gagasan dasarnya ialah menyajikan seni pertunjukan rakyat yang dapat disuguhkan di rumah, di bawah ponon, di mana saja. "Justru hal ini membuktikan bahwa kesadaran berkesenian sudah makin tinggi, karena orang menyadari manfaat kesenian," tambahnya. Kesadaran seperti itu niscaya juga berkat kehadiran TIM, yang selama ini harus diakui telah menciptakan suasana berkesenian. Karena itu, menurut Rendra, peranan TIM sudah cukup baik sebagai pusat kesenian meskipun dananya terbatas. Dalam keterbatasan dana itu, TIM tak bisa melaksanakan semua gagasan. Tapi dedikasi pengelolanya patut dihargai, yang "dengan gaji sedikit dan peralatan seadanya, mereka mengelola TIM dengan gagah berani". Budiman S. Hartoyo dan R. Fadjri
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini