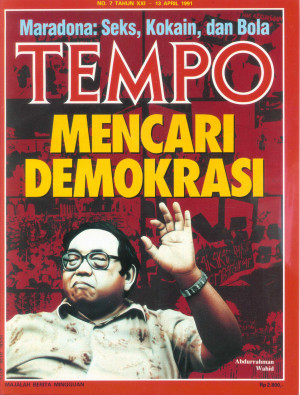Dalam sebuah buku kecil bernama Sihanouk Reminisce, Pangeran Norodom Sihanouk mengungkap persahabatannya dengan 13 kepala negara dari seluruh penjuru dunia. Dengan blak-blakan ia mengenang pertemuan, persahabatan, dan kadang menyentil sahabat-sahabatnya itu. Berikut ini sosok Sukarno, Mao Zedong, dan Ceausescu di mata Sihanouk. Kemudian dikunci dengan wajah Sihanouk sendiri yang 45 tahun menjadi negarawan, tulisan Bernard Krisber. SUKARNO SAYA berjumpa Sukarno pertama kali dalam pertemuan bersejarah Konperensi Asia-Afrika di Bandung, April 1955. Waktu itu saya kurang fasih berbahasa Inggris. Sebab, saya memilih belajar bahasa Latin dan Yunani daripada bahasa-bahasa modern, di sekolah menengah Prancis di Saigon. Saya bercita-cita menjadi guru besar kebudayaan Prancis, Latin, dan Yunani. Untunglah, Sukarno ahli bahasa yang jempolan. Bukan hanya bahasa Belanda dan tentu saja Indonesia -- termasuk bahasa Bali, tapi Sukarno juga fasih berbahasa Prancis dan Pali, bahasa suci India kuno yang tetap digunakan oleh biarawan Budha, termasuk di antara sesama biarawan Khmer kami. Inggrisnya juga bagus. Karena itu, kami dengan cepat bisa berkomunikasi, sejak pertemuan pertama itu, tanpa perlu penerjemah bahasa Prancis. Sukarno lebih suka mengeja namanya dengan "Su" daripada "Soe" (ini panggilan dari orang-orang Belanda). Jadi, bisa diucapkan "Su" juga dalam bahasa Prancis. Meski begitu, ia tetap memakai "Soekarno", dengan selalu mengingatkan cara menyebut namanya. Kalau kamu kenal Sukarno, tidak bisa tidak kamu akan menyukai dia. Begitu juga 140 juta rakyat Indonesia, yang sampai kejatuhannya, memuja dia sebagai seorang bapak. Dia seorang pembicara berbakat. Kalau itu dilakukan dalam bahasa tanah airnya, ia mampu menyalakan semangat massa. Dan dengan bahasa Inggris siapa pun pendengarnya akan terpikat dan terpesona. Kata-katanya bermagnet dan kerap dibumbui kutipan kalimat tokoh-tokoh dalam sejarah. Sukarno mengucapkan langsung dalam bahasa aslinya, umpamanya "l'exploitation de l'homme par l'homme". Saya sendiri, benar-benar, mendengar dengan tekun setiap kata-katanya. Sukarno seorang yang tahu estetika dan dendi. Ia suka mengenakan pakaian seragam Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata. Untuk menghindari ejekan kalau memasang semua bintang penghargaan, ia menyederhanakan dekorasi dadanya dalam satu papan. Dan menyempurnakan penampilannya, ia menyembunyikan rambutnya yang tipis di balik pici walau ia harus menderita kepanasan karena itu. Sukarno menggandrungi Kamboja dan mengunjungi kami lima kali dalam enam tahun antara 1959 dan 1965 -- kunjungan terbanyak dibanding pemimpin bangsa lainnya. Sebaliknya, saya dan istri saya, Monique, membalas tiap kunjungannya, dan yang pertama konperensi AA itu. Sukarno benar-benar seorang pahlawan dalam perjuangan anti penjajahan, tapi begitu ia menjadi pemimpin negara ia mulai memimpin dengan gaya "Pasha" -- atau lebih cocok dianalogikan dengan seorang raja Jawa kuno di masa jaya. Tidak ada yang lebih gembira dengan gaya hidupnya selain rakyatnya, yang mengagumi dia, dan saya sendiri tidak kaget dengan sikapnya yang seperti raja. Yah, meskipun saya senang berada di antara rakyat Khmer, saya juga tak mengelakkan bahwa saya punya darah raja. Yang paling disukai Sukarno adalah Phnom Penh, Angkor, dan Sihanoukville. Saya sering mendengar ia menanyakan kepada anggota partainya, mengapa mereka tidak membuat Jakarta sebersih dan seindah Phnom Penh. Tentu saja, ibu kota kami lebih kecil, lebih mudah diatur. Untuk mengawalnya ke mana-mana kami memilihkan guru-guru sekolah yang paling menarik dari semua daerah. Tetapi reputasinya, sebagai playhoy, kurang nampak, paling tidak selama kunjungannya ke Kamboja. Yang tampak, Don Juan ini sebagai gentleman sejati yang tidak pernah mencoba menaklukkan terang-terangan salah satu di antara gadis-gadis kami -- secantik apa pun. Monique diam-diam terpesona pada Sukarno, seperti halnya terhadap Nikita Khruschchev. Itu ternyata menyalakan api dalam hati Sukarno yang gampang terbakar. Ini secara tidak langsung menyebabkan kami akrab. Ternyata, ia juga sering mengatakan bahwa satu-satunya wanita yang pantas dikaguminya adalah istri saya Monique. Tapi kesetiaannya pada persahabatan adalah pencegah setiap godaan dalam soal ini. Tak urung juga reputasinya dalam soal perempuan membuat orang bertanya, "Kenapa Sukarno sering betul ke Kamboja?" Saya percaya jawaban yang sederhana: Sukarno adalah orang yang menghargai persahabatan murni. Ia boleh jadi punya teman-teman pasangan orang ternama seperti suami istri Nasser, Tito, Ho Chi Minh, Zhou Enlai, Mao Zedong, dan Raja-Ratu amat cantik Sirikit. Tapi dalam diri saya dan Monique, ia menemukan lebih dari sekadar teman biasa. Ia menemukan seorang abang dan adik. Di Istana Kerajaan di Phnom Penh, ia dikelilingi oleh banyak wanita Indonesia, baik anggota rombongannya maupun staf kedutaan. Mereka bersama wanita Kamboja pilihan menyiapkan hidangan Indonesia kesukaannya. Bersama kami, ia merasa seperti di rumah. Ia bebas mencopot jaketnya, membiarkan kancing bajunya terbuka, telanjang kaki, mendinginkan tubuh dengan kipas angin -- ia benci AC, dan menikmati pijatan wanita Kamboja dan Indonesia yang hormat dan perhatian padanya. Kawan-kawan Arab, Eropa, atau komunis Cinanya tidak bisa menandingi ini. Meskipun saya kawannya, saya harus mengakui bahwa ia punya kesalahan. Saya yakin ia, kalau masih hidup, akan menyadarinya kini. Yaitu, khususnya, ketidakmampuannya membangun bangsa dan ekonominya setelah memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Pengganti Sukarno, Presiden Soeharto, dapat mencapai pembangunan fisik dengan lebih jauh. Uniknya, Presiden Soeharto menyadari bahwa rakyatnya memiliki cinta yang dalam terhadap tokoh karismatik Sukarno. Soeharto, baru-baru ini, memberikan penghargaan pada Sukarno atas perannya dalam sejarah bangsa. Tumbangnya Sukarno pada 1966 tidak mengurangi kesetiaan di kalangan rakyat pada si Bung, sebagaimana juga kecintaan mereka -- seperti yang saya rasakan. Dengan menganggap saya teman dekat dan benar-benar saudara, ia mengungkapkan rahasia perkawinannya yang ruwet. Tahun 1955, saya mendapat kehormatan untuk bertemu istri pertamanya, Nyonya Fatmawati, tokoh penting dalam perjuangan memerdekakan bangsa. Wanita yang dicintai dan dihormati oleh banyak orang Indonesia. Ia wanita cantik, terhormat, dan bermartabat. Sayangnya, pertemuan singkat pertama ini hanya satu-satunya perjumpaan kami. Sukarno punya empat istri. Hartini, istri keduanya yang cantik dan menyenangkan. Dewi, istri Jepangnya yang pintar, yang dipetik pengusaha Jepang dari Copacabana Tokyo untuk Sukarno. Dan Haryati, yang daya tariknya tak saya lupakan. Pada 1967, Sukarno mengalami saat sulit. Ia menjalani tahanan rumah setelah digulingkan tentaranya. Dewi meninggalkannya, kembali ke Jepang. Dalam keadaan itu, setidaknya, menurut laporan pers, Sukarno tetap mempertahankan reputasi asmaranya. Ia kawin dengan anak sekolah yang cantik, umurnya baru 16, hanya beberapa saat sebelum mengembuskan napas terakhir. Sukarno dan saya punya selera yang sama dalam hal musik, nyanyian, dongeng, dan kerajinan. Bersama Hartini, ia mengawal saya dan Monique ke berbagai kawasan Nusantara. Kami melakukan perjalanan bersama dengan pesawat udara, kapal, dan mobil ke Bogor, Yogyakarta, Surabaya, dan pulau-pulau menarik dari Sumatera ke Bali. Saya ingat suatu ketika di pesawat, angin kencang bertiup diiringi kilat dan geledek. Hartini mabuk udara. Saya mendekati dan menyarankan untuk memanggil dokter pribadi yang ikut bersama kami. Tapi, Hartini menjawab -- dengan suara yang cukup keras untuk didengar Sukarno -- bahwa perhatian saya sudah cukup mengobatinya. Hartini jelas tidak naksir saya, tapi ia sedang menyindir suaminya yang begitu sibuk memperhatikan Monique. Sukarno punya banyak pengetahuan tentang seni Khmer, peradaban Angkor, dan tarian klasik Kamboja. Putri saya, Bopha Dewi, menyajikan tarian klasik yang indah itu untuknya, di Kamboja dan Indonesia. Ia juga bisa tarian klasik Indonesia. Betapa kagetnya saya suatu kali ketika Sukarno menyatakan tertarik pada putri saya itu dan bermaksud melamarnya. Sayangnya, Bopha, yang suka bergonta-ganti suami itu, masih mencintai suami ketiganya. Saya katakan pada Sukarno agar bersabar. Barangkali Bopha bisa menjadi istri kelima atau keenamnya -- Hartini tidak keberatan. Saya katakan pada Sukarno, Bopha suka berganti suami semudah mengganti ban mobil. Mendengar ini, Sukarno dan Hartini tersipu. Hanya pria yang sangat terlatih bisa meredam persaingan dan kecemburuan di antara istri-istrinya. Suatu ketika, Ratna Sari Dewi meminta kami mengundangnya bersama Bung Karno, untuk makan malam. Karena tahu kami menghargai Hartini, Bung Karno mengatur makan malam tak resmi di salah satu ruang Istana Merdeka. Monique merasa tidak enak soal ini dan khawatir apa jadinya kalau Hartini tahu. Acara baru berjalan setengah, Dewi dengan secercah senyum dan wajah lesu mohon diri. Badannya sakit, katanya. Ia lalu rebahan di sofa di ruang duduk. Bung Karno kebingungan, seperti Robert Taylor menghadapi Greta Garbo dalam film Wanita dengan Bunga Camelia. Adegan melodramatis ini hanya berlangsung sesaat. Sebab, beberapa menit kemudian, Dewi sudah merasa sembuh dan bergabung lagi untuk menghabiskan pencuci mulut. Sebelum meninggalkan kami, ia memeluk Bung Karno. Beberapa hari kemudian Hartini mendengar pengkhianatan kami -- entah siapa yang membisikinya. Saya kena getahnya, ketika berlangsung peringatan ke-10 Konperensi AA, di Istana Bogor, nyonya rumah Hartini melemparkan senyum masam pada saya. Dan kemudian, setelah meninggalkan tempat perjamuan, ia mendekati Zhou Enlai, bukan saya. Tampaknya, kesamaan nasib yang mendekatkan saya dan Sukarno. Tahun '50-'60-an, kebijaksanaan luar negeri Sukarno dan saya hampir sama kelihatannya. Kami berdua sama-sama anti-penjajahan, anti-imperialis, dan mendukung gerilyawan Vietkong dan Vietnam Utara dalam perjuangannya "memerdekakan" Vietnam Selatan dan mempersatukan keduanya. Tapi, ada sedikit perbedaan. Pasalnya, anti-imperialisnya Sukarno lebih banyak dalam kata-kata daripada "sesungguhnya". Sedikit banyak Indonesia yang luas itu "memberi hati" pada Amerika. Sementara itu, Kambojaku yang sempit diapit antara dua negara yang kuat dan mengancam, Muangthai, dan Vietnam Selatan. Keduanya bukan hanya sekutu AS, tapi juga bersekongkol dengan gerilyawan Khmer Serei, yang dilatih dan dilindunginya. Baik Sukarno maupun saya menghadapi persoalan dalam negeri yang sama. Kami sama-sama menyeimbangkan persaingan antara militer sayap kanan dan komunis revolusioner. Masing-masing dari kami mencoba menampung kedua faksi ini dalam pemerintahan, dan berharap mereka bisa belajar kompromi dan rukun. Sukarno memperlihatkan kebajikan yang tak semestinya dan bahkan menyetujui bangunnya Partai Komunis Indonesia. Tak ragu lagi ini usaha mengimbangi pengaruh militer yang makin kuat. Di Kamboja, meskipun pemerintah memanfaatkan komunis intelektual, saya tetap keras terhadap oposisi dari kalangan pengikut Mao, anti-kerajaan dan gerakan revolusioner ekstremis Khmer Merah. Di antara mereka berdiri tokoh-tokoh Ieng Sary, Saloth Sar (nama lama Pol Pot), Son Sann, dan Nuon Chea, grup yang dikenal sebagai "Kelompok Empat" Demokratik Kamboja. Agaknya, Sukarno menyokong Vietkong dan perjuangan Vietnam untuk menyenangkan pihak oposisi yang anti-imperialisme. Hingga yang tampak cuma kulit dan teori daripada yang sebenarnya. Ini kelihatan, misalnya, dalam kunjungan Sukarno ke Hanoi. Sering Sukarno bertemu dengan Ho Chi Minh. Di sana ia dimanjakan dengan serombongan artis cantik. "Delegasi artis-artis dari Vietnam Utara" datang ke Indonesia, termasuk cewek cantik Tonkin. Sukarno menerima delegasi dengan mencium kedua pipinya! Dukungan kuat saya, sebaliknya, bukan basa-basi. Saya memberikan tempat berlindung di perbatasan Kamboja-Vietnam Selatan. Saya memerintahkan tentara saya mengangkut senjata-senjata dari Cina dan Soviet di Sihanoukville ke markas Vietkong. Tapi kedua cara pendekatan anti-imperialis kami, akhirnya, gagal mencegah tindakan brutal tentara. Sukarno lebih dahulu jatuh dan kemudian pemerintahan saya. Namun, saya tidak senaif Sukarno memandang komunis dapat dibujuk untuk mencapai tujuan mereka secara demokratis. Ia percaya dapat menciptakan masyarakat tempat komunis bisa dipercaya untuk memainkan sebuah peran demokratis. Akibatnya, ia terlalu simpatik dan akomodatif terhadap PKI, yang sebetulnya berbahaya dan pengaruhnya makin luas. ABRI, yang kuat dan konservatif secara politis, mulai protes dan protes makin keras. Bagaimanapun pikiran Sukarno dan saya, akhirnya, kami sama-sama gagal. Suatu hari, Sukarno mengundang saya dan Monique ke kapalnya untuk memancing di pelabuhan Jakarta. Tamu yang lain, istri keempatnya Haryati, seorang jenderal antikomunis penting dan istrinya yang pro-Barat, juga pengikut Mao, Aidit. Sukarno pikir, saya bisa "mempertemukan" jenderal kanan yang berpengaruh ini dengan Aidit. Kendati saya raja berpendidikan Prancis, saya juga teman akrab Mao Zedong dan Zhou Enlai. Lebih jauh, saya punya menteri-menteri komunis di pemerintahan saya. Meski usaha itu patut dipuji, Sukarno gagal mengakurkan tentara yang reaksioner dan "peliharaannya" -- PKI yang berkiblat ke Cina. Tragisnya, salah perhitungan ini menyebabkan "Presiden Seumur Hidup" ini terjungkal dari singgasananya. Saya sendiri gagal menyatukan kedua sayap ini. Untuk Monique sendiri pertemuan ini membuatnya gelisah. Di situ ada Haryati. Akan jadi urusan lagi kalau bertemu Hartini -- yang menurut saya mata-mata pribadinya lebih canggih daripada CIA-nya Nixon atau Kissinger. Tidak setiap pemimpin asing mencintai Sukarno seperti saya. Teman dekat saya Charles de Gaulle, umpamanya, menganggap Sukarno seorang playboy. Sikap De Gaulle berbeda-beda dalam soal ini. Ia menutup akses ke Prancis untuk Sukarno, tapi membukanya untuk playboy yang lain, saya. Masyarakat Barat mengerutkan kening. Perhatian Sukarno pada saya tak pernah terputus, dalam masa sulit sekalipun. Tahun 1965, lima tahun sebelum kematiannya, ia mengirimi saya surat dan bingkisan indah sekali: Sebuah keris berukir dari emas dan gading. MAO ZEDONG Ketika Mao Zedong meninggal, September 1976, ribuan telegram dan pesan berisi perasaan turut berdukacita mengalir dari berbagai penjuru dunia. Sayangnya, nama saya tak tertera sama sekali dalam daftar nama orang yang bagaikan tak ada akhirnya itu. Tak hadirnya nama saya dalam daftar tersebut sungguh mencolok sehingga saya mendengar pemerintah Cina sangat tersinggung dan menyangka saya tak kenal perasaan terima kasih. Padahal, sebenarnya pada ketika itu saya sedang berada dalam sekapan Khmer Merah .... Pertemuanku yang terakhir dengan Ketua Mao terjadi pada September 1975, lima tahun setelah saya terpaksa menyingkir ke Cina sebagai akibat dari kudeta Lon Nol pada 1970. Masa pengungsian di Beijing itu diperpanjang dengan adanya kudeta balik Khmer Merah. Setelah Pol Pot sepenuhnya yakin bahwa seluruh oposisi telah dilumatkan, ia mengundang saya untuk balik ke Pnom Penh. Buat membujuk saya agar mau kembali ke Kamboja, Pol Pot mengutus Khieu Samphan dan Ny. Ieng Sary dengan membawa undangan resmi. Saya menerima ajakan itu tanpa ragu sedikit pun karena kerinduan akan tanah air dan kesadaran ingin menolong rakyat saya sendiri. Setelah mengambil keputusan itu layak bagi saya untuk mengucapkan kata-kata perpisahan kepada sang ketua. Ia menerima kami di ruang bacanya, dan di kamar yang kecil itu terlihat buku berserakan tak teratur di atas kursi-kursi dan meja. Tampaknya, tak seorang pun berani membereskannya. Saya berani mengatakan pemandangan itu sangat mengesankan. Jelas pada waktu itu Mao telah jadi seorang yang invalid, cara bicaranya tersendat-sendat. Ia hanya bisa mengucapkan beberapa kata saja kepada kami dan itu dilakukannya dengan susah payah. Untuk bergerak saja ia memerlukan pertolongan dua perawat. Mao memegang tangan saya untuk waktu yang cukup lama. Ia mengucapkan beberapa kata selamat datang yang kedengarannya seperti bersungut-sungut. Juru bahasa yang hadir di situ juga mengalami kesukaran untuk menerjemahkannya kepada kami. Untunglah, dalam ruangan itu hadir pula seorang spesialis yang mengerti suara yang keluar dari mulutnya. Ia pun dapat mengartikan gerakan mulut dan bahasa isyarat Mao ke dalam kata-kata. Sang ketua kelihatannya sangat letih. Raut wajahnya kelihatannya tak wajar, gerakannya sangat lamban atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Kepalanya seperti hancur ketika ia mencoba tersenyum. Keadaannya sungguh mencekam. Di ruang itu dalam upacara perpisahan tersebut hadir pula Khieu Samphan dan Ny. Ieng Sary. Ada juga sahabat lama saya yang setia, Penn Nouth bersama istrinya, dan istri saya Monique. Dengan susah payah orang besar itu mencoba mengucapkan pesan terakhirnya secara langsung kepada saya dan rekan-rekan saya. Ia meminta kepada kedua pemimpin Khmer Merah itu agar tidak memperlakukan dengan buruk kepada saya, Monique, dan anak-anak kami, Siamoni dan Nartindrapong. Ia juga meminta agar kami tak dipaksa mengerjakan tugas-tugas berat. Ia juga meminta saya agar tidak mengundurkan diri dari kedudukan presiden Khmer Merah Kamboja. Pada saat itulah Mao menyampaikan pesan patetis dengan menggunakan tangannya. Dengan menggunakan tangan kanannya ia melipat ke belakang satu jari tangan kirinya. Barangkali yang dimaksudkannya adalah menggambarkan secara fisik bahwa antara Sihanouk dan Khmer Merah hanya ada satu perbedaan, tetapi ada empat persamaan kepentingan. Ia mendesak agar saya tak meninggalkan rekan-rekan Khmer Merah saya, dan saya harus mendukung rezim Khmer Merah baik di muka rakyat Khmer maupun di muka masyarakat dunia. Jadi, Mao telah memilih untuk mendukung Khmer Merah seperti dukungannya terhadap Revolusi Kebudayaan, gerakan merusak yang diilhami oleh Jiang Qing, istrinya. Pada masa yang bersamaan ketika Revolusi Kebudayaan berlangsung, Zhou Enlai telah memperingatkan para pemimpin Khmer Merah mereka akan menghadapkan rakyat Khmer dengan kesengsaraan kalau mereka menganut langkah-langkah kriminal dan berlebihan seperti Revolusi Kebudayaan. Zhou adalah tokoh cerdas dan bijaksana yang selalu menjabat perdana menteri di bawah Mao. Saya merasa risi dengan permintaan Mao agar saya setia. Sebagai seorang komunis yang keras dan pionir revolusi kaum proletar, ia telah berharap agar saya mendukung kamerad-kameradnya yang Khmer Merah di Pnom Penh. Jawaban saya atas permintaannya itu tak tegas, tapi juga tak negatif. Saya mencoba menahan diri saya hanya dengan memperlihatkan senyuman sebagai tanda menghormati anjurannya. Mao, kalau saja ia masih hidup, mestinya tak sadar bahwa tak lama setelah itu para pengikut Pol Pot telah melakukan perbuatan yang jauh lebih kejam ketimbang apa yang dilakukan istrinya, Jiang Qing, bersama dengan Kelompok Empatnya. Ia juga pasti tak akan dapat membayangkan bahwa begitu balik di Kamboja, saya dan keluarga saya dijebloskan ke tahanan rumah dan semua hubungan kami dengan dunia diputuskan. Saya harus mengatakan bahwa Jiang Qing tak pernah mengurus suaminya yang jauh lebih tua darinya. Jelas Jiang Qing hanya memperhatikan kesehatannya sendiri ketimbang kesehatan suaminya. Pada masa-masa kejayaannya dokter-dokter tak pernah beranjak jauh daripadanya dan selalu menyediakan obat baginya. Sebaliknya, Ny. Liu Shaoqi benar-benar mengabdi kepada sang ketua. Sebelum dia dan suaminya yang begitu dihormati jatuh martabatnya sebagai akibat Revolusi Kebudayaan, wanita yang bisa saya katakan suci itu selalu mengurus Mao tanpa ragu. Mao sendirilah yang mengatakan, Ny. Liu mengurusnya bagaikan seorang anak wanita yang begitu berbakti terhadap ayahnya. Saya tak pernah membayangkan sedikit pun bahwa nasib buruk akan menimpa pasangan Liu. Mungkinkah pengabdian yang begitu tinggi Ny. Liu terhadap Mao justru telah menyalakan api kebencian dan kecemburuan Jiang Qing kepadanya? Jiang Qing pribadilah yang memperhinakan Ny. Liu di atas panggung di muka umum dan kemudian Jiang Qing pribadi yang memerintahkan agar wanita itu dipenjarakan. Tapi, terhadap kami Ny. Mao selalu baik dan bersikap manis. Ia selalu memuji-muji Monique sebagai wanita cantik. Mao adalah orang dengan perawakan tinggi. Tanda-tanda bahwa ia orang udik jelas. Dibandingkan dengan Zhou Enlai ia kurang canggih, kurang "halus" dalam tingkah laku, dan kurang " bangsawan". Walaupun senyuman Mao kurang canggih, ia jujur dan menyenangkan. Wajahnya dengan dahinya yang lebar memancarkan kecerdikan dan kearifan. Matanya dengan pandangan menusuk dan tak berhenti bergerak seakan mengajak kita bermain kucing mengejar tikus. Sayangnya, dalam permainan itu yang jadi tikusnya adalah saya. Hubungannya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama bawahan dan orang-orang biasa, berbau hubungan ayah dan anak. Ia bukan tipe diktator dan bahkan tidak tiranis. Dalam keadaan-keadaan yang tak resmi orang bisa salah mengira bahwa dia seorang kepala desa. Saya berjumpa untuk pertama kalinya dengan Zhou Enlai pada 1955 di Bandung semasa konperensi Asia-Afrika. Setahun kemudian saya bertemu dengan Mao di Beijing. Dengan didampingi Zhou saya berada di mobil dan ketika saya masuk gerbang, Mao sudah menunggu di pintu rumahnya menyambut saya. Ia telah keluar dari rumah untuk menyambut saya secara pribadi. Itu merupakan suatu kehormatan tinggi dan kejutan bagi saya. Pada waktu saya pulang, Mao mengantarkan ke mobil dan kembali masuk ke rumah hanya setelah mobil saya lenyap dari pandangannya. Kapan saja saya berkunjung ke Mao, baik di Beijing maupun Beidahe, sebuah tempat peristirahatan tepi pantai yang menjadi favorit para pemimpin Cina, ia selalu mempertahankan sikapnya yang menghormati saya. Hanya saja pada waktu kami bertemu pada September 1975, ketika fisiknya sudah payah, kami tak bisa berdekatan dengannya. Apalagi mendampingi saya menuju ke mobil pada waktu meninggalkannya. Zhou Enlai tak pernah mengajak saya berbicara tentang ideologi atau malah mencoba membujuk saya untuk menerima komunisme. Tapi, Mao pernah mencobanya. Ia selalu menganjurkan saya untuk lebih agresif. Saya teringat pada suatu hari di Beidahe ketika kami makan siang bersama dan kemudian meneruskan pertemuan itu dengan omong-omong selama beberapa jam. Tiba-tiba setelah cukup lama ngobrol ke sana-kemari, Mao menanyakan pada saya suatu pertanyaan yang menusuk. "Malang," katanya memulai, Anda, Sihanouk, pemimpin tujuh juta rakyat, sebuah negara kecil. Anda juga memeluk Pancasila, lima prinsip hidup berdampingan hidup secara damai. Kemudian Anda mengeluh tentang tetangga-tetangga Anda yang lebih kuat, Muangthai dan Vietnam Selatan. Menurut Anda, kedua negara itu mengancam kedaulatan negara Anda. "Andaikan Anda pemimpin sebuah negara besar, katakanlah dengan rakyat sebanyak 50 juta dan punya tentara yang kuat. Lalu, apakah Anda akan begitu bijaksana, rendah hati, dalam membela diri?" Dari pertanyaan itu saya mengerti bahwa saya harus menunjukkan kepadanya bahwa saya memiliki juga bakat politik. Saya tak berani mengatakan kepada veteran revolusi itu bahwa saya yakin seseorang tak bisa mencapai tujuannya baik dengan sikap setengah-setengah maupun dengan cara konfrontasi. Karena itulah saya hanya menjawab, "Tidak, Pak Ketua. Kalau saya punya angkatan bersenjata yang kuat dan saya yakin bisa mengalahkan mereka, saya tak akan rendah hati. Saya akan keras. Tidak bijaksana kalau saya hanya berdiam diri saja, lantaran di masa lalu baik Vietnam maupun Muangthai pernah merebut wilayah kami. Saya akan membalas." "Baik," katanya. "Bagus, Anda jujur. Saya menyukai Anda." Pada 1970, setelah kup Lon Nol, Mao secara serius mengatakan bahwa saya harus menjadi seorang komunis. Ia menyatakan itu dengan kata-kata seperti, "Anda pantas jadi komunis. Sejak sekarang pertimbangkanlah untuk memeluk komunisme." Lalu saya jawab, "Pak Ketua, Saya tak paham akan komunisme, Marxisme, atau Leninisme. Saya pernah membaca buku kecil merah Anda, dan itu sudah cukup. Saya setuju saja dengan gagasan-gagasan Anda, tapi saya tak paham akan komunisme. Saya tak akan menjadi seorang komunis yang baik." Tapi, ia mendesak terus. Dengan perantaraan penerjemah bahasa Prancisnya yang pandai ia mencoba membujuk saya untuk membaca singkatan-singkatan ajaran komunis, yang maksudnya agar komunisme dan Leninisme mudah dimengerti. Tapi, pada akhirnya, saya hanya mengatakan kepadanya, "Pasti, Pak Ketua, saya tak bisa. Saya terlalu tua untuk mengganti falsafah hidup saya. Saya sangat percaya akan Budhisme. Maafkan saya." Saya kira ia telah kehilangan segala harapannya kepada saya. Karena itulah ia kemudian berkata, "Lupakan saja, saya tetap menyukai Anda." Mao sering mengatakan kepada saya bahwa ia tak menganjurkan kultus individu terhadapnya. Ia mengatakan justru rakyatlah yang ingin mengagung-agungkannya. Secara pribadi ia tak menyukai gambar-gambar, potret, dan patungnya yang dibuat untuk menghormatinya. Tapi, ia berpikir bahwa ia harus menurut pada kemauan rakyat. Jadi, adalah sesuatu yang tragis untuk menyaksikan gambar, potret, dan patung-patung itu lenyap begitu ia wafat. Tapi, paling tidak gambarnya yang begitu dikenal masih tergantung di gerbang Tiananmen -- tempat yang memang layak untuk menghormatinya. Tak ada seorang pun yang bisa menolak bahwa Mao adalah pahlawan revolusioner. Sebelum meninggalkan tribun, Presiden Mao, ditemani rekan Marsekal Lin Biao dan Perdana Menteri Zhou, dengan ramah mengajak saya berbicara selama setengah jam. Kata-kata mereka jelas bertujuan mendorong semangat saya yang mulai lemah itu, untuk memperbaiki nasib tanah air saya. Marsekal Lin Biao, yang bertubuh pendek, kurus, dan sikapnya membosankan, tampak tidak menarik di samping Mao yang bertubuh besar dan si sopan Zhou. Lin Biao sering menyela perkataan Mao dan dengan suara keras menyatakan ia anti-Amerika. Ia mencoba meyakinkan saya bahwa bangsa Cina dan kekuatan bersenjatanya akan terus mendukung "sampai tercapai kemenangan akhir". Cina akan memberikan bantuan bagi kelompok perlawanan terhadap Lon Nol. Mao dan Zhou adalah pribadi yang sangat kontras. Karisma Zhou terletak pada kepriayiannya. Mao dihormati karena rasa cintanya pada rakyat Zhou hanya punya sedikit kesalahan politik dalam menangani persoalan Cina. Mao, yang lebih suka bertindak dengan tangan keras, melakukan beberapa kegagalan diawali dengan "Lompatan Jauh ke Muka" tahun '50-an. Kesalahan terakhir Mao yang paling besar "membiarkan" Jiang Qing dan Kelompok Empatnya menjerumuskan negara dalam kekacauan. Saya ragu bahwa Mao memang bermaksud menyakiti rakyatnya, tapi tampaknya ia pada waktu itu mungkin tidak menguasai keadaan secara menyeluruh. Massa telah menganggapnya sebagai seorang Dewa Komunis, yang tidak bisa melakukan kesalahan. Tapi saya telah belajar bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Kelemahan Mao yang paling fatal harus dicari di sesuatu yang mirip drama Shakespeare: menangani wanita. NICOLAE CEAUSESCU Natal 1989, seratus kilometer dari Bukarest, Rumania, Presiden Nicolae Ceausescu dan istrinya Elena divonis mati oleh pengadilan darurat. Eksekusi olek sepasukan kecil tentara Rumania berlangsung tak lama setelah pengadilan kilat itu. Saya sudah lama "diangkat" sebagai "teman" oleh Ceausescu. Tokoh ini mendukung perjuangan saya melawan imperialisme Amerika, sejak hari pertama kudeta Lon Nol 1970. Seperti diketahui, kudeta -- yang dilakukan saat saya berkunjung ke Uni Soviet -- itu menumbangkan kepemimpinan saya di Kamboja. Waktu itu seluruh Eropa -- termasuk Blok Soviet -- langsung mem- berikan pengakuan pada rezim Lon Nol. Kecuali tiga negara: Yugoslavia di bawah Presiden J.B. Tito, Albania, dan Rumania yang dipimpin Ceausescu. Ceausescu saat itu sudah dikenal di dunia sebagai tokoh yang berani menunjukkan ketidaktergantungan pada "saudara tua Uni Soviet". Ia menolak hadirnya pasukan Kremlin di negaranya, dan ia juga mengecam invasi Moskow ke Cekoslovakia selama "musim semi Praha" 1968. Tahun 1972, dengan kapasitas sebagai satu-satunya kepala negara Kamboja paling bonafide, saya melakukan kunjungan resmi ke Yugoslavia, Albania, dan Rumania. Di negeri komunis yang disebut terakhir sambutan paling hangat -- baik dari rakyat maupun pemimpinnya -- saya terima. Saya senang pada Ceaucescu, yang saat itu berusia 54 tahun. Saya sendiri baru 50 tahun. Tubuhnya agak pendek untuk ukuran Eropa. Ia paling-paling cuma satu sentimeter lebih tinggi dari saya yang 163 cm. Ceausescu bertampang menyenangkan, dengan rambut pirang berombaknya. Nicolae Ceausescu mengajak ke berbagai kota dan provinsi di Rumania -- yang pada 1972 merupakan negara berpemandangan elok dan masih makmur. Bukarest, yang disebut-sebut sebagai "Paris kecil", dengan monumen-monumen dan gereja kuno yang terawat baik, adalah kota yang bersih dan menawan. Jalan-jalan rayanya dihiasi tanaman kembang, taman-taman bersuasana romantis, dan toko-toko penuh barang. Kami berempat -- Ceausescu dan saya, Elena dan Monique -- juga mengunjungi desa-desa, tempat para petani tampak hidup bahagia dan relatif makmur. Hampir semua orang tinggal di rumah-rumah kecil khas Rumania, dengan kebun sayur mungil. Hadirnya banyak bunga, tampaknya, bukan karena kunjungan saya semata karena jelas tanaman kembang sudah ada jauh sebelumnya. Di kota, seperti halnya di pedesaan, menurut perasaan saya, sih, rakyat Rumania tampak terbuka, gembira, dan bersemangat. Tampak jelas mereka mencintai pemimpinnya, Ceausescu. Semua itu tanpa paksaan, karena mereka menyambut teman saya ini, ke mana pun ia pergi, dengan tangan terbuka. Saya merasa dekat dengan rakyat Rumania dan sampai kini masih menyimpan perasaan sayang pada mereka. Anehnya, mereka bernasib, dalam kualitas tertentu, hampir sama dengan rakyat Kamboja -- walau mereka berbeda kebudayaan. Kini saya merasa ikut sedih dengan nasib malang masyarakat Rumania, yang menderita dan disiksa Ceausescu, selama tahun-tahun akhir pemerintahannya. Selama kunjungan saya tahun 1972, 1974, dan 1975, kami banyak membincangkan masalah konflik AS-Khmer. Ceausescu kerap menyatakan ia lebih menyukai "kompromi" antara dua kubu yang berlawanan. Dan saya menanggapi dengan menyebut justru pihak Nixon-Lon Nol lah yang menolak bernegosiasi dengan kelompok perjuangan Kamboja saya. Tahun 1974, Ceausescu mengizinkan Hang Thun Hak, PM rezim Lon Nol, berkunjung ke Bukarest. Ceausescu mengundang saya untuk bertemu dan bernegosiasi dengan Hang Thun Hak. Saya tolak dengan dua alasan: saya lebih suka berembug langsung dengan pihak Amerika dan karena Tentara Merah Khmer saat itu sudah merebut 80% wilayah Kamboja. Saya kembali ke Rumania pada 1982 dan 1987, dua tahun sebelum kematian Ceausescu, untuk kunjungan paling akhir. Pada 1982, setelah lepas dari "tahanan rumah" rezim Pol Pot, saya merasa terkejut dengan perubahan yang terjadi di Rumania: negeri ini jauh merosot keadaannya ketimbang sedasawarsa sebelumnya. Rakyat Rumania di sepanjang jalan yang kami lalui banyak yang enggan menatap iring-iringan mobil yang kami tumpangi. Bahkan tak sedikit yang berani sengaja memberikan punggung mereka pada Ceausescu. Tak ada lagi sambutan meriah untuk Ceausescu. Tampak jelas rakyat Rumania, yang pada 1970-an masih ceria, sudah bungkam dan tidak demonstratif. Tentunya hadir pula gerombolan penyambut yang diatur oleh pemerintah Bukarest. Tapi tampak jelas keterpaksaan dalam sikap mereka. Saya juga melihat kemerosotan baik di Bukarest maupun di provinsi: tempat gereja-gereja tua yang cantik dibumiratakan. Kami sekaligus merasa malu dan merasa bersimpati pada rakyat Rumania, saat itu. Lebih tak enak karena kami disambut dan dijamu mewah oleh Ceausescu. Suatu pagi, Monique dan saya mendampingi tuan rumah kami berlayar dengan kapal mewah di sebuah danau. Rakyat, yang berjajar di tepi, secara sengaja memunggungi kami. Monique dan saya tak punya banyak pilihan, selain pura-pura tidak menyaksikan sikap permusuhan rakyat Rumania pada pasangan pemimpinnya itu. Pasangan Ceausescu tampak sedih, tak lagi dicintai dan dikagumi rakyat mereka. Tuan rumah kami tak banyak bicara selama berlayar, dan satu-satunya topik pembicaraan cuma "problem Kamboja". Saya ke Rumania lagi pertengahan musim dingin 1987. Musim salju di Paris begitu molek. Bahkan di Beijing dan Pyongyang musim dingin tidak menyedihkan. Tapi di Bukarest musim dingin itu tampak mengibakan. "Paris kecil" kini begitu gelap dan menakutkan pada malam hari. Tentara dan polisi disiagakan di berbagai tempat. Tak diragukan lagi, mereka berjaga-jaga melindungi Ceausescu. Tak tampak banyak orang di jalan-jalan dan di taman-taman. Kedai kopi, bar, dan restoran -- yang biasanya sibuk dan penuh uap panas minuman -- tutup. Saya merasa seperti tamu khusus pada pertunjukan film Dracula versi Hollywood. Nicolae Ceausescu tampak menyukai obrolan kami soal masalah Kamboja, seperti biasanya. Ia akan nyerocos terus soal topik itu, bahkan saat jamuan makan malam kenegaraan. Di tengah alunan lagu dari orkes kamar ternama Rumania, ia sengaja menaikkan suaranya, agar tertangkap oleh kuping saya. Saya tak pernah berhasil menggiringnya ke topik pembicaraan lain. Dan sementara menjawab sopan sanjungan saya atas keberhasilan pembangunan nasionalnya, Ceausescu tak pernah mau mendiskusikan politik dalam negeri pemerintahannya secara mendalam. Saya merasa topik masalah Kamboja merupakan peluang bagi Ceausescu untuk "melarikan diri" dari masalah politik dan sosialnya sendiri. Monique dan Elena hampir selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan politik saya dengan Ceausescu -- yang lebih banyak Kambojanya ketimbang Rumania. Elena kadang-kadang nimbrung dengan sepatah dua kata dalam diskusi kami. Dan pernyataan Elena pada umumnya mendukung pendapat sang suami. Elena tak bisa disebut berwajah cantik. Tapi ia tampil anggun dan tampak jelas sangat menguasai peraturan main "kelas atas". Ia menyukai busana bagus dan berdandan dengan selera bagus. Ia cerdik dan cerdas -- bahkan saat mendiskusikan masalah Kamboja, Elena banyak tahu kenyataan-kenyataan yang ada dan mampu mencerna berbagai segi yang berbeda dalam masalah kami itu. Ceausescu beberapa kali di tahun 1988 mengundang saya lagi ke Rumania. Untuk mendiskusikan lebih lanjut masalah Kamboja, katanya. Undangan ini diulang pada musim semi 1989. Ceausescu mengatakan, melalui dubesnya di Pyongyang, "Paris sangat dekat dengan Bukarest," dan karenanya saya bakal mudah mampir ke Bukarest. Saya dengan susah payah berhasil menolak undangan-undangan itu, dengan alasan jadwal penuh selama menyiapkan Konperensi Kamboja di Paris. Baik Monique maupun saya tetap menganggap Nicolae dan Elena Ceausescu sebagai teman. Begitu pula sebaliknya dari pihak pasangan Rumania itu. Tapi dengan berjalannya waktu, pada saya dan istri tumbuh perasaan tak enak dan malu mengingat masalah sosial dan ekonomi Rumania -- saya tidak menyebut kondisi politik, karena suasana politik cuma saya ketahui dari koran Prancis yang saya baca. Yang jelas, kualitas kehidupan sangat merosot di Rumania. Setelah kematian Nicolae dan Elena Ceausescu yang tragis, saya tentunya masih akan tetap menghormati Ceausescu, yang telah mendukung perjuangan kelompok perlawanan Kamboja. Tapi saya masih bingung, soal yang satu ini: mengapa Ceausescu begitu besar perhatiannya pada masalah kemiskinan Kamboja. Waktu saya tanya hal ini, ia menjelaskan bahwa dirinya mengecam segala jenis campur tangan kekuatan asing di Dunia Ketiga, seperti Kamboja, karena ia juga ingin Rumania tetap independen. Hanya saja saya sempat terpukul dengan begitu kontrasnya kebijaksanaan politik luar negeri Ceausescu dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam negeri yang diambilnya. Bagaimana mungkin Ceausescu begitu tulus menyatakan keprihatinannya atas masalah rakyat Kamboja kami, padahal pada saat yang sama ia menindas rakyatnya sendiri? Bagaimana mungkin ia begitu jahat pada rakyatnya yang pernah sangat mencintai dirinya? Tampaknya, Nicolae mempunyai obsesi ketakutan akan utang luar negeri Rumania. Ketakutan yang menyebabkan ia pada tahun '70-an -- sampai saat ia mati -- untuk secara drastis meningkatkan ekspor dan seminimum mungkin melakukan impor. Kebijaksanaan ini dimaksudkan sebagai salah satu cara mempertahankan sistem komunis -- tak peduli keputusan ini akan menyengsarakan rakyat Rumania. Tapi upaya mengurangi utang luar negeri ini tampak konyol mengingat pabrik-pabrik besar baru justru dibangun, termasuk bangunan-bangunan megah, seperti istana kediaman, yang tak ada gunanya. Ia mendirikan sejumlah gedung mewah untuk dirinya sendiri dan kerabat serta konco-konco dekatnya. Pada saat yang sama ia menghancurkan bangunan-bangunan tua bersejarah yang indah. Saya tidak berupaya membuat alasan-alasan buat teman saya, pasangan Ceausescu yang tetap mendapat tempat terhormat di hati saya dan istri. Saya cuma merasa saat Nicolae menjadi lebih tua, keseimbangan mentalnya agak terganggu. Kemampuan penalarannya merosot tajam. Banyak tokoh terkenal dalam sejarah dikenal sinting. Tapi bila penyakit jiwa menimpa kepala negara, jutaan orang harus menderita. Itulah yang terjadi di Rumania. Namun, kita harus ingat bahwa ada kejahatan yang lebih besar dari apa yang dilakukan Ceausescu: kejahatan yang dilakukan Hitler dan Pol Pot, misalnya. Kemalangan rakyat Rumania juga disebabkan karena Nicolae sangat dipengaruhi istrinya, Elena. Di bawah tekanan sang istri ia melancarkan kebijaksanaan perusakan. Kekuatan apa yang dimiliki wanita ini sehingga bisa menyetirnya sedemikian rupa? Walau saya menghormati pikiran-pikiran Elena, saya tidak menganggap ia menarik. Sudah lama saya ingin menemukan kekuatan Elena yang tersembunyi, tapi akhirnya soal kekuatan apa sebenarnya yang dimiliki Elena atas suaminya masih tetap merupakan misteri. Kekuatan Elena itu merupakan kekuatan iblis. Karena Elena cenderung condong pada totaliterisme, kediktatoran, tidak toleran, komunis yang tidak manusiawi, dan memuja diri sendiri. Nicolae dan Elena merupakan pasangan "megalomaniak". Kini saya sering mengenang percakapan-percakapan kami dulu, saat Ceausescu tak pernah tampak kehilangan kendali emosinya. Elena pun dulu selalu tampil menyenangkan, tenang, anggun saat menemani Monique dan saya. Saya sedikit lega, menyaksikan saat-saat akhir mereka di muka juru tembak: mereka tetap menunjukkan sikap berani dan terhormat. SIHANOUK PEMBUAL JAGOAN Tentang Sihanouk sendiri dalam buku Sihanouk Reminisces, ditulis oleh Bernard Krisher kepada biro Newsweek di Tokyo. PERKENALAN dengan Pangeran Norodom Sihanouk tak akan pernah terjadi jika saya tidak mengenal Sukarno terlebih dahulu. Sementara itu, pertemuan dengan Sukarno sungguh tidak terduga dan lucu. Ketika itu tahun 1963. Sebagai koresponden yang masih hijau di Tokyo, saya ditugasi memburu Tunku Abdul Rahman dan Sukarno yang sedang berunding di sana. Tunku Abdul Rahman mudah dicari. Sebagian besar waktunya dihabiskan di masjid, berdoa. Tinggal menunggu di sana, beres. Sukarno sungguh susah ditemukan. Ia pergi ke mana-mana: berbelanja, ke bioskop, atau tiba-tiba menyelinap pergi dengan beberapa cewek. Dan setiap malam, di rumah-rumah geisha yang terkenal di Tokyo saat itu, seperti Shinraku, ada pesta besar. Belum lagi penjagaan ketat pengawalnya. Mungkin sedang beruntung, tiba-tiba saya memergoki Sukarno di toko barang antik Imperial Hotel. Ia sedang menawar sebuah patung kuno cantik. Sukarno tampak ngiler betul dengan patung itu. Dan di depan belasan orang-orangnya, ia menunjuk sang pemilik toko dan dengan suaranya yang keras dan khas ia berteriak, "Saya presiden Indonesia, pemimpin 100 juta orang. Saya ingin diskon 50 persen!" Segera saya ambil notes dan berusaha mencatat. Tiba-tiba Sukarno berpaling dan menunjuk saya, ia bertanya apa yang saya lakukan. Saya jawab saja bahwa saya adalah koresponden Newsweek. "Saya tak suka Newsweek. Mereka cuma menulis kebohongan," teriak Sukarno, sementara dua pengawalnya segera meringkus saya. "Tapi ... saya suka kamu," katanya tiba-tiba. Lalu ia meminta notes saya, dituliskannya di sana, I Like You, dan ditandatanganinya. Kemudian semuanya beres. Saya menyatakan keinginan mengunjungi Indonesia. Ini kesempatan besar, sebab saya tahu wartawan Barat, apalagi Amerika, tak diizinkan masuk negeri itu. Setelah mendesak bahwa saya tak akan membuat berita bohong, Sukarno setuju. Sejak itu, beberapa kali saya mengunjungi Jakarta dan persahabatan saya dengan Sukarno semakin erat. Pangeran Sihanouk mengunjungi Jakarta pada Agustus 1964, ketika saya kebetulan di sana. Di Istana, Sukarno memergoki saya dan langsung membawa saya ke Pangeran. Dengan hangat, ia memperkenalkan saya pada tamunya. Saya manfaatkan kesempatan, minta visa untuk mengunjungi Kamboja. Seperti Indonesia, Kamboja menutup pintu rapat-rapat bagi wartawan Barat. Bunga-bunga pujian yang diberikan Sukarno amat manjur. Tanpa ragu, Sihanouk setuju mengundang saya masuk negerinya. Esoknya, visa untuk sebulan sudah keluar, stempel besar menghiasi halaman paspor saya "Atas perintah Monseigneur". Kata Prancis ini adalah panggilan sehari-hari Sihanouk di Kamboja. Saya baru berkesempatan memanfaatkan harta karun ini pada Februari 1965. Satu bulan di Kamboja benar-benar pengalaman yang luar biasa. Sayangnya, saya gagal mewawancarai Sihanouk. Bisa jadi, waktunya memang salah. Atau memang seharusnya saya tak berada di Phnom Penh. Mungkin cuma gara-gara rayuan Sukarno, sang pangeran merasa tak enak menolak saya. Meskipun begitu, saya tetap memburunya dalam berbagai kesempatan di mana ia muncul di depan umum. Misalnya saja, ketika melakukan inspeksi ke tangsi militer atau membuka sekolah baru. Dalam tiap kesempatan itu, kami selalu berjabatan tangan dan berbicara tentang acara itu. Ke mana pun saya pergi, saya selalu tersentak melihat bagaimana hebatnya popularitas Sihanouk di mata rakyatnya. Ia dipuja dan disembah rakyatnya, dan ia menyukainya. Kecintaan rakyat itu bukan hal yang dibikin-bikin. Rakyat benar-benar mengultuskannya secara manusiawi. Ia tak memerlukan patung atau monumen. Pokoknya, ia adalah pangeran dalam arti yang sepenuh-penuhnya dari kata itu. Pangeran. Dan sang pangeran ternyata adalah orang yang sangat sensitif, terutama terhadap pers Barat. Kesan saya, tak ada hal lain yang lebih mengusik sang pangeran dibandingkan dengan kritik pers asing atas dirinya atau bangsanya. Satu contoh masih saya ingat benar bagaimana sang pangeran murka gara-gara sebuah artikel di sebuah koran ekonomi terbitan Amerika. Surat kabar itu memuat daftar peringkat negara-negara Asia berdasarkan Gross National Product atau GNP yang dihasilkannya. Celakanya, daftar yang berdasarkan statistik PBB itu menempatkan Kamboja sebagai juru kunci. Kamboja ada di bawah Laos, tetangganya yang sama miskinnya. Bahwa hal itu berdasarkan fakta dari PBB tak membuat Sihanouk menerima kenyataan. Surat protes segera dikirim ke koran itu, bahkan juga ke PBB. Esoknya, semua headline koran dan Radio Kamboja berisi surat protes Sihanouk. Selain sangat sensitif terhadap pers, ada hal lain yang saya lihat sangat menonjol dari Sihanouk. Untuk melindungi kemerdekaan Kamboja, ia mengembangkan "seni" untuk bersikap tidak konsisten dan tak terduga-duga. Pada pandangan saya, kebimbangan-kebimbangan yang tampak dari tindakan Sihanouk itu sebenarnya sangat konsisten dan diperhitungkan dengan cermat. Seperti seorang pemain akrobat berjalan di tali, ia harus selalu menyesuaikan keseimbangan dengan ayunan tali tempat ia berpijak. Itulah yang dilakukan Sihanouk. Setiap ia bangun pagi, situasi yang dihadapinya berbeda dengan kemarin. Setiap kali itu pula Sihanouk harus menyesuaikan diri. Untuk itu, ia harus menjadi pembual yang paling jagoan. Dan ia memang jago membual. Celakanya, Amerika tak pernah mengerti Sihanouk dengan kepribadiannya yang terombang-ambing meloncat ke sana-kemari itu. Sebenarnya, kunci untuk memahami Sihanouk adalah mendudukkan masalah bahwa dia adalah pemimpin negara kecil yang tak berdaya. Negeri yang sangat membutuhkan bantuan asing. Bantuan itu akan datang, bahkan negara-negara besar akan berlomba untuk memberi bantuan. Namun, harga yang harus dibayar adalah menjadi sekutu dan masuk ke kubu si pemberi bantuan. Bagi Sihanouk, satu-satunya strategi yang paling ampuh adalah menjadi orang yang paling tak bisa ditebak. Memainkan satu sisi melawan sisi yang lain, dan tetap membuat semua orang bertanya-tanya. Ini pekerjaan rumit di mana Sihanouk telah menjadikannya sebagai "seni" dan ia adalah masternya. Sayang, strategi lompat sana-sini ini tak selamanya manjur. Ketika api perang Vietnam mulai menelan Kamboja, dan ketika Henry Kissinger (Menteri Luar Negeri Amerika saat itu) merekayasa komplotan untuk menyingkirkan sang pangeran, Sihanouk harus menghadapi kenyataan. Ia tersingkir. Dalam sebuah artikel di Newsweek menjelang penyingkiran Sihanouk, saya menulis, Sihanouk yakin Amerika akan segera terusir dari kawasan Asia. Sayangnya, saya membuat satu kesalahan total dalam artikel yang sama. Kesalahan yang saya sesali sampai sekarang. Kesalahan ini pula yang menjadi awal retaknya hubungan saya dengan Sihanouk saat itu. Untuk membuat tulisan saya seimbang, saya mengutip desas-desus yang beredar di kalangan intelektual dan mahasiswa yang menentang keluarga Raja. "Ibu Pangeran Sihanouk dikenal sebagai orang yang gila uang. Disebut-sebut pula, ia menjalankan beberapa konsesi bisnis di kota, termasuk beberapa rumah bordil di pinggiran." Tujuan membuat tulisan itu menjadi berimbang tercapai. Pembaca di Amerika menganggap liputan itu pas, dan publik mendapatkan gambaran tentang situasi sebenarnya di Kamboja. Tidak bagi Sihanouk. Ia habis-habisan menyerang artikel itu dan saya. Tentu saja serangan Pangeran itu menyulut kemarahan massa. Demonstrasi besar meletus, kaca-kaca jendela Kedutaan Amerika dipecahkan. Saya dituduh sebagai mucikari. Hanya beberapa hari sesudah itu, Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Artikel saya disebutkan sebagai salah satu sebab serius, selain serangan di perbatasan yang menyebabkan beberapa penduduk tewas. Sejak itu saya juga dilarang masuk Kamboja. Sebenarnya saya tetap menaruh hormat pada Pangeran. Tetapi, sebagai wartawan, saya tak ingin minta maaf. Saya kira tulisan itu cukup adil dan saya tak punya maksud jahat. Saya juga khawatir, permintaan maaf secara langsung akan disebarluaskan olehnya di dalam Kamboja, lalu ke seluruh dunia. Kalau itu terjadi, buntutnya jelek bagi Newsweek yang akan terlihat sangat lemah dan bodoh. Untung, saya menemukan satu cara. Saya lalu berbicara dengan Sirik Martak, Duta Besar Kamboja di Tokyo, yang cukup berpengaruh. Berbarengan dengan itu, saya juga mengirim satu kartu ulang tahun buat Pangeran. Saya sudah mulai bisa mengikuti cara berpikir orang Asia, isyarat tidak langsung itu sudah cukup untuk menyampaikan perasaan saya. Benar, dari Martak, saya juga mendapat isyarat bahwa Pangeran menerima salam saya dan pintu Kamboja terbuka lagi. Saya bisa datang kapan saja. Dan ternyata kepergian saya kembali ke Kamboja tak pernah terjadi. Tak lama setelah itu, Lon Nol dan Martak merancang kudeta dan menjatuhkan Pangeran. Maka, Sihanouk mendukung Khmer Merah untuk menentang rezim Lon Nol-Martak. Tetapi, ketika Khmer Merah menang, Pangeran dikenai tahanan rumah dan lima orang putranya terbunuh. Sejak itu, saya tak pernah lagi bertemu muka dengan Sihanouk sampai tahun 1979 -- ketika Khmer Merah akhirnya tersapu habis oleh tentara Vietnam. Saat itu, Pangeran berada di PBB untuk berbicara soal Kamboja. Tiba-tiba saja telepon saya berdering, Pangeran meminta saya menemuinya di Plaza Hotel, New York. Di situlah kami berpelukan dan berciuman, sebagaimana kebiasaan Kamboja. Seharian kami bersama, sebuah reuni yang luar biasa. Saya lalu merekam sebuah wawancara yang panjang. Karena tak mendapat tempat di Newsweek, wawancara itu saya berikan ke Shukan Asahi sebuah majalah Jepang yang sangat luas peredarannya. Wawancara yang sampai menyita hampir seluruh halaman depan, koran sore Asahi Evening News. Dari situ, hampir semua koran dan kantor berita di seluruh dunia mengutipnya. Dari situ pula orang tahu, bertahun-tahun penahanan dan isolasi di istana ternyata tak sedikit pun mengurangi semangat Pangeran untuk mendapatkan kembali tahtanya dan membangun negerinya. Sejak itu, pers Barat -- yang dulu selalu dicacinya, dituduhnya menyebarkan kebohongan -- sekarang sudah berubah menjadi sekutunya yang terbesar. Ketika pemerintah negara-negara Barat belum menyatakan apa-apa, pers sudah menyebarluaskan segala hal tentang Sihanouk dan menggalang dukungan. Sudah menjadi sifat dunia, orang menyukai dua hal. Underdog dan orang yang berhasil mempertahankan diri terhadap kemelut. Sihanouk bisa termasuk ke dalam dua hal itu. Sebagai teman yang menulis buku ini, saya terdorong untuk meninggalkan kebebasan, sebuah kebiasaan dalam jurnalistik. Saya merasa cukup adil jika Pangeran juga memiliki hak untuk mengubah beberapa hal, terutama jika saya membuat kutipan-kutipan yang mungkin bisa mempermalukannya. Tapi saya benar-benar terkejut dan senang -- dan kekaguman saya pada Pangeran menjadi semakin dalam -- ketika ia usai membaca bab pertama yang saya tulis ini. Pesannya, "Saya tak perlu memeriksa kesan-kesan tentang Sihanouk, saya menghargai sepenuhnya kebebasan Anda untuk menilai dan menuliskannya."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini