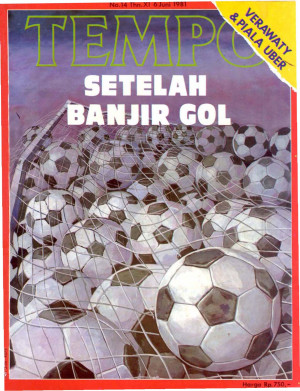SUTRADARA Sjuman Djaja masygul. Ia mengurung diri di kamarnya di
Hotel Bumi Hyatt, Surabaya. Film Bukan Sandiwara yang
disutradarainya ternyata gagal meraih satu Citra pun dalam
Festival Film Indonesia di Surabaya (27-30 Mei). Padahal
sejumlah pengamat menjagokan film itu dengan Jenny Rachman
(pemeran utama), Lukman Hakim Nain (juru kamera), dan Sjuman
Djaja sendiri, untuk memperoleh Citra.
Dewan juri -- diketuai Sjamsoe Soegito -- tentu saja punya
pilihan lain (lihat box). Film Bukan Sandiwara gagal memperoleh
penilaian tinggi, demikian seorang juri, karena dianggap kurang
mencerminkan sikap nasionalisme. Maklum katanya, film itu
terlalu mengagungkan pembuatan bayi tabung yang berasal dari
sperma orang Jepang. Jika hal itu menjadi alasan pokok
penilaian, tentu saja menggelikan.
Tergesa-gesa
Sekalipun demikian, juri melihat suatu hal positif dari
penggarapan film dewasa ini. Para sineas dinilainya telah
cenderung "meletakkan kekuatan film pada segi cerita, isi, serta
keindahan pengungkapannya." Tapi juri mengeluh karena film
Indonesia masih jarang mengemukakan cerita kalangan masyarakat
bawah. Penyelesaian cerita dikritiknya sering kali dikerjakan
dengan mudah. Juga logika cerita, menurut juri, masih diabaikan.
Berbeda dengan juri FFI (1980) di Semarang, juri FFI di Surabaya
menjabarkan penilaiannya di atas kertas 2,5 halaman folio saja.
Sedang juri FFI di Semarang mencatatkan penilaian di atas kertas
60 halaman dengan segala penjelasan yang njlimet. "Penjurian
tahun ini memang agak tergesa-gesa," kata seorang juri FFI kali
ini.
Dari sejumlah karyawan dan artis film, tentu saja, ada yang tak
puas dengan keputusan juri. Bintang film Roy Marten dan Farouk
Afero, misalnya sangat kecewa. Keduanya mengatakan bahwa pilihan
juri terhadap pemeran utama pria dan pemeran pembantu pria tidak
tepat. Tapi sudahlah "kalau saya protes nanti dikira mengada-ada
karena kalah," kata Roy Marten, 29 tahun.
Sekalipun kalah, Roy Marten menyarankan agar sistem penjurian
diubah. Untuk menilai setiap film dengan cermat dan teliti,
diusulkannya agar diadakan penilaian pra nominasi dengan waktu
yang tidak terlalu sempit. Ia jelas menyesalkan cara kerja juri
FFI kali ini yang menilai 54 film cerita dan 10 film dokumenter
hanya dalam tempo 24 hari. Dalam waktu sempit itu dianggapnya
juri tidak mungkin cermat mengamati.
Koran Kompas dalam tajuk rencananya ( 13 April) juga pernah
mempersoalkan waktu penilaian yang sempit itu. Setiap hari juri,
tulisnya, harus menilai duasampai tiga film dan
mempertanggungjawabkan tiga belas unsur dalam film itu. Cara
penjurian semacam itu "suatu pekerjaan yang mengandung tuntutan
kelewat tinggi." Maka Kompas mengusulkan sistem penjurian pra
seleksi dengan melibatkan karyawan dan artis film di dalamnya.
Sejumlah kalangan memang pernah tidak percaya terhadap
integritas dan otoritas beberapa orang yang duduk dalam dewan
juri. Ada yang menyebut bahwa juri anu dan itu jarang sekali
menonton film Indonesia. Mereka baru menonton film Indonesia
kata kalangan itu, justru di saat peniiaian diselenggarakan.
Mudah-mudahan tuduhan tersebut tidak benar. Anggota juri FFI di
Surabaya terdiri dari: Dr. Mulyono Gandadibrata, Mochtar Lubis,
Dr. Alwi Dachlan, H. Misbach Jusa Biran, Frans Haryadi, Sjamsoe
Soegito dan Duduh Durachman. Mereka telah dipilih Yayasan
Festival Film Indonesia, tentu saja berdasarkan kualifikasi
kecakapan yang dimiliki masing-masing. Siapakah di antara mereka
- jika ada -- yang jarang menonton film Indonesia?
Tapi hanya soal kecakapan dan keputusan juri yang mengurangi
selera makan. Festival di Surabaya itu berlangsung semarak dan
menyenangkan. Menteri Penerangan Ali Moertopo bersama sejumlah
karyawan dan artis film (sekitar 300 orang), terbang ke sana
dengan Boeing Jumbo 747 Garuda.
Hari pertama tiba (27 Mei) di Surabaya itu, para artis film
segera diarak keliling kota. Dengan penuh antusias masyarakat
setempat mengelu-elukan bintang pujaan mereka sepanjang jalan.
Hari berikutnya, mereka diarak ke Sidoardjo, Gresik dan
Bangkalan (Madura). Di berbagai tempat itu mereka secara
sukarela memberikan hiburan gratis. Mengantar para artis film
itu, Menteri Ali Moertopo senantiasa berpidato dengan penuh
semangat. Ia kelihatan tidak letih sekalipun baru saja sembuh
dari serangan jantung. Sambutan masyarakat "sangat luar biasa,"
katanya.
Setiap malam panggung utama di Stadion Gelora 10 November juga
diisi acara seronok yang dipadati pengunjung. Jika stadion di
Surabaya itu penuh, masyarakat masih bisa menyaksikan panggung
hiburan terbuka di sepanjang Jl. Pemuda dan depan Kantor
Gubernuran. Pemilihan "Cak dan Ning" Surabaya pun
diselenggarakan. Semua acara itu diselenggarakan gratis. Panitia
FFI (dengan biaya Rp 200 juta) sejak awal memang sudah bertekad
menjadikan pesta itu "dari rakyat untuk rakyat."
Tapi Slamet Rahardjo, sutradara dan bintang film, merasa kikuk
juga dengan sambutan meriah itu. "Apakah sudah pantas film kita
dielu-elukan seperti demikian?" ujarnya. "Mudah-mudahan sambutan
meriah itu jadi cermin masyarakat film, agar kelak (dalam meng
hasilkan film) mereka tidak mengecewakan."
Adakah kemajuan dalam festival kali ini? "Jelas ada," sahut
Ismail Soebardjo, sutradara yang dapat Citra. Ia menyebut bahwa
masuknya empat film dalam nominasi film cerita terbaik merupakan
salah satu tanda kemajuan. Soemardjono, bekas Sekjen Majelis
Musyawarah Perfilman Indonesia juga mengeluarkan pendapat
serupa. Munculnya sejumlah sutradara muda, katanya, merupakan
kemajuan. "Yang masih perlu ditekankan adalah usaha menciptakan
film dengan ciri Indonesia."
Suatu kemajuan lagi, tentu saja, ialah film terbaik tahun ini
-- Perempuan Dalam Pasungan -- hanya dibuat dengan biaya Rp 97
juta. Ini termasuk hemat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini