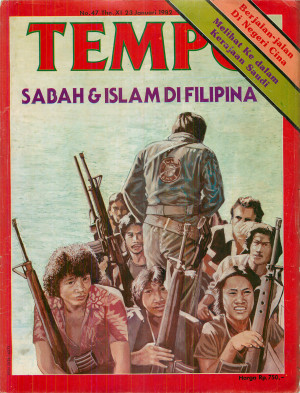INDONESIAN WORKERS AND THEIR RIGHT TO ORGANISE
INDOC Indonesian Documentation & Information Centrel, 148 hlm.
Leiden, 1981.
KEADAAN perburuhan sering memberikan warna yang penting dalam
situasi ekonomi dan politik sebuah negara. Trade Unionism di
Inggris jelas menunjukkan itu. Solidaritas di Polandia apalagi.
Di Indonesia kita memiliki HPP (Hubungan Perburuhan Pancasila)
-- yang antara lain menggariskan bahwa buruh bukan hanya
komponen, melainkan "partner" pemerintah dalam usaha
pembangunan. Secara obyektif, perburuhan di Indonesia cukup
sulit dengan adanya buruh tani dalam jumlah yang besar-di
samping buruh industri yang semakin membanyak. Terutama setelah
Kenop, keresahan buruh terasa menjadi-jadi.
Sebuah buku, yang mungkin lebih tepat disebut dokumen, yang
muncul dari Negeri Belanda, menyoroti masalah ini. Penulisan
Indonesian Workers ini dilakukan oleh sejumlah orang -- di
antaranya juga orang-orang Indonesia--yang tergabung dalam
INDOC, sebuah organisasi bebas yang melakukan dokumenusi tentang
Indonesia. Karena itu tak mengherankan bila pembaca terus dibawa
pa.la reportase kasus-kasus perburuhan yang sebelumnya telah
dilaporkan di berbagai penerbitan nasional pada tahun-tahun
1979-80. Beberapa sumber yang mereka pakai antara lain Angkatan
Bersenjata, Berita Buana, Kompas, Merdeka, Pelita, Sinar
Harapan, Suara Karya serta mingguan TEMPO, Topik dan beberapa
publikasi luar negeri.
Membaca kasus-kasus ini kita langsung saja mengenali: kasus PT
Fairchild Semiconducter (hlm. 38): kasus pilot-pilot Garuda
(hlm. 35) kasus pemogokan dan pengaduan ke DPR dari buruh-buruh
Hotel Horison (hlm. 60) pemeriksaan keperawanan di PT Southern
Cross Textile Industry (hlm. 43)- kasus pemogokan di Hotel Bali
Hyatt (hlm. 59) penguncian 34 buruh dalam kamar selama sehari
penuh karena meminta status pekerja tetap (hlm. 59) kasus PT
Textra (hlm. 1), serta puluhan kasus lain.
Secara umum kasus-kasus ini menggambarkan perlakuan tak wajar
pada kaum buruh upah yang tak masuk akal, jam kerja yang,
melampaui batas, kondisi kerja yang buruk, tidak adanya jaminan
kerja, status kerja yang tak jelas. Dari semua keluhan yang
timbul, yang terdengar paling nyaring adalah keluhan
kesewenang-wenangan majikan. Bisa jadi karena terlalu minimnya
kontrol dari pihak luar, misalnya pemerintah.
Itulah yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan yang
berlebih-lebihan. Sedang buku Indoc ini menganggap sikap
pemerintah Orde Baru cukup membingungkan karena mengandung
ambivalensi dan kontradiksi. Satu-satunya organisasi yang
dipercaya pemerintah mewakili kaum buruh adalah FBSI --yang oleh
ketuanya sendiri, Agus Sudono, disebut sebagai organisasi "tak
bergigi", yang memiliki pejabat-pejabat yang "brengsek" dengan
kecenderungan korupsi dan mudah dimanipulasi oleh pengusaha
(hlm. 67). Sampai-sampai timbul julukan "anggota Serikat Kerja
Amplop" (envelope unonists, hlm. 89).
HPP, yang sebenarnya belum pernah diundangkan, hanya menjadi
"sepoton nasihat untuk para pengusaha . . . (dan) . . .
propaganda buat buruh" (hlm. 66). Dalam catatan kaki sebuah bab
yang berjudul Government, Employers and Workers: Partners or
Protagonists?, ada sebuah kutipan dari Permadi, ketua Lembaga
Konsumen Indonesia "Saya khawatir HPP hanyalah untuk melindungi
yang kuat dan mengorbankan yang lemah . . . HPP tak bisa
meninabobokan segala-galanya. Kaum buruh tah boleh dibebani
kewajiban-kewajiban, sementara hak-hak mereka diambil . . . tak
ada iklim demokrasi dalam dunia perburuhan. Semua pekerja
terpojok karena mereka hanya dapat memilih FBSI (hlm. 74),
karena saluran-saluran resmi lainnya sangat terbatas.
Kutipan ini menarik bila dikaitkan dengan bab mengenai asal usul
dan FBSI sekarang. Secara historis, SB di Indonesia muncul tahun
50-an sebagai alat partai-partai politik yang sedang
mempersiapkan pemilu. Tetapi sejak 1957, dengan diumumkannya SOB
(keadaan perang darurat), militer ditempatkan menjadi penengah
dalam seluruh sistem kenegaraan. Dengan demikian partai-partai
politik mengalami penjinakan--dan akibatnya juga serikat-serikat
buruh.
Salah satu konsekuensi HPP adalah implikasinya bahwa hak mogok,
yang merupakan salah satu hak dasar buruh, dan yang juga diakui
UU, praktis berlaku di kertas saja. Berbagai tokoh berkata
dengan adanya HPP sebenarnya pemogokan tak diperlukan--bahkan
bertentangan dengan HPP. Memang ada kecenderungan pihak penguasa
untuk melihat semua tindakan pemogokan sebagai "subversi",
"tindakan kriminal" (hlm. 70), atau melawan investasi asing
(hlm. 104). Dan bahwa pengorganisasian buruh adalah bagian dari
gerakan komunis yang terlarang.
Intimidasi politik dilihat sebagai satu cara untuk mengontrol
buruh secara aman oleh pihak penguasa, tanpa kekhawatiran akan
reperkusi. Bila ada intervensi, itu biasanya dari pihak tentara
atau polisi yang sering hanya menguntungkan kaum pengusaha. Pada
akhirnya misi FBSI pun, yang juga dibentuk di bawah supervisi
militer dan aparatus negara, dilihat oleh para penulis Indoc ini
sebagai "menjual tenaga kerja Indonesia kepada calon-calon
penanam modal asing . . . dan untuk memberi jaminan bahwa tenaga
kerja ini akan sederhana dalam tuntutannya, patuh, dan sangat
murah" (hlm. 78).
"Kaum buruh adalah partner pengusaha dan pemerintah"--spanduk
yang sering kita lihat di jalanan. Ini dikomentari demikian:
"Bila Karl Marx kebetulan lewat, ia pasti akan terbahak-bahak
dan hampir terjatuh untuk membaca spanduk itu. Dia tak pernah
membayangkan, bahwa pada suatu zaman, pada suatu negara, akan
terdapat sekelompok buruh yang begitu sopan dan menerima nasib
bahwa mereka akan menerima gaji mereAka, apakah memadai atau
tidak, tanpa sedikit pun keluhan. Saya pikir, sesampainya di
rumah, dengan kehabisan napas, ia akan mengambil bukunya
'Capital' dan melemparkannya ke dalam kali Cikapundung. Untuk
apa semuanya itu, menulis buku bertahun-tahun lamanya untuk
membela kelas buruh, bila sekarang semuanya berpelukan seperti
paman dan keponakan?" (hlm. 99, Mahbub Junaedi dalam Pelita
2.4.80).
Hal ini memang mungkin, karena komposisi tenaga kerja industri
Indonesia sekarang ini merupakan suatu massa yang sangat muda
dalam usia maupun pembentukannya, sering berpendidikan rendah,
wanita-wanita muda, bahkan buruh anak-anak pun tak jarang.
Mereka tak punya kepastian kerja, mendapat upah yang sangat
rendah, mudah dikontrol, dan terus-terusan berubah karena
tingkat pengangguran yang tinggi. Pihak pemilik modal tidak
pernah kekurangan orang yang ingin bekerja betapapun buruk
kondisinya.
Buku ini juga menganalisa masalah kebijaksanaan politik, keadaan
lapangan kerja dan kondisi kerja di Indonesia secara cukup
tajam. Tetapi jangan dikira mereka melulu bicara yang
jelek-jelek. Mereka mencatat kunjungan sewaktu-waktu Gubernur
Tjokropranolo ke pabrik-pabrik untuk mengecek standar upah dan
kondisi kerja, yang dianggap sebagai intervensi positif yang
pertama atas nama buruh. Mereka juga melihat hukum di Indonesia
bisa dikatakan progresif dari segi pemberian cuti hamil,
menyusui dan cuti haid, walaupun dalam prakteknya tidak selalu
sesempurna di kertas.
Dari segi sistematika dan isi, buku ini menarik dan ditulis
secara persuasif. Cukup pandai pula mereka menghindari
kemungkinan dikritik sebagai "orang-orang Barat" yang tak
betul-betul tahu keadaan Indonesia--dengan menggunakan semua
bahan mereka dari sumber-sumber dalam negeri. Bahkan kritik dan
analisa yang mereka lancarkan kadang diambil juga dari
kutipan-kutipan penerbitan nasional tadi.
Analisa mereka sebenarnya tak terlalu berbeda dengan hal-hal
yang ditulis di dalam negeri. Misalnya seperti yang dapat dibaca
dalam berbagai artikel mengenai perburuhan di majalah Prisma,
Langit Makin Mendung-nya LBH ataupun kafa pengantar buku Tanya
Jawab Hukum Perburuhan, juga dari LBH. Tetapi, kebiasaan di
Indonesia tampaknya justru lebih memperhatikan yang datang dari
luar--baik positif ataupun negatif. Tak ada salahnya bila buku
ini pun diperhatikan, bila kita benar-benar ingin melaksanakan
hubungan perburuhan yang berdasarkan Pancasila.
Julia I. Suryakusuma
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini