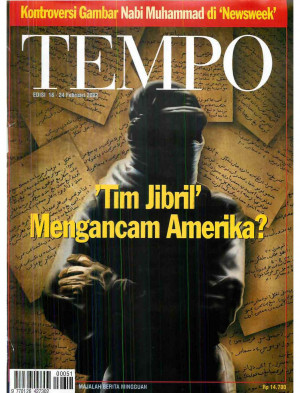Di Bawah Langit Tak Berbintang
Penulis : Utuy Tatang Sontani
Penerbit : PT Dunia Pustaka Jaya
Syahdan, pada 1957, Utuy Tatang Sontani terbang ke Tashken, Uni Soviet. Teman-teman dekat Utuy mulai mengendus sikap mesra Utuy dengan "hantu" komunis saat dia menghadiri pembentukan Persatuan Pengarang Asia-Afrika itu, satu organisasi yang diyakini sementara orang sebagai mantel gerakan komunis internasional.
Ini menjadi penting bukan hanya karena Utuy adalah sastrawan Angkatan 45, tetapi terutama karena dia pembaru penulisan naskah drama pada zamannya. Dia memperkenalkan bentuk penulisan naskah lakon yang baru, yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan seting panggung, sehingga membaca naskahnya seperti membaca cerita. Sementara Pramoedya Ananta Toer melimpahkan peng-alaman dan pandangan pribadinya dengan menulis novel dan cerita-cerita pendek, Utuy menumpahkan bakatnya dalam penulisan lakon. Sastrawan satu angkatan ini dua-duanya sama-sama produktif. Dan dua-duanya menemukan "nasib" sial karena sama-sama bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), gerakan kebudayaan yang dominasinya terhenti setelah meletusnya Gerakan 30 September 1965.
Utuy berangkat ke Beijing pada 1965 bukan sebagai pengarang, tetapi sebagai penderita penyakit liver yang ingin mendapat perawatan di sana. Pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok mengundang ratusan pemuka Indonesia untuk menghadiri ulang tahun berdirinya negara itu, 1 Oktober 1965. Utuy, Agam Wispi, dan Sobron Aidit terjebak di sana. Mau pulang, ngeri mendengar ganasnya perlakuan terhadap kaum kerabatnya di Tanah Air.
Tertahan di RRC yang berhaluan komunis, keadaan mereka jauh dari berbinar-binar. Mereka diperlakukan sebagai anasir asing yang memiliki hubungan buruk dengan negara asal mereka. Apalagi kelak di kemudian hari, demi kepentingan pasar, RRC menginginkan pulihnya hubungan dengan Indonesia, setelah hubungan diplomatik terputus menyusul G30S. Utuy dan kawan-kawan disingkirkan dari Beijing dan disekap dalam penampungan khusus yang dijaga ketat.
Dia menulis perjalanannya menuju pembuangan: "…Di situ hanya ada tempat tidur lengkap dengan kasur dan bantalnya, sebuah meja dengan kursinya, sebuah baskom dengan termosnya, dan sebuah lemari tempat menaruh koper dan pakaian. Setelah aku dibiarkan mengaso sebentar, orang yang membawa aku ke gedung itu pun kembali muncul dengan membawa pakaian tentara untukku, lengkap mulai dari handuk sampai peci. Dan bersamaan dengan itu dia pun menyerahkan beberapa jilid buku Mao Cetung."
Ketika Revolusi Kebudayaan berkobar di RRC pada 1966, kitab kecil bewarna merah yang diceritakan Utuy itu dicetak melebihi jumlah kitab suci yang mana pun di seluruh dunia. Buku itu diperlakukan sebagai penunjuk jalan yang tiada taranya dalam melawan revisionisme modern terhadap Marxisme yang dipelopori Uni Soviet serta pembersihan terhadap najis borjuis. Politik telah membuat buku kecil itu menjadi semacam mukjizat. Orang bisu, katanya, bisa berbicara begitu kutipan Mao dibacakan.
Para pelarian politik Indonesia memperoleh perlakuan tidak senonoh di negara yang menjadi idola mereka. Mereka dihukum untuk mempelajari kesalahan Partai Komunis Indonesia, antara lain mencari kesalahan partai "mengapa sampai terpukul pada peristiwa 30 September." Utuy menolak terlibat dalam diskusi, dan dengan sinis Utuy menampik, " … saya tahu apa tentang itu semua?"
Dia dimasukkan ke dalam kelompok diskusi untuk melakukan otokritik. Pegangannya adalah buku merah berisi kutipan pikiran Mao. Ketika pemimpin kelompok memintanya belajar dari buku Mao, Utuy menolak dengan mengatakan, "Bagi saya yang namanya belajar itu ialah mempelajari manusia. Mempelajari manusia, termasuk diri saya sendiri, untuk ditulis menjadi buku. Tapi yang dipelajari orang-orang di sini justru sebaliknya. Mereka membaca buku untuk mendapatkan petunjuk tentang apa manusia, tentang apa itu kesahalan Aidit, kesalahan Nyoto, dan sebagainya, yang notabene sekarang sudah pada mati." Aidit dan Nyoto dua tokoh PKI yang jadi sahabat dekatnya.
Utuy tidak hanya menulis kenangannya tentang pertentangan politik di kalangan orang-orang kiri Indonesia yang hidup seperti berada di bawah langit tak berbintang di RRC. Tak ada arah. Tiada harapan. Dia juga sempat mencatat hubungan gila dalam komunitas kecil orang Indonesia di perantauan itu. Seorang pemuda babak-belur dihajar karena tertangkap basah bermain cinta dengan istri orang lain. Amboi jujurnya! Pengarang Awal dan Mira itu juga menceritakan hubungan mesranya dengan Sutinah, istri seorang tokoh PKI yang sudah bertahun-tahun tak pernah bersetubuh dengan suaminya yang sakit, dan berkunjung ke RRC sekalian untuk berobat.
Bertambah lama, sikap pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok terhadap para pelarian politik itu bertambah buruk. Beredar kabar bahwa mereka akan dipindahkan ke desa-desa, untuk menyucikan diri mereka dari sikap hidup borjuis yang katanya menyebabkan hancurnya PKI. Ada yang bependapat, daripada dipindahkan ke desa, yang berarti dimasukkan ke kurungan yang lebih terkutuk, lebih baik meninggalkan Tiongkok, sekalipun dituduh pengkhianat yang memihak revisionis Uni Soviet, musuh nomor satu negara itu.
Utuy tetaplah seorang seniman. Ketika ada orang yang datang mengajaknya melarikan diri keluar dari Tiongkok, jawabannya khas: "Saya ini invalid. Kalau ikut keluar dari Tiongkok, jelas akan menjadi penumpang yang membebani. Padahal, untuk menjadi penumpang saja saya tidak mau. Apalagi kalau yang ditumpangi itu dinamakan partai."
Dia menjadi orang merdeka ketika sampai di Moskow. Dan tak ada orang yang dia kenal di ibu kota Uni Soviet itu. Dia hanya ingat Igor, yang pernah menjadi penerjemahnya ketika menghadiri Konferensi Pengarang Asia-Afrika di Tashken pada 1957. Padahal Moskow memiliki ribuan Igor. Akhirnya, Utuy bertemu dengan seseorang yang kemudian mengajaknya mengajar bahasa Indonesia di Institut Bahasa Timur.
Seniman besar Lekra penulis Tak Pernah Menjadi Tua itu meninggal di Moskow pada 17 September 1979. Kepada seorang penyair Lekra yang mendampinginya saat meng-hadapi maut, Utuy berpesan, jika dia meninggal agar dikuburkan secara Islam. "Biar bagaimana, saya ini orang Islam dan kakek saya haji…," katanya. Kawan yang mendampinginya itu kemudian menemui pejabat yang berhubungn dengan urusan pemakaman di Moskow, dan permintaan itu dikabulkan.
Ajip Rosidi, penjaga gawang yang gigih dari kebudayaan Sunda saat ini, memberikan pengantar yang diliputi perasaan heran bercampur penyesalan, bahwa Utuy Tatang Sontani, yang "karya-karyanya begitu individualistis", bisa aktif dalam Lekra, organisasi mantel PKI di bidang kebudayaan. Agaknya, banyak juga yang tidak paham mengapa Utuy memilih dimakamkan secara Islam. Pembodohan diri dengan menampilkan sikap semacam itu tidaklah mengherankan. Karena penyamarataan sikap politik kiri dengan ateisme itulah juga yang telah dijadikan lawan-lawan kaum komunis sebagai senjata untuk memusnahkan musuh mereka secara fisik, terutama pada tahun 1965-66.
Ajip, yang mengenal dekat penulis drama kelahiran Cianjur 31 Mei 1920 itu, memberikan penilaian yang terkesan merendahkan. Keterlibatan Utuy dalam Lekra, kata Ajip, "hanyalah karena ia tanpa mengerti akan situasinya, terseret oleh hubungan-hubungan pribadi dengan tokoh Lekra yang menjadi sahabatnya, seperti Hendra Gunawan." Bertambah gundah perasaan membaca uraian Ajip, kalau diingat bahwa kemaslahatan yang dibawa global-isasi dan demokratisasi sekarang ini adalah bahwa tak satu pihak pun yang berhak mengklaim memperoleh wewenang dari "atas" untuk menyatakan penyesalan, apalagi menghukum, terhadap seseorang karena keyakinannya pada satu gagasan—kecuali itu fasisme. Pilihannya pada Lekra, atau PKI sekalipun, tidaklah memakzulkan bahwa bagaimanapun Utuy adalah kekayaan budaya Sunda, kekayaan Indonesia.
Tetapi sikap Ajip itu tidak mengurangi penghargaan akan nilai kemanusiaan yang diketengahkannya, terutama ketika dia ber-temu dengan Utuy yang sedang terbaring di satu rumah sakit di Moskow. Dalam peng-antarnya untuk memoar Utuy, Ajip sekaligus menunjukkan betapa rendahnya peradaban Orde Baru yang menolak jenazah pengarang itu untuk dimakamkan di tanah airnya sendiri. Ketika Utuy meninggal di Moskow, keluarganya di Jakarta meminta izin pemerintah Republik supaya jenazahnya bisa dibawa pulang. "Pemerintah RI begitu takut kepada bahaya laten komunisme, sehingga orang yang sudah menjadi layon pun dianggap berbahaya untuk dikuburkan di tanah tempat darahnya tertumpah pertama kali—ketika komunisme di seluruh dunia sudah gugur berontokan," demikian tulis Ajip Rosidi.
Martin Aleida
Penulis, pemerhati masalah politik dan kebudayaan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini