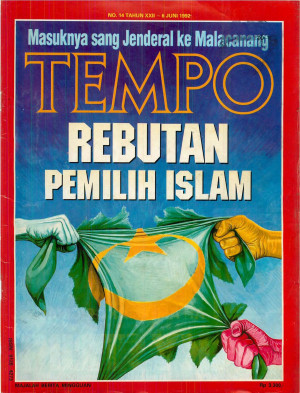"MEMILIH atau tidak memilih?" ujar Hamlet. Disadari atau tidak, saat ini bangsa Indonesia menghadapi dilema yang sama dengan pangeran dalam lakon Shakespeare tersebut. Bedanya, Hamlet cuma punya satu pilihan. Kita lebih rumit: kalau memilih, siapa yang dipilih? Menyamakan mimbar politik dengan panggung tonil sudah klise, memang. Namun, kampanye Pemilu 1992, yang berakhir pekan ini, memang klise. Dari lima tahun ke lima tahun, skenario yang dimainkan ituitu juga. "Jagoannya" tetap sama, cuma tambah gemuk karena makmur. "Lawannya" juga sama dan tetap kerempeng. Tetap mampus, seperti Hamlet, pada akhir cerita. Kalau dalam putaran kali ini ia sedikit lebih "ganteng dan rapi", harap maklum, topeng termasuk ekspor nonmigas Indonesia yang paling besar setelah jam karet. Maka, membandingkan kampanye 1992 dengan teater Shakespeare mungkin terlalu tinggi. Ia lebih pas disebut lenong: ada jawaranya, ada artisnya, dan ada badutbadut yang suaranya keras. Yang terakhir ini kunci bagi suksesnya sebuah kampanye. "Demokrasi!" katanya, dan ha, ha, ha, kita tertawa senang. Senang bahwa demokrasi kita lain dengan demokrasi macam Filipina atau Amerika yang amburadul. Senang karena dapat kaos gratis dan bisa melanggar lampu merah. Senang karena perut yang kosong untuk sementara waktu tak lagi terasa. Melupakan masalah. Itulah hakikat hiburan demokrasi atau bukan demokrasi. Esai Foto: Donny Metri, R. Fadjri, Robin Ong, dan Rully Kesuma Teks: Yudhi Soerjoatmodjo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini