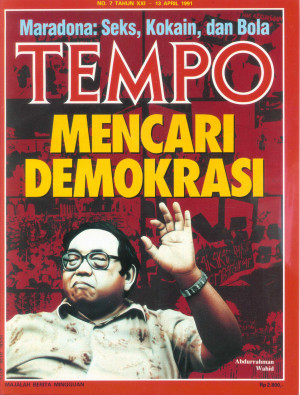PARA ahli sastra Indonesia umumnya sependapat bahwa sejarah kesusastraan Indonesia bertolak dari 1920-an. Ini ditandai dengan berdirinya penerbit Balai Pustaka (BP) pada 1917, yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan politik etis Belanda bagi kaum pribumi. Namun, pengertian yang sudah melekat itu kini dicoba. Di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, awal Maret lalu, Prof. Willen Vladimir Sikorsky, ahli sastra Indonesia dari Uni Soviet, membuka mata kita. "Ini kesalahan yang sungguh mendasar," kata Kepala Jurusan Timur dan Afrika Kursus Tertinggi Bahasa-Bahasa Asing Kementerian Luar Negeri Uni Soviet. Tampaknya, dia memang serius. "Badan penerbit tak bisa dijadikan patokan lahirnya sebuah tradisi sastra," kata pakar sastra Indonesia dengan disertasinya Pembentukan Sastra Modern Indonesia. Ia juga menulis beberapa buku mengenai satra Indonesia dan salah satunya, Kesusasteraan Indonesia di Moskow. Sastra Indonesia katanya, lahir dari suatu proses panjang. Sebelum era Balai Pustaka, di Indonesia, sudah muncul karya-karya sastra yang lebih bersemangat Indonesia ketimbang Sitti Nurbaya atau Salah Asuhan. Sikorsky menunjuk beberapa tulisan Semaun dan Mas Marco Kartodikromo, yang sudah menjadi bacaan masa itu. "Sayang, buku-buku itu tak dikategorikan ke dalam khazanah sastra Indonesia hanya karena ditulis dalam bahasa Melayu rendah," katanya. Memang, dalam pengertian "konvensional", sastra Indonesia dipatok sejak BP. Bahkan BP sendiri sebenarnya punya tugas menyiapkan buku-buku bacaan -- sastra umum -- yang bersifat mendidik masyarakat pribumi. Belanda sengaja memasang jaring sensor untuk tak meloloskan buku-buku yang "meracuni" masyarakat, dengan tulisan berbau komunisme dan pornografis. Dalam hal bahasa, Belanda pun punya kriteria. Buku BP harus memakai bahasa Melayu tinggi. Bukan Melayu rendah atau pasar. Ini tentu saja menguntungkan para sastrawan asal Minangkabau, Sumatera Barat, yang sudah menguasai Melayu tinggi. Apalagi setelah Sumpah Pemuda 1928, yang menetapkan bahasa itu menjadi bahasa Indonesia. Karya-karya mereka otomatis menjadi model sastra yang dianggap layak mendapat stempel Indonesia. Misalnya, roman Marah Rusli Sitti Nurbaya (1922), Salah Asuhan (1928) oleh Abdul Muis, dan beberapa karya Nur Sutan Iskandar yang terbit pada 1920-an. Selama ini, di mata para ahli sastra Indonesia, seperti H.B. Jassin dan A. Teeuw, bahasa memang menjadi faktor penentu dalam menggolongkan sejarah karya sastra. Sampai-sampai para sastrawannya pun dijuluki Angkatan Balai Pustaka. Dan di situlah duduk perkaranya. Penabalan bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa Indonesia dengan serta-merta menafikan karya sastra yang sudah berkembang --dalam bahasa daerah atau Melayu rendah. Ada beberapa sastrawan dan pakar yang punya pikiran sejalan dengan Sikorsky. Misalnya saja Yakob Sumardjo, ahli sastra Indonesia dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Bahkan, dia yakin bahwa proses itu telah dimulai jauh sebelum 1900. Yakob menunjuk cerita-cerita rekaan berbahasa Melayu rendah, yang dimuat dalam surat kabar terbitan 1860, setengah abad sebelum BP lahir. Sampai dengan awal 1900, karya sastra berbahasa Melayu rendah berkisar antara 800 dan 900 judul. Sementara itu, BP hanya punya 400-500 karya. Sikorsky memang punya resep baru untuk menetapkan penggolongan sastra. Ukuran utama, katanya, adalah adanya " pencerahan". "Yakni, pemikiran-pemikiran baru yang keluar dari batas-batas konvensi," kata Sikorsky. Untuk menggolongkan sebuah karya sastra ke dalam sastra Indonesia atau sastra daerah, kriterianya adalah isi atau semangat yang terkandung di dalamnya. Dengan konsep itu, Sikorsky menunjuk karya-karya Ronggowarsito pada tahun 1880-an. Menurut dia, karya-karya itu merupakan bagian dari proses panjang terbentuknya sastra Indonesia. Ronggowarsito memperlihatkan terobosan baik di bidang pemikiran maupun bentuk kesusastraan. Dia sudah mengenal prosa -- bentuk yang sebelumnya dikenal dalam sastra Jawa. Dia telah mengupas masalah universal manusia Indonesia, seperti kemiskinan, kemanusiaan, kondisi sosial, dan mengkritik pangreh praja, walau temanya cuma penentangan nilai-nilai tradisional Jawa ketika itu. "Ini merupakan pencerahan terhadap masyarakat Indonesia," kata Sikorsky. Sebaliknya, Sitti Nurbaya, menurut Sikorsky, tak layak digolongkan ke dalam khazanah sastra Indonesia. Di situ, tak ada "pencerahan". Sitti Nurbaya adalah persoalan adat, bukan persoalan manusia universal Indonesia. Bila kriterianya harus menampilkan masalah yang benar-benar problem manusia Indonesia, Karkono Kamajaya, Ketua Yayasan Javanologi Panunggalan Yogyakarta, pun ikut mendukungnya. "Banyak sastra Jawa yang berisi kehidupan masyarakat dan tak berbau istana sentris," katanya. Artinya, "tak ada alasan kuat untuk menolak sastra Jawa masuk ke dalam jajaran sastra Indonesia," ia menambahkan. Ia pun membuka contoh Serat Kalatida karya Ronggowarsito. Serat itu merupakan ungkapan protes penulisnya atas perilaku raja, yang hanya memikirkan kepentingan sendiri dan mengabaikan rakyat. Ia mengecam gaya foya-foya para abdi di sekitar istana, "amenangi jaman edan, yen ora melu edan ora bakal keduman (mengalami zaman edan, kalau tak ikut main gila tak bakal kebagian)". Ini memang masalah universal. Bukan hanya untuk orang Jawa dan Keraton Surakarta, melainkan juga berlaku bagi semua orang Indonesia. Bahkan sampai sekarang. Priyono B. Sumbogo, Ida Farida
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini