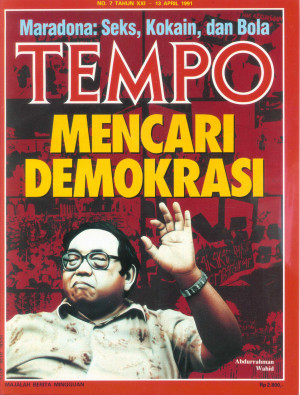SALAH satu budaya Jepang yang diwariskan dari masa pendudukan 1942-1945 adalah upacara bendera. Upacara itu, sampai kini, telah menjadi tradisi yang kita lakukan dengan setia, paling tidak, pada setiap tanggal 17. Di zaman Jepang, upacara bendera tak hanya dilakukan setiap bulan, melainkan saban hari kerja. Dilakukan di sekolah-sekolah dan kantor-kantor dengan penghormatannya kepada Tenno Heika. Seperti kebiasaan kita sekarang, upacara yang diisi dengan ikrar kesetiaan kepada negara Dai Nippon itu ditutup dalam suasana spiritual dengan mengheningkan cipta, yang disebut dulu mokto dalam bahasa Jepangnya. Bahwa upacara bendera itu masih kita pertahankan sebenarnya merupakan hal yang unik. Bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara yang pernah dijajah Jepang sudah meninggalkannya dan tak menjadikannya sebagai adat tata cara resmi nasional. Mengapa? Alasan pertama, upacara bendera di negeri kita dilembagakan barangkali harus dicari pada kebiasaan di dalam masyarakat tradisional. Mereka punya kebiasaan menghadap pihak penguasa yang memerintah. Para punggawa menghadap bupati atau lurah setiap hari sebelum tugas pemerintahan dimulai. Kebiasaan menghadap atasan itu kita lihat juga dalam wayang. Pada adegan awal yang disebut jejeran, para pangeran sowan menghadap raja. Upacara itu tak hanya bertujuan memberikan laporan dan menerima pengarahan, tetapi juga untuk menunjukkan kesetiaan kepada orang yang mewakili pimpinan negaranya. Alasan kedua, mungkin juga bisa ditemukan adanya kecenderungan dan kesukaan kita mengadakan upacara. Rupanya, belumlah menjadi perbuatan yang sesungguhnya sebelum diresmikan lewat upacara. Dengan upacaralah kita meninggalkan alam permainan dan memasuki suasana kesungguhan. Di sinilah disiplin diri dan aturan yang dianut bukan suatu hal yang boleh ditertawakan. Kepatuhan dan ketekunan adalah barang-barang langka di tengah pergaulan kita, yang biasanya santai dan masa bodoh. Abdi keraton yang membersihkan kereta raja harus menyediakan sesajian bunga dan menyan supaya kesungguhan tugas membersihkan kendaraan yang dianggap keramat itu menjadi halal dan sah. Pada saat mengikuti upacara bendera pun, orang berlaku dan bertutur sungguh-sungguh. Selama upacara, mereka tak boleh lagi main-main. Alasan ketiga rupanya lebih sesuai dengan tujuan resmi upacara bendera. Di tengah masyarakat Indonesia yang terdiri dari berpuluh-puluh kelompok bahasa, suku bangsa, kebudayaan, kepercayaan, adat kebiasaan, tanggapan hidup, norma-norma susila, yang terpisah pula hidupnya di atas beribu-ribu pulau besar dan kecil, upacara bendera itu bertugas sebagai alat pemersatu. Situasi Indonesia dengan negara bekas jajahan Jepang lainnya di Asia Tenggara memang berbeda. Indonesia punya ciri kebinekaan. Di dalam upacara itu, diulang-ulang kesetiaan kepada asas dan cita-cita nasional, yakni kesatuan dan persatuan bangsa di tengah-tengah perbedaan yang ada. Sementara itu, masalah kesatuan dan persatuan tampaknya tak terlalu masalah di negara bekas jajahan Jepang lainnya. Di Jepang sendiri, upacara bendera menjadi sumber ilham bagi pelembagaan budaya, yakni mengucapkan ikrar atau sumpah. Misal- nya saja, yang dilakukan perusahaan besar Matsushita. Seperti yang diuraikan R.T. Pascale dan A.G. Athos di dalam buku The Art of Japanese Management, perusahaan yang memproduksi alat-alat listrik dan barang-barang elektronik dengan merek dagang National, Panasonic, Quasar, dan Technics itu termasuk satu dari lima puluh korporasi terbesar di seluruh dunia. Suksesnya diraih dengan cara mengimbangi latihan keterampilan pekerjanya dengan latihan meresapkan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Matsushita. Bagi Matsushita, nilai-nilai spiritual sama pentingnya dengan mutu produksi dan keuntungan materi. Watak dan moral pekerja perlu dipelihara. Untuk tujuan itu, setiap pukul 8 pagi, di kantor Matsushita dan berbagai cabangnya yang terdiri dari sekitar 87.000 tenaga buruh di Jepang dibacakan ayat-ayat falsafah perusahaan serta bernyanyi bersama-sama. Asas-asas pokok, kepercayaan, dan nilai-nilai perusahaan itu di antaranya berbunyi tenaga-tenaga industri bertanggung jawab atas mengusahakan kemajuan, mengembangkan kemakmuran masyarakat, dan mengabdikan diri kepada pertumbuhan kebudayaan dunia. Semua itu harus dicapai melalui nilai-nilai spiritual, yakni kebaktian nasional lewat industri, keadilan, harmoni dan kooperasi, perjuangan ke arah perbaikan, hormat dan rendah hati, penyesuaian dan peleburan, dan akhirnya rasa terima kasih. Ikrar bersama dan serempak di seluruh negeri Jepang didukung dan mendukung pengelolaan perusahaan yang rasional dan efisien. Pekerja ditempatkan sesuai dengan bakat dan perhatiannya. Gagasan-gagasan baru dari bawahan didengar, bahkan dianjurkan. Kecakapan lebih diutamakan daripada senioritas. Diskusi-diskusi diadakan untuk menyelesaikan pertentangan pendirian. Hubungan dengan majikan jarang bersifat resmi. Gaya kerja adalah langsung menuju masalah dan memecahkannya. Tenaga atasan tak jarang berhubungan dengan bawahan yang jauh lebih rendah. Upacara bendera kita pun seharusnya mewariskan pula nilai dari Jepang itu di dalam praktek hidup sehari-hari. Kesetiaan yang kita ikrarkan di dalam upacara itu kepada filsafat bangsa, Pancasila, UUD 1945, dan Sapta Prasetya (bagi Korpri), harus bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Misalnya penerapan kemanusiaan dan keadilan yang merata. Jaminan kehidupan tak hanya untuk mereka yang mampu. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa pandang bulu dan kedudukan. Kepentingan masyarakat dan negara diutamakan mendahului kepentingan pribadi dan golongan. Tanpa pengelolaan masyarakat secara obyektif, adil, dan rasional, upacara bendera yang kita lakukan setiap bulan hanya tinggal rutin, kosong, tak bermakna, dan menjadi tindakan basa-basi. Bahkan munafik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini