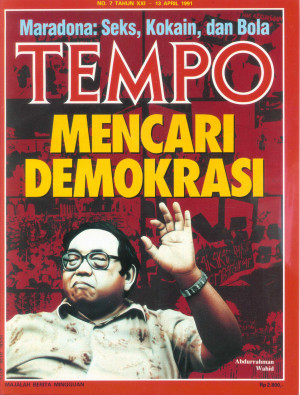ZAKAT adalah rukun Islam yang keempat sesudah puasa. Tidak kebetulan jika kewajiban zakat, terutama fitrah, ditunaikan sesudah orang menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Di sini, zakat berkedudukan sebagai voluntary law. Pelaksanaannya tergantung iman, kesadaran dan tanggung jawab sosial, apabila orang tidak mau disebut "mendustakan agama", seperti dikatakan dalam surat al Ma'un. Puasa, dengan merasakan langsung tidak makan dan minum di siang hari selama sebulan, secara kolektif, dimaksudkan dan diharapkan bisa menumbuhkan solidaritas, dan akhirnya tanggung jawab sosial. Sebagai konsep, zakat mengandung makna serba ganda. Zakat adalah ibadah yang mengandung makna hubungan dengan Allah, baik secara pribadi maupun sesama manusia. Secara harfiah, zakat bisa berarti "membersihkan" atau "memutihkan" kekayaan dan penghasilan. Juga berarti "menumbuhkan" rohani seseorang. Seseorang yang membayar zakat mengharapkan keridhaan Allah dan dampaknya bersifat sosial. Dulu, ketika zakat lebih banyak diberikan seseorang secara langsung, sebagai ibadah, demi menunaikan rukun Islam masyarakat memang kurang menyadari implikasi sosial zakat. Adalah K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah tahun 1912, yang memelopori pembentukan panitia pengumpulan dan pendistribusian zakat, karena rasa tanggung jawab sosial yang ditimbulkan oleh surat al-Ma'un, sehingga kini kita mengenal lembaga Amilin. Sejak itu, zakat, di tengah-tengah suasana Pergerakan Nasional, berkembang menjadi konsep sosial. Kini konsep zakat menjadi lebih hidup sebagai salah satu instrumen pemerataan sosial-ekonomi, dalam pemikiran pembangunan. Sebetulnya, orang jangan lupa bahwa zakat, bersama-sama dengan infak, sedekah, dan wakaf, telah berjasa besar dalam perkembangan Islam. Monumennya adalah masjid, sekolah pondok pesantren, panti asuhan, dan berlangsungnya berbagai kegiatan dakwah dan penyantunan sosial. Kini pandangan masyarakat bergeser ke hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Ini logis, karena 4 di antara 8 asnaf (yang berhak atas pemanfaatan zakat), yaitu fakir, miskin, gharimin (yang berutang), dan riqab (hamba sahaya), berkaitan dengan soal kemiskinan. Dengan berkembangnya konsep muzakki (wajib zakat), zakat kini sudah menjadi bagian dari corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan). Dalam perkembangan pemikiran sosial-ekonomi, baik yang ditulis oleh para ulama modern seperti Yusuf Qardhawi (baca Fiqh al Zakah, yang sudah diterjemahkan menjadi buku Hukum Zakat, setebal 1.117 hlm.), maupun para sarjana ekonomi lulusan universitas Barat, zakat dijadikan salah satu titik tolak terpenting dalam pembahasan konsep pembangunan terutama dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan kemiskinan. Namun, dari sinilah mulai timbul frustrasi. Melihat kenyataan dewasa ini, zakat belum tampak menimbulkan dampak sosial-ekonomi, paling banter hanya kentara sebagai gejala karitas. Sebagai konsep pembangunan, zakat hanyalah memberi gambaran utopia, seperti pernah dikatakan oleh Gus Dur. Sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial, zakat hanyalah sebuah mitos. Paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan zakat tidak efektif sebagai instrumen kebijaksanaan keadilan sosial. Pertama, potensi zakat belum bisa diaktualkan secara optimal, karena kurangnya kesadaran wajib zakat, kurang jelasnya perhitungan zakat untuk berbagai sektor, menurut konsep modern, dan belum dirasakannya ada kepastian hukum syariat. Kedua, mobilisasi zakat belum efektif, sehingga belum bisa dikumpulkan hasil zakat dalam jumlah besar, karena pembayaran zakat dilakukan secara terpencar-pencar, tidak adanya sentralisasi organisasi Amilin yang berskala nasional atau regional. Dan ketiga, distribusi dan pemanfaatan zakat belum didasarkan pada metode pembangunan. Dalam suatu ceramahnya di LPPI, atas undangan Bank Indonesia, pemrakarsa dan Direktur Grameen Bank, Bangladesh, Dr. Mohammad Yunus, pernah ditanya apakah banknya sudah memanfaatkan dana zakat. Ia menjawab bahwa ia tidak gagal dalam memenuhi kewajiban zakatnya. Tapi orang yang lima tahun yang lalu selalu menerima zakatnya kini tetap miskin. Sedangkan Grameen Bank, yang memberi pinjaman kredit mini (di Indonesia dipraktekkan dalam suatu proyek rintisan oleh LPPI, yang memberi pinjaman maksimum Rp 30.000 dalam tempo 9 bulan), ternyata telah memberi dampak yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan golongan miskin, yang keberhasilannya diakui oleh Bank Dunia. Tapi ia belum menggunakan dana zakat. Hukum fikih di negeri itu belum memungkinkannya. Sampai sekarang, zakat di Indonesia tak lebih hanyalah sebuah gejala karitas. Tapi pemanfaatan kredit, dengan cara seperti dilakukan oleh Grameen Bank atau banyak LSM di Indonesia, masih banyak hambatannya, terutama dari segi hukum fikih konvensional. Demikian pula halnya dengan masalah mobilisasi. Itulah mengapa masyarakat berharap ada tindakan terobosan. Dengan latar belakang itulah didirikan BAZIS, yang sekarang sudah ada di 21 provinsi dan berdasar SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama 19 Maret 1991 itu, BAZIS berstatus LSM. Motifnya bukan Piagam Jakarta (karena umumnya orang sudah tidak ingat), tapi kepedulian sosial pada pihak pemerintah dan tanggung jawab sosial pada masyarakat. Paling tidak, sudah ada dua BAZIS yang berhasil. Pertama BAZIS DKI Jaya, yang telah berhasil menghimpun dana Rp 1,8 milyar tahun 1990, dan BAZ Ja-Bar yang beroleh Rp 8 milyar pada 1988. Yang pertama lebih banyak menghimpun dana infak dan sedekah, sedangkan yang kedua sukses dalam mobilisasi zakat fitrah. Keduanya juga sudah berhasil mengarahkan penggunaannya dalam bentuk pinjaman. Ini suatu kemajuan tersendiri. Amilin di desa Putukrejo, Kediri, Jawa Timur, sudah lebih berhasil menggunakan dananya selama bertahun-tahun untuk pembangunan desa, bekerja sama dengan LKMD, termasuk untuk pembangunan prasarana jalan dan perumahan rakyat. Tapi semuanya itu barulah mampu menimbulkan dampak marginal, dalam skala pembangunan nasional. Dalam tempo dekat, MUI Pusat akan membentuk dua lembaga, Yayasan Dana Da'wah dan Bank Mu'amalat Islam Indonesia. Kedua Lembaga itu juga mempunyai rencana untuk menghimpun dan memanfaatkan potensi ZIS dan wakaf. Lembaga-lembaga di atas mungkin bisa mengubah utopia dan mitos menjadi kenyataan, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tapi mereka harus lebih dahulu mengatasi tiga masalah. Pertama, menembus ketentuan hukum fikih konvensional. Kedua, mengatasi kecurigaan kaum politikus. Dan ketiga, menciptakan manajemen yang efektif dan efisien. Faktor ketiga adalah yang paling mudah dicapai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini