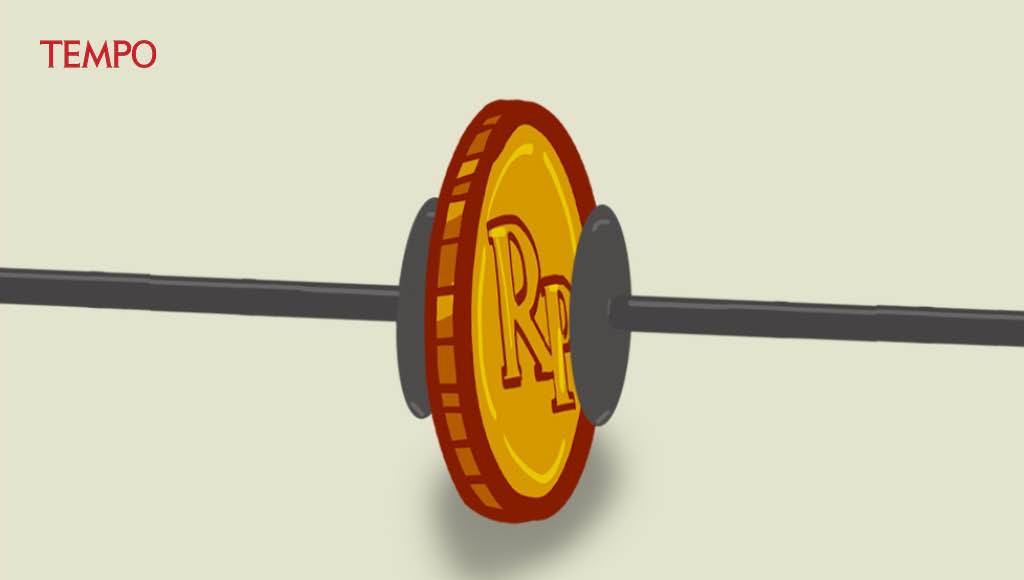Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KESIBUKAN Robi dalam sebulan terakhir semakin bertambah. Di tengah-tengah konsentrasinya menjalankan bisnis, direktur utama perusahaan kelapa sawit ini harus bolak-balik Medan-Jakarta menyelesaikan perkara dengan dua bank asing di Ibu Kota. Perusahaannya yang berbasis di Sumatera Utara itu terancam merugi ratusan miliar rupiah lantaran melakukan transaksi derivatif lewat kedua bank tersebut.
Dua pekan lalu, Robi bersama 10 pengusaha asal Medan ngeluruk ke kantor Indonesia Law Society di gedung Summitmas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Mereka mengadukan nasibnya kepada Hotman Paris Hutapea, Presiden Perkumpulan untuk Penegakan & Pengembangan Hukum Bisnis itu, sekaligus meminta nasihat penyelesaian sengketanya dengan bank yang telah memfasilitasi transaksi derivatif.
Kebetulan pengacara ternama ini sedang mewakili PT Kalbe Farma Tbk. menggugat JP Morgan dalam perkara transaksi derivatif senilai US$ 19,2 juta. ”Bank Indonesia harus melindungi para pengusaha yang menjadi korban transaksi derivatif,” kata Hotman kepada Tempo di Jakarta pekan lalu.
Bukan hanya pengusaha di tanah Batak yang kelimpungan. Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Amirudin Saud, ada 25 pengusaha anggota asosiasinya di berbagai daerah yang juga terancam rugi sekitar US$ 100 juta (kurang-lebih Rp 1 triliun) karena meneken kontrak transaksi derivatif, terutama dengan bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia.
Bank-bank itu meminta para pengusaha membayar tagihannya. Tapi, kata Amirudin, yang juga Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, para pengusaha itu memutuskan untuk mengemplang karena kontrak derivatif yang diteken tak adil.
Kisah itu hanya sekelumit kisruh kontrak transaksi valuta asing perbankan dalam dan luar negeri dengan para pengusaha sejak krisis menghantam dunia pada September 2008. Kontrak valuta asing itu sebenarnya berawal dari keperluan lindung nilai (hedging) untuk meminimalkan risiko gejolak nilai tukar. Belakangan, instrumen lindung nilai ini bermetamorfosis menjadi bentuk-bentuk produk investasi spekulatif alias structured product (lihat ”Lindung Nilai Versus Spekulasi”).
Saat rupiah stabil di bawah 10 ribu per dolar Amerika Serikat, transaksi derivatif itu aman-aman saja. Heboh transaksi ini mulai terjadi ketika nilai tukar rupiah melewati 10 ribu per dolar, bahkan hingga 12 ribu. Jatuhnya harga komoditas dan pasar ekspor akibat resesi global membuat pendapatan perusahaan, eksportir, dan importir anjlok. Buntutnya, mereka tak sanggup lagi memenuhi kontrak transaksi derivatif, yang mengharuskan mereka menyetor dolar dalam jumlah tertentu.
Banyak perusahaan, eksportir, dan importir yang merana gara-gara transaksi derivatif. Tak terkecuali perusahaan negara. PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., PT Elnusa Tbk., dan PT Danareksa Sekuritas tergelincir oleh transaksi valuta asing ini. Bank nasional yang umumnya agen penjual produk asing juga kena getahnya lantaran tagihan derivatif nasabahnya macet.
Inilah yang mendera Bank Danamon dan CIMB Niaga. Kedua bank itu terpaksa mencadangkan kerugian tagihan derivatif masing-masing Rp 660 miliar dan Rp 400 miliar. Kerugian derivatif ini ikut berperan menjungkalkan laba Danamon dari Rp 2,1 triliun pada 2007 menjadi Rp 1,5 triliun pada 2008, dan laba CIMB Niaga (dulu Bank Niaga) menjadi Rp 678 miliar dari Rp 1,5 triliun pada 2007.
Berdasarkan data Bank Indonesia, total transaksi derivatif (lindung nilai murni) mencapai US$ 60-70 miliar, dengan transaksi spekulatif diperkirakan US$ 3,5-3,9 miliar atau sekitar Rp 36-48 triliun. Tapi seorang pemain valuta asing heran melihat nilai transaksi hedging di Indonesia yang bisa mencapai sekitar US$ 65 miliar.
Perusahaan negara dan korporat mana, kata dia, yang jika dikumpulkan transaksi hedging-nya begitu besar, melebihi cadangan devisa nasional yang hanya US$ 50,9 miliar. ”Apanya yang harus dilindungi sehingga nilainya sedemikian besar,” ujarnya kepada Tempo di Jakarta. ”Boleh jadi terbalik, yang spekulatif mencapai US$ 60 miliar.”
Terlepas dari masalah data yang ada, muncul kekhawatiran perusahaan atau bank yang rontok akan bertambah jika kisruh penyelesaian transaksi derivatif ini berkepanjangan. Terlebih lagi, transaksi ini juga telah banyak menjungkalkan perusahaan di berbagai negara.
Tapi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Halim Alamsyah yakin nilai produk spekulatif di Indonesia masih cukup aman. Secara nilai, kata dia, jumlahnya relatif kecil, hanya 6,7 persen dari total transaksi hedging di Indonesia.
Selain itu, sampai Januari lalu, sekitar 40 persen transaksi spekulatif yang bermasalah sudah diselesaikan oleh bank dan nasabahnya, dari kontraknya ditutup (unwound) sampai direstrukturisasi. Sampai akhir Januari 2009, nilainya tinggal sekitar Rp 29 triliun (US$ 3 miliar). Jika ada kerugian pun, kata dia, hanya 10-20 persen atau US$ 30-60 juta. ”Jadi, dari sisi response policy, kami (Bank Indonesia) tak perlu banyak campur tangan,” ujarnya kepada Tempo di Jakarta pekan lalu.
Sisa transaksi spekulatif itu pun, kata Halim, hanya ada sampai pertengahan Juli tahun ini. Setelah masa itu, produk spekulatif tak ada lagi karena bank sentral sudah melarangnya lewat Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 pada Desember lalu.
Wakil Direktur Utama Bank Danamon Jos Luhukay sependapat dengan Halim. ”Nilainya relatif kecil. Yang bermasalah tinggal sedikit karena sudah banyak diselesaikan oleh bank dan nasabahnya,” ujarnya, seraya menambahkan, ”Produk derivatif itu produk legal. Ini untuk memproteksi laiknya asuransi.”
Berbeda dengan keduanya, seorang bankir papan atas justru khawatir terhadap dampak produk itu. Sengketa derivatif, kata dia, telah membuat risiko keuangan di Tanah Air bertambah tinggi. Itu tecermin dari naiknya credit default swap Indonesia sebesar 500-600 basis point, lebih tinggi dibanding Filipina dan Vietnam. ”Kita dianggap lebih berisiko dibanding dua negara itu. Ini tak pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.
Credit default swap merupakan premi asuransi yang dibeli investor surat utang untuk mengamankan risiko gagal bayar atas surat utang yang dibeli. Hal itu kian menyulitkan beberapa bank mencari pendanaan, terutama dari luar negeri. ”Ini juga belum memperhitungkan risiko transaksi derivatif yang mempengaruhi rupiah kita.”
Pemain valuta asing tadi juga mengingatkan, transaksi derivatif bisa berdampak negatif terhadap perbankan nasional. Tergelincir dalam melakukan transaksi spekulatif berpotensi menggerus laba dan ujung-ujungnya akan menekan rasio kecukupan modal (CAR). ”Kalau sudah menyeret perbankan, bisa menjadi bom waktu. Jangan sampai ada Badan Penyehatan Perbankan jilid kedua,” katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dradjad Wibowo, meminta Bank Indonesia tak memandang remeh persoalan ini karena telah mengakibatkan rupiah bergejolak. ”Transaksi ini memicu adanya permintaan dolar yang semu (artifisial),” katanya. Tak mengherankan bila sampai saat ini rupiah masih terus tertekan. Sejak awal Februari hingga akhir pekan lalu, rupiah masih terus melemah di kisaran 11.950-12.100 per dolar.
Potensi gejolak rupiah masih akan terjadi bila penyelesaian sengketa antara bank dan nasabahnya berlarut-larut. Terlebih lagi bila bank tak mau mengalah dan memaksa nasabah tetap membayar penuh kekalahannya dalam transaksi derivatif. ”Ini berarti ada dolar yang harus diserahkan. Jadi ancaman kepada rupiah masih ada,” ujar Dradjad.
Berkaca pada masalah ini, ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebutkan transaksi spekulatif memang harus dibatasi, bahkan dilarang. ”Sama sekali tidak membantu konsumen domestik,” katanya. Terlebih lagi struktur produk derivatif yang ada di Indonesia saat ini ternyata memang cenderung bisa melemahkan rupiah dalam jangka panjang.
Jika transaksinya kecil, memang tidak akan bermasalah. Tapi, kata dia, jika nilai transaksinya besar, akan ada insentif bagi para pemain valas di luar negeri untuk menyudutkan rupiah lewat transaksi non-delivery forward (bermain valuta asing tanpa penyerahan dolar yang riil). Para pemain asing juga bisa menggunakan laporan-laporan riset yang melemahkan rupiah. Ini jelas berbahaya.
Padjar Iswara, Yandhrie Arvian
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo