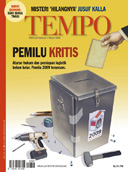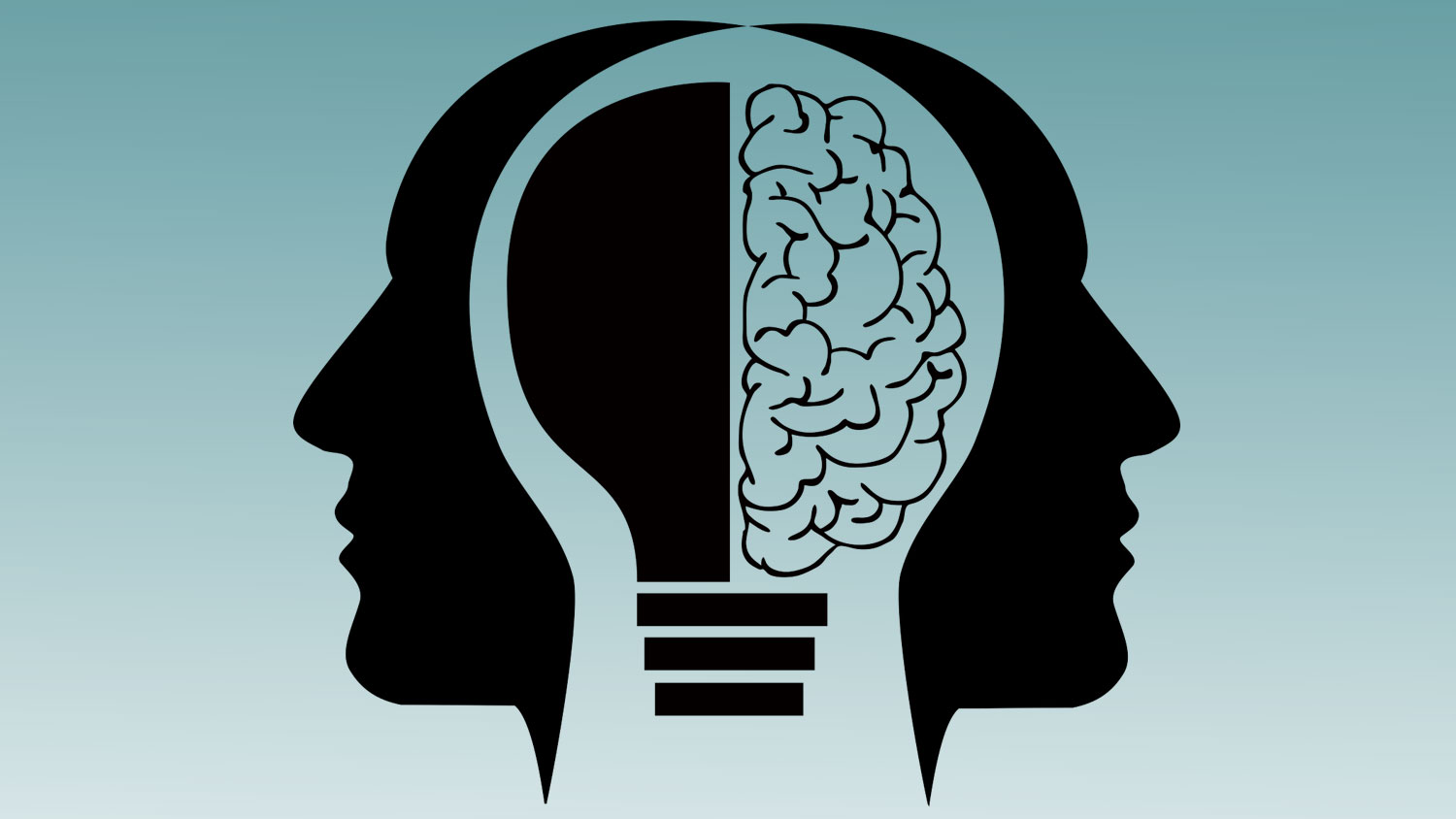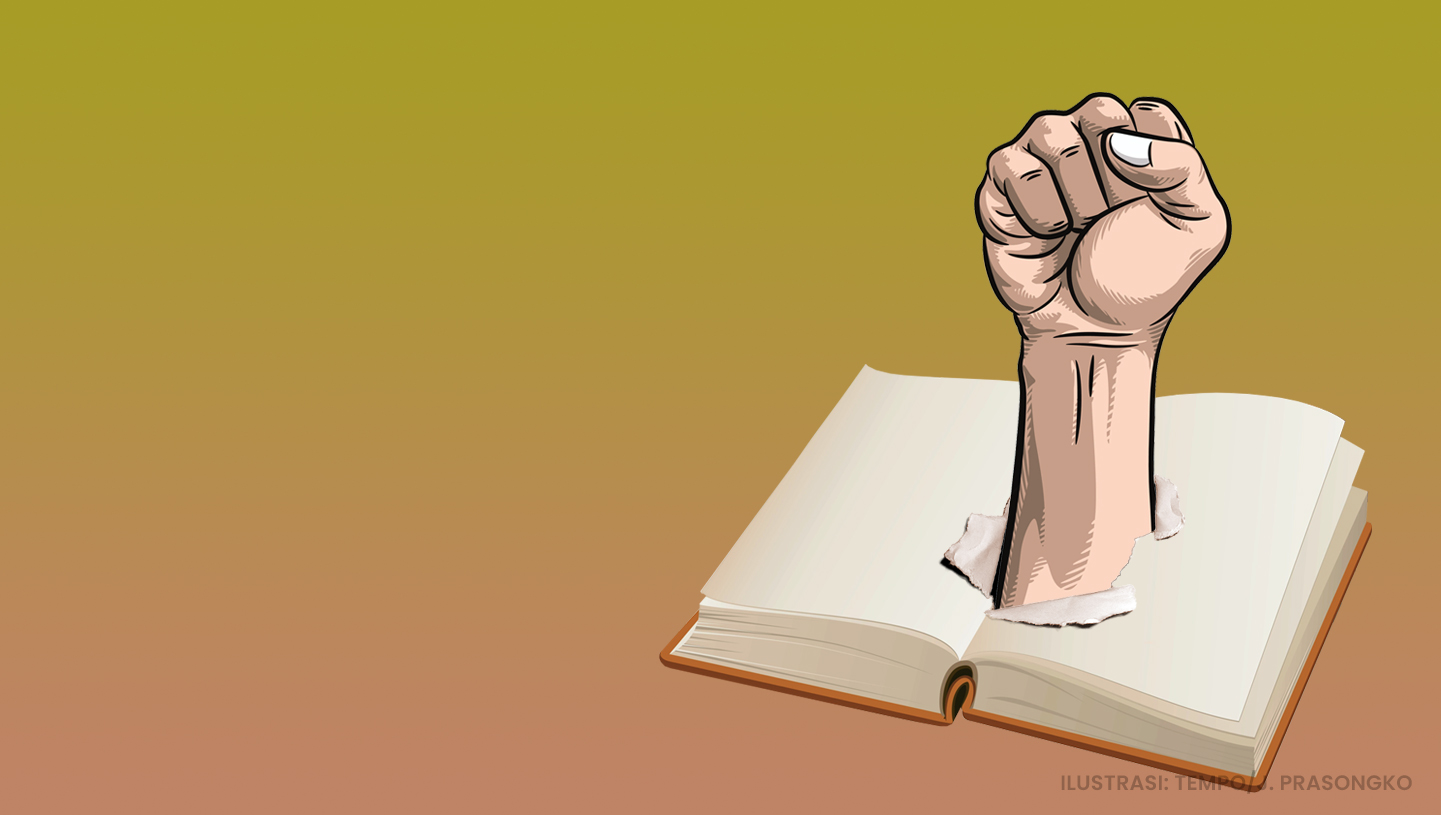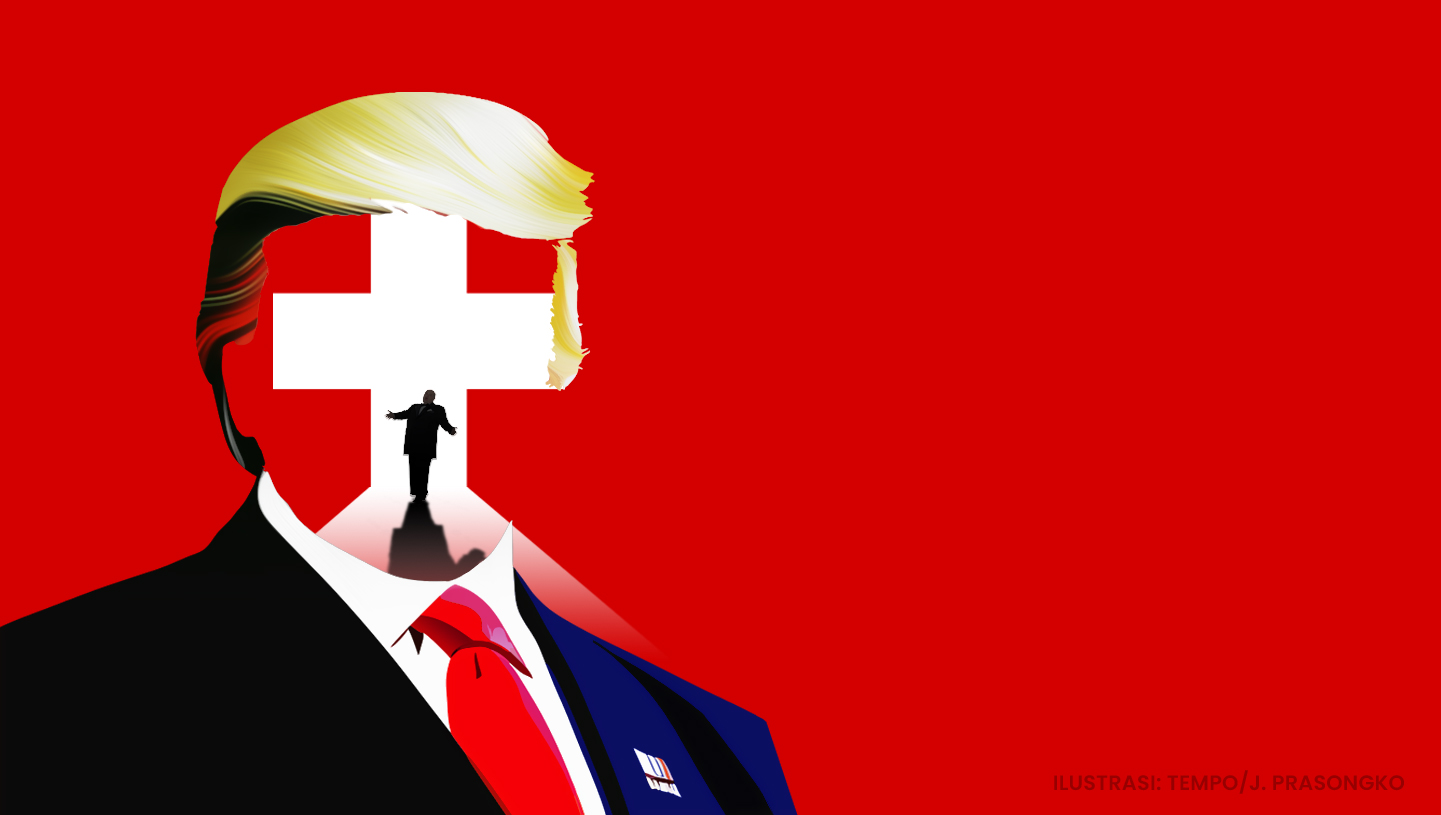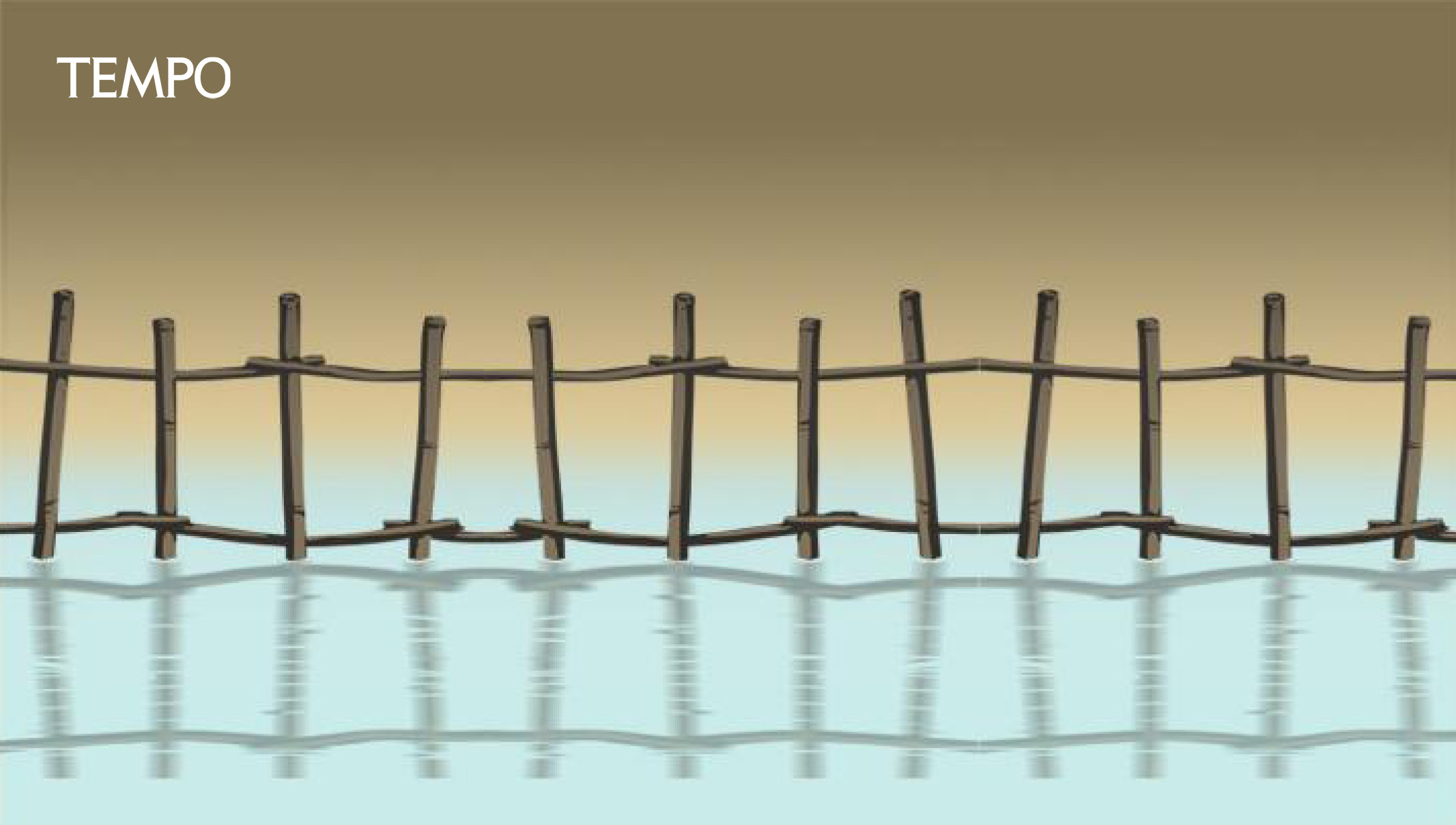Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Lain bangsa, lain proses demokratisasi, lain pula persoalan kebahasaannya.
Di Uni Soviet, penguasa komunis mempraktekkan politik dan ideologi monolitik. Keragaman diharamkan. Kebudayaan dan bahasa lokal pun dibunuhi secara sistematis selama tujuh dasawarsa.
Konsekuensinya, selepas komunisme, politik bahasa di negaranegara pecahan Uni Soviet mesti dimulai bukan dari titik nol melainkan ”minus sekian”. Potensi lokal, termasuk bahasa, mesti dihidupkan ulang dan direorientasikan sejalan dengan tuntutan perubahan. Demokratisasi kebahasaan (linguistic democratization) bahkan makan waktu lebih panjang dibanding liberalisasi ekonomi dan demokratisasi politik.
Keadaan hampir serupa terjadi di Eropa Timur dan Tengah. Sebagai konsekuensi kekeliruan politik mendasar selama beberapa dasawarsa komunisme, demokratisasi berhadapan dengan lemahnya individu, komunitas, dan lokalitas. Revitalisasi bahasa lokal dan pencarian bahasa pemersatu (lingua franca) pun jadi agenda tak sederhana, tak murah, dan tak sebentar.
Di Amerika Latin, demokratisasi sejak awal dan pertengahan 1980an mendatangkan persoalan revitalisasi kebudayaan dan bahasa lokal kaum pribumi atau penduduk asli. Selama masa otoritarianisme panjang, umumnya di bawah kendali junta tentara, kebudayaan dan bahasa lokal itu ditindas bahkan dilenyapkan secara sistematis. Demokratisasi pun memfasilitasi tumbuhnya gerakan sosial bagi pemulihan hakhak penduduk pribumi yang terampas.
Di tengah keberagaman proses itu, kasus Afrika Selatan menarik dicatat khusus. Di masa Apartheid, keragaman bahasa lokal, bahasa suku dipelihara dan dijadikan instrumen eksploitasi dan pemecah belah masyarakat. Masyarakat kulit hitam dibiarkan mempertahankan bahasa lokal dan tak punya bahasa lintas suku, lingua franca, sebagai alat hubung antarkelompok.
Karena keragaman bahasa lokal itulah ”mayoritas masyarakat kulit hitam” terpenjara sebagai identitas statistik dan bukan kekuatan politik. Penguasa Apartheid lalu memetik buahnya: menjadi minoritas yang menikmati ruang lapang dan rentang panjang penindasan atas mayoritas.
Masyarakat pun dijauhkan dari bahasa Inggris untuk mencegah kemungkinan terbangunnya kesatuan atau integrasi perlawanan dari beragam suku asli berkulit hitam. Dalam konteks inilah, manakala perjuangan demokrasi menguat, bahasa Inggris menjadi semacam simbol resistensi dan protes kaum tertindas.
Gelombang demokratisasi di bawah kepemimpinan elegan Nelson Mandela pun mendatangkan berlapislapis perkara kebahasaan. Politik bahasa diarahkan pada dua tujuan. Di satu sisi, keragaman bahasa lokal dipelihara sambil diberi orientasi baru: memperkuat komunitas dan egalitarianisme. Di sisi lain, lingua franca dibangun sebagai jembatan hubung antarmasyarakat multibahasa.
Politik bahasa diarahkan pada ”pelembagaan paham keragaman bahasa”. Dalam kerangka ini, hakhak kebahasaan ditempatkan dalam posisi sentral di dalam konstitusi baru Afrika Selatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lalu, didirikan pula lembaga yang secara khusus memantau hakhak kebahasaan, yakni Dewan Bahasa PanAfrika Selatan (Panslab, Pan South African Languages Board) dan Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak Kebudayaan, Agama, dan Kebahasaan Komunitas (Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities).
Gregory Hankoni Kamwendo pun mencatat dalam Nordic Journal of African Studies (2006) bahwa demokratisasi Afrika Selatan dicirikan oleh praktek desentralisasi rencana dan program kebahasaan serta pengembangan budaya konsultasi dan demokrasi partisipatoris dalam formulasi kebijakan kebahasaan. Ketika analis menyebut Afrika Selatan sebagai contoh sukses dalam ”Gelombang Ketiga Demokratisasi” mereka kerap kali alpa bahwa sukses itu disokong kelayakan politik bahasa.
Bagaimana dengan kita? Demokratisasi sejak 1998 memang menjadikan Indonesia sebagai penyelenggara pemilu nasional dan lokal, eksekutif dan legislatif yang sibuk. Di tengah kesibukan ini, politik bahasa terabaikan. Demokratisasi ternyata tak sertamerta membangunkan kesadaran kalangan prodemokrasi terhadap pentingnya penataan ulang politik bahasa dan kebijakan kebahasaan.
Akibatnya, setelah berjalan lebih dari satu dasawarsa, demokratisasi tak punya agenda politik kebahasaan yang layak. Demokratisasi, sekadar misal, masih menganaktirikan agenda debirokratisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang formal dan birokratis dan bahasa yang digunakan publik dalam pergaulan seharihari pun cenderung terpisah dalam dua ruangan kedap suara. Keduanya tak saling menegur, mengakrabi, dan melengkapi.
Maka, demokratisasi kita belum mematangkan bahasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo