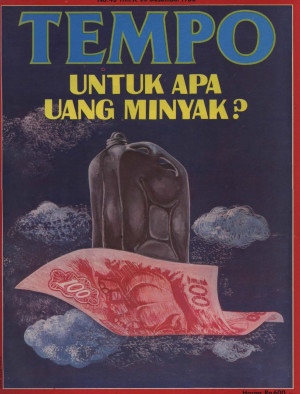PERANG Korea berkecamuk di awal tahun 1950-an. Dunia gawat,
karena Amerika Serikat dan sekutunya berhadapan dengan Uni
Soviet dan sekutunya di jairah kecil itu. Tapi bagi
perekonomian sebagian negara Asia perang itu justru membawa
berkah. Indonesia mengalami apa yang kemudian disebut The Korean
Boom.
Selama perang itu, karet membubung harganya. Sutikno Slamet,
kini 66 tahun, waktu itu pejabat tinggi di Kementerian Keuangan,
mengenang masa itu dengan mengatakan "Devisa kita memuncak,
mcncapai 500 juta dollar."
Tapi ia mengatakan juga "Naiknya devisa melahirkan tekanan
inflasi dalam negeri." Cadangan devisa yang baik, menimbulkan
kecenderungan untuk impor. Jusuf Wibisono, Menteri Keuangan
pada Kabinet Sukiman (1951) dan kemudian juga Kabinet Ali
Sastroamidjojo (1956) mengatalcan "Kalau dulu, cadangan devisa
itu semuanya dipakai untuk impor, karena tak punya pilihan
lain." Agaknya lebih banyak barang konsumsi ditelan.
Tapi "boom Korea" habis di tahun 1952. Pemerintah, yang
semula tak begitu mengacuhkan akibat inflatoar yang terjadi,
kini harus menghadapi kenyatan keras. Pendapatan pemerintah
hampir seluruhnya hasil perdagangan luar negeri--merosot hebat,
sementara pembelanjaan menjalar terus.
Defisit yang menyolok dalam neraca pembayaran terjadi di
tahun 1952. Usaha untuli mengatasi itu tak cukup kuat. Harga
dalam negeri mendaki. Cadangan devisa anjlok dari Rp 6 milyar
(195") menjadi Rp 3,6 milyar (1953).
Buat mengatasi anjloknya cadangan devisa, dilakukan
beberapa tindakan. Awal 1952 dilakukan devaluasi rupiah jadi
sepertiga dari nilainya semula. Cukai ekspor dalam pelbagai
tarif dikenakan, tapi dalam tingkat yang sedik it I.bih rendah
dari pajak ekspor yang berIaku sebelumnya.
Tapi langkah itu tak juga efektif. Maka lisensi impor dan
alokasi pemakaian devisa diperketat. Agaknya inilah yang
dimaksudkan Sjafruddin Prawira.
Negara, Gubernur sank Indonesia di tahun 1957 (pernah jadi
Menteri Keuangan, 1949-1950), ketika ia mengatakan pekan lalu.
"Dulu, setiap orang yang membeli devisa, harus punya surat resmi."
Pelbagai tindakan dilakukan untuk mengerem impor, hingga
Benjamin Higgins, seorang sarJana Amerika yang banyak membahas
perkembangan perekonomian Indonesia, dalam tulisan di tahun 1957
mengatakan sistem tarif Impor yang berbeda-beda itu, yang
disebut untuk "meransang" impor, sebenarnya suatu "sistem yang
merangsang orang Indonesia untuk tidak mengimpor."
Tapi toh menjelang akhir 1952 usaha ini mulai nampak
hasilnya. Para importir misalnya diharuskan membayar —ang muka
sebesar 40% (kemudian naik sampai 75%). Sistem pengontrolan
neraca pembayaran ini agaknya efekrif, dalam mengendurkan
tekanan pada cadangan devisa. Di tahun 1953, berkurangnya
cadangan devisa mencapai Rp 1,5 milyar--mendekati target (Rp 1,3
milyar) .
Tapi di tahun 1954 krisis neraca pembayaran yang serius
terjadi. Kabinet Ali Sastroamidjojo menggantikan Kabinet Wilopo,
Agustus 1953. Dengan niat memindahkan bisnis perdagangan luar
negeri ke tangan pengusaha Indonesia, Kabinet Ali
membagi-bagikan lisensi impor dan alokasi cadangan devisa keEpada
perusahaan nasional yang disebut sebagai "Benteng".
Kebijaksanaan ini memang berhasil menggalakkan sejumlah
perusahaan nasional. Pengaruhnya juga baik terhadap peredaan
inflasi kurang ketatnya alokasi cadangan devisa menyebabkan
mengalirnya barang impor, persis ketika daya heli meningkat,
sebagai akibat defisit anggaran belanja.
Namun korupsi yang terjadi akibat "lisensi istimewa" itu
mengurangi efek anti-inflasi yang terkandung. Sementara itu,
cadangan devisa merosot Rp 1,2 milyar di pertengahan pertama
1954 (targetnya hanya separuh dari itu).
Pemerintahpun dengan cepat melakukan tindakan drasfis.
Pemberian lisensi impor dan alokasi cadangan devisa sangat
dikurangi. Impor merosot hebat selama 1955. Tapi akibarnya
ternyata inflasi karena sebagian penting konsumsi orang
Indonesia berasal dari impor.
Kabinet Ali diganflkan Kabinet surhanuddin Harahap. Sasaran
utama peredaan inflasi, yang memang nyaris menjangkau wilayah!
pedalaman. Kabinet surhanuddin Harahap (rerkenal dengan
ringkasan "BH") lantas menyederhanakan prosedur impor. Tapi
serentak dengan itu, importir harus membayar uang muka Rp 5
juta, guna menjamin pembayaran devisa dan untuk pungutan atas
impor.
Stabilitas harga memang tercapai. Penawaran uang turun 5%
dalam beberapa bulan saja. Harga barang impor turun 15% selama
paruhan kedua tahun 1955. Pasar gelap uang dapar dipukul.
Namun menurunnya pelbagai harga barang itu disertai dengan
akibat merosotnya cadangan devisa dari Rp 2,7 milyar di akhir
1955 menjadi Rp 1,25 milyar di akhir Juni 1956. Padahal, di
tahun itu, negara Asia Tenggara lain berhasil meraih cadangan
devisa yang besar.
Sjafruddin Prawiranegara mengakui, bahwa kecenderungan
penggunaan cadangan devisa di masa lalu (dalam demokrasi
parlementer) lebih berorientasi pada politik partai pemerintah.
"Justru itu, lebih berat dibandingkan dengan zaman sekarang
dalam demokrasi parlementer, usia jabatan menteri tak panjang,
paling lama dua tahun," katanya pula.
Memang ada peniIaian, bahwa beleid Kabinet "BH" (menjelang
Pemilu 1955) adalah untuk menarik simpari dengan menurunkan
harga barang impor. Sedang garis Kabinct A li ialah menarik
simpati dengan lisensi impor serta alokasi cadangan devisa
kepada pengusaha nasional. Apapun udang di balik batunya, rasa
tak puas meluas terus, terhadap pelbagai beleid yang terutama
diarahkan hanya ke masalah neraca pembayaran.
Agustus 1953, saat-saat tergusurnya sistem demokrasi
parlementer, pembaruan moneter secara drastis dilakukan. Sutikno
Slamet, dipanggil dari Washington tempat ia bekerja pada sank
Dunia. Ia diangkat jadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Karya. Ia
mengadakan devaluasi uang 500-an dan 1000an dikecilkan jadi 10%
dari nilai semula. 90% deposito di semua bank yang di atas Rp
25.000 dibekukan, untuk jadi pinjaman bagi pem>rintah.
Tindakan ini ada hasiinya. Cadangan devisa naik, sekitar
300 juta dollar, kata Sutikno. Tapi mulai 1961, hasil itu leleh
kembali. Ekspor Ihdonesia setelah perang Korea bagain1anapun
selalu merosot, antara lain karena penetapan nilai rupiah yang
tak realistis, hingga pendaparan dari ckspor tak menggairahkan.
Semenrara itu --- seperti dalam masa "Demokrasi Terpimpin" --
belanja pemerintah membengkak oleh pembelian senjata dan provek
"mercu suar".
Maka cerita yang beredar di tahun 1966, ketika "Demokrasi
Terpimpin" rontok, ialah bahwa cadangan devisa Indonesia di
tahun itu praktis nol. Dan itu kembali terulang sepuluh tahun
kemudian ketika BI terpaksa membayari utang-utang jangka pendek
yang dibuat oleh Pertamina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini