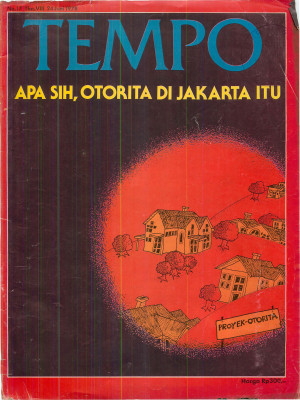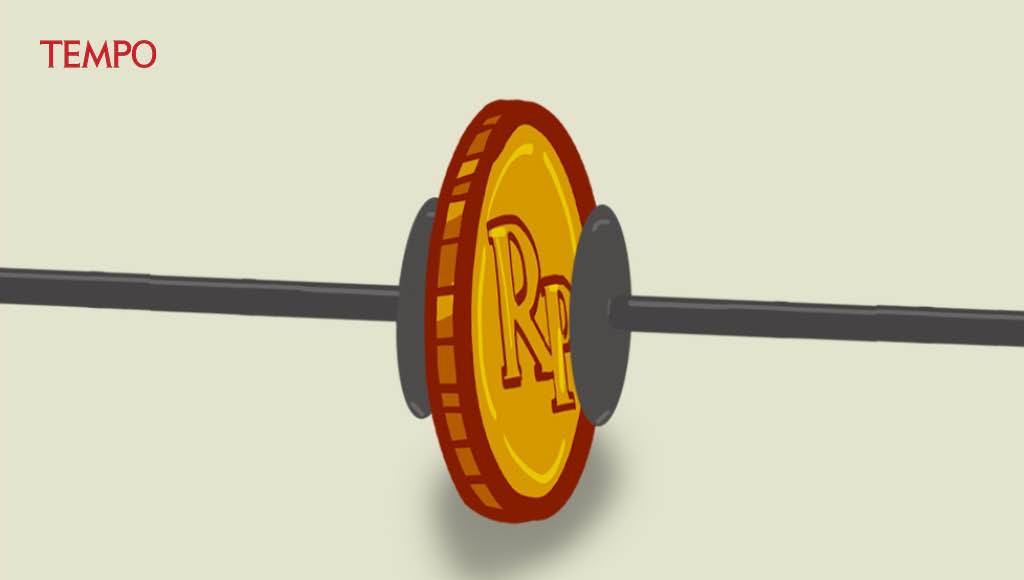BELUM pernah gengsi karet alam begitu naik seperti sekarang.
International Rubber Study Group minggu lalu di New York memberi
perhatian khusus tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dunia yang
makin meningkat.
Indonesia, sebagai produsen karet alam yang menempati urutan
kedua di dunia (sesudah Malaysia) mengirim delegasi besar ke
sidang IRSG itu. Ketiga unsur --perdagangan, pertanian dan
perindustrian -- dalam delegasi Indonesia itu pasti akan membawa
pulang tantangan baru, terutama di bidang produksi. Kenapa?
Berikut ini permasalahannya:
Setelah karct alam mengalami masa pasang surut yang mencemaskan,
sekarang pelan-pelan makin kelihatan bahwa dunia karet alam
sekurangnya sampai akhir abad ini tak akan segelap seperti yang
dikira semula. Industri pemakai karet alam sekarang mengkonsumir
lebih banyak karet dari yang sanggup dihasilkan. Gejala ini
sebenarnya sudah kelihatan sejak 1970, namun dulu perbedaannya
begitu kecil hingga belum sempat menarik perhatian.
Tapi ketika tahun lalu IRSG dalam Rubher Statis Bulletinnya
mengungkapkan bahwa konsumsi karet alam dunia sudah melampaui
produksinya dengan 200.000 ton, negara penghasil karet alam
mulai meninjau lagi kebijaksanaannya di bidang karet. Dalam
sidangnya di Kuala Lumpur Januari lalu, Asosiasi Negara
Penghasil Karet Alam (ANRPC) memutuskan, bahwa masalah
persediaan penyangga (buffer stock) bukan lagi masalah utama.
Tadinya masalah cadangan penyangga ini dilihat sebagai
satu-satunya cara untuk memperbaiki harga karet alam yang
gerakannya tak menentu itu.
Dalam komunike yang dikeluarkannya sesudah sidang tersebut ANRPC
melihat bahwa situasi pasaran karet "akan tetap baik" dan
meramalkan bahwa "dalam waktu 10 tahun mendatang dunia akan
kekurangan suplai karet alam, karena kebutuhan akan terus
melonjak." Perkiraan IRSG yang terakhir mengungkapkan bahwa pada
1990 kekurangan ini akan mencapai 2 juta ton, sedang pada 1985
akan 1,6 juta ton.
Memang agak merisaukan bagi Indonesia, di saat situasi karet
yang baik ini, justru prestasi ekspor karet tahun lalu kurang
mengesankan. Benar bahwa devisa dari karet naik dengan 6%
menjadi US$566 juta, tapi kenaikan ini terutama karena harga
karet yang naik sedangkan volume ekspor malahan turun dengan
20.000 ton menjadi hanya 826.000 ton.
Alhasil, pada 1977 kedudukan karet sebagai penghasil devisa
digeser oleh kopi, yang waktu itu bisa menghasilkan US$614 juta.
Dalam situasi di mana Indonesia harus mendorong ekspor
nonminyaknya -- karena minyak makin kehilangan pamornya di masa
mendatang ini -- apa yang terjadi pada karet bisa merupakan
contoh bahwa Indonesia mungkin akan kehilangan kesempatan. Sebab
utama adalah lambatnya pertambahan produksi karet. Dan ini
merupakan hal yang cukup berat untuk diatasi.
Usaha meningkatkan produksi karet alam di sini sedikit
terlambat. Untuk mengejar ketinggalan ini, mau tak mau, dalam
Pelita III nanti Pemerintah harus ngebut. Rencana peremajaan
ulang seluas 50.000 hektar tiap tahun mesti dilaksanakan, sebab
kalau tidak, maka produksi karet Indonesia pada 1985 hanya akan
mencapai 977.000 ton. Malaysia pada saat itu makin jauh
meninggalkan Indonesia dengan produksi hampir 2,6 juta ton.
Pertumbuhan produksi karet memang lambat beberapa tahun terakhir
ini. Dibanding peningkatan produksi Malaysia dan Muangthai yang
melaju 6 sampai 7% tiap tahunnya, maka pertambahan produksi
karet Indonesia hanya merangkak dengan 1,7%. Dari kedudukannya
sebagai raja karet sebelum Perang Dunia yang menguasai separuh
produksi karet dunia, Indonesia kini hanya memprodusir
seperempat produksi dunia.
Beres
Sulitnya, masalah peningkatan produksi karet bukan hanya
perluasan areal atau peremajaan pohon. Petani karet kita -- dari
mana sebagian besar devisa karet dihasilkan -- hanya menerima
30% harga fob. Tapi petani Malaysia menerima 60% sampai 70% fob.
Jelas ada yang tak beres dalam rantai pemasaran karet di sini.
Dengan sedikitnya bagian yang diterima petani dari setiap US$1
ekspor karet, mereka kehilangan perangsang untuk memprodusir.
Perkebunan tak dirawat dengan cermat, peremajaan pohon
diabaikan, dan bibit yang ditanam sering asal bibit saja, bukan
bibit unggul.
Di sini masalahnya adalah bagaimana saluran antara petani dan
pengekspor karet bisa diperpendek, hingga bagian yang lebih
besar dari harga fob bisa dinikmati petani. Barangkali perlu
belajar sedikit dari Malaysia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini