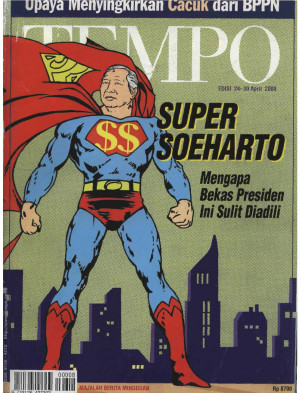Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hari itu, Kamis pekan lalu, belum siang betul. Jakarta masih malas-malasan. Tapi, di ruang dealing valuta asing, suhu hampir mendidih. Di antara sulur kabel yang berantakan, corong mike yang bertonjolan, dan layar monitor yang terus berkedip-kedip, belasan sumber suara seperti bergetar bersama-sama. Semua harus didengarkan. Hampir tiap lima menit, puluhan nasabah di ujung telepon ramai-ramai minta penambahan pembelian dolar. Suasana makin gaduh setelah sebuah bank besar dari Singapura tiba-tiba melempar bom, "Berani beli pada Rp 7.965." Maka, wuss…, tak tertahankan lagi, harga mata uang Amerika itu terus melambung.
Hari itu, "takdir" sang trader memang belum menjadi kenyataan. Tapi ia tak meleset terlampau jauh. Sore itu, harga dolar ditutup pada posisi Rp 7.985, harga termahal selama enam bulan terakhir, sekaligus termahal sejak Gus Dur naik takhta jadi presiden. Pekan ini, para pemain pasar uang menaksir, harga dolar akan terus membubung melampaui batas angka keramat Rp 8.000.
Bagi kehidupan awam, loyonya rupiah memang belum berarti banyak. Tapi, bagi sejumlah ekonom, jatuhnya rupiah bersamaan dengan rontoknya harga saham dan penurunan peringkat surat utang Indonesia tak bisa dianggap remeh. Sjahrir, ekonom gaek yang sudah lama bertapa dari kebisingan dunia bisnis, misalnya, menilai bahwa pelbagai kejatuhan itu "menunjukkan perekonomian kita makin merosot, jauh lebih buruk ketimbang era sebelumnya."
Harus diakui, kejatuhan rupiah memang bisa menjadi ancaman yang memprihatinkan. Jika keterusan, kenaikan harga dolar akan mendongkrak biaya produksi dan akhirnya memompa harga barang. Ujung-ujungnya: ancaman inflasi. Tapi, sulit dibantah pula, kejatuhan nilai tukar itu bukan semata-mata potret kegagalan perekonomian. Menurut para pemain pasar uang, anjloknya rupiah terutama didorong oleh derasnya permintaan dolar sejumlah perusahaan di dalam negeri. Untuk apa? Ada banyak pendapat.
Sebagian analis yakin, membeludaknya kebutuhan dolar itu berkaitan dengan banyaknya utang swasta yang jatuh tempo. Menurut seorang pejabat bank sentral, tagihan utang luar negeri swasta yang harus dibayar mencapai US$ 29 miliar. Besarnya tagihan ini membuat keder sejumlah perusahaan sehingga berusaha memborong dolar sebelum kehabisan. Menurut laporan jaringan kantor berita Dow Jones, pada hari itu ada banyak perusahaan Indonesia yang membeli mata uang dolar sebanyak US$ 3 juta sampai US$ 4 juta dari pasar uang dalam sekali pukul. Kepanikan ini pelan-pelan merembet dan membuat perburuan dolar makin seru.
Tapi teori panik ini dibantah seorang kepala bagian treasury sebuah bank asing ternama di Jakarta. Kalaupun ada pembayaran utang, katanya, jumlahnya tak mungkin sebesar itu. Sebagian besar perusahaan yang punya pinjaman dolar, kini, masih berada dalam proses perundingan restrukturisasi utang. Biasanya, mereka membuat semacam standstill agreement, utang tak perlu dibayar sampai negosiasi rampung.
Lalu, mengapa perusahaan-perusahaan ini berburu dolar? "Mereka perlu untuk membiayai impor," katanya. Ia menunjuk permintaan mobil dan barang mewah yang terus menanjak. Mau tak mau, permintaan ini akan mendongkrak impor barang modal dan bahan baku sehingga menggerakkan permintaan dolar. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, sejak Januari lalu, aktivitas impor melonjak pesat.
Jika benar itu yang terjadi, tak ada alasan untuk terlampau khawatir. Kejatuhan nilai tukar rupiah karena ledakan impor barang modal dan bahan baku justru merupakan sinyal bahwa perekonomian sudah mulai bergerak. "Ini sangat menggembirakan," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom.
Tampaknya, kejatuhan nilai tukar rupiah itu merupakan buntut dari banyak kejadian. Selama sebulan terakhir, posisi mata uang Indonesia itu terus terancam dari kurs "langgengnya" di Rp 7.400 per dolar. Dari sektor ekonomi, ancaman itu dipicu penundaan pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF) yang semula akan dicairkan April lalu. Penundaan ini tiba-tiba saja membalikkan seluruh optimisme yang sempat merebak di awal pemerintahan Gus Dur. Publik kecewa. Gosip bahwa tim ekonomi dalam kabinet tak mampu bekerja, kini, mendapatkan konfirmasi.
Tekanan makin kencang setelah lembaga rating internasional Standard & Poor menurunkan peringkat surat utang Indonesia dari CCC+ menjadi SD alias selected default (sebagian terancam tak terbayar). Ini merupakan buntut dari keputusan pemerintah untuk mengantre di Paris Club meminta penjadwalan utang. Tekanan yang bertubi-tubi ini membuat rupiah makin kalang-kabut.
Sementara itu, secara riil, permintaan dolar memang meningkat. Sebagian karena naiknya impor, sebagian lagi lantaran kenaikan suku bunga dolar. Dengan bunga deposito dolar 6 persen dan swap (premium yang harus dibayar untuk membeli dolar pada tahun depan) 5 persen, bunga rupiah yang cuma 10 persen tidak menarik lagi. Praktis, "Tanpa tekanan IMF dan rating pun, orang cenderung memilih dolar," kata seorang pemain pasar uang di Jakarta.
Sudah begitu, tekanan dari sisi politik tak kurang besar. Kendati masih empat bulan lagi, sidang umum MPR (Agustus nanti) sudah mulai membuat gaduh. Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais sama-sama mendesak agar Presiden membuat pidato pertanggungjawaban, bukan sekadar laporan, dalam sidang itu. Tentu saja pidato seperti ini membuka kemungkinan adanya "penolakan" anggota sidang. Singkat kata, pasar membaca dengan jelas ada upaya untuk menjegal Gus Dur di tengah jalan.
Tekanan politik dan ekonomi itu kemudian digongi oleh rumor dari, biasalah, pasar uang Singapura. Kabarnya, sebuah lembaga investasi dari Amerika Serikat telah menjual rupiah senilai US$ 10 juta untuk ditukar dengan dolar Singapura, di pasar New York. Gosip yang tak jelas juntrungannya ini makin menggoyahkan kekuatan rupiah. Maka, jadilah rupiah tersangkut ke posisi terendah selama enam bulan terakhir.
Bagi ekonom Nomura Securities Singapura, Adrian Panggabean, jatuhnya rupiah tak perlu ditanggapi terlampau serius. Hal itu, katanya, tak mencerminkan kukuh tidaknya landasan perekonomian Indonesia. Secara umum, perekonomian kita mulai membaik. Inflasi terkendali, bunga bank turun, kurs cenderung stabil, dan pertumbuhan ekonomi mulai positif. Likuiditas perekonomian juga cukup tersedia. Perbankan bahkan lagi kebanyakan duit, sampai harus terus-menerus disedot oleh bank sentral.
Selain itu, Adrian mencatat pelbagai perkembangan baru yang lebih khusus, misalnya premium risiko Indonesia sudah menurun dari 500 basis poin akhir tahun lalu menjadi 425 saat ini. Dibandingkan dengan premium risiko negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia masih tetap tinggi. "Tapi laju penurunannya amat progresif," katanya.
Di samping itu, pemakaian kapasitas produksi terus meningkat. Semester pertama tahun lalu, misalnya, pemakaian kapasitas produksi cuma sekitar 57 persen, lalu perlahan naik menjadi 60 persen di semester kedua, dan sekarang, menjelang semester kedua 2000, sudah mendekati 67 persen. Ini petunjuk yang jelas bahwa penyerapan produk mulai meningkat. Tingkat konsumsi merangkak naik.
Tapi itu semua memang bukan berarti kita sudah keluar dari krisis. Menurut perhitungan Adrian, dengan semua perbaikan itu, kita baru kembali ke posisi tahun 1996. Artinya, "Kita ini masih mundur tiga tahun." Untuk mencapai posisi seperti sebelum krisis (1997), ada satu pertanyaan yang mesti dijawab: apakah pertumbuhan yang hanya dihela oleh konsumsi akan bertahan lama?
Sayangnya, hampir semua ekonom berpendapat sama: tidak. Menurut Umar Juoro, Direktur Cides, bagi perekonomian, konsumsi hanyalah perangsang sementara. "Mustahil ia bisa bertahan terus dari tahun ke tahun," katanya. Ia memberi contoh: toh, orang tak mungkin membeli mobil 10 biji atau membeli TV sampai 20 buah saban tahun. Singkat kata, daya rangsang konsumsi ini terlalu singkat. Pertumbuhan akan lebih langgeng jika didorong investasi.
Inilah yang menjadi pangkal kekhawatiran para ekonom. Dalam dua tahun terakhir, gairah investasi jangankan naik, malah cenderung menurun. Memang betul, saat ini tambahan investasi baru belum diperlukan mengingat pasar belum mampu menyerap seluruh kapasitas produksi yang ada. Tapi, dalam jangka panjang, investasi yang mandek akan mengancam perekonomian. Tanpa investasi baru, pengangguran akan membeludak.
Ancaman pengangguran ini makin serius karena sejumlah perusahaan yang kini masih beroperasi terancam tutup. Menurut perhitungan Umar Juoro, beberapa usaha diperkirakan akan memangkas jumlah pekerja, atau malah sekalian menutup pabrik, lantaran tak mampu mengakomodasi tuntutan kenaikan upah buruh. Selain itu, lemahnya penerapan hukum dan maraknya praktek pemerasan, terutama terhadap perusahaan di daerah, akan memperbesar ancaman ini.
Ekonom Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan, juga sepakat bahwa perekonomian sudah mulai tumbuh. Sayangnya, kualitas dan kelestarian pertumbuhan ini masih dipertanyakan. "Jangankan untuk terbang," katanya, "kita ini baru berjalan untuk sekadar bertahan hidup." Ia menilai, perekonomian Indonesia saat ini berhasil bertahan tanpa sumber dana baru, tanpa berhubungan dengan perbankan. Situasi seperti ini tak bisa dipertahankan dalam jangka panjang.
Lalu, apa yang harus dilakukan? Berjibun. Yang terpenting, tentu, membereskan pekerjaan restrukturisasi perbankan dan utang swasta, yang hingga kini masih terseok-seok. Selain itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap perbankan sebagai sumber dana, pemerintah perlu menciptakan pasar obligasi yang lebih sehat.
Selain penyelesaian teknis ekonomis seperti itu, Ikhsan juga melihat perlunya penyelesaian politis. "Kalau mau ekonomi berjalan sehat," katanya, "Gontok-gontokan untuk menggusur Gus Dur harus dihentikan."
Dwi Setyo, Edy Budiyarso, Biro Jakarta
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo