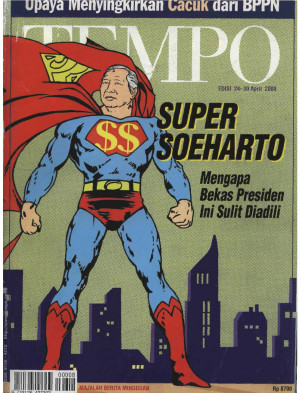Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apa gerangan yang dipikirkan laki-laki itu seraya berjalan pulang? Barangkali ia sadar betapa sembarangan sikapnya tadi: ia tak tahu, ada yang lebih kuasa pada nadi leher seorang lain—ya, ada yang lebih kuasa atas hidup dan mati ketimbang sejuta laki-laki yang menghunus pedang. Barangkali ia akhirnya mengerti kenapa Rasul Tuhan itu tak membunuhnya: ia juga tak merasa berkuasa. Pada saat seseorang merasa dapat menentukan nasib seorang lain, pada saat ia merasa bisa "menjengkal nyawa", pada saat itu ia mengangkat diri jadi Yang Mahakuasa. Kemanusiaan, dengan segala keterbatasannya, pun disisihkan: menghilangkan nyawa seseorang sama artinya dengan membinasakan semua manusia.
Barangkali laki-laki Arab di abad ke-6 itu juga mengerti bahwa Nabi hendak bersikap adil, juga kepada orang yang memusuhinya. Barangkali ia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa keadilan bukanlah pembalasan. Mungkin akhirnya ia juga sempat menyaksikan sebuah saat yang sering dibanggakan dalam sejarah: kemenangan orang-orang muslim atas Mekah tak diikuti dengan pembasmian. Para bekas musuh itu tetap hidup di kota itu. Keadilan adalah sikap berimbang, karena keadilan adalah bagian dari sikap berhati-hati agar tak ada yang berkelebihan, juga dalam amarah.
"Berkelebihan", sebagaimana "pembalasan yang setimpal", tak bisa diartikan secara harfiah: rasa amarah hanya bisa benar-benar dianggap "berkelebihan" dan pembalasan bisa dengan tepat dinilai "setimpal" apabila rasa takut, rasa tertindas, dan rasa sakit bisa diukur. Tetapi bagaimana itu bisa diukur? Siapa yang akan mengukur? Di kamar penyiksaan, di tempat-tempat kekejaman, jerit itu tak bisa diringkaskan dengan kata-kata, dengan bahasa, dengan segala hal yang tumbuh dari konvensi. Rasa sakit itu, untuk memakai kata-kata Pramoedya Ananta Toer, adalah "nyanyi sunyi seorang bisu".
Pada akhirnya, seorang yang berdiri di hadapan orang lain akan berdiri tak gegabah. Ia datang tanpa sikap seorang perumus. Ia bukan seorang pengukur. Ia tak bisa mengacungkan pedang dengan lurus dan memutuskan: "Kau, hai kafir, telah bersikap kurang ajar 100 persen, maka kau harus kuhajar 100 persen." Ia bahkan sebenarnya tak bisa memastikan: "Kau telah mengacungkan pedang ke dekat leherku, sebab itu kau tentu hendak membunuhku…." Bukankah bisa saja dikatakan bahwa orang yang mengancam itu justru datang untuk menguji iman dan ketabahan?
Saya membayangkan wajah di abad ke-6 itu karena di hari-hari ini masa silam diingat (dan dibayangkan) hanya dengan kegetiran yang tak selesai-selesai. "Aku telah dianiaya di Badu sebelum tahun 1965," kata si Fulan. "Aku telah dianiaya di Fulan sejak tahun 1965," kata si Badu. Saya membayangkan peristiwa kecil di Jazirah Arab di abad ke-6 itu karena hari-hari ini ada suara bising, "la victim, c'est moi".
Hubris, atau takabur, sering datang dari pintu belakang. Tiba-tiba saja ia menyusup merasuki kita. Seperti seorang penguasa yang mengatakan, "Negara, itulah aku," seorang teraniaya yang menunjuk diri dan berkata "Sang korban, itulah aku" juga bersalah karena ia mengangkat diri sebagai pemegang monopoli atas ingatan dan percakapan. Memegang monopoli itulah yang dilakukan oleh "Orde Baru" dengan memermak buku sejarah sebagaimana para penyiksa memermak wajah para tapol. Dengan cara yang lain, itu juga yang dilakukan oleh si Fulan dan si Badu dalam benci mereka yang berkepanjangan.
Tapi bukankah harus dicatat: pengalaman yang dikenang adalah suatu pengalaman yang tak terbatas? Bukankah apa saja bisa saya timba dan saya bentuk dari dalamnya?
Menyadari hal ini adalah menyadari betapa bisa sewenang-wenangnya ingatan. Sebab itu, setiap tarikh memerlukan kebebasan. Di depan sejarah tiap orang perlu untuk bisa mengemukakan dan juga mempersoalkan tiap versi tentang masa lalunya. Tapi perlunya kebebasan itu bukan bertolak karena hak. Perlunya kebebasan itu berangkat dari kesadaran akan batas.
Maka, yang jadi soal bukanlah sejauh mana kita akan memaklumi masa lalu itu. Yang jadi soal pada mulanya bukanlah maaf dan rekonsiliasi, melainkan kerendahan hati. Bahkan dengan pedang di tangan, dengan hak untuk menghukum, kita tak bisa serta-merta menebas leher. Kita bisa bersalah, kita pernah bersalah.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo