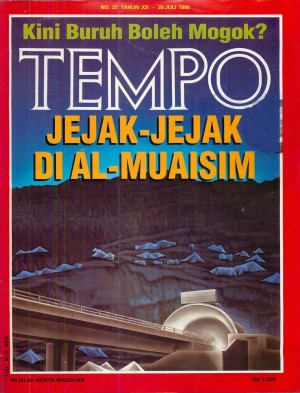INILAH impian yang jadi kenyataan: terlaksananya program jetisasi di perusahaan swasta. Semenjak awal Agutus 1990, Sempati Air (SA) akan beroperasi dengan pesawat bermesin jet Fokker 100, yang dibelinya dari pabrik Fokker, Belanda. Direksi SA, yang memperkenalkan pesawat barunya di Hotel Borobudur, Jakarta, tampak berbinar-binar. Sempatilah yang mengukir sejarah, sebagai maskapai swasta pertama, yang menggunakan jet untuk penerbangan noncarter. Selain itu, direksi SA bisa lebih berbesar hati lantaran ketujuh pesawat jet tersebut dibeli dengan modal sendiri. Lain halnya Merpati, yang, karena berstatus BUMN, memperoleh pesawat jet limpahan dari Garuda. Terlepas dari kebanggaan yang mencuat, dengan tujuh armada barunya yang akan diterima secara bertahap hingga semester II tahun depan -- mau tidak mau -- pengelola SA harus berhitung lebih cermat. Soalnya, belum ada izin bagi swasta untuk menerbangi rute luar negeri, yang masih merupakan monopoli Garuda Indonesia. Selain itu, jalur lokal pun masih diatur cukup ketat. Padahal, seperti pernah dikemukakan M. Soeparno, Dirut Garuda, pesawat jet baru bisa beroperasi dengan efisien, kalau jarak terbang yang ditempuhnya memadai. Pendapat serupa dikemukakan juga oleh Sularto Hadisumarto, Ketua Umum INACA (Indonesia National Air Carrier Association). "Pemilik pesawat jet harus sudah memperhitungkan dengan matang untung rugi dari pengoperasiannya," katanya kepada Bisnis Indonesia. Mengapa? Menurut Sularto, untuk mencapai titik impas, sebuah pesawat jet minimal harus mencapai 200 jam terbang dalam sebulan. Kurang dari itu, perusahaannya akan merugi. Apalagi, tarif terbang delapan sen dolar per kursi per kilometer dinilai terlalu murah. "Boleh dibilang paling murah di dunia," kata G.B. Rungkat, Senior Vice President Bouraq Indonesia Airlines. Bahkan, tarif delapan sen itu jauh lebih rendah dari yang direkomendasikan IATA, yang 18 sen dolar per kursi per kilometer. "Masalahnya, selain biaya operasi langsung, masih harus diperhitungkan biaya-biaya lain seperti bunga pinjaman dan cicilan pesawat," ujar Rungkat. Berdasarkan kalkulasi tersebut, tak pelak lagi, langkah yang diambil Sempati sungguh cukup berani. Untuk tujuh pesawat yang dibelinya, dengan harga total sekitar 224 juta dolar (sekitar Rp 403 milyar), SA harus membayar cicilan sekitar 2,1 juta dolar per bulan. Pengeluaran seperti itu berlanjut selama 12 tahun. Berat sekali, tentu. Tapi SA sudah punya strategi yang mantap. Fokker 100 pertama, yang akan dioperasikan awal Agustus ini, direncanakan menempuh jalur Jakarta-Medan pulang pergi (sehari dua kali), dan Jakarta-Solo p.p. sehari sekali. Kalau ditotal, pesawat itu akan terbang sekitar 325 jam per bulan. Ini pun masih di atas jam terbang minimal. Dengan langkah itu, plus tingkat pengisian tempat duduk minimal 65%, "Kami yakin, Fokker 100 bisa mencapai titik impas dalam waktu enam tahun," ujar Hasan M. Soedjono, Presdir SA. Begitu pula untuk tiga Fokker 100 lainnya, yang datang beruntun pada akhir Agustus, September, dan Desember nanti -- Hasan sudah punya rute. Pesawat-pesawat itu direncanakan menerbangi jalur Jakarta-Balikpapan, Jakarta-Ujungpandang, dan Jakarta-Surabaya. Lalu kalau dihitung-hitung, jumlah jam terbangnya setiap bulan tetap masih di atas 200 jam per bulan. Sedang tiga pesawat lainnya akan dimanfaatkan SA untuk menyinggahi bandara-bandara yang tidak bisa dilandasi oleh pesawat berbadan besar. "Soalnya, bobot Fokker 100 tak beda dengan F-28," kata Hasan. Dengan peta kegiatan seperti itu, SA -- disadari atau tidak -- akan "mengambil kue" Garuda dan Merpati. Dan itulah yang diharapkan swasta selama ini. "Kesempatan menikmati jalur-jalur yang dimonopoli Garuda akan membuat persaingan semakin sehat," kata pemimpin sebuah penerbangan. Garuda mungkin sekali tidak sampai terganggu porsinya, tapi Merpati bisa direpotkan. BUMN ini selalu harus menempatkan diri sebagai nomor dua (sesudah Garuda), dalam segala hal. Kecuali, barangkali, dalam memanfaatkan pesawat CN-235 buatan IPTN, yang kabarnya lebih banyak jam parkirnya, ketimbang jam terbangnya. Di pihak lain, Hasan mengakui, jalur-jalur penerbangan Fokker 100 milik SA tidak diperoleh berdasarkan fasilitas. Tegasnya, tidak lantaran saham SA dimiliki oleh PT Yayasan Tri Usaha Bakti milik Angkatan Darat (40%), Humpuss (25%), Nusamba milik Bob Hasan (35%). Pemberian izin penerbangan kepada SA, menurut Bob Hasan, "Merupakan konsekuensi bagi pemerintah yang mengajak swasta berpartisipasi dalam membangun perhubungan udara." Sementara itu, maskapai yang melayani carter sudah lama menikmati jalur-jalur gemuk Garuda. Indonesia Air Transport (IAT), milik grup Bimantara, contohnya. Maskapai ini mengoperasikan 21 pesawat kecil berkapasitas 10-24 penumpang -- tujuh di antaranya bermesin jet dan bebas menerbangi jalur gemuk mana pun. "Itu karena kami hanya melayani kalangan konsumen tertentu," kata R. Soekardjono Sosrohamidjojo, Direktur Pelaksana IAT. Berbekal kelonggaran itu, IAT bisa mengangkut turis dari negara-negara di Eropa langsung ke daerah tujuan wisata seperti Pulau Komodo, dan Telaga Warna di Flores. Dan karena carter, IAT tidak terikat tarif yang dipatok pemerintah. Dari tarif 1.450 dolar per jam, "Lima belas persen merupakan keuntungan," tambah Soekardjono. Kalau jetisasi sudah merebak ke swasta, apakah langkah Sempati dan IAT kelak bisa diikuti oleh Bouraq dan Mandala? Nah, itu masih tanda tanya. Yang pasti, ada peluang untuk pemakaian pesawat jet oleh swasta. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara. Sobirin Misbach, ada berucap, "Silakan saja (maksudnya, melakukan jetisasi). Yang penting, jangan membeli pesawat sejenis yang telah diproduksi IPTN." Lantas jalurnya bebas juga, Pak? Budi Kusumah, Moebanoe Moera, Sugrahetty Dyan K., dan Linda Djalil
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini